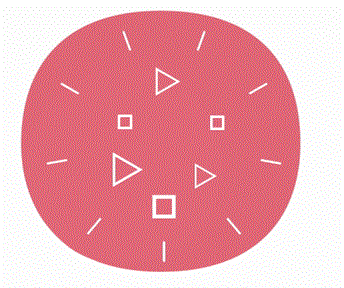Membaca tulisan Hamid Basyaib yang bertajuk “Aku, Individualisme Maksimum Chairil Anwar” membangkitkan kembali pengalaman saya menelisik karya-karya Chairil Anwar bertahun silam, terutama untuk beberapa judul puisi yang memang kental dengan pengalaman pribadi penyair terkait beberapa nama yang ditulis juga di dalam puisi itu.
Ambil contoh puisi “Mirat Muda, Chairil Muda” berikut ini;
MIRAT MUDA, CHAIRIL MUDA
di pegunungan 1943
Dialah, Miratlah, ketika mereka rebah,
Menatap lama ke dalam pandangnya
coba memisah matanya menantang
yang satu tajam dan jujur yang sebelah.
Ketawa diadukannya giginya pada
mulut Chairil; dan bertanya: Adakah, adakah
kau selalu mesra dan aku bagimu indah?
Mirat raba urut Chairil, raba dada
Dan tahulah dia kini, bisa katakan
dan tunjukkan dengan pasti di mana
menghidup jiwa, menghembus nyawa
Liang jiwa-nyawa saling berganti. Dia rapatkan
dirinya pada Chairil makin sehati;
hilang secepuh segan, hilang secepuh cemas
Hiduplah Mirat dan Chairil dengan deras,
menuntut tinggi tidak setapak berjarak
dengan mati.
1949
Sekilas, puisi ini terasa begitu personal, atau individualis, menceritakan pengalaman percintaan antara Sumirat dan Chairil Anwar belaka. Setidaknya hal itu yang terkesan, bahkan kemudian diperpanjang dengan kisah di balik terciptanya puisi ini dalam sebuah tulisan pendek yang diberi judul “Mengkritik Puisi Chairil Anwar ‘Mirat Muda, Chairil Muda’ Melalui Pendekatan Ekspresif” yang dimuat dalam sebuah blog milik Jennyfer Puji tahun 2017 silam.[1]
Namun jika kita teliti lagi, Chairil Anwar menuliskan pada larik pertama dengan “Dialah, Miratlah, ketika mereka rebah” yang ingin menyampaikan bahwa “dia” yang adalah “Mirat” adalah sama seperti “mereka” yang “rebah.” Di sini, ada kesan bahwa aku lirik dalam puisi tersebut menggunakan Mirat, nama perempuan yang dicintai, sebagai sebuah metafora bagi sebuah hal yang bersifat dugaan kepada sekelompok yang umum atau paling tidak berjumlah banyak (mereka). Prinsip ini seturut dengan gaya bahasa atau majas sinekdoke pars pro toto.
Pada larik pertama ini, bisa dianggap adanya pertimbangan untuk meletakkan pengalaman pribadi kepada pandangan terhadap fenomena dalam masyarakat, semacam refleksi dari micro pada macro cosmic-nya. Puisi ini, didasarkan tulisan keterangan di bawah judul yaitu “di pegunungan tahun 1943” seakan memberi tahu bahwa Chairil Anwar tengah mengenangkan percintaannya (yang kemudian berakhir dengan kegagalan di tahun 1944), sementara puisi itu sendiri terbit pada Februari 1949 tak lama dari peristiwa Agresi Militer Belanda II yang mengakibatkan ditangkapnya para pemimpin Republik Indonesia termasuk Sjahrir (tokoh yang banyak dibantu oleh Chairil di masa pendudukan Jepang), sampai berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara.
Jadi bisa disinyalir bahwa dalam puisi tersebut ada semacam harapan untuk tetap menjaga cinta dari dan kepada mereka yang seolah telah kalah, seperti para pemimpin negeri yang ditangkap dan dibuang oleh Belanda.
Tentu anggapan saya bisa salah, misalkan dengan bantahan bahwa “mereka” yang dimaksud dalam larik pertama adalah Mirat dan Chairil seperti tertulis pada larik-larik lainnya. Tetapi, larik “Mirat raba urut Chairil, raba dada” membuat kita bisa bertanya, “Mengapa tidak ditulis ‘Mirat raba urut aku, raba dadaku’ di situ?” Apalagi pada larik sebelumnya terdapat pertanyaan (dari Mirat) yang menggunakan kata “kau” dan “aku.”
Dari banyak pengalaman saya bertemu seseorang, jarang sekali orang yang menyebut dirinya dengan nama ketika menulis atau berbicara, meski memang ada yang sebagai kebiasaan masa kecil berlanjut hingga dewasa. Tetapi, rasanya ganjil bagi seorang Chairil Anwar yang sering sekali menggunakan kata “aku” dalam puisi-puisinya menyebut dirinya sendiri Chairil seperti pada puisi tersebut, yang tampaknya menjadi satu-satunya puisi yang memuat nama dirinya sebagai Chairil itu.
Selanjutnya, bisa ditilik lagi tiga larik terakhir, yang tertulis dengan sedikit parafrasa, “Hiduplah Mirat dan Chairil dengan deras, (dengan cara) menuntut tinggi (agar) tidak setapak berjarak dengan mati.” Di sini tersirat kesengajaan untuk membuat Mirat dan Chairil seperti “Romeo & Juliet” dalam puisinya yang bertajuk “Catetan Th. 1946” atau seperti nama-nama lain yang menjadi alusi dalam puisi-puisinya seperti Ahasveros, Eros, Thermopylae, dan lainnya.
Agaknya “Mirat dan Chairil” dalam “Mirat Muda, Chairil Muda” menjadi semacam sodoran kepada khalayak untuk menggunakan pengalaman pribadi Chairil Anwar sebagai bagian dari kehidupan umum. Yakni, kehidupan pemuda dan pemudi tidak boleh jatuh atau rebah pada pilihan asal berani dan jujur, tetapi harus sampai pada mengetahui liang jiwa dan nyawa agar tidak takut surut langkah karena dibatasi maut.
Pada puisinya yang lain, meski dengan judul yang terasa begitu personal juga, yaitu “Buat Gadis Rasid” Chairil Anwar malah seperti tengah menyoal perkara yang di luar interaksi antara dirinya dengan seseorang lain, untuk lebih jelasnya bisa dilihat puisi tersebut secara lengkap, yaitu;
BUAT GADIS RASID
Antara
daun-daun hijau
padang lapang dan terang
anak-anak kecil tidak bersalah, baru bisa lari-larian
burung-burung merdu
hujan segar dan menyebar
bangsa muda menjadi, baru bisa bilang “aku”
Dan
angin tajam kering, tanah semata gersang
pasir bangkit mentanduskan, daerah dikosongi
Kita terapit, cintaku
– mengecil diri, kadang bisa mengisar setapak
Mari kita lepas, kita lepas jiwa mencari jadi merpati
Terbang
mengenali gurun, sonder ketemu, sonder mendarat
– the only possible non-stop flight
Tidak mendapat.
1948
Di sini jelas sekali bahwa bagian yang personal adalah larik “Kita terapit, cintaku” dan “Mari kita lepas, kita lepas jiwa mencari jadi merpati . . .” ketika penggunaan kata kita merujuk kepada dua belah pihak yang memiliki relasi.
Beberapa hal yang disinggung oleh Chairil Anwar pada puisi tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang baru tiga tahun merdeka, dan masih terancam dikuasai kembali oleh Belanda. Larik“anak-anak kecil tidak bersalah, baru bisa lari-larian” bisa diintepretasikan bahwa saat itu bangsa Indonesia khususnya sastra Indonesia masih mencari-cari jati diri dan bentuknya dengan mencoba berbagai keinginan dan tujuan selain mewarisi yang sudah dianggap masa lalu.
Mungkin yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah keinginan dan upaya Chairil Anwar untuk lepas dari pengaruh sastra era Pujangga Baru, dan langkah semacam itu tidak bisa dan tidak boleh disalahkan, karena dengan kemerdekaan Indonesia pada 1945 artinya ada “padang lapang dan terang” yang bisa digunakan untuk membangun “sastra Indonesia.”
Pada larik lainnya, terdapat pendapat dari Chairil Anwar bahwa ada kondisi “bangsa muda menjadi, baru bisa bilang ‘aku’” yang seakan merujuk kepada pengaruh individualisme yang sedang melanda (sastra) Indonesia dan pengaruh itulah yang oleh Chairil Anwar didayagunakan untuk revolusi dalam perpuisian.
Chairil Anwar bukannya tidak sadar bahwa individualisme dalam puisi-puisinya itu tidak memiliki pertentangan berat, karena itu bisa dibaca perubahan peta dan iklim yang terjadi tiba-tiba dalam puisi itu, padahal baru ditulis “hujan segar dan menyebar” tapi dilanjutkan dengan “dan angin tajam kering, tanah semata gersang, pasir bangkit mentanduskan, daerah dikosongi,” sementara kesadaran itu ditulis oleh Chairil sebagai keluhan “Kita terapit, cintaku” yang menunjukkan kondisi yang tidak nyaman dalam upaya tersebut.
Kesadaran dan keluhan itu, seolah-olah mengindikasikan bahwa sebenarnya ia tidak sendirian dalam melakukan pencarian, eksplorasi, revolusi terhadap sastra Indonesia. Kata kita lagi-lagi merujuk pada sejumlah orang, bukan pihak yang soliter.
Selebihnya, dalam puisi itu, bisa ditemukan semacam program kerja (sastra) Chairil Anwar yaitu:
- mengecil diri,
- selalu mencari (kebaruan),
- terbang (bisa dianggap sebagai upaya menulis yang terbaik), dan
- mengenali gurun, sonder ketemu, sonder mendarat (bisa dianggap melihat peta persaingan tapi tidak akan terpengaruh), dan
- the only possible non stop flight (sekalipun) tidak mendapat (apa-apa), yang berarti bahwa menyair akan selalu menjadi pekerjaan utamanya dan itu yang akan terus dia lakukan. Ini sejalan dengan “sekali berarti sudah itu mati” dalam puisinya yang lain.
Jika “mengecil diri” menjadi hal yang diamalkan, bukankah seharusnya Chairil Anwar tidak memancarkan karya-karya yang bersifat individualisme? Mungkin hal ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa justru dengan karya-karya yang bersifat personal itulah Chairil Anwar merevolusi sastra Indonesia, khususnya puisi.
Sekarang coba dilihat puisi “Derai Derai Cemara” khususnya bait ke dua, yang seolah menjadi suatu sikap permisif pada hal-hal yang akhirnya tidak berjalan mulus sesuai rencana. Di sana disebutkan “aku sekarang orangnya bisa tahan/ sudah berapa waktu bukan kanak lagi/ tapi dulu memang ada suatu bahan/ yang bukan dasar perhitungan kini.”
Bisa jadi, memang upaya “mengecil diri” itu tidak bisa dilakukan. Artinya, Chairil Anwar tetap menulis puisi dengan dasar yang personal, pengalaman hidupnya. Pada puisi “Aku Berada Kembali”, ada bagian yang menegaskan bahwa ia memang seperti mendapat keleluasaan untuk menulis yang demikian. Di sana ditulis ”Hanya/ Kelengangan tinggal tetap saja. / Lebih lengang aku di kelak-kelok jalan; / lebih lengang pula ketika berada antara / yang mengharap dan yang melepas.”
Jika kembali dicermati, sebenarnya ada batasan dalam keleluasaan yang ditulis oleh Chairil Anwar, yaitu berada pada suatu antara. Artinya, memang perlu telisik lebih dalam saat bersentuhan dengan apa yang terlihat seperti pengalaman personal pada puisi-puisi Chairil Anwar, apakah benar peristiwa yang ada dalam tubuh puisi itu tertutup bagi mereka yang disebut, atau bisa ditarik ke lingkup yang lebih luas lagi, bahkan ke dalam hidup kita sendiri?
Meskipun begitu, masih dalam puisi yang sama, Chairil Anwar merasa masih ada ganjalan. Mungkin benar rencananya tidak berjalan dengan semestinya. Padahal sudah jelas bahwa ada niatan dan langkah untuk “mengecil diri,” karena itu ia menulis ‘Telinga kiri masih terpaling/ ditarik gelisah yang sebentar-sebentar seterang guruh.” yang seolah menunjukkan bahwa sebenarnya “kerja belum selesai, belum apa-apa.”
Barangkali, puisi yang paling pas untuk menunjukkan betapa Chairil Anwar memperlakukan keegosentrisannya adalah puisi “Yang Terampas dan Yang Putus” ketika ia menulis, “aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang/ dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu;” yang jika dibayangkan bahwa “kematian” justru akan masuk ke dalam ruang (kamar) bernama “aku” dan “aku” setelah mengalami “kematian” itu tidak hilang malah melepas kisah baru.
Hal itu terasa sekali perbedaannya dengan aku lirik yang dituliskan Amir Hamzah dalam puisinya “Padamu Jua” yang ingin masuk pada kesunyian ketika kekasih menunggu si aku lirik. Dengan perkataan lain, aku lirik dalam puisi Amir Hamzah adalah bagian dari semesta, sedangkan bagi Chairil Anwar, kata aku justru adalah semestanya. Paling tidak, semesta bagi kehendaknya.
Tangerang Selatan, 17 Juli 2022
[1] (http://sastradanbahasaindonesiaku.blogspot.com/2017/06/mengkritik-puisi-chairil-anwar-mirat.html).

Dedy Tri Riyadi
Dedy Tri Riyadi, penyair yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja iklan. Pernah menjadi penyair muda terbaik dan penulis puisi terbaik untuk suatu festival dan situs sastra. Buku puisi terakhir diterbitkan bertajuk Berlatih Solmisasi, sempat masuk daftar panjang Kusala Sastra Khatulistiwa. Sedang merencanakan menerbitkan naskah yang tidak menang lomba dengan sejumlah tambahan dan perbaikan.