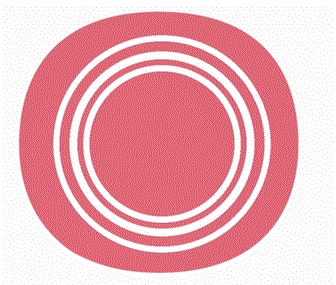—Untuk Nirwan Dewanto dan Saut Situmorang
Banyak jalan dalam membicarakan karya sastra. Kajian budaya, kajian pascakolonial, pembacaan dekat (baik dalam baju modern maupun pascamodern), hanyalah sebagian kecil dari keanekaragaman cara kita mengkaji karya sastra. Sebagai situs kritik sastra yang dikelola oleh Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)—dan operasionalnya dibiayai oleh dana publik—tengara.id tidak mungkin mengabaikan kebinekaan itu dan hanya mengakui salah satu saja sebagai kritik sastra yang baik dan benar. Kami membuka diri terhadap pelbagai kemungkinan bentuk telaah karya sastra itu—sejauh semua itu berwujud tulisan yang bermutu dalam keseluruhan bentuknya. Itulah kritik sastra dalam pemahaman kami.
Sewaktu editorial tengara.id edisi perdana menyentil pembacaan dekat dan membandingkannya dengan pembacaan jauh, tentu bukan berarti tengara.id menolak tulisan yang menggunakan pendekatan pembacaan dekat atau hanya memprioritaskan tulisan dengan pembacaan jauh atau dengan pendekatan kajian budaya. Apa yang kami suratkan di situ adalah tawaran—jika bukan tantangan—untuk menjelajahi wilayah telaah yang jarang disinggahi kritikus kita. Sebab pembacaan jauh—yang tidak bisa disamakan dengan “membaca karya terjemahan”—adalah suatu pendekatan yang belum banyak diamalkan di Indonesia, bahkan di lingkungan akademis.
Tentu saja, maksud kami bukan menjadikan Franco Moretti sebagai kanon seperti disampaikan oleh Saut Situmorang, karena sumbangsih Moretti adalah justru mendorong kita memperluas rentang perhatian hingga menjangkau mereka yang selama ini tak terbaca karena dianggap “kurang sastra” atau jauh dari status kanonik (The Great Unread).
Di luar aneka pendekatan yang bisa digunakan dalam menelaah karya sastra, fakta yang kita hadapi akhir-akhir ini adalah kelangkaan apa yang disebut “kritik sastra”. Dalam kalimat yang Malthusian bisa dirumuskan begini: Karya sastra berkembang berdasarkan deret ukur, sementara kritik sastra bergerak menurut deret hitung. Tanpa mengurangi penghargaan pada apa yang telah dikerjakan oleh kaum akademisi di kampus-kampus, sudah sejak lama kita menderita miskin telaah sastra. Sementara, generasi penulis kita hari ini lebih tertarik mengerjakan karya sastra kreatif—karena itu mungkin bentuk yang paling mudah dan masuk akal untuk digarap. Adapun telaah sastra—apakah bentuknya kita sebut “kritik sastra” atau “kajian budaya”—membutuhkan bukan hanya imajinasi, tetapi ketajaman pembacaan, kecocokan pendekatan (teoretis)—dan tidak boleh dilupakan: keterampilan menulis.
Karena itu, perlu uji coba sejumlah pendekatan lain yang bisa memperkaya peralatan kita dalam membicarakan karya sastra (dan lingkungan di sekitarnya). Jika kritik sastra yang selama ini kita kenal lebih mengutamakan pembacaan dekat, belakangan ini kita juga berhadapan dengan pendekatan pembacaan jauh. Yakni, membaca suatu korpus besar hingga mencapai ribuan bahkan belasan ribu judul dengan peranti sains data dan statistika, untuk kemudian melihat morfologi sastra secara longue durée dan dalam skala gigantis (meliputi serba-sastra, serba-manusia). Tawaran itu, dengan kata lain, adalah sekaligus juga tawaran untuk memperkaya perkakas kritik sastra, dan dengan itu memperluas batas-batas kritik sastra.
Mengapa batasan kritik sastra perlu diperluas? Tentu jawabnya sebagian bisa ditemukan dalam perubahan realitas sastra itu sendiri. Sastra hari ini semakin ditandai oleh gejala kelintas-wahanaan (transmediality). Sebuah buku sastra hari ini boleh jadi adalah album musik esok hari atau film tahun depan, bahkan video game lima tahun mendatang. Ini berlaku bukan hanya terhadap “sastra pop” yang selama ini dipandang sebelah mata, tetapi juga aneka sastra yang biasanya dikategorikan sebagai “sastra serius”. Perlahan, tetapi agaknya pasti, sastra menjadi bagian dari arus budaya populer yang ditandai oleh aneka bentuk kelisanan, termasuk aneka bentuk kelisanan di media sosial. Bagaimana semua itu mengubah cara karya sastra dibaca, dan memberi dampak pada bentuk sastra itu sendiri? Inilah salah satu pertanyaan tentang “gelagat” sastra kita hari ini.
Banyak pertanyaan muncul dari situ. Bagaimana kritikus sastra menghadapi kemungkinan bahwa sastra menciut jadi sejumput konten dalam rantai-pasokan industri multimedia hari ini? Bagaimana kritikus sastra melihat para sastrawan menghadirkan citra dirinya di media sosial dan memobilisasi pengaruh di tengah aneka pusat pengaruh yang tampaknya mulai bergeser dari lembaga budaya besar ke para pemengaruh media sosial (influencers)? Bagaimana proses kanonisasi sastra terstruktur oleh algoritma media sosial yang cenderung membentuk kamar gema (echo-chamber) dan memfasilitasi kelahiran semacam pendekar-pendekar dalam dunia kang-ouw sastra tingkat lokal? Singkat kata: Bagaimana kritikus sastra memaknai ekosistem sastra hari ini?
Bertanya tentang batas kritik sastra hari ini adalah sesungguhnya bertanya tentang hal yang dibuat muskil oleh hari ini, yaitu apa kekhasan wahana (medium specificity) sastra? Apakah sastra pada dasarnya adalah semata-mata tulisan, sebuah buku? Rasanya tidak lagi demikian. Diskusi tentang kekhasan wahana, seperti halnya diskusi tentang kekhasan metode kritik sastra, datang dari sebuah masa ketika suatu cabang seni atau ilmu hendak memisahkan diri dari cabang lain.
Di musik ini terjadi misalnya dalam Eduard Hanslick (1825-1904) yang mendefinisikan karya musik sebagai “bentuk bunyi bergerak,” di seni rupa dalam Clive Bell (1881-1964) yang mendefinisikan karya rupa sebagai “bentuk bermakna,” dan akhirnya juga di kritik sastra dalam pemikiran para “Kritikus Baru dari Selatan” (Southern New Critics). Konteks institusional yang melatari estetika para “Kritikus Baru” dari era 1920-an ini adalah keperluan menyusun sebuah argumen bagi jurusan sastra yang mandiri dari filologi. Inilah yang mendorong mereka merumuskan sebuah disiplin pembacaan dekat yang menempatkan teks sebagai “ikon” yang pada dirinya bersifat mandiri dan swatuju (autotelic): non-representasional, impersonal, murni. Inilah juga yang melatari penerimaan modernisme T.S. Eliot, dengan segala usaha “melarikan diri dari kepribadian” dan temperamen klasisismenya, dalam pantheon Kritik Baru.
Keadaan yang memungkinkan segala pembicaraan tentang kekhasan wahana itu semakin sulit ditemukan hari ini. Justru sebaliknya, di mana-mana kita jumpai gejala kelintas-wahanaan. Dunia sastra kita dewasa ini tidak lagi iseng sendiri dan jauh di pulau, tetapi kian jadi bagian dari hubungan saling-pengaruh budaya yang lebih luas. Membaca karya sastra tentu penting, tetapi membaca ekosistem sastra juga tak kalah penting. Keduanya harus dicatet, keduanya harus dapat tempat.
Untuk itulah tengara.id membuka diri bagi tulisan-tulisan yang membahas bukan hanya tentang sebuah teks sastra, tetapi juga aneka kupasan tentang ekosistem sastra, ataupun pembacaan jauh dengan korpus besar. Seraya berterima kasih atas tanggapan-tangapan kritis yang muncul, kami menantikan tulisan-tulisan yang memberikan suatu argumen yang kokoh dan segar tentang sastra, dalam aneka bentuknya—dan itu tadi: berwujud tulisan yang bermutu dalam keseluruhan bentuknya—tengara.id tentu akan siap menampung. Seperti tercantum dalam undangan menulis kami: “Telaah yang tajam, mendalam, memberi perspektif baru, tentu saja, akan kami prioritaskan. Kami juga menantikan tulisan-tulisan dalam bentuk dan gaya memikat. Panjang tulisan, maksimal 10.000 kata dalam bahasa Indonesia.”
tengara.id
tengara.id adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas karya sastra Indonesia melalui pembacaan, pembedahan, dan penilaian yang dilakukan dengan landasan argumen dan teori yang bermutu.