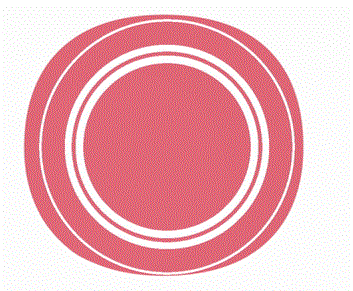Tanggapan Tomy D. Ginting atas klaim Saut Situmorang bahwa Chairil Anwar telah melakukan “modernisasi bahasa ucap yang radikal atau revolusioner” dalam perpuisian Indonesia, karena ia menggunakan kata aku sebagai subjek-lirik, sangat baik. Argumen Ginting meyakinkan, disertai tinjauan sejarah dan sedikit ulasan linguistik yang memadai, terutama atas penggunaan aku dalam karya-karya para pendahulu Chairil—bahkan hingga ke Raja Ali Haji dari abad ke-19.
Meski di bagian akhir esainya Ginting bersikap humble bragging secara tidak perlu, dan mengumbar sarkasme dengan dosis yang terlalu tinggi terhadap orang yang pendapatnya sedang disanggahnya, pada hemat saya model kritik yang disajikannya secara keseluruhan adalah cara yang baik dan berguna.
Cara ini pasti lebih bermanfaat, setidaknya memberi tambahan informasi yang relevan untuk melihat aspek historis dalam proses pembentukan karya-karya Chairil Anwar, bahkan kalaupun dilepaskan dari aneka predikat pujian terhadap Chairil, terutama predikat pembaru atau pelopor puisi modern Indonesia. Patut pula dipuji sikap Ginting, yang tidak terseret arus deras pemujaan terhadap Chairil dan kepenyairannya (bukan pada syairnya).
Tersirat bahwa Ginting menagih uraian dan argumen yang lebih meyakinkan (dari Saut Situmorang atau siapa pun yang menekuni karya-karya Chairil) bahwa Chairil memang layak dipredikati pembaru atau pelopor puisi modern kita. Jika predikat itu disandarkan hanya pada penggunaan kata aku dalam puisi Chairil, Ginting membantahnya dengan argumentatif. Ia seolah berkata: “Saya ingin mendengar alasan yang lebih kaya dan kokoh daripada sekadar pemakaian kata aku—yang sudah jelas telah digunakan oleh para penyair pendahulu Chairil.”
Argumen dan penjelasan semacam itulah yang juga langka dalam sejumlah diskusi yang diadakan dalam rangka peringatan 100 tahun Chairil Anwar akhir-akhir ini.
Terlihat jelas pembahasan tentang Chairil pada umumnya tidak sebanding dengan asumsi tentang kebesarannya sebagai penyair (yang karena itu usia seratus tahunnya perlu dirayakan dengan aneka acara oleh banyak kelompok atau ahli, seperti tampak dari “demam Chairil Anwar” di beberapa kota).
Sebagai awam yang sekadar pengagum Chairil Anwar (saya hanya membaca satu-dua puisinya), penjelasan dan argumen seperti itulah yang ingin pula saya dengar dari mereka yang dianggap ahli tentang Chairil dan posisinya dalam perpuisian dan kesastraan pada umumnya.
Sangat mengecewakan bahwa yang saya dapatkan, misalnya, dari sebuah diskusi yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta dan Salihara pada 14 Juni 2022, nyaris sepenuhnya aspek-aspek gossipy dan dimensi personal, yang itu pun pastilah tidak berlaku khas pada Chairil Anwar.
Seorang anak milenial di paruh pertama abad ke-20 yang punya kapasitas intelektual seperti dirinya, di sebuah zaman ketika kebanyakan penduduk yang jumlahnya masih sedikit, dan tentunya dengan lapisan terpelajar yang masih amat sangat kecil, tentunya cukup lazim untuk berperilaku seperti Chairil Anwar—anak rantau yang sering bokek, gagal mengejar gadis idaman yang cantik dan kaya, kenal dengan beberapa politisi pergerakan (apalagi salah satu tokoh terpentingnya adalah pamannya sendiri). “Eksentrisitas” serupa juga jamak terjadi pada kaum intelektual sezamannya di pelbagai bidang dan profesi.
Dalam diskusi berjudul “Chairil: Sekarang!” itu (entah kenapa judulnya membentak begitu), seorang pembicara perlu menegaskan bahwa sikap keren dan charming Chairil di masa itu kira-kira setara dengan Nicholas Saputra (ini nama bintang film tampan yang populer), dan kecantikan gadis yang digandrunginya (Ajati, dibaca Ayati dan bukan Adjati) disetarakan dengan Dian Sastro atau Wulan Guritno—dua aktris kontemporer yang juga terkenal. Sebagai sekadar ilustrasi (yang diniatkan untuk kocak) pun pembandingan ini sungguh sia-sia untuk meningkatkan pengertian kita tentang kepenyairan Chairil Anwar.
Pembicara lain, yang menyatakan tekad membara untuk bagaimanapun juga akan membuat film layar lebar atau film seri tentang Chairil Anwar, tidak henti mengungkapkan betapa dalamnya studi yang telah bertahun-tahun dikerjakannya tentang Chairil. Namun, isi uraiannya berputar-putar di sekitar keremeh-temehan pribadi si penyair—seakan-akan seluruh aspek pengalaman seorang pemuda-penyair yang wafat dalam usia 26 sungguh berharga untuk ditekuni dan dikabarkan kepada khalayak (karena niscaya unik dan mengandung sebentuk kearifan hidup yang istimewa).
Saya menunggu dengan kesabaran yang saya gandakan tiga kali lipat untuk mendengar apa tantangan-tantangan teknis dan artistik yang mungkin dihadapinya dalam upaya memindahkan puisi Chairil Anwar ke medium layar film, dan strategi apa yang barangkali bisa dikerjakannya untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. (Mudah-mudahan di bagian lain diskusi itu ia memaparkan hal-hal penting ini; saya tidak sempat mendengarkannya sebab setelah acara berlangsung 30-an menit, sisa kesabaran saya habis tuntas; tidak sanggup lagi menanggung pelecehan dan penyia-nyiaan intelektual lebih jauh).
Rasanya seluruh durasi yang saya ikuti terus berputar di kisaran yang sama: kedua pembicara (Agus Noor dan Salman Aristo), bahkan juga moderator (Ahda Imran), seolah berlomba mengumbar pengetahuan mereka tentang sisi-sisi remeh-temeh dalam kehidupan si penyair (yang tipikal anak muda seusia Chairil Anwar)—pernahkah ia mampir ke Yogyakarta, siapa perempuan-perempuan di dalam kehidupan Chairil, dan sejenisnya.
Agus Noor bahkan membandingkan puisi-puisi cinta Chairil dengan sajak-sajak karya moderator Ahda Imran, yaitu untuk memikat “dedek-dedek cantik” atau yang berkonotasi seperti itu. (Tapi, ini mungkin ironi yang terselip tidak sengaja dalam gurauan yang diniatkan untuk lucu itu: mengungkap motif Chairil dalam membuat puisi bernuansa asmara—seberapa jauh dugaan ini bisa dipertanggungjawabkan?).
Ginting membatasi pembahasannya pada klaim Saut Situmorang tentang “modernisasi bahasa ucap” Chairil Anwar dengan bertumpu pada penggunaan kata aku sebagai subjek-penyair. Ia tidak membahas isi karya Chairil tersebut—yang bisa dipastikan merupakan puisi paling masyhur sepanjang masa di tanah air kita. Maka di sini saya mencoba sedikit membahas isi puisi tersebut, yang bagi saya tidak kurang merupakan penegasan individualitas yang ketandasannya tidak berpreseden, bahkan hampir tidak kita temukan dalam puisi-puisi pasca-Chairil hingga hari ini.
“Aku” merupakan penegasan individualitas yang mencengangkan diukur dari semangat zaman di masa itu. Chairil Anwar bukan hanya hidup di tengah suatu masyarakat yang mengutamakan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, tapi juga hidup dalam sistem politik kolonial Jepang yang sangat menekankan konformitas.
Maka seorang sastrawan, seperti dicatat penulis M. Balfas, menulis komentar atas puisi Chairil tersebut dengan judul “Hendak Menjadi Orang Besar?”—individualisme Chairil dicibir bahkan oleh seorang pengarang. Armijn Pane sebagai redaktur majalah Pandji Poestaka menolaknya karena watak individualitas puisi itu. Editor Nur Sutan Iskandar memuatnya dalam majalah Timoer setelah Chairil mengirimnya ke sana, tapi mengubah judulnya menjadi “Semangat”—pembingkaian ini seakan mau mengubah makna puisi itu menjadi tidak individualistis dan terkesan congkak.
Sungguh luar biasa bahwa Chairil, saat itu (1943) baru berusia 21, menegaskan individualitasnya sejak dalam judul puisinya—sebuah judul satu-kata yang juga tidak lazim di masa itu. Ia menegaskan ke-aku-annya bukan dengan semangat menonjolkan diri atau menyajikan potret indah tentang dirinya, justru sebaliknya—ini pun suatu keberanian dan kejujuran yang mengagumkan.
Ia bukan sekadar mengaku sebagai “binatang”, tetapi “binatang jalang”, suatu karakter keburukan ganda—dan ia bahkan berani mengakui bahwa ia “dari kumpulannya terbuang.” Selain mengakui bahwa perilaku sosialnya berbeda, ia dengan nada rendah menerima bahwa ia tersingkir dari komunitasnya—dan ini bukan masalah baginya.
Ia bukan hanya mengungkapkan interioritas atau solilokui yang emosional dan sentimental seperti para pendahulu pengguna aku seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah atau Raja Ali Haji (sebagaimana beberapa baris puisi mereka dicontohkan oleh Ginting), tetapi mengekspresikan sesuatu yang lebih “fisikal” dan dapat diidentifikasi dengan aktif oleh pembacanya; berbeda dari ekspresi-ekspresi subjektif-personal para pendahulu yang hanya bisa diterima oleh pembaca, tanpa bisa “dilihat”.
Ia juga berani mengakui bahwa ia menderita (mungkin karena suatu penyakit, mungkin juga karena situasi hidup keseharian yang menekannya), tapi ia menegaskan bahwa derita besar itu akan ia atasi dengan tegas (kubawa berlari); ia mengungkapkan penderitaannya bukan dengan semangat mencari simpati, melainkan justru buat menyatakan kegigihan sikapnya untuk melawan nasib buruk itu seorang diri, tanpa perlu bantuan siapa pun.
Yang tidak kalah menggetarkan: dengan segala deritanya, ia bukan hanya tidak berputus asa, tetapi justru menegaskan ketakgentarannya untuk melanjutkan hidup; ia bahkan bertekad untuk hidup selama mungkin (seribu tahun lagi).
Bila ajalnya tiba, katanya, ia tak ingin ada yang mendoakan, termasuk doa agar hidupnya lebih panjang; ia juga menyatakan kepergiannya tidak perlu ditangisi, juga oleh orang yang terdekat dengannya (Kalau sampai waktuku/kumau tak seorang kan merayu/Tidak juga kau/ Tak perlu sedu sedan itu).
Maka ia memenuhi janji yang diringkas dalam judul puisinya; bahwa apa pun yang terjadi pada dirinya, bahkan hingga soal kematiannya, semuanya adalah urusannya sendiri. Derita itu ia hayati sendiri, upaya pemecahannya pun pasti ia akan atasi sendiri; pendeknya seluruh perkara adalah urusan “aku” sendiri.
Maka bagi saya foto ikonik Chairil Anwar, sebuah pose close up yang menggambarkannya bersikap acuh-tak-acuh dengan sorot mata tajam, dan dengan bibir dan jari yang menjepit sebatang rokok yang mengepulkan asap, merepresentasikan dengan tepat ke-aku-annya, kalaupun belum tentu mewakili semua puisi yang pernah ditulisnya.
Sedangkan untuk keremeh-temehan kehidupannya—yang setara belaka dengan berita tentang penyanyi Agnismoe operasi plastik di dokter mana dan selebritas Rabunjauh baru saja membeli mobil bersayap tiga dengan harga sekian—biarlah menjadi sajian tabloid Cuk & Jancuk dan sejenisnya. Mereka punya ladang nafkah khas sendiri, yang tidak perlu diusik—atau ditiru.
Para pengulas Chairil Anwar yang serius, atau setidaknya yang berpretensi demikian, tidak perlu menghancurkan kebesarannya yang terkesan justru ingin mereka hormati, dengan cara menonjol-nonjolkan semua hal tentang Chairil, kecuali satu hal terpenting: mengulas sungguh-sungguh kualitas karya-karyanya—jika mungkin: dengan tambahan tentang relevansinya sekarang dan sejauh mana ia menanamkan pengaruh pada penyair-penyair kontemporer.

Hamid Basyaib
Hamid Basyaib adalah mantan wartawan, dan Komisaris Utama Balai Pustaka (2015-2020). Ia menerbitkan banyak buku tentang isu Islam, sosial, politik, budaya, sains, dan buku anak-anak. Dua buku terbarunya Membela Sains dari Obskurantisme Filsafat dan Kitab Keadilan dan Kisah-kisah Lainnya.