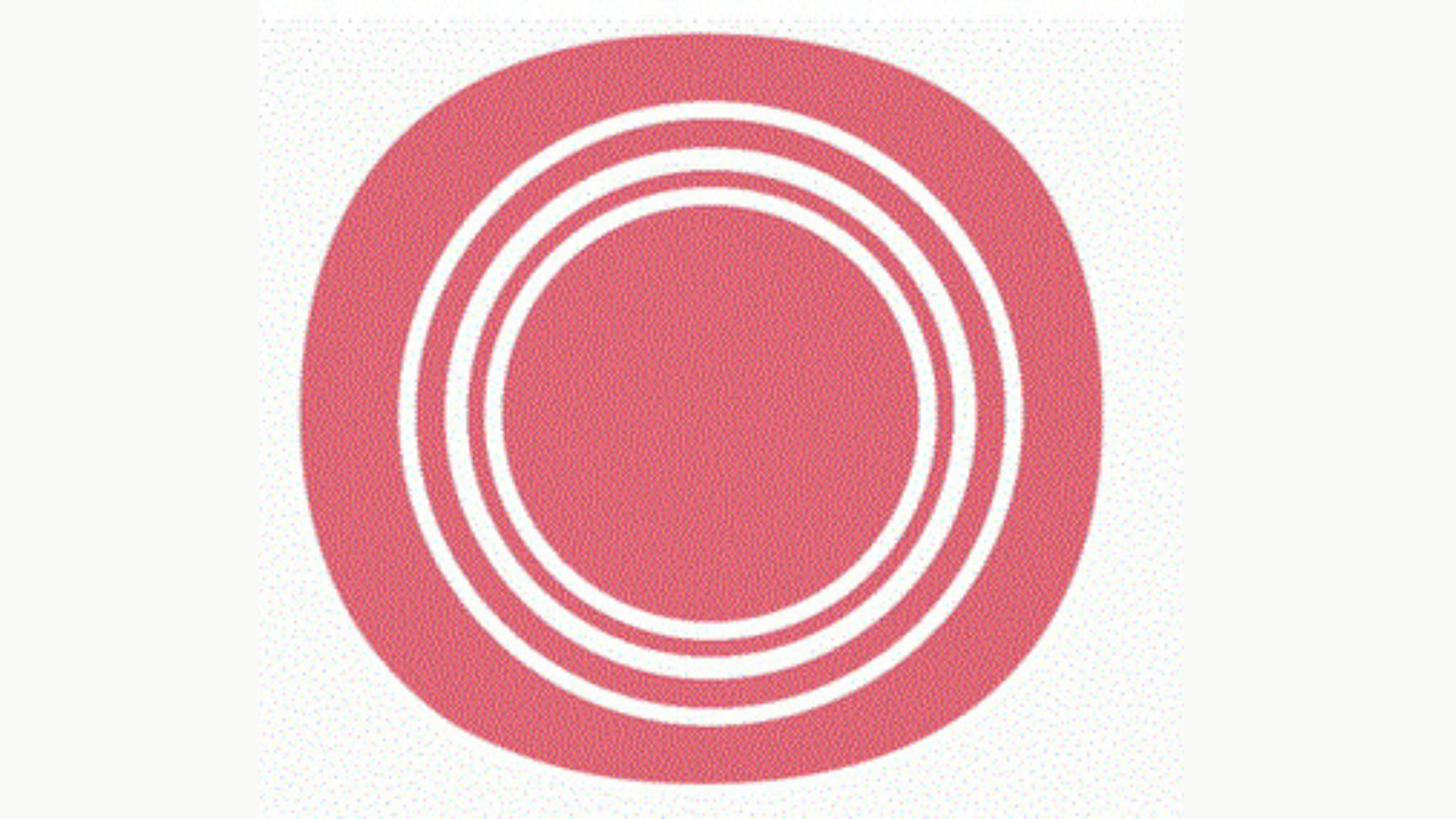BAGIAN DUA
Saat Seekor Orangutan Datang
1
Sore itu, di wilayah pusat pembangunan IKN, seekor orangutan datang.
Mata cokelatnya yang dalam, biasanya memancarkan kearifan rimba, kini menyimpan sekelebat kebingungan, seolah semalam ia bermimpi berada di sarang yang utuh, namun paginya terbangun di tengah hiruk pikuk konstruksi para pekerja dengan suara-suara bising. Setiap gerakannya adalah simfoni melankolis, perlahan ia mengayunkan tubuhnya yang kekar, memegang dahan-dahan rapuh dengan jemari yang terasa berat, seperti membawa beban seluruh spesiesnya di setiap ayunan.
Udara sore itu membawa aroma tanah basah bercampur semen, bukan lagi aroma lumut dan bunga hutan yang penuh kesejukan. Setiap hela napas orangutan itu terasa seperti upaya keras; paru-parunya yang telah terbiasa menghirup oksigen murni dari paru-paru dunia, kini harus beradaptasi dengan partikel-partikel tak kasat mata dari ambisi manusia.
Sore itu, tidak ada yang menduga, lantaran semua telah diamankan dan semua terlihat begitu tenang. Kedamaian seolah menyelimuti seluruh kawasan.
Tidak ada juga yang menyadari kapan tepatnya ia muncul. Pagi itu, para pekerja proyek melihatnya duduk diam di tengah jalan utama yang baru dicor, di atas aspal yang belum sepenuhnya kering. Ia seolah membatu, tidak menatap siapa-siapa, hanya duduk seperti sedang menunggu sesuatu yang tak pernah dijelaskan dalam rencana induk pembangunan.
“Kita tunggu saja satgas satwa datang,” ujar seorang mandor sambil menghembuskan asap rokok.
Hanya saja sebelum tim konservasi tiba, ada seekor orangutan lagi yang datang. Lalu, tiga. Lalu, sembilan. Lalu, satu rombongan yang tidak terhitung, datang dari rimba yang digunduli tiga bulan lalu. Mereka tidak menyerang. Tidak memanjat. Hanya duduk. Diam. Seperti sedang mengadakan ritual yang entah apa. Hari itu juga, setelah kerumunan orangutan itu datang berkumpul, pembangunan dihentikan sementara. Papan reklame bertuliskan “Ibu Kota Masa Depan” ditutupi terpal biru.
Sementara itu, orangutan terakhir yang muncul, melangkah ke depan dan duduk tepat di halaman istana yang baru dibangun. Ia duduk di atas prasasti batu, dan dengan satu jari, menunjuk ke arah matahari terbit. Tidak ada yang begitu paham dengan semua isyarat itu. Orang-orang proyek tidak tahu harus berbuat apa selain mengusir, namun mereka juga tidak tahu bagaimana cara untuk mengusir semua orangutan yang berkumpul itu.
“Apa maksud jemari yang menunjuk itu?”
Tidak ada yang sadar, kecuali satu orang: seorang pegawai arsip nasional yang dikirim ke IKN untuk memindahkan dokumen-dokumen sejarah penting dari Jakarta.
Dia menemukan bahwa dalam peta kuno milik Dayak Balik, lokasi istana baru itu dulunya disebut tanah peringatan.
“Tempat di mana yang dilupakan akan kembali dengan cara yang tak bisa ditolak.”
Dia sudah mencoba melaporkan temuannya, tapi suratnya hilang entah di meja siapa.
Di televisi, siaran menampilkan drone-shot indah: gedung putih mengilap, hutan urban artifisial, dan anak-anak sekolah dasar menyanyikan lagu nasional di depan tugu keadilan. Tidak ada orangutan di sana. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang pernah dibunuh dan di mana mereka dikubur.
Narator berita berkata:
“Inilah wajah baru Indonesia: modern, inklusif, dan bebas dari beban sejarah.”
Sementara itu, di balik kamera, seekor orangutan melintasi jalanan beton. Ia menatap lurus ke arah jendela redaksi. Wartawan yang melihatnya bergidik: seolah-olah ada yang memanggil dari balik lipatan waktu. Dari antara tanggal yang dipotong.
Beberapa minggu kemudian, di sebuah tenda makan pekerja, para teknisi mulai membicarakan mimpi yang sama:
Mereka melihat jalan raya berubah menjadi akar. Gedung-gedung tumbuh rerimbunan daun. Dan patung presiden masa depan roboh karena disentuh kawanan orangutan.
“Kalian semua mungkin lelah saja,” kata kepala proyek. Setelah itu, dia sendiri mulai tidur dengan lampu yang tetap dibiarkan menyala.
2
Malam itu, kota yang belum diresmikan itu memasuki fase panjang penuh mimpi. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang bermimpi lebih dulu—orang-orang proyek, atau tanah itu sendiri. Satu hal yang pasti bahwa, dalam tidur-tidur yang tidak nyenyak, mereka bergantian mendengar suara yang serupa. Bukan teriakan. Bukan ledakan. Melainkan desir dedaunan yang telah mereka musnahkan.
Seorang pekerja bangunan terbangun dengan tangan menggenggam tanah, padahal dia tidur di barak lantai yang jauh dari tanah. Di bawah kuku-kukunya, ada beberapa potongan akar yang seolah bertumbuh. Dia seolah pernah menggali sesuatu tanpa dia sadari sepenuhnya. Malam itu juga, dengan segala ganjilan yang dirasakan, dia memilih untuk tetap melanjutkan tidurnya. Dia pun kembali tertidur, hingga tak lama kemudian, dia kembali bermimpi.
Dia melihat dirinya memalu batu yang menangis. Tangannya berdarah, selain itu dia juga mendengar suara jeritan dari dalam tanah. Lalu dia berjalan di lorong gedung yang belum dibangun, di mana dinding-dindingnya terbuat dari papan nama orang-orang hilang. Setiap langkahnya menyalakan satu nama, lalu mematikannya. Dia sekuat tenaga berusaha berlari ke luar, sialnya lantai gedung itu berubah menjadi lumpur merah, yang perlahan menelan kedua kakinya. Di tengah lumpur itu berdiri seorang anak perempuan, membawa peta. Dia menunjuk satu titik dan berbisik: “Dulu, di tempat inilah ayahku dikuburkan. Sekarang ini…, sekarang ini semua sudah jadi lapangan upacara.”
Pekerja itu tersentak bangun. Napasnya tersendat. Tapi tak ada suara. Di luar, hutan plastik yang baru ditanam masih berdiri kaku, seperti para pengganti yang menolak bernapas. Di beberapa barak sebelah, seorang mandor bermimpi pula. Dia berdiri di menara tertinggi kota, dan dari sana, dia melihat sungai berubah arah. Airnya naik, tidak turun. Dia membuka matanya, namun dunia tidak berubah. Masih sepi. Masih bersih. Terlalu bersih.
Namun ketika dia mulai memeriksa bekas sepatunya di pagi hari, ada daun tua menempel. Bukan dari pohon yang tumbuh hari ini. Melainkan dari jenis dedaunan dari sejumlah pohon yang seharusnya telah ditebang dua musim lalu.
3
Pagi itu, akhirnya IKN genap setahun setelah diresmikan, sebuah sekolah unggulan di jantung Ibu Kota Negara (IKN) tampak seperti biasa. Barisan siswa berseragam putih-merah menyanyikan lagu kebangsaan dengan nada datar, di halaman yang bersih dan dipenuhi tanaman buatan. Bendera merah-putih berkibar, tertiup angin yang rasanya tidak berasal dari pohon manapun.
Di ruang kelas 5B, Ibu Sekar berdiri di depan papan tulis digital. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kilatan lain. Dia tidak membuka pelajaran dari modul resmi, melainkan dari sebuah buku lusuh bersampul coklat tua. Di atasnya tertulis: “Sejarah Alternatif Nusantara.”
“Hari ini,” ucapnya pelan, “kita akan belajar dari yang tidak ditulis lagi dalam buku-buku pelajaran.”
Anak-anak mulai saling pandang. Mereka terbiasa dengan angka-angka pembangunan, kisah kejayaan tokoh-tokoh arsitek negara, dan dongeng tentang teknologi ramah lingkungan. Tapi hari itu, mereka mendengar nama-nama aneh, mulai dari Marsinah, Munir, Widji Thukul. Nama-nama yang tidak ada di soal ujian.
Di sudut belakang kelas, Danu mencatat diam-diam. Dia tahu persis nama-nama itu. Ibunya sering menyebutnya sebelum tidur, dengan nada setengah berdoa, setengah takut. Ibunya adalah satu dari ribuan mahasiswa yang pernah duduk di aspal Jakarta tahun 1998. Sekarang, dia tak pernah berbicara keras di depan umum. Tapi kepada Danu, dia menyerahkan sebuah buku kecil sebelum anak itu dikirim ke IKN untuk sekolah:
“Bacalah buku ini kalau kamu lupa, kenapa kami semua dulu memilih untuk bersama-sama turun ke jalan.”
“Bu…, ini buku apa?”
Ibunya tak ingin berkomentar lebih, dia membiarkan anaknya mencari jawaban sendiri. Pikiranya, dengan membaca buku ini, seharusnya dia paham apa yang sebenarnya terjadi.
Buku itu ditulis tangan. Di dalamnya ada puisi, pamflet fotokopian, dan catatan nama-nama yang hilang.
Di halaman terakhir tertulis: “Kita tidak pernah benar-benar mati, selama ada yang berani bicara.” Danu menyimpan buku itu baik-baik.
Hari itu, saat Ibu Sekar menyebut satu nama, Danu spontan mengangkat tangan.
“Bu, benar ya…. dulu ada yang hilang waktu demo?”
Ibu Sekar menatap Danu lama. Anak-anak lain menoleh. Beberapa tertawa kecil. Tapi, Sekar hanya mengangguk.
“Hilang. Tapi, mungkin belum selesai.”
Selama dua minggu setelah itu, pelajaran sejarah 5B berubah jadi ruang sunyi. Tak ada suara permainan, tak ada tawa, hanya narasi-narasi yang tak pernah disiarkan di televisi nasional. Anak-anak mulai menyalin sendiri kisah yang mereka dengar. Beberapa menggambar wajah dari deskripsi mulut ke mulut. Seorang anak bahkan menggambar gedung istana lama dengan retakan di atasnya.
Suatu malam, Danu bermimpi.
Dia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah lapangan upacara sekolahnya. Tapi bukannya bendera, yang dikibarkan adalah kemeja berdarah. Di sekelilingnya, anak-anak lain duduk dengan tenang, mendengarkan suara yang tak berasal dari speaker. “Jika kalian tidak belajar dari masa lalu, masa lalu akan belajar datang kepada kalian.”
Danu terbangun dengan tangan gemetar. Dia membuka buku kecil warisan ibunya dan mencium aroma debu tua yang hangat. Keesokan harinya, sekolah gempar. Di dinding luar ruang kelas 5B, ada mural yang tidak diketahui siapa pelakunya. Wajah-wajah tanpa nama, angka-angka tahun, dan satu kalimat besar, “Apakah kalian siap hidup tanpa ingatan?”
Kepala sekolah memanggil semua guru. Investigasi internal dilakukan. Ibu Sekar dipindahkan ke bagian administrasi. Danu dilarang membawa buku ke kelas. Tapi, mereka lupa satu hal: cerita sudah berpindah.
Anak-anak mulai menyebarkan nama-nama itu lewat kode. Di kertas-kertas ulangan, di balik label botol minum, bahkan dalam bentuk permainan rahasia: “Cari Nama yang Hilang.” Mereka tak sepenuhnya mengerti politik, tapi mereka tahu satu hal: ada sesuatu yang sedang dikubur dan disembunyikan hidup-hidup. Satu bulan kemudian, dalam lomba pidato tingkat IKN, seorang siswa dari kelas 5B berdiri di podium. Dia perlahan membuka pidatonya dengan suara gemetar:
“Hari ini, saya tidak akan bicara tentang inovasi digital. Saya akan bicara tentang sejarah tempat ini. Apa yang pernah ada dan seharusnya ada. Karena saya yakin, kota masa depan tidak bisa dibangun dari lupa. Saya ingin bisa melihat apa yang sebenarnya ada”
Ruangan sunyi. Juri-juri gelisah. Tapi, salah satu jurnalis tua di pojok ruangan tersenyum. Dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia dengan mudah bisa merasakan semangat yang serupa dengan apa yang dulu dilakukan kawan-kawannya.
Pada malam itu, dalam tidur para guru dan pejabat pendidikan, nama-nama kembali berdatangan. Tidak dalam bentuk ancaman. Melainkan sesuatu yang bergema. Dan dari jauh, seekor orangutan duduk di bawah menara sekolah, memandangi kelas itu. Ia tidak berbicara. Tidak mengganggu. Hanya menjadi saksi—seperti pohon terakhir yang belum ditebang.
4
Di ujung kota IKN, di antara taman patung yang tak selesai, ada satu bangunan kecil yang tak tercantum di peta resmi. Bentuknya seperti kepala orangutan. Fasad dari logam hitam dan kayu tua yang diambil dari pohon-pohon terakhir. Tak ada yang tahu siapa yang membangunnya, tapi setiap malam, lampunya menyala.
Seorang anak magang dari kementerian kebudayaan, Kirana, menemukan bangunan itu saat tersesat. Di dalamnya, tidak ada pengunjung. Hanya benda-benda yang diletakkan begitu saja: sepatu penuh tanah merah, kaset VHS berlabel “Mei 1998,” senter rusak, kemeja mahasiswa, serta poster buram yang menuntut keadilan. Di dindingnya, tak ada nama. Tapi jika berdiri cukup lama, seseorang terkadang bisa tiba-tiba mendengar bisikan-bisikan.
Kirana tidak langsung melapor. Dia datang kembali, membawa kamera. Tapi, setiap foto yang diambil otomatis akan hilang dari galeri ponsel. Saat menemukan semua itu, dia mencoba memuaskan rasa ingin tahunya. Dia mencari informasi apa pun yang bisa menghubungkan benda-benda itu dengan peristiwa sejarah.
Kirana kembali ke kantor kementerian, tetapi tidak menceritakan temuannya secara detail. Dia hanya mengajukan izin untuk mengakses arsip-arsip lama. Dia mulai menghabiskan jam makan siangnya di perpustakaan kementerian, membolak-balik kliping koran digital dan laporan investigasi yang sudah lama berdebu.
Dia mengetikkan kata kunci seperti “Mahasiswa 1998”, “Tragedi Mei”, “penghilangan paksa”, dan “sepatu merah” ke dalam mesin pencarian internal.
Dalam sebuah berkas yang sangat tua dan ditandai sebagai “Sensitif/Tidak Untuk Publikasi”, dia menemukan deskripsi barang bukti dari sebuah kasus yang ditutup tanpa penyelesaian. Daftar barang itu sangat mirip dengan apa yang dilihatnya:
- Sepatu kulit, warna coklat, terdapat bercak tanah liat merah.
- Satu kotak kaset VHS, label buram, bertuliskan 05/98.
- Pakaian: Kemeja flanel biru tua, logo universitas X.
Tidak ada alamat atau lokasi yang disebutkan dalam berkas itu, hanya kode area. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah kalimat di bagian akhir laporan otopsi yang ditarik: “Pihak keluarga menuntut keadilan. Lokasi terakhir diketahui: sebuah bangunan tak bertuan di pinggiran kota.”
Kirana menyadari bahwa bangunan yang ia temukan bukanlah sekadar rumah kosong. Itu adalah tempat memori yang tersembunyi, sebuah monumen bisu yang sengaja disembunyikan dari sejarah resmi. Keheningan dan hilangnya foto itu bukan karena kerusakan teknis, tetapi seolah-olah tempat itu sendiri menolak untuk diabadikan secara mudah, hanya bisa dikenali oleh mereka yang benar-benar mencari.
Malam itu, Kirana memutuskan untuk kembali ke bangunan itu, kali ini tidak hanya dengan kamera, tetapi juga dengan recorder digital. Dia ingin menangkap bisikan-bisikan itu, karena ia mulai curiga bahwa bisikan itu adalah nama-nama dan rintihan yang terlupakan. Dia harus membuktikan bahwa tempat itu nyata, dan bahwa kisah di dalamnya harus diceritakan. Dia akhirnya menulis di buku catatan lalu membuka catatannya dengan menyatakan, “Ini bukan museum biasa. Ini semacam tempat menunggu. Seperti para benda di dalamnya sedang menunggu ada yang bersaksi.”
Suatu malam, Kirana melihat seekor orangutan berdiri di depan bangunan itu. Ia memandangi kaca depan yang memantulkan dirinya seperti manusia yang kehilangan ingatan. Di tangannya, ia memegang buku catatan kecil. Kirana mendekat, tapi makhluk itu tak bergeming. Hanya matanya yang bergerak, seolah meminta agar Kirana terus menghidupkan rasa ingin tahu dan pencariannya akan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini.
Besoknya, bangunan itu menghilang dari tempatnya. Tapi dalam laptop Kirana, muncul folder baru berjudul “jangan_tutup_ini”. Dia tidak mengingat pernah mengunduhnya. Di dalamnya: arsip lengkap nama-nama korban, saksi, dan dokumen yang pernah dikira musnah. Dia mulai mencetak semuanya. Dia tahu ia akan dipecat. Tapi dirinya juga tahu, ada hal yang lebih penting dari pekerjaan. Di hari terakhirnya, saat dia keluar dari gedung kementerian, seekor orangutan melintas di zebra cross. Semua kendaraan berhenti. Tak ada yang tahu kenapa. Tapi, tidak ada yang membunyikan klakson. Semua diam. Menyaksikan. Seperti menunggu bab yang belum selesai ditulis.
5
Di toko suvenir resmi IKN, pemerintah menjual boneka orangutan sebagai bentuk “komitmen ekologis masa depan”. Boneka-boneka itu lucu, berbulu halus, dan memakai selempang kecil bertuliskan “Saya Sahabat Lingkungan!”.
Seorang anak pejabat, Sita, sangat menyukai boneka itu. Dia menamainya Akar. Akan tetapi sejak membelinya, dia sering didatangi mimpi yang aneh. Dalam mimpinya,
Akar menjadi besar, tidak lucu, dan matanya seperti memanggil dari kejauhan. Dalam satu mimpi, Akar berdiri di atas podium DPR dan membacakan daftar orang hilang. Dalam mimpi lain, ia duduk di kelas sejarah dan berkata kepada guru: “Kalau kami ini sahabat lingkungan, kenapa kalian semua membakar rumah kami?”
Sita mulai menggambar gambar-gambar yang membuat ibunya khawatir: istana hancur, hutan tumbuh dari lantai kota, dan boneka Akar yang menatap orang-orang sambil berkata, “Kita belum selesai bicara.” Psikiater keluarga menyarankan boneka itu dibuang.
Malam itu, angin berubah arah. Dan satu berita kecil muncul di berbagai media sosial, ada penampakan seekor orangutan liar di taman pusat IKN. Sayangnya, saat kamera mencoba menangkapnya, hanya bayangan yang terlihat. Seolah-olah kota itu sedang bermimpi lagi—dan kali ini, mimpi buruknya belum ingin usai.
6
Di satu bagian IKN yang belum dibuka untuk publik, terletak sebuah terowongan bawah tanah yang dibangun untuk kabel-kabel utama kota pintar. Tak ada peta publik yang mencantumkannya, dan hanya sedikit pekerja yang tahu jalur pastinya. Namun pada suatu malam, suara misterius terdengar dari dalamnya.
Bukan suara mesin. Bukan denting logam. Tapi nyanyian.
Nyanyian yang pelan, dengan nada lama, seperti lagu pengantar tidur dari zaman yang tak lagi diajarkan. Pekerja yang mendengarnya, Sarman, semula mengira itu efek suara gema dari pipa-pipa panjang. Tapi semakin dia mencoba untuk mendengarkan dengan teliti, semakin aia merasa lagu itu seperti memiliki lirik. Bukan dalam bahasa Indonesia. Tapi, dalam sesuatu yang terasa seperti … ingatan.
Malam berikutnya, Sarman kembali, membawa perekam. Dia berjalan perlahan masuk ke terowongan, melewati gulungan kabel dan genangan air. Di tengah lorong, dia melihat sesuatu yang aneh, ada seekor orangutan duduk di bawah lampu neon yang berkedip. Orangutan itu tidak bergerak. Hanya memegang sesuatu, ada sebuah buku catatan basah di tangan kanannya. Sarman mematung. Ketika dia mendekat, lampu padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara, “Kami tidak marah. Kami hanya menunggu kalian selesai berbohong.”
Ketika lampu kembali menyala, orangutan itu menghilang. Sarman mengira dia hanya berhalusinasi, hanya saja, saat dia melihat ke tanah, ada sesuatu yang tertinggal, buku yang tadi dipegang orangutan itu benar-benar ada. Sarman membuka halaman pertama, ada coretan tangan, campuran aksara lama dan tulisan Latin. Dia membaca semua itu dengan dahi yang berkerut. Membaca dengan pelan sembari diikuti pertanyaan-pertanyaan yang bertumbuh. Sarman menyimpan buku itu diam-diam. Dia mulai merasa takut. Akan tetapi, dia juga merasa terpanggil.
Dia mulai menyalin isi buku itu ke dalam unggahan anonim di forum daring. Tak banyak yang membaca. Tapi, beberapa orang mulai menambahkan kisah mereka. Nama-nama yang hilang. Tempat-tempat yang pernah digusur. Lagu-lagu yang dilarang.
Lama-lama, unggahan itu membentuk arsip baru: bukan arsip resmi, tapi yang hidup dari mulut ke mulut, dari puing ke puing. Mereka menyebutnya, “Dokumen dari Bawah Tanah”.
Beberapa bulan kemudian, terjadi gempa kecil di IKN. Tidak besar, tapi cukup membuat satu gedung retak. Anehnya, retakan itu membentuk pola melingkar. Dari atas drone, terlihat seperti simbol mata yang sedang menangis. Hari itu, Sarman tidak datang kerja. Dia menghilang. Tapi dalam ruang tidurnya, ditemukan beberapa barang di atas kasur: topi proyek, kamera rusak, dan selembar kertas-kertas yang bertuliskan pesan-pesan larangan untuk berhenti membangun gedung-gedung yang mengorbankan hutan. Tak ada berita resmi tentang hilangnya Sarman. Yang ada hanya dalam siaran radio komunitas lokal, seseorang mulai memperdengarkan kembali nyanyian lama itu. Lebih pelan. Lebih dalam. Seolah tanah sendiri sedang bernyanyi.
Dan dari kejauhan, di balik pohon artifisial yang dipasang ulang, seekor orangutan mengamati. Ia tak muncul di siaran langsung. Dan orangutan, ia selalu hadir di sudut mata yang merasa bersalah. Beberapa orang mulai menyebut fenomena ini sebagai mitos kota baru. Ada juga yang tahu lebih dari itu. Mereka yang bermimpi. Mereka yang mendengar tanah bergumam. Sesuatu yang tidak ingin mereka dengarkan.
Dan akhirnya, pada tahun ke-5 pembangunan, sebuah bunga liar tumbuh di tengah jalan tol yang belum selesai. Tak ada yang menanamnya. Tapi di kelopaknya, ada pola samar yang tampak, yaitu sidik jari manusia dan cakar hewan. Tak bisa dicabut. Tak bisa dibakar. Karena setiap helainya menyimpan pesan-pesan rahasia yang dulu tak sempat diucapkan.
Lalu pada malam ulang tahun kota, ketika lampu pesta menyala, semua layar LED mendadak padam satu per satu. Digantikan oleh satu kalimat putih di latar hitam,“Apakah kalian benar-benar sudah selesai membangun, atau baru mulai menghancurkan kembali?”
7
Di IKN, beberapa orangutan datang.
Akan tetapi, mereka sebenarnya tidak pernah datang. Manusia yang datang merebut hutan dengan terpaksa. Manusia-manusia itu hanya terus menggerus dan membuat semua yang semula berdiri jadi datar, semua yang hidup jadi mati. Hutan itu tidak ditebang, melainkan dikuliti perlahan, seperti tubuh yang disayat dalam diam, hingga batang-batang menjelma tulang-tulang telanjang, dan akar yang tak sempat berpamit menyembul seperti sisa-sisa luka purba. Orangutan itu tidak datang. Ia tersisa. Ia adalah saksi dari segala yang tercerabut: sarang-sarang yang dulu bergoyang diterpa angin, pohon yang menyimpan jejak kelahiran, bau buah yang hanya dikenal oleh lidah rimba, dan bisikan malam yang tidak pernah didengar oleh alat ukur kota. Kini semuanya disulap menjadi angka dan retorika, luas lahan, nilai investasi, proyeksi pertumbuhan. Hutan menjadi statistik dan harapan penguasa yang hendak meraup keuntungan sebanyak mungkin. Kehidupan dalam hutan pada akhirnya hanya menjadi paragraf-paragraf semu dalam siaran pers.