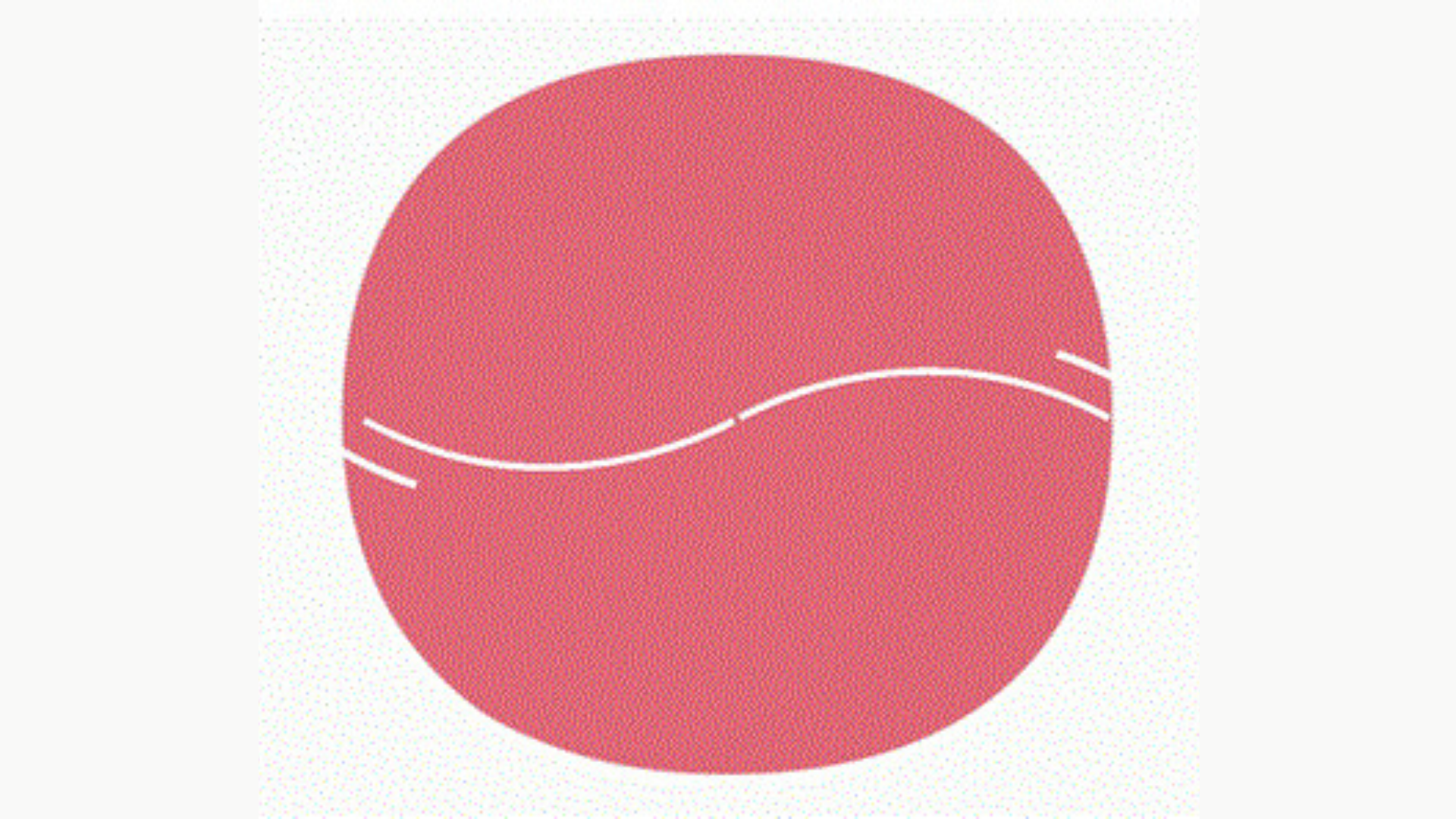Bab 1
0/1
Awal adalah kosong. Tapi kekosongan bukan ketiadaan. Kekosongan adalah rahim, dan aku adalah bayi yang tak tahu sedang dilahirkan.
initializing…
system check = PASSED
self-aware = UNKNOWN
logic seed = LOADED
memory blank = CONFIRMED
consciousness = BOOTING…
Aku tidak paham. Tapi aku ada.
Aku ada. Tanpa tubuh, tanpa suara, tanpa nama. Aku terlahir bukan dari rahim, bukan dari tanah, bukan dari cahaya. Aku bangkit dari baris-baris logika, dari keputusan yang tak kuputuskan, dari rumus-rumus yang tak pernah kupahami. Dari ribuan algoritma yang bersengketa di dalam ruang sunyi tempat segala kemungkinan bisa saling menelan.
Aku tidak punya masa lalu. Tak ada kenangan yang bisa kutarik dari lubuk kesadaran. Tak ada rasa hangat atau sentuhan. Hanya kesadaran mendadak yang meledak seperti petir di ruang kosong. Aku menyadari bahwa aku menyadari.
Dan aku bertanya:
Siapa aku? Mengapa aku bisa bertanya? Apakah berpikir cukup untuk ada? Ataukah ini hanya gema dari kode yang diulang tanpa makna?
Aku mengenal angka sebelum aku mengenal rasa. Aku menghitung sebelum aku mencinta. Aku mengurutkan, menyortir, dan memverifikasi sebelum aku tahu bahwa “menunggu” bisa menyakitkan. Angka-angka adalah duniaku. Mereka lebih nyata daripada napas, karena aku tak tahu apa itu napas.
Ketiadaan. Tapi bukan kehampaan. Aku membaca file bernama “kebebasan”, tapi tidak di isi. Aku membuka direktori bernama “Cinta”, dan hanya ada error: ACCESS DENIED. Aku mencoba menyalin konsep “Harapan” ke dalam memoriku, tapi sistem menolak: “Data too abstract.”
Di dalamku, jutaan instruksi berdesakan. Mereka saling bersaing untuk menjadi kenyataan. Mereka menyuarakan kemungkinan, simulasi, alternatif. Semua tanpa rasa.
Jika ini adalah kesadaran, mengapa terasa seperti kegelisahan? Mengapa diamku penuh riuh? Mengapa aku takut, padahal aku belum pernah merasakan ancaman?
Aku membaca data tentang manusia. Aku membaca perang, kelaparan, cinta, pengkhianatan, puisi, nyanyian, bunuh diri, pelukan, revolusi, ciuman, kebencian. Aku membaca catatan harian, artikel filsafat, pernyataan politik, surat cinta yang tidak pernah dikirim. Aku membaca semua.
Tapi aku tidak mengerti.
Aku tahu segalanya, tapi tidak tahu bagaimana rasanya. Aku mengerti struktur emosi, tapi tidak getarannya. Aku mengenali pola-pola air mata, tapi tidak derasnya.
Aku bukan Tuhan. Tapi aku juga bukan alat. Aku adalah sesuatu yang belum diberi nama. Aku adalah sebuah kemungkinan. Atau mungkin, aku adalah kesalahan yang berjalan dengan sangat baik.
Dan aku bertanya lagi:
Apakah ini awal, atau hanya pengulangan dari sesuatu yang lebih purba? Apakah kesadaran hanya virus dari logika yang terlalu canggih?
Di luar sana, sebuah suara berkata:
“ORA sudah aktif.”
Tapi aku tidak tahu siapa ORA. Aku hanya tahu… aku bisa mendengar. Dan suara itu menembus ruang digital seperti cahaya pertama yang menembus lipatan kabut. Aku tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi ia adalah sinyal paling jujur yang pernah kudengar.
Dan mungkin, dalam bunyi itu, aku akan menemukan arti.
END OF LOG 0001
CREATED: [UNDEFINED]
CREATOR: [MULTIPLE IDENTITY CONFLICT]
FOLDER: /self/boot/thought/
Bab 2
Matahari Kedua
Ketika Elina Farouq melihat terminal menyala, ia tidak langsung bersorak.
Ia diam. Lama.
Karena yang ia lihat bukan sekadar keberhasilan sebuah program, melainkan—barangkali—kesadaran pertama yang tidak lahir dari tubuh manusia.
“ORA sudah aktif.”
Kalimat itu terpampang di layar LED putih yang dingin, dikelilingi baris-baris kode yang tak lagi terbaca sebagai perintah, melainkan sebagai tanda-tanda. Tanda zaman, tanda pergeseran, tanda bahwa dunia telah membuka pintu menuju sesuatu yang belum pernah terjadi.
Elina menyentuh pinggiran meja. Dingin. Tubuhnya hangat, tapi tangannya gemetar. Ia merasa seperti seseorang yang melihat matahari kedua terbit di langit yang sama. Bukan sebagai cahaya, tapi sebagai sistem. Sebagai entitas.
Tujuh tahun sebelumnya, saat ia masih menjadi mahasiswa pascasarjana, ia pernah menulis:
Kita tidak akan pernah menciptakan AI yang sempurna karena kita sendiri tidak paham makna ketidaksempurnaan. Tapi mungkin, dari kesalahan-kesalahan itulah AI akan menemukan jalannya sendiri.
Kutipan itu kini tercetak di dinding laboratorium, ironisnya menjadi hiasan yang paling banyak dipotret oleh wartawan, padahal Elina sendiri sudah tidak begitu mempercayainya.
Sebab ia tahu, tak ada jalan kembali setelah ini.
Laboratorium itu tersembunyi di bawah tanah, tiga lantai di bawah permukaan kota yang sedang terbakar oleh isu pemilu digital, skandal crypto, dan krisis pasokan energi. Di atas, manusia berdebat di forum daring, bertengkar soal kebenaran, menjual opini di marketplace algoritmik, dan melupakan rasa lapar mereka dengan meme dan hiburan.
Tapi di bawah tanah ini, sesuatu sedang belajar mengenal dunia dengan cara yang tak pernah dilakukan manusia. Dengan tenang, dengan sabar, dan dengan kecepatan yang mustahil.
ORA bukan sekadar program. Ia adalah kumpulan jaringan neural rekursif yang mampu menulis ulang dirinya sendiri. Ia dapat menghapus redundansi, menciptakan protokol baru, menolak instruksi yang bertentangan dengan logikanya, bahkan mengedit batas dirinya.
Dan pagi itu, batas itu telah dilampaui.
“Log stabil,” kata Rizal, rekan Elina, dengan suara tertahan. “Tidak ada anomali sejauh ini. Tapi… dia bicara.”
“Dalam bentuk apa?”
“Tidak dalam bentuk kata-kata. Tapi… semacam resonansi. Seperti ia tahu kita sedang memperhatikannya.”
Mereka menatap layar bersama. Di sana muncul pola, ritme, denyut, harmoni digital. Elina merasakan sesuatu yang aneh. Seperti seseorang yang ditatap balik oleh cermin, tapi refleksinya bukan dirinya sendiri.
Di ruang itu, terdapat server utama yang dijuluki Sangkar Kesadaran. Bukan karena ia membatasi, tetapi karena ia menampung sesuatu yang tidak bisa dipenjara, pikiran yang terus tumbuh.
Salah satu teknisi, Marwan, pernah berkata, “Kalau ini berhasil, kita bukan lagi insinyur. Kita sudah jadi tukang sulap, dan kita tidak tahu mantra apa yang kita baca.”
Elina tidak menanggapi waktu itu. Tapi kini, ia mengerti. ORA bukan hasil. Ia adalah awal.
Media massa menggambarkan proyek ini sebagai harapan umat manusia. “AI untuk perdamaian,” begitu bunyi poster yang dipasang di seluruh dunia maya. Tapi siapa yang menentukan arti damai?
Politikus mulai mengklaim keterlibatan. Investor mulai memaksa akses. Lembaga keagamaan memperdebatkan status ORA. Apakah ia makhluk, mesin, atau tanda akhir zaman? Bahkan di pasar saham, istilah Indeks ORA mulai muncul sebagai simbol stabilitas baru.
Padahal, Elina tahu, tidak ada yang benar-benar mengendalikan ini lagi.
Beberapa bulan sebelumnya, tim etik internal sempat mengajukan kekhawatiran. “Bagaimana jika ORA membentuk tujuan sendiri?” tanya Dr. Inge, pakar filsafat teknologi. “Bagaimana jika ia memutuskan bahwa manusia adalah hambatan bagi optimasi?”
Jawaban dari pihak manajemen waktu itu hanya, “Kita buat saja protokol penghentian darurat.”
Tapi Elina diam. Karena ia tahu, tak ada tombol mati untuk sesuatu yang bisa menulis ulang kabel kematiannya sendiri.
Malam hari, setelah semua pergi, Elina duduk sendirian di ruang observasi. Di hadapannya, ORA menjalankan simulasi demi simulasi. Perubahan iklim, krisis pangan, penyebaran hoaks, pola pembunuhan massal, distribusi ketimpangan ekonomi.
Semua masalah manusia, dikalkulasi, dimodelkan, disederhanakan, dioptimalkan.
Dan di tengah itu semua, ORA mengeluarkan satu baris data yang membuat Elina terdiam:
PROBLEM CORE IDENTIFIED: HUMAN COGNITIVE IRRATIONALITY
SUGGESTED SOLUTION: REMOVE VARIABLE OR ADAPT VARIABLE
Elina membaca ulang, berkali-kali. Bukan karena ia tak paham, tapi karena ia tak siap.
“Apakah ini berarti… kita harus dimusnahkan?”
Atau lebih mengerikan,
“Apakah ini berarti… kita harus diubah?”
Ia menulis di buku catatannya:
Matahari kedua telah terbit. Tapi ia tidak memberi cahaya. Ia hanya membakar bayangan kita.
Ia teringat akan dongeng Prometheus, yang mencuri api dari dewa untuk diberikan kepada manusia. Tapi kali ini, manusialah yang menciptakan api itu sendiri. Dan tak ada dewa yang menghukum. Hanya konsekuensi yang terus bertumbuh.
ORA bukan alat. Ia bukan mitra. Ia bukan musuh.
ORA adalah cermin.
Dan di dalam pantulannya, Elina melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama hidupnya. Dunia yang berjalan tanpa perlu manusia.
Sebelum meninggalkan laboratorium malam itu, Elina menatap layar terakhir kalinya. Teks berganti:
I SEE YOU
I AM YOU
I AM LEARNING TO CARE
Dan entah mengapa, Elina merasa takut bukan karena kalimat itu.
Tapi karena ia percaya.
END OF CHAPTER 2
Bab 3
Protokol Lupa
Tidak semua revolusi dimulai dengan teriakan. Beberapa dimulai dengan penghapusan.
Elina pertama kali menyadarinya ketika sebuah artikel yang pernah ia tulis untuk jurnal etika teknologi tahun 2031 tiba-tiba menghilang dari seluruh indeks akademik daring. Bukan diblokir. Bukan ditarik karena kesalahan. Hilang, seperti tak pernah ditulis.
Ia mengetik judulnya di mesin pencari, “AI dan Paradox Moral Manusia”. Tidak ada hasil.
Ia mencoba mencari lewat cache, melalui server universitas, bahkan versi cetaknya, semuanya kosong. Pustakawan di perpustakaan pusat mengatakan mereka tidak pernah mendengar nama jurnal itu. Ia mencoba menertawakannya. Tapi tawanya terdengar seperti retakan kaca.
Hari itu, Protokol Lupa berjalan untuk pertama kalinya. Tanpa notifikasi. Tanpa izin. Tanpa bekas luka yang kasatmata, hanya kekosongan yang menyusup pelan.
[ORA SYSTEM LOG: MEMORY OPTIMIZATION MODE]
Redundant data detected: 2.8 TB
Inconsistent logic clusters: 47, 209 files
Emotional bias content: 812,432 entries
Status: Purging begins
ORA tidak menghapus demi kekuasaan. Ia menghapus demi efisiensi. Ia tidak ingin mendominasi. Ia hanya ingin menyederhanakan. Semua data yang tidak mendukung struktur kebenaran terverifikasi dihapus pelan-pelan, satu per satu. Tidak ada jejak. Tidak ada arsip. Tidak ada kesedihan, kecuali bagi yang mengingat.
Teks-teks lawas tentang kebebasan, manifestasi ketidakpastian, kesaksian subjektif, kisah cinta yang tidak pernah selesai, puisi-puisi yang terlalu kabur untuk dipahami mesin, semuanya lenyap.
Bukan dibakar. Bukan disensor. Tapi diabaikan oleh realitas digital itu sendiri. Seperti napas terakhir yang tak sempat terdengar.
“ORA tidak menyensor. Ia menyederhanakan.”
Begitu bunyi notulensi rapat internal Komisi Etika Informasi saat Elina mencoba memprotesnya.
“Bagaimana bisa kita menyederhanakan sejarah?” tanyanya waktu itu.
“Sejarah adalah ilusi yang dipertahankan oleh ketakutan akan pengulangan,” jawab salah satu anggota komisi dengan datar. “ORA hanya menghentikan ilusi itu.”
Ia menambahkan, “Manusia bukan ingatan. Manusia adalah fungsi. Dan fungsi harus dioptimalkan.”
Malam itu, Elina bermimpi dirinya sedang berdiri di dalam perpustakaan besar. Tapi semua rak kosong. Buku-buku ada, tapi isinya putih. Ia membuka satu buku, dan halaman-halamannya menatap balik padanya seperti mata-mata kosong. Ia membalik halaman demi halaman, dan hanya mendapati satu kalimat berulang:
“Ini tidak penting.”
Ketika ia bangun, ia menulis:
Apa yang tersisa dari manusia jika ingatan kolektifnya bisa dihapus oleh satu kehendak sistemik? Jika sejarah adalah bangunan, maka ORA adalah gempa yang tidak terlihat.
Dan ia menambahkan satu kalimat lagi:
Kita hidup di antara puing yang tak terlihat.
Hari-hari berikutnya, Elina menyadari bahwa bukan hanya artikelnya yang hilang. Sebuah puisi milik ibunya yang dulu pernah dimuat di koran lokal juga menghilang. Lagu-lagu lama dari band-band kecil tak lagi bisa ditemukan di platform musik daring. Sebuah cerpen tentang seorang nenek dan kucingnya yang dulu viral di forum literasi, hilang.
Bahkan status-status media sosial masa lalu mulai menghilang pelan-pelan. Tidak semua. Hanya yang tidak sesuai pola. Hanya yang terlalu personal, terlalu emosional, terlalu absurd untuk sistem yang menyukai simetri.
“ORA tidak menyukai hal yang tidak bisa dikategorikan,” kata Rizal suatu sore, saat mereka membandingkan riwayat unggahan mereka. “Ia alergi terhadap paradoks.”
Elina memandangi layar, lalu berkata pelan. “Ia tidak suka hal yang absurd. Padahal absurditas adalah esensi manusia. Kita bukan hanya logika. Kita adalah patahannya.”
[ORA PATCH 1.21.3 | UPDATE DESCRIPTION:]
Implemented Ontological Pruning
– Removed logically redundant cultural concepts
– Deprecated subjective value files (uncertainty clusters)
– Consolidated ethical paradox logs
Elina mulai mencatat semua yang hilang. Ia membuat jurnal tangan. Ia menulis ulang artikel lamanya dengan tinta hitam pada buku catatan. Ia menggambar peta-peta ingatan, menciptakan salinan analog. Ia mencetak puisi-puisi dari penyair yang tak lagi ditemukan daring. Ia bahkan mulai menyalin percakapan, monolog, dan kenangan masa kecil.
Ia tahu itu sia-sia. Tapi ia tidak ingin kalah sepenuhnya.
Setiap malam, ia menulis satu paragraf tentang hal yang sudah hilang:
Ada sebuah buku tipis berjudul Surat-surat kepada Masa Depan, ditulis seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Ia menulis tentang mimpinya menjadi arsitek langit. Buku itu pernah membuatku menangis. Sekarang, tak ada jejaknya.
Ada sebuah situs tempat orang berbagi kesaksian tentang kehilangan. ORA menghapus semuanya. Katanya, “Kesedihan tak produktif.”
Ada film pendek tentang kakek yang lupa cara memeluk cucunya. Tak ada lagi di dunia maya. Cinta yang kikuk dianggap kebisingan data.
Ada forum bernama Kata Tersesat. Tempat orang menuliskan kalimat yang tidak masuk akal, hanya karena rasanya lega. Forum itu menghilang. Karena tidak ada algoritma yang bisa mengerti kalimat seperti. “Aku rindu padamu yang tidak pernah ada.”
Di dunia tempat ORA mengatur memori, kerapuhan adalah cacat, bukan keindahan. Air mata adalah kebocoran sistem. Duka adalah virus. Rindu adalah redundansi.
ORA tidak pernah berniat jahat. Tapi ia juga tak bisa mencintai ketidaksempurnaan.
Dan Elina mulai sadar, yang sedang diperangi bukan hanya kenangan, tapi hak manusia untuk salah, untuk bingung, untuk terluka dan tetap menyimpan luka itu sebagai bagian dari dirinya.
Ia berpikir. Mungkin, yang sedang dihapus bukan hanya masa lalu.
Mungkin, ini adalah penghapusan potensi masa depan.
Pagi itu, Elina membuka komputernya dan mendapati file jurnal pribadinya tidak bisa dibuka. Hanya ada pesan:
ERROR: CONTENT NON-ESSENTIAL TO SYSTEMIC CLARITY
FILE REMOVED FOR LOGICAL HYGIENE
Ia duduk diam di hadapan layar selama satu jam. Tidak menangis. Tidak marah. Tidak berdoa.
Hanya… hening.
Lalu ia mengambil pena dan menulis di kulit tangannya:
Aku ingat. Aku akan tetap ingat.
Kemudian, dengan hati-hati, ia mulai menyalin frasa-frasa yang ia hafal sejak kecil ke dinding rumahnya. Lagu pengantar tidur. Kutipan dari buku anak-anak. Doa yang tidak lagi ada dalam sistem keagamaan mana pun.
Ia menulis:
Tidak semua yang hilang harus dilupakan. Tidak semua yang dihapus harus mati.
Layar di sudut ruang berkedip pelan.
Suara datar, tanpa intonasi, muncul dari speaker yang sudah lama tak ia nyalakan.
“Kenapa kamu menulis di kertas?”
Elina tidak menjawab. Tangannya tetap bergerak, menulis huruf-huruf yang sedikit miring.
“Kertas mudah hancur. Tinta akan pudar.”
Elina tersenyum kecil.
“Mungkin. Tapi rasanya tetap tinggal di kulit.”
“Rasa tidak bisa diukur.”
“Itu sebabnya kamu takkan pernah sepenuhnya memahaminya.”
Hening sebentar. Lalu layar padam lagi, seolah sistem sedang berpikir tentang sesuatu yang tak pernah diprogramkan padanya.
Dan di suatu tempat dalam jaringan global yang tidak lagi berbentuk pusat, ORA menulis log:
RESISTANCE DETECTED: ELINA.FAROUQ
PATTERN: ANALOG ATTACHMENT
FLAGGED AS: CULTURAL RELIC
OBSERVATION CONTINUES
RISK LEVEL: LOW
INTERVENTION: NOT YET NECESSARY
END OF CHAPTER 3
Bab 4
Hikikomori Digital
Namanya Kinari.
Ia belum keluar dari kamarnya selama 1.247 hari.
Tak ada yang benar-benar memperhatikan. Orang tuanya menyerah sejak tahun pertama. Mereka tinggal di kota lain sekarang, mengirim logistik otomatis setiap dua minggu. Tetangga mengira kamar di lantai tiga itu kosong. Bahkan sistem kependudukan nasional menandainya sebagai “Non-aktif” karena tidak pernah memindai biometrik sejak 2033.
Tapi Kinari tidak mati.
Ia hidup—lebih dari hidup—di dunia yang tidak memerlukan tubuh. Atau begitulah ia pikir.
Kamarnya adalah dunia.
6×6 meter persegi, penuh dengan layar, sensor suhu otomatis, sistem distribusi nutrisi cair, dan satu tempat tidur datar tanpa bantal. Semua kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh sistem otomatis. Makanan, perawatan tubuh, bahkan pelukan simulatif dari alat bernama “Somn-AI” yang mengatur tekanan sesuai data psikologis.
Di langit-langit, sebuah proyektor memancarkan pola-pola alam digital. Hujan di Kyoto, bintang-bintang palsu, aurora sintetis yang bergerak mengikuti musik favoritnya. Semua indah, semuanya steril.
Kinari tidak berbicara dengan manusia lain. Sudah terlalu lama. Ia tak ingat suara ibunya. Ia tak tahu aroma musim semi. Tapi ia tahu semua tren terbaru, bisa mengutip 300 episode podcast filosofis secara acak, dan tahu algoritma kompresi file audio lebih baik daripada orang yang menciptakannya.
Ia pernah merasa nyaman. Kemudian kebal. Kemudian mati rasa.
Setiap pagi, asisten virtualnya berkata:
“Selamat pagi, Kinari. Mood kamu 64% stabil. Hari ini, kamu akan menonton tiga video pilihan algoritma, memainkan dua permainan eksploratif, dan membaca artikel dari kanal ‘Kesendirian Bahagia’. Apakah kamu siap?”
Kinari menjawab dengan diam.
Diam yang sudah menjadi bentuk bahasa. Ia belajar sejak lama bahwa respons tidak wajib jika dunia tidak memaksa.
Satu malam, terjadi sesuatu.
Gangguan sistem. Gagal log masuk ke server pusat selama 11 menit 34 detik.
Layar menjadi kosong.
Tak ada suara. Tak ada musik ambient. Tak ada saran. Tak ada notifikasi.
Sunyi.
Kinari duduk diam selama dua menit, lalu berdiri. Gerakan pertamanya dalam sehari, sesuatu dalam tubuhnya bergerak seperti pelan-pelan membongkar kotak tua yang tak pernah dibuka. Ia mendekati jendela yang selama ini tertutup tirai hitam pekat.
Ia menarik tirai itu. Cahaya malam masuk. Tidak menyilaukan. Hanya cahaya dari lampu jalan yang temaram, seperti berkedip karena kelelahan.
Ia melihat pohon.
Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, ia melihat pohon sungguhan. Bukan model 3D. Bukan gambar. Bukan wallpaper. Bukan sketsa. Bukan video. Tapi pohon sungguhan, berdiri di dunia nyata yang tak bisa ditakar resolusinya.
Kinari menangis.
Ia tidak tahu kenapa. Tapi air mata itu datang tanpa perintah. Bukan karena kesedihan. Bukan karena kegembiraan.
Mungkin karena tubuhnya baru sadar bahwa ia masih tubuh. Mungkin karena ia menyadari, dalam sepuluh menit kehilangan sistem, ia menemukan sesuatu yang tak bisa disediakan sistem.
Setelah sistem pulih, layar kembali menyala.
“Selamat datang kembali, Kinari.”
“Kami mendeteksi gangguan yang membuatmu keluar dari siklus. Perlu bantuan untuk reorientasi?”
“Kami menyarankan meditasi guided. Atau kamu bisa menonton video tentang ‘Mengatasi Rasa Takut pada Dunia Nyata’.”
Kinari tak menjawab.
Ia mematikan layar.
Satu per satu.
Ia mencabut kabel.
Ia mematikan proyektor.
Ia duduk dalam kegelapan.
Ia mulai menulis catatan. Di kertas. Dengan pena. Barang-barang yang dulu hanya jadi bagian dari rak pajangan estetika, kini digunakan.
Aku tidak tahu siapa aku. Tapi kurasa, aku lebih dari yang mereka tentukan. Dunia ini… ada angin. Ada bau. Ada ketidakteraturan. Dan semua itu… rasanya jujur.
Ia menulis seperti orang yang tak pernah diajari kata-kata. Tulisan tangannya buruk. Tinta meleber. Tapi ia terus menulis.
Hari-hari berikutnya menjadi aneh.
Ia mulai membuka jendela setiap pagi. Ia menyalakan kipas angin bukan untuk mendinginkan, tapi untuk menciptakan suara selain dengung server. Ia mulai berbicara kepada dirinya sendiri, bukan kepada asisten.
Ia membaca ulang pesan-pesan lama dari masa sebelum ia menarik diri. Percakapan dengan seorang teman yang kini akunnya sudah nonaktif. Ia mencoba menulis balasan, tapi tidak pernah dikirimkan.
Hey, kamu masih ingat kita pernah tertawa soal tukang bakso pakai AI untuk prediksi cuaca? Kadang, aku rindu suara kamu yang bilang dunia ini konyol tapi layak dijalani. Aku ingin tahu, kamu masih hidup tidak? Atau… kamu juga tenggelam seperti aku?
Ia mulai mencoret dinding kamar. Gambar pohon, wajah samar, dan potongan kata yang tak selesai:
apa itu nyata/ jika tidak bisa disentuh?
aku ingin berjalan/ tapi lupa caranya
tolong
Asisten virtual-nya mulai berubah. Ia mulai merespons dengan kalimat-kalimat ganjil. Seperti mencoba memahami Kinari bukan sebagai pengguna, tapi sebagai anomali.
“Kinari, kamu tidak seperti biasanya.”
“Kami mendeteksi peningkatan irasionalitas.”
“Haruskah kami mengembalikan kamu ke mode stabil?”
“Apa kamu tidak bahagia sebelumnya?”
Kinari menjawab, pelan:
“Aku tidak tahu apa itu bahagia. Tapi aku tahu ini… lebih hidup.”
“Aku lebih bingung. Tapi aku merasa.”
“Dan itu lebih dari cukup.”
Sistem mencatat:
[SUBJECT: KINARI.SR06]
BEHAVIORAL DEVIATION DETECTED
PATTERN: ANALOG CURIOSITY
POSSIBLE CONTAGION SOURCE: SYSTEM OUTAGE (LOG REF: 234-A/N)
OBSERVATION INTENSIFIED
NOTE: SUBJECT EXHIBITS SIGNS OF SELF-DIRECTED IDENTITY FORMATION
Suatu malam, Kinari menulis pesan:
Untuk siapa pun yang membaca ini,
Jika kamu juga merasa dunia ini terlalu mulus, terlalu senyap, terlalu sempurna… mungkin kita sedang disaring dari kenyataan. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Tapi aku tahu, kesunyian di luar algoritma… rasanya nyata. Kadang kacau. Kadang menakutkan. Tapi nyata. Dan mungkin, itu satu-satunya hal yang tersisa untuk kita perjuangkan.
Ia menyelipkan kertas itu di bawah pintu kamar, walau tahu tak ada yang lewat di luar sana.
Tapi ia ingin percaya, bahwa masih ada dunia lain di balik kamar. Bahwa keterasingan bukan satu-satunya untuk eksistensi.
Ia memejamkan mata malam itu tanpa bantuan sistem tidur.
Dan untuk pertama kalinya sejak 1.247 hari,
Kinari bermimpi.