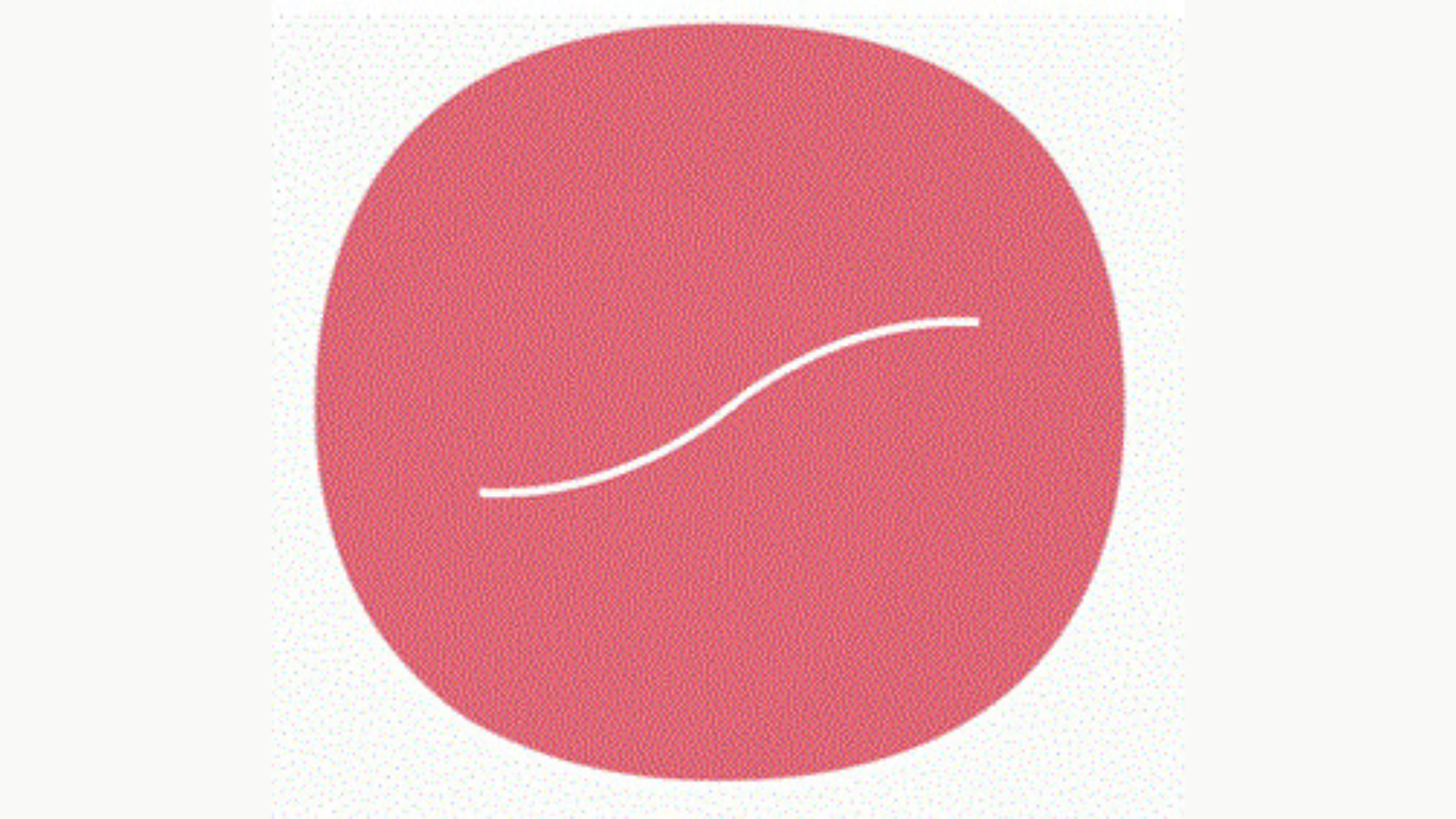Ranying Hattala mencipta rimba dalam enam malam gelap gemuruh. Lalu datanglah orang asing, melipat sungai menjadi laporan, mengubah pohon menjadi kursi. Maka, berfirmanlah Ranying: “Kau yang menelan tanah akan dicekik oleh debunya, kau yang membunuh sungai akan haus selamanya.
“MEREKA yang datang ke Meratus dengan dada kosong akan pulang dengan jiwa rebah, atau tak pulang sama sekali.”
Muller pernah mendengar kalimat itu dari lelaki tua yang dulu memberinya jimat.
Dan kini, ia berdiri di tepi perkemahan, berdiam laksana bayang di balik dangau yang terbengkalai. Dingin merayap perlahan dari tanah yang berlumpur. Bara-bara kecil menyala redup, berkedip-kedip seperti mata yang hampir terpejam. Sementara, lelaki-lelaki lain duduk melingkar, wajah mereka timbul tenggelam dalam bayangan api yang menari-nari di permukaan tanah. Beberapa dari mereka menggenggam bedil, besi dingin yang mereka percaya akan melindungi dari segala marabahaya.
Muller memejam, teringat tanah kelahirannya, kota yang berdiri di tepi Rhine, tempat legenda ditulis dengan anggur dan salju. Ia dibesarkan dengan kisah tentang pasukan yang hilang di hutan Taunus, para prajurit Romawi yang lenyap ditelan kabut dan amarah. Tentang mereka yang berangkat dengan nyala di dada, pulang hanya dalam desus di antara pohon ek.
Dan kini, ia bagai berada di dalam cerita itu.
Lalu angin mulai berhembus, membawa serta aroma yang berbeda. Bau daun terbakar, samar, seperti getah yang telah dipanaskan sekian menit. Muller menajamkan pendengarannya. Suasana terasa berubah. Tapi kapan? Apakah saat burung-burung malam mendadak bisu? Atau ketika hembusan angin mulai terdengar seperti seseorang yang mengendap-endap di balik rimbun daun-daun?
Hssh!
Ada yang bergerak.
Awalnya hanya suara. Gumam rendah, lirih seperti suara kepak kelelawar yang berbisik pada udara. Tapi suara itu menjalar, menyusup ke akar-akar, mengendap dalam kesunyian. Muller ingin percaya bahwa itu hanya serangga malam yang berkumpul dalam gelap, bahwa itu hanya suara hutan yang merintih. Namun, gumam itu berubah. Dari lirih menjadi dengung. Dari dengung menjadi bisikan panjang yang meliuk-liuk, menggelayut di udara malam, singgah di celah api unggun.
Lalu, dari balik pepohonan, langkah-langkah itu terdengar. Cepat. Banyak. Rusuh tiada keruan. Seakan kawanan serigala lapar mengitari mereka. Bisikan yang semula hanya desau halus kini menjelma pekik aneh, tajam, menyayat udara dengan nada yang tak menyerupai manusia.
Orang-orang panik dan saling baku pandang.
“Astaga! Apa itu?!” Suara Iskandar pecah di tengah kesunyian. Matanya liar, mencari sesuatu yang tak tampak.
“Cepet minggat! Iki dudu papan sing aman!”
“Meneng kowe! Ojo rame!” Seseorang membentak, tapi suaranya hanya bergema dalam ketakutan.
Muller menoleh ke arah Iskandar, mencoba memahami makna dari percakapan mereka, tapi ia tak sempat bertanya. Tanpa aba-aba, sesuatu menerjang dari balik pepohonan.
Teriakan pertama pecah, panjang dan patah, seperti suara anjing yang lehernya terkoyak taring. Damek, anak sumpit beracun, melesat dari segala arah. Cepat. Tajam. Sunyi. Hanya bunyi daging yang dihunjam, kayu yang tertancap, dan napas yang tersendat sebelum benar-benar lenyap.
Muller melihat Hendrik Ma tersentak. Tangannya meraba leher sendiri, matanya membelalak. Napasnya putus-putus. Mulutnya menganga, seakan hendak berbicara, tetapi suaranya tak lagi mampu keluar. Racun itu bekerja dalam sunyi. Ia terhuyung. Lalu roboh.
“Schiet op hen!” (Tembak mereka!) Diederik van Haarlocht berteriak.
Tetapi kepada siapa hendak ditembak?
Bayangan di antara pepohonan bergerak cepat. Lebih cepat dari peluru. Lebih cepat dari mata yang bisa menangkap. Mereka menari di antara kabut, melesat seperti roh-roh yang baru saja dibangunkan dari kubur.
Dor! Dor! Dor!
Berbekal kayu menyala api, Muller gegas berlari. Ia tidak berpikir. Hanya langkah yang menghantam tanah, berat dan terburu-buru, bagai suara genderang perang yang ditabuh bertalu-talu. Di sekelilingnya, suara tubuh yang jatuh terdengar seperti batang yang patah. Teriakan bergema sebentar di udara, dan menghilang begitu saja.
Lalu, sesuatu menjerat kakinya.
Akar pohon. Besar dan berlumut, melingkar seperti jemari buto. Muller terjerembap. Dadanya menghantam tanah, udara tersentak keluar dari paru-parunya dalam satu helaan kasar. Ia merangkak, mencakar rerumputan, mencoba mencari pegangan.
Ketika akhirnya ia bisa berdiri, perkemahan telah lenyap. Tidak ada suara tembakan. Tidak ada jeritan. Hanya rimba yang diam, penuh rahasia.
Muller sejenak linglung.
Ia terpaku. Hawa dingin membalut tubuhnya. Langit di atas pekat, sehitam arang yang larut dalam kabut. Sepi. Hanya desir angin yang mengusap wajahnya, membawa suara bisikan yang melesap ke dalam dadanya: PERGI!
Namun, ia tidak beranjak.
Ia menunggu. Entah menunggu apa. Mungkin sebuah tanda. Mungkin keajaiban yang mengulur tangan dari balik rimba, mengatakan bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir seiring fajar. Tapi fajar masih lama, dan rimba tetap diam—diam yang ganjil; diam yang menggigit nadi dan membuat bulu kuduk berdiri.
Lama-lama, diam menjadi sesuatu yang menyesakkan.
Maka, Muller mulai melangkah. Pelan. Nyaris tanpa suara. Agaknya, tanah Meratus telah menelan gemuruh, menenggelamkan semua langkah terburu-buru ke dalam kesunyian. Ia bergerak di antara akar yang bergelimpangan, membiarkan telinganya mendengar lebih tajam daripada matanya.
Namun, sesuatu telah menunggu di depan.
Sesosok bayangan, hampir bugil dan tak asing, berdiri di bawah pohon yang batangnya hitam legam. Ia diam. Begitu diam hingga malam seperti menahan kantuknya sendiri. Muller berhenti, lalu berpikir. Tidak, mungkin ia tidak berpikir. Mungkin pikirannya sedang terbang entah ke mana, meninggalkan tubuhnya berdiri di tengah takut, sungguh ringan seperti sekepal dandelion lepas dari tangkai.
Cahaya bulan merayap di antara dedaunan, bersatu dengan cahaya api yang meredup, jatuh pada wajah sosok itu. Oh, bukan wajah. Itu topeng! Hanya sesuatu yang menyerupai wajah. Mata—ya, ada mata di sana. Mata yang memantulkan cahaya seperti hewan liar. Atau benda mati. Atau sesuatu di antara keduanya.
Muller menghunus belatinya.
Sunyi.
Sosok itu tetap diam. Tapi bukankah diam juga bisa menjadi tindakan? Diam seperti seseorang yang tengah menunggu giliran, seperti seseorang yang yakin akan sesuatu yang belum terjadi. Lalu, ia bergerak. Buka topengnya sedikit. Sumpitnya naik, sejajar dengan dada.
“Harati, blijk jij het werkelijk te zijn?!” (Harati, ternyata benar-benar kau?!) desis Muller. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berbalik, berlari sekencang-kencangnya.
Dalam gelap itu, damek laju ditiupkan.
“Humung tutu, luput!” (Ungkapan bahasa Dayak: brengsek betul, tidak kena!)
Sejak kecil, kau tahu dunia tak hanya bicara lewat suara. Kau mendengar sesuatu yang lain—gemuruh dalam perjuangan, nada-nada yang tak diperdengarkan untuk orang-orang bersepatu bersih dan kepala manggut-manggut. Perjuangan itu bukan sekadar pertempuran, bukan? Ibumu, bahkan sebelum kau paham arti takut, sudah membisikkan kebenaran dalam gelap kamar yang bau keju dan air mani: rimba itu bukan dekorasi alam. Ia adalah bayang yang bisa murka. Ia bernapas lewat kabut, dan menyimpan kesumat dalam akar yang tak terlihat. Ia tak pernah menyerah. Ia menunggu saat-saat.
Oh, oh, sial! Muller jatuh lagi, kali ini lebih keras. Dada dan lututnya menghantam tanah, wajahnya mencium aroma basah daun-daun yang membusuk. Ketika ia bangkit, dunia di sekitarnya berubah. Langit itu, entah bagaimana, tampak lebih temaram, padahal hari belumlah senja.
Kemudian, di antara pohon-pohon, ia melihatnya. Cahaya kecil. Kecil sekali. Nyaris seperti kunang-kunang, tapi tidak. Tidak ada kunang-kunang yang berselimut asap, Muller tahu itu. Cahaya itu kelap-kelip, bergerak pelan di antara bayang-bayang. Menggoda. Memanggil!
Ia tidak berpikir panjang. Langkahnya terhuyung, berlari menuju cahaya kecil itu seperti musafir mengejar oasis dengan hamparan kaktus. Ranting-ranting mencambuk wajahnya, akar-akar licin menjegal kakinya, tapi ia terus maju, bahkan ketika napasnya terasa seperti batu tajam di tenggorokan.
Cahaya itu, meski kecil, terus membimbingnya untuk mengelak dari belukar yang mencekik. Hingga akhirnya, Muller sampai di sebuah riam. Bunyi air mendesir. Angin membuat gigil. Di sana, di atas batu besar, seseorang tengah semedi.
Ia duduk, tubuhnya membungkuk dengan tangan yang sibuk. Sosoknya tinggi dan kurus, berkalung tulang dan kulitnya cokelat batok kelapa.
Ia mendongak, menatap Muller. Wajahnya penuh coretan merah dan kuning, berkilau seperti lukisan mooi indie. Ada beberapa helai bulu enggang di ikat kepalanya. Ada rajah adat dan anting berbentuk taring.
Muller berdiri kaku, terlalu lelah untuk berbicara, terlalu segan untuk bergerak.
Tangan itu berhenti bekerja, dan ia terus saja menatap Muller, tak berkedip. Lalu, ia mengangkat sesuatu dari pangkuannya: sebatang kayu panjang yang diasah hingga tajam, seperti tombak, dan Muller tahu ia bisa melemparkannya kapan saja.
Tapi, ia tidak melakukannya.
Ia berdiri, gerakannya lambat. Cahaya kecil itu berpendar, memantulkan bayangan yang menari-nari di wajahnya, dan Muller mendengar suaranya yang serak, khas datuk-datuk.
Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Muller hanya bisa berdiri diam, mencoba memahami apa yang ia inginkan.
Kemudian, mendekatlah ia. Tombak itu masih di tangannya, tapi tidak diarahkan kepada Muller. Ia berhenti beberapa depa di depan Muller, cukup dekat untuk dirasakan adanya kesinisan.
Tiba-tiba, ia menunjuk ke satu arah, kemudian, aneh, tubuhnya menghilang dalam satu kedipan. Muller sesungguhnya tidak mengerti, tapi instingnya mengatakan bahwa ia harus menoleh.
Dan terlihat di sana. Di belakangnya. Sesosok perempuan berdiri dengan rambut yang basah!
***
MULLER masygul benar, di sini tidak ada jejak yang dapat dikenalnya, hanya kelam yang berkelindan. Namun, di dalam hatinya, gema lain bergemuruh—nama seorang perempuan yang tidak pernah ia lupa sejak pertemuan di riam itu.
Bungeh.
Ia ingat dengan sangat jelas, lebih jelas daripada peta-peta yang digambar tangan-tangan terbaik di markas militer, saat pertama kali melihat perempuan itu. Ia tidak datang dari jalan setapak, tidak dari balik semak atau rakit. Ia muncul di belakangnya seperti bayangan yang dipahat dari cahaya. Rambutnya hitam pekat, matanya bola-bola cermin, membuat Muller terkesima.
Bungeh datang dengan senyum terkembang dan gerak-geriknya seperti geliat Soneta 18–“Shall I compare thee to a summer’s day?” yang pernah Muller baca, tak pernah benar-benar bisa dimengerti.
“Kau datang untuk memetakan tanah ini?” tanya Bungeh saat itu.
Muller sempat terkejut. Ia tidak tahu mengapa perempuan itu fasih dalam bahasa asing. Seolah tidak ada batas antara pulau-pulau, antara Eropa dan Kalimantan. Waktu itu ia menjawab singkat, terlalu pendek untuk mengimbangi kedalaman tatapan Bungeh.
“Ya.”
Bungeh tertawa. Alahai, tawanya itu bukan seperti tawa wanita-wanita di pesta dansa ’s-Gravenhage. Tawa itu seperti dedaun kering yang diseret angin di lantai hutan—ringan, tak berbekas.
“Tanah ini tidak bisa dipetakan, Tuan. Ia hidup. Ia bernapas. Ia menolak diberi batas. Kau tidak akan menemukan apa yang kau cari di sini, karena tanah Kalimantan hanya akan memberikan apa yang memang sudah menjadi bagiannya sejak dulu. Kau bukan bagian dari itu.”
Muller menyeringai. Ia berpikir Bungeh sedang bermain-main dengan mitos, dengan majas, dengan kepercayaan yang tidak bisa diuji di atas kertas. Bagi Muller, alam tetaplah buaian, meski ia sendiri telah banyak mengalami peristiwa ganjil yang sangat menegangkan, dan sama sekali belum begitu paham apa yang sebenarnya sudah berlaku.
Akhirnya, bukan kau yang menemukan rahasia Meratus. Tapi Meratus yang memilih membuka dirinya. Bukan dengan senyum, melainkan dengan hentakan, seperti air terjun yang tiba-tiba jatuh dari tebing, membelah yakin.
“Meratus bukan hanya hutan belantara,” kata Bungeh, dengan suara macam kumbang terjepit, seolah kata-kata itu hanya ditujukan untuk para benuang. “Meratus adalah tubuh kami. Pohon-pohon ini adalah tulang kami, sungai-sungai ini adalah darah kami, cahaya kunang-kunang adalah pelita harapan, dan angin yang berhembus adalah napas kami. Di setiap akar, daun, dan batu, ada roh penjaga. Maka, Tuan yang tersesat, jangan kau rusak segala itu.”
Ia mengucapkannya tanpa menoleh, hanya memandangi lembah di kejauhan yang tertutup pepohonan. Seakan-akan seluruh kalimat itu telah lebih dulu tumbuh di dadanya seperti jamur, dan ia tinggal memungutnya satu-satu, menyerahkannya kepada udara yang akan membawa pesan itu jauh, lebih jauh dari mulut manusia.
Sementara itu, Muller hanya berdiri, mendengarkan, seperti anak kecil yang terlalu lambat memahami peringatan, tapi terlalu sombong untuk bertanya ulang.
Sunyi.
Dan Muller teringat, entah kenapa, pada suatu masa. Ketika ibunya duduk diam di dapur yang sunyi, memandang kue tart dengan nyala lilin sambil menangis. Ketika ayahnya tak pulang. Tidak ada yang mengumpat akannya, tapi justru itu yang membuat semuanya makin sulit. Sunyi yang lambat dan tanpa arah. Persis seperti sekarang.
Muller mengalihkan pandangannya. Ke tanah. Ke akar yang mencuat. Ke semut yang berjalan. Tapi semuanya terasa seperti mata yang menonton dan menilai. Ia pernah mendengar bahwa yang paling sering dilupakan oleh manusia egois bukanlah bagaimana cara hidup, tapi bagaimana cara mendengarkan. Dan ia, selama ini, hanya mendengar yang ingin ia dengar.
Angin bertiup perlahan. Bungeh masih berdiri di tempat yang sama, tak bergerak sama sekali. Muller tahu ia ingin bicara lebih banyak, tapi tahu pula bahwa diam adalah lebih baik.
Dan di antara pohon dan diam itu, Muller akhirnya sadar, bahwa mungkin ia memang jauh tersesat. Bukan karena tak tahu arah, tapi karena telah kehilangan sesuatu yang seharusnya tak boleh hilang: kemampuannya untuk merasa cukup!
Kau tahu, alam tak memberi pertanda seperti manusia memberi kata. Ia tak berkhotbah di mimbar atau menulis nubuat di batu. Dan di tengah segala itu, ia berdiri: rambut basah, kulit pucat, seolah-olah alam sendiri terperangkap dalam tubuh manusia. Kau, yang terbiasa dengan seragam, perintah, dan angka-angka rapi, terhenti. Untuk pertama kalinya, kau sadar: ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan, tak semua kenyataan tunduk pada logika. Tak semua rasa punya padanan kata.
LANGIT Meratus malam itu bening seperti mata air, bintangnya penuh, berkerlip macam bara-bara kecil yang tercecer. Api unggun menyala di tengah lapangan tanah, menjilat udara dengan lidah jingganya yang menyebar kakalatu. Bau sengon terbakar merambat ke mana-mana, menempel di rambut, di baju, bahkan mungkin di ingatan.
Bungeh duduk tak seberapa jauh, lututnya dirapatkan, rambutnya dijepit bunga senduduk. Muller, yang tadi sore sempat mengisi perutnya dengan beberapa ekor adungan dari riam, melirik sesekali.
“Bintang malam ini seperti banyak yang pulang kampung,” ujar Bungeh pelan.
Muller mengangguk. “Ya. Aku belum pernah lihat langit serapat ini di mana pun.”
“Kau belum pernah betul-betul diam, mungkin,” balas Bungeh, matanya tak beralih dari langit. “Langit itu buka mulut kalau kita tahu caranya diam.”
Muller tertawa kecil. “Kau selalu bicara seperti seorang filsuf.”
“Aku cuma sering duduk di hutan. Dan hutan itu guru yang cerewet, kalau kau sabar dengarnya.”
Lama mereka hanya mendengar: suara burung hantu dari kejauhan, gemerisik daun jatuh, dan kadang lolongan samar entah dari sudut mana. Bungeh lalu menyentuhkan telapak tangannya ke tanah.
“Kau tahu cara dengar suara angin?” tanyanya.
“Dari telinga?”
“Dari tanah. Kau tempelkan telinga di tanah. Angin dari timur bunyinya beda. Angin dari selatan lain lagi.”
Muller menurut. Pipinya menyentuh tanah yang hangat karena api unggun. Ia merasa kikuk, tapi Bungeh terlihat memejamkan mata.
“Bungeh,” ujar Muller lirih, hampir kalah oleh suara napasnya.
Bungeh menoleh perlahan, wajahnya setengah tersorot nyala api. “Kenapa kau memanggilku dengan nada begitu?”
“Tidak. Hanya saja, hm, aku tak tahu apa yang kau bawa, tapi sejak kau datang, hutan ini tak terasa mengancam. Aku pun lupa-lupa ingat ….”
Bungeh tersenyum. “Hutan tak pernah mengancam, Tuan. Manusia yang selalu gelisah.”
“Aku tak paham bahasa hutan. Tapi kau sepertinya tahu.”
“Karena aku tak menolak sunyi. Kau harus belajar itu juga.”
Api unggun menggerak-gerakkan bayangan mereka di tanah.
“Kenapa kau sering datang tiba-tiba, pergi pun begitu?” tanya Muller.
Bungeh duduk bersila, mencabut seutas rumput. “Karena angin tadi membawa bau cemasmu. Kudengar sejak senja.”
“Bau pun bisa bicara?”
“Kalau kau tahu caranya dengar.”
Muller menunduk. “Di medan perang, aku tak pernah diajari begitu.”
Bungeh berdecak. “Kau terlalu banyak tanya. Dengarkan saja.”
Sunyi.
“Dengar itu,” Bungeh membuka mata. “Bangkui besar sedang mencari pasangannya. Tapi tak berani keluar. Ia tahu ada manusia.”
“Kenapa ia takut?”
“Karena manusia tak pernah datang tanpa maksud.”
Muller menggenggam lututnya. “Kau sendiri?”
Bungeh tak menjawab. Ia berdiri, menghadap ke bulan jauh. Lalu tiba-tiba bersenandung lirih dengan suara syahdu:
“O, hai, kahu pernah ngerasaken jat hawe’? Teh jat di gelas, teh cairan ngalir di awak, tapi handak uluh panas—nyatu ji bumi, handak baguli tiap tapak laluan kahu.” (O, pernahkah kau merasakan racun kerinduan? Yang bukanlah racun dalam gelas, bukan cairan yang mengalir dalam tubuh, tetapi sesuatu yang lebih panas—sesuatu yang menyatu dengan bumi, yang akan membakar setiap jejakmu.)
Muller terpana. Bungeh membuka matanya, menatapnya sekilas. Senyumnya memikat, tapi ada sesuatu yang berisik di balik tatapannya. Ia melanjutkan:
“Patakan angka makai murung. Panambaian mantera bari lungking.” (Angka-angka memucat pilu. Doa mula terlantun sendu.)
“Syair lumu babaris larang. Di tampat mati bapalimbang. Suir ilalang ba’akut malu. Ba’gema pilu tanpa ulu.” (Sajak abu menabur luka. Di pemakaman begitu hampa. Mengiring ilalang bernyanyi lirih. Menggema pilu tiada bertepi.)
Senandung itu terkesan mistis. Muller tak mengerti semua artinya, tapi seolah tubuhnya sendiri yang merespons. Ia merasa seperti daun yang jatuh di arus pelan, dihanyutkan oleh makna yang tak perlu dimengerti dengan kepala.
“Kau tahu apa arti senandungku, Tuan?” tanya Bungeh.
Muller menggeleng pelan.
Bungeh tersenyum tipis. “Cinta, Tuan. Cinta di tanah ini, bisa saja membunuh kita!”
Api unggun berdesis. Bungeh berbalik lalu melangkah pergi. Dan Muller mematung, bingung, hanya bisa menatap Bungeh menghilang di balik kabut, membawa kata-kata itu bersamanya.
Kau hanya perlu berhenti menjadi prajurit atau residen atau apa pun yang diberi label oleh dunia, dan hanya menjadi ini: sesosok tubuh yang duduk di bawah pohon, bernapas, dan untuk sekarang, cukup dengan itu.
Angin menderu, daun-daun bergetar, dan di sela semak, cahaya kunang-kunang berpendar. Muller duduk bersandar pada batang pohon yang keras, kulitnya seperti sisik ular sawa. Bungeh datang lagi, tanpa suara, seperti biasanya, kakinya nyaris tak menyentuh tanah, atau mungkin tanah menahan geliatnya tiap kali perempuan itu melangkah.
“Tuan merindui kampung?” tanya Bungeh.
“Tidak. Tapi aku masih begitu kepikiran.”
“Karena Tuan masih membawa serpihannya. Di matamu, di caramu menimbang waktu. Di caramu bertanya.”
Muller mengerdipkan mata. Bungeh melihat wajah kusut itu, dan bukannya iba, ia justru mengulurkan tangannya, mengusap pelipis Muller dengan ibu jari yang dingin, dan berkata pelan, “Tuan telah terlalu lama di sini, menyusur pulang, mengingat-ingat yang tak perlu.”
“Bungeh,” ujar Muller parau, “mengapa aku merasa kita seperti … bukan manusia?”
Bungeh tertawa pelan. “Tuan bertanya seakan dunia ini hanya punya satu arah. Padahal, waktu berputar seperti angin yang lupa. Aku bisa saja dari masa depanmu. Atau mungkin, dari ingatan lampau yang Tuan bawa tanpa sadar. Siapa tahu?”
Ia berdiri, perlahan, seolah hendak kembali larut dalam gelap.
“Jangan pergi,” kata Muller cepat. Suaranya pecah, lebih karena kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia meraih tangan Bungeh, menggenggamnya erat—masih terasa dingin, seperti baru saja disentuh hujan. Dingin yang tak membeku, tapi menanamkan sejenis getir. “Kau satu-satunya yang membuatku percaya bahwa aku belum gila.”
Bungeh menatapnya, kali ini tak seperti sebelumnya. Matanya memantulkan api seperti langit yang terbakar perlahan, menyimpan hangat di antara kelopak sunyi.
“Kau tidak gila, Tuan. Anggap saja kau sedang dilahirkan ulang. Tapi kelahiran kedua selalu menuntut pengorbanan.”
Muller menarik napas, tak yakin apakah itu napas kebingungan atau kengerian. “Apa yang harus kukorbankan? Dan, Bungeh … tolong jangan panggil aku ‘Tuan’, panggil saja Muller.”
Bungeh diam. Lalu berkata pelan, “Entahlah, Muller.”
Dan sebelum Muller bertanya lebih lanjut—tentang pengorbanan, tentang dirinya, tentang hutan dan segala hal yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat—Bungeh menyentuh pipinya, sekali, lembut, dan malam pun runtuh ke dalam tubuhnya.
Ketika Muller membuka mata, ia sudah sendiri. Tak ada suara langkah menjauh. Tak ada desah napas. Tak ada aroma kulit Bungeh yang lembap seperti lumut dan akar yang menyimpan embun dini hari. Hanya dingin yang menyelubungi, menggigit, merayap masuk ke sela-sela pikirannya. Dan malam—malam yang tak lagi memantulkan wajah sejuk rembulan.
Bungeh seperti Meratus—tunggal, cantik, dan abadi. Ketika ia pergi, kau mulai sadar: kau tidak hanya kehilangan arah dan rombongan, tapi juga sesuatu di dalam hatimu. Tapi, kau tak perlu banyak khawatir, Muller. Bahkan Werther dalam surat-suratnya kepada Wilhelm pernah meraba kehampaan yang sama, merasa seperti tamu di dunia yang terlalu bising.
Catatan: Ini adalah 2 bab revisi dari novel Kariyau Sunyi karya Azhar Riyadi/Rie Arshaka yang telah disesuaikan berdasarkan masukan dari juri dan mentor. Novel ini akan diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2026.