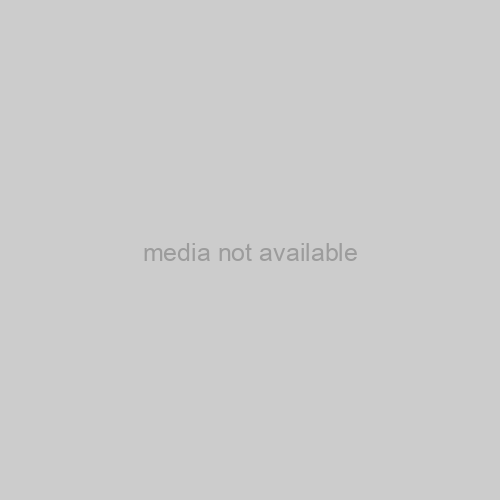Dalam perjalanan panjang sastra modern, tidak banyak istilah yang mengalami nasib seaneh “polifoni.” Awalnya, polifoni hanyalah salah satu cara Bakhtin menjelaskan kekuatan narasi Dostoevsky. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, istilah ini berubah menjadi semacam label prestise. Ia menjelma menjadi semacam ukuran mutlak yang dipakai untuk menilai kualitas prosa, seakan-akan novel yang tidak polifonik pasti kurang modern, kurang mendalam, atau bahkan hanya sekadar variasi lama yang kurang layak dibaca.
Misalnya, dalam percakapan informal antarpenulis, istilah “polifoni” dan “monofoni” telah menjadi penanda mutu. Seorang penulis mengisahkan bahwa kemenangan di sebuah lomba sastra dikaitkan dengan keberhasilan mengelola bentuk polifonik. Sebaliknya, naskah yang ia kirim ke penerbit ditolak karena dianggap “monofonik.” Ini menunjukkan bahwa istilah yang awalnya bersifat teoretis telah bergeser menjadi semacam stempel estetik, bahkan di luar diskusi akademik.
Ahmad Sahal, misalnya, dalam “Sastra, Ambiguitas, Dan Tawa Tuhan (2009) menyatakan secara implisit bahwa dengan cara itulah polifoni dalam novel (Saman) seperti dikemukan Bakhtin menemukan sosoknya. Pernyataan ini menempatkan polifoni sebagai indikator kemajuan naratif, dan menjadi salah satu rujukan awal di Indonesia yang menandai Saman sebagai model “prosa modern” dibanding “narasi lama.” Ini adalah contoh nyata bagaimana istilah polifoni mulai menjadi standar nilai bentuk.
Kemudian, Zen RS dalam poster yang diunggah akun Dewan Kesenian Jakarta (2025) bahkan lebih jelas pemosisian hierarki itu. Kutipannya ini menempatkan kebebasan tokoh (ciri khas polifoni) sebagai indikator “kebagusan” novel, dan sebaliknya, menganggap kendali pengarang (karakteristik monofoni) sebagai sesuatu yang negatif. Dalam pernyataan ini, kebebasan tokoh diasosiasikan dengan kebaikan estetika, dan narasi terpusat dianggap sebagai “pamer.” Ini mencerminkan keyakinan populer yang menyamakan polifoni dengan superioritas estetik. Karena dikutip oleh lembaga resmi (DKJ), poster ini memperkuat gejala bahwa diskursus dominan hari ini menempatkan polifoni di posisi hierarkis.
Melihat Konteks
Untuk memahami konteksnya, kita harus kembali ke Rusia abad ke-19. Dostoevsky menulis pada masa ideologi saling berbenturan tanpa kompromi, seperti Ortodoksi Kristen, ateisme Eropa, sosialisme utopis, nihilisme. Dalam novel-novelnya, semua pandangan itu hidup dalam ketegangan. Ivan Karamazov dengan skeptisisme yang keras, Alyosha dengan kepercayaan religius yang lembut, Smerdyakov dengan kebencian yang sunyi dan sembunyi. Tidak ada satu pun suara yang diberi cap “benar” oleh pengarang. Dialog mereka tak pernah selesai, bahkan ketika cerita berakhir.
Bakhtin, yang terpesona pada Dostoevsky, menciptakan istilah polifoni untuk menjelaskan fenomena itu. Ia menyebut polifoni sebagai bentuk “pluralitas kesadaran ideologis” di mana tokoh-tokoh menjadi pusat kebenaran sendiri, bukan sekadar boneka yang dipakai pengarang untuk berkhotbah. Dalam Problems of Dostoevsky’s Poetics (1984), Bakhtin menulis: “Dalam roman Dostoevsky, kesadaran para tokoh tidak tunduk pada kesadaran pengarang. Dialog ideologis yang berlangsung tidak memiliki titik henti definitif.”
Kalimat ini kemudian dikutip ratusan kali dalam kritik sastra kontemporer. Namun, seringkali kutipan itu diambil setengah hati. Banyak yang mengira polifoni hanya berarti “banyak suara.” Padahal, polifoni adalah banyak suara yang setara, merdeka, dan tidak diredam menjadi satu kesimpulan moral. Artinya setiap novel dengan kesimpulan moral secara dominan itu monofoni. Tapi bukan berarti buruk.
Kita bisa membandingkannya dengan Leo Tolstoy. Dalam Anna Karenina, walau narasi menampilkan beragam perspektif—Anna, Levin, Karenin—semuanya akhirnya tunduk pada satu nada moral. Tolstoy tidak memberi kebebasan mutlak pada setiap kesadaran. Ia meyakini ada nilai yang bisa menilai hidup manusia. Karena itu, novel itu monofonik. Namun, monofoni Tolstoy bukan kelemahan, bukan buruk, melainkan pilihan estetik yang sesuai zamannya.
Itulah yang jarang dibahas dalam diskursus populer, bahwa polifoni bukan bentuk yang superior secara mutlak. Polifoni hanya cocok untuk pengarang yang sungguh percaya relativitas kebenaran total. Untuk pengarang lain yang meyakini nilai moral tertentu, monofoni adalah bentuk yang paling jujur.
Contoh yang lebih kontemporer bisa kita lihat pada George Orwell. Dalam 1984, semua suara hanya berfungsi memperkuat kengerian totalitarianisme. Winston Smith boleh berdialog, tetapi pembaca tidak pernah ragu. Novel itu berpihak pada kebebasan individu dan melawan kebohongan negara. Ini monofoni yang konsisten. Apakah 1984 karena itu menjadi karya yang lemah? Justru sebaliknya, monofoninya menjadi sumber intensitas yang membuat novel itu tak terlupakan.
Begitu pula Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea seluruhnya disaring melalui kesadaran Santiago. Tidak ada pertarungan ideologis yang setara. Semua hanya cermin dari satu keyakinan, bahwa harga diri manusia tak bisa dirampas. Hemingway percaya narasi sederhana yang jujur lebih kuat daripada kerumitan palsu. Dalam esai-esai dan bukunya Death in the Afternoon (1932), bisa disimpulkan bahwa kebenaran sering kali tidak memerlukan ornamen.
Lalu mengapa hari ini polifoni justru dianggap puncak modernitas? Seperti dinyatakan dalam esainya Ahmad Sahal, pernyataan Zen RS dan contoh penolakan penerbit karena menganggap bukan polifoni. Barangkali jawabannya ada pada perkembangan kritik sastra abad ke-20 yang dipengaruhi pascamodernisme. Ketika kritik strukturalis dan pascastrukturalis menekankan relativitas, pluralitas, dan dekonstruksi makna, banyak pembaca mulai curiga pada narasi yang terlalu tegas. “Monofoni” jadi sinonim dogmatis, sementara “polifoni” dianggap plural, demokratis, toleran. Kira-kira begitu.
Sayangnya, di Indonesia, kecenderungan itu sering dibawa tanpa bekal epistemologis yang matang. Akibatnya, polifoni menjadi jargon yang dipakai untuk menaikkan nilai karya secara instan. Kita seolah tak lagi membaca novel, tetapi hanya mencari label. Begitu novel punya banyak sudut pandang, seakan-akan ia otomatis lebih canggih daripada yang lain.
Contoh paling terang dari tren ini adalah poster Zen RS yang diunggah akun Dewan Kesenian Jakarta tahun 2025 di bawah ini.

Dalam poster berwarna oranye itu, Zen RS difoto sedang berbicara sambil mengangkat tangan. Di bawah fotonya tertera kutipan: “Novel jadi jelek kalau pengarangnya terkesan pamer pengetahuan. Novel yang bagus justru membiarkan tokohnya hidup sendiri, berbicara secara alami bukan dikendalikan pengarang.”
Kutipan ini mencerminkan dua kecenderungan. Pertama, kecurigaan terhadap pengarang yang memusatkan narasi (yang disebut “pamer pengetahuan”); kedua, glorifikasi kebebasan tokoh seakan-akan itu satu-satunya tanda kebesaran prosa. Padahal, apa yang dimaksud “membiarkan tokoh hidup sendiri” juga tidak sederhana. Bahkan dalam polifoni Dostoevsky pun, pengarang tetap merancang batas.
Perlu dicatat bahwa tidak semua narasi yang padat pengetahuan layak disebut “pamer.” Karya Borges, Umberto Eco, dan bahkan Olenka Budi Darma menunjukkan bahwa pengetahuan bisa diintegrasikan secara puitik dan psikologis. Pedanticism hanya terjadi ketika pengetahuan tidak menyatu dengan narasi, tetapi tampil sebagai upaya pamer atau sok tahu. Oleh karena itu, kutipan Zen RS sebaiknya dipahami sebagai reaksi terhadap bentuk tertentu dari pedanticism, bukan terhadap pengetahuan itu sendiri.
Kutipan dari Zen RS barangkali tidak berbicara langsung soal polifoni, tapi mencerminkan diskursus populer yang mengidealkan kebebasan tokoh dan alergi terhadap kontrol naratif yang terlalu sadar diri. Pola ini sejalan dengan penilaian positif terhadap narasi polifonik dalam ulasan-ulasan terhadap Saman, misalnya di mana banyaknya suara dan kurangnya dominasi narator diposisikan sebagai bentuk modern yang lebih tinggi. Dan itu merujuk pada pengertian polifoni Bakhtinian.
Kita bisa bandingkan dengan Kafka. Dalam The Trial, Joseph K. tidak hidup dalam kebebasan penuh. Semua suaranya justru terkurung dalam absurditas sistem hukum. Tapi justru karena keterkurungan itu, novel Kafka begitu berdaya. Bayangkan jika Kafka menulis banyak bab di mana Joseph K. berdialog panjang tentang filsafat hukum dengan petugas pengadilan. Barangkali kita akan kehilangan rasa ngeri yang membeku di setiap kalimatnya.
Poster Zen RS bukan satu-satunya. Kita juga menemukan bias serupa dalam pengantar Ahmad Sahal di antologi Cerpen Pilihan Kompas 1999: Derabat yang menyebut Saman sebagai novel polifoni. Sahal menulis dengan semangat ingin menunjukkan kebaruan bentuk. Namun, seperti yang nanti akan kita kupas lebih detail, Saman lebih tepat disebut multivokal progresif, bukan polifoni radikal.
Semua contoh ini menunjukkan bahwa polifoni sering dijadikan stempel yang menyederhanakan keragaman estetika. Kita lupa, bentuk bukan sekadar format kosong. Bentuk lahir dari keberanian pengarang memilih cara melihat dunia. Dostoevsky memilih polifoni karena ia percaya kebenaran tidak tunggal. Tolstoy memilih monofoni karena ia yakin ada nilai moral. Hemingway memilih monofoni karena ia percaya kesederhanaan. Kafka memilih monofoni karena absurditas tidak memerlukan debat panjang. Itulah sebabnya, diskusi kita tidak akan sekadar mencari siapa yang lebih unggul. Tujuan esai ini adalah membongkar asumsi hierarki yang merayap di banyak diskursus sastra Indonesia bahwa ada anggapan pluralitas bentuk otomatis lebih agung daripada kejujuran satu suara.
Bagian berikut akan menunjukkan secara rinci bagaimana asumsi itu tercermin dalam pembacaan atas Olenka, Saman, dan karya-karya yang lain.
Multivokalitas dan Kesalahpahaman
Ketika perdebatan tentang monofoni dan polifoni mulai mengemuka di Indonesia, dua karya yang sering dijadikan contoh adalah Olenka karya Budi Darma dan Saman karya Ayu Utami. Kedua novel ini sering diposisikan seakan-akan mewakili puncak kebaruan bentuk dalam prosa Indonesia mutakhir. Namun, jika kita membaca lebih pelan, akan tampak jelas betapa perbedaan keduanya sangat signifikan—dan betapa label “polifoni” kerap dipaksakan hanya karena keinginan menciptakan hierarki estetis.
Mari kita mulai dengan Olenka. Novel ini secara konsisten dinarasikan oleh Fanton Drummond. Semua pengalaman, ingatan, kecemasan, dan keraguan dikisahkan melalui satu kesadaran tunggal. Bahkan ketika ia mengutip Chairil Anwar, mencatat surat Mary Carson, atau merujuk eksistensialisme Sartre, kutipan itu tidak menjadi pusat kesadaran baru. Mereka hanya serpihan yang diserap kembali ke dalam monolog Fanton. Ini bukan dialog ideologis yang setara, melainkan kolase yang mendalamkan perasaan keterasingan.
Dalam salah satu adegan paling intens, Fanton menulis: “Aku memungut fragmen puisi Chairil Anwar, menyalin surat Mary Carson, mencatat petikan Sartre—semua untuk memastikan bahwa cintaku padanya bukan ilusi.”
Kalimat ini sering dikutip pengamat sastra untuk mendukung klaim polifoni. Padahal, kalau kita cermati, semua rujukan itu hanya fungsi retoris. Chairil, Carson, Sartre tidak memiliki agensi. Mereka tidak merumuskan ide-ide yang menyaingi kesadaran narator. Ini monofoni modernis yang memakai kolase bukan untuk pluralitas ideologis, melainkan untuk menggambarkan bagiaman berantakannya batin.
Suwondo, dalam bukunya Membaca Olenka Dalam Perspektif Bkhatin (2022), mengakui bahwa Olenka memuat banyak pikiran, genre, dan suara. Namun di bab kesimpulan, ia juga menulis bahwa polifoni dalam novel ini “hanya sampai pada tingkatan tertentu.” Klaim itu sebenarnya adalah pengakuan tak langsung bahwa Olenka tak sepenuhnya polifonik. Jika semua suara tetap diredam menjadi cermin kesadaran Fanton, maka kita berhadapan dengan monofoni. Polifoni bukan soal jumlah kutipan, melainkan apakah kutipan itu menjadi pusat ideologis yang mandiri.
Bakhtin sendiri secara tegas membedakan polifoni dari sekadar teknik kolase. Dalam Problems of Dostoevsky’s Poetics, ia menjelaskan bahwa polifoni adalah: “Seni menyusun dialog ideologis yang membiarkan semua suara tetap berdiri setara, tanpa digiring pada satu simpulan moral.”
Dengan kata lain, kalau pembaca bisa merasakan satu nilai dominan yang memayungi semua narasi, maka novel itu tetap monofonik. Olenka jelas memenuhi kriteria ini. Keputusasaan, kesepian, dan keraguan Fanton menjadi lensa tunggal yang membingkai segalanya.
Sebaliknya, Saman karya Ayu Utami sering dijadikan contoh polifoni Indonesia kontemporer. Dalam pengantar Derabat, Ahmad Sahal menyebut Saman berhasil memecah narasi menjadi polifoni yang merdeka. Sekilas, klaim ini tampak masuk akal. Novel itu memang menampilkan empat tokoh utama—Yasmin, Laila, Shakuntala, dan Saman—masing-masing dengan narasi, fragmen memori, dan sikap hidup yang berbeda. Struktur bab pun tidak linear, melainkan meloncat-loncat di antara mereka.
Tetapi, sekali lagi, polifoni bukan sekadar banyak suara. Polifoni menuntut kesetaraan ideologis yang membuat semua suara berdialog tanpa dominasi. Dalam Saman, kita melihat semua narasi justru diarahkan pada satu kritik moral, yaitu perlawanan terhadap patriarki dan hipokrisi agama. Tidak ada pertarungan nilai yang terbuka. Tokoh-tokoh tidak saling mengoreksi dalam dialog ideologis yang setara. Semua fragmen akhirnya menjadi barisan argumen yang menopang gagasan pusat novel. Dalam Saman, tokoh Shakuntala memandang cinta sebagai sesuatu yang menuntut kebebasan tubuh. Jika kebebasan itu dibatasi norma, yang muncul hanyalah kepura-puraan.
Kalimat itu bukan sekadar pernyataan personal. Ia menjadi benang merah yang muncul di narasi Laila dan Yasmin. Semua tokoh pada akhirnya merumuskan kebebasan sebagai puncak kebenaran. Tidak ada suara lain yang secara serius menegosiasi klaim itu. Dalam arti Bakhtinian, ini belum polifoni. Ini multivokal progresif—banyak suara yang bergerak menuju satu horizon moral.
Apakah itu membuat Saman karya lemah? Sama sekali tidak. Justru keberanian Ayu Utami untuk memilih satu nada yang konsisten adalah sumber kekuatannya. Namun, menyebut Saman polifoni sama seperti The Brothers Karamazov hanya akan menyesatkan pembaca. Karena itu, kita perlu memisahkan penghargaan atas kualitas dengan kebiasaan menempel label prestise.
Suwondo, Sahal, Zen RS, dan banyak pengamat lain seakan ingin menegaskan bahwa pluralitas bentuk otomatis lebih baik. Padahal, pluralitas bentuk tidak selalu mencerminkan pluralitas ideologis. Sebaliknya, monofoni pun bisa menyimpan kompleksitas. Kafka hanya memakai satu suara Joseph K., tetapi absurditas yang lahir darinya melampaui kebisingan banyak narasi. Demikian pula Chekhov. Dalam Ward No.6, Dr. Ragin berdialog dengan pasien yang menderita delusi. Tetapi narasi Chekhov secara konsisten menciptakan satu atmosfer getir. Tidak ada pluralisme ideologis total. Semua percakapan menjadi selubung ironi yang merujuk pada absurditas eksistensi. Ini monofoni subtil yang sering keliru dibaca polifoni. George Orwell dalam 1984 lebih ekstrem lagi. Semua percakapan hanya untuk mempertebal satu ketakutan: kebohongan totalitarianisme. Tidak ada suara yang diberi kebebasan menjadi pusat kebenaran alternatif. Dan justru karena itu novel Orwell mengguncang pembaca.
Dalam sastra Indonesia, Pramoedya Ananta Toer pun menulis dengan monofoni tegas. Bumi Manusia memang memberi ruang tokoh lain berbicara. Namun semua percakapan tetap menguatkan kesadaran Minke sebagai pusat narasi. Begitu juga Cantik itu Luka Eka Kurniawan—narator mahatahu yang ironis tetap mendominasi semua perspektif.
Semua contoh ini menunjukkan bahwa monofoni bukan tanda kemunduran. Ia hanya cara lain bercerita. Kejujuran pengarang terhadap bentuknya jauh lebih penting daripada klaim pluralitas semu. Kutipan Zen RS, sekali lagi, di Instagram DKJ 2025 menjadi puncak dari kecenderungan hierarki ini. Ketika ia mengatakan bahwa novel jadi jelek kalau pengarangnya terkesan pamer pengetahuan. Novel yang bagus justru membiarkan tokohnya hidup sendiri, berbicara secara alami bukan dikendalikan pengarang, Zen sesungguhnya sedang merumuskan standar estetika yang meminggirkan monofoni.
Pernyataan itu terdengar simpatik, tetapi di baliknya ada bias anggapan bahwa semua narasi harus plural, bebas, “alami.” Padahal, dalam sejarah sastra, tidak ada yang lebih alami daripada satu suara manusia yang jujur terhadap kecemasannya. Jika kita ingin adil pada sastra, kita harus melepaskan hierarki yang pura-pura netral ini. Polifoni bukan puncak. Monofoni bukan dasar. Keduanya hanyalah bentuk yang menunggu kesungguhan pengarang untuk dihidupi.
Menolak Hierarki
Jika kita menoleh ke sejarah panjang novel, kita akan melihat sesuatu yang sering luput dalam debat polifoni-monofoni, bahwa setiap bentuk lahir dari pergulatan pribadi pengarang. Tidak ada satu pun karya besar yang lahir hanya untuk mematuhi teori. Tidak ada satu pun pengarang hebat yang duduk di mejanya sambil berkata: “Aku akan membuat novel polifonik yang sempurna.” Bahkan Dostoevsky sendiri tidak menulis The Brothers Karamazov untuk menciptakan kategori baru. Ia hanya menulis karena yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan zaman tidak bisa dijawab oleh satu keyakinan tunggal. Maka polifoni baginya bukan sekadar teknik—ia adalah keharusan eksistensial.
Tolstoy pun sebaliknya. Ketika ia menulis Anna Karenina, ia justru percaya ada nilai moral yang harus dijaga. Narasinya mungkin luas, perspektifnya plural, tetapi semua diikat satu benang penilaian etis. Karena Tolstoy tak percaya relativisme total. Hemingway, Orwell, Kafka—mereka semua setia pada satu suara yang bagi mereka adalah satu-satunya cara untuk merumuskan pengalaman. Inilah yang seharusnya menjadi pelajaran, bahwa bentuk bukan tren. Bentuk adalah keputusan. Dan keputusan itu selalu politis, etis, dan personal.
Ketika diskursus sastra modern mulai menciptakan hierarki, kita menyaksikan bagaimana label menjadi lebih penting daripada keberanian bercerita. Orang berlomba-lomba memproklamasikan “ini polifoni,” “ini monofoni,” seakan-akan label itu sudah menjadi cap mutu. Lebih parah lagi, klaim itu kerap diulang tanpa pengujian kritis. Buku Suwondo tentang Olenka misalnya, meskipun layak diapresiasi atas ketekunannya membaca detail teks, tetap terjebak dalam kesimpulan kabur—bahwa polifoni Olenka “hanya sampai tingkatan tertentu.” Pernyataan itu secara tidak langsung mengakui kebingungan definisinya.
Suwondo memang menunjukkan kelebihan—mampu mendeteksi kehadiran banyak referensi dalam Olenka. Tetapi ia kurang tegas membedakan antara kolase intertekstual dan pluralitas ideologis. Padahal di situlah inti persoalan. Sebab, kalau setiap narasi kolase kita sebut polifoni, maka Ulysses James Joyce pun hanya polifoni semu. Ulysses menampilkan banyak gaya, banyak kutipan, tetapi pada akhirnya tetap disatukan satu pengalaman kesepian Leopold Bloom. Joyce bermain-main dengan bentuk aliran kesadaran, tetapi tidak melepaskan kendali atas makna akhir. Inilah yang disebut Brian McHale sebagai “pluralitas retoris,” bukan pluralitas ideologis.
Kita juga harus mempertanyakan tendensi dalam kritik Ahmad Sahal yang secara tegas menyebut Saman polifonik. Padahal, jika kita baca lebih cermat, semua narasi dalam Saman justru bergandengan erat untuk mengukuhkan satu horizon etis, yaitu kebebasan tubuh perempuan dan kritik terhadap represi negara. Tokoh-tokohnya boleh berbicara dari sudut pandang yang berbeda, tetapi tidak satu pun yang sungguh menjadi pusat kebenaran alternatif. Tidak ada dialog ideologis yang setara. Yang ada adalah harmoni progresif, sebuah orkestra yang sudah ditentukan nadanya. Tentu saja, sah-saja di mana Sahal ingin menegaskan kebaruan bentuk. Namun, kebaruan itu tidak selalu berarti polifoni. Kadang ia hanya berarti keberanian membongkar tema yang tabu. Dan itu sama berharganya dengan pluralitas sudut pandang.
Poster Zen RS menambah ilustrasi betapa bias polifoni telah menjadi retorika populer dalam wacana sastra Indonesia mutakhir. Ketika Zen berkata, “Novel jadi jelek kalau pengarangnya terkesan pamer pengetahuan. Novel yang bagus justru membiarkan tokohnya hidup sendiri,” ia menegaskan asumsi seakan-akan semua prosa hebat harus plural, harus longgar, harus “alami.” Padahal pertanyaannya kemudian alami menurut siapa?
Yang patut dicermati, pandangan seperti ini tidak berdiri sendiri. Dalam laporan resmi Sayembara Novel DKJ 2018, istilah “monofonik” justru digunakan sebagai kritik terhadap kualitas narasi. Mari kita perhatikan bagian Tinjauan Umum Naskah: “…alur yang terlalu mudah ditebak, penokohan yang terkesan monofonik dan generik.” Dalam catatan lain, salah satu karya bahkan disebut “dimaksudkan sebagai novel polifonik tetapi monofonik”—seolah-olah bentuk monofonik adalah bentuk kegagalan, bukan pilihan naratif. Dalam lanskap penjurian semacam ini, monofoni tak diberi tempat sebagai kemungkinan estetik yang sah, tetapi diposisikan sebagai bentuk regresi atau keterbatasan teknis.
Pola ini menunjukkan bahwa bias polifoni telah menjelma menjadi semacam selera dominan, bukan sekadar kerangka apresiasi alternatif. Jangankan menjadi medan eksperimentasi naratif yang terbuka, polifoni kini tampil sebagai dogma evaluatif, yaitu yang tidak plural, tidak layak. Maka kritik atas narasi tunggal bukan lagi soal etika representasi, tetapi telah merambah ke penghakiman estetik. Dalam konteks ini, pembelaan terhadap bentuk monofonik bukanlah nostalgia terhadap masa lalu, melainkan pembelaan terhadap keragaman bentuk yang justru kini terancam oleh pemonopolian pluralitas itu sendiri.
Menariknya, pandangan seperti ini bukan berdiri sendiri. Ia merayap, menular ke dalam berbagai bentuk lain yang lebih tersirat—dalam ulasan, pengantar, hingga keputusan penerbitan. Ketika seorang penulis ditolak karena naskahnya dianggap “terlalu monofonik,” atau ketika pengantar antologi menyebut narasi yang plural sebagai lebih kompleks dan lebih unggul, maka kita tidak lagi berhadapan dengan opini Zen sebagai individu, tetapi dengan sebuah bias kolektif yang telah merembes ke dalam tubuh sastra kontemporer. Dalam konteks seperti inilah kritik terhadap polifoni bukanlah penolakan terhadap keberagaman suara, melainkan ajakan untuk memulihkan nilai pada bentuk-bentuk yang justru memilih kedalaman daripada keramaian.
Ada perbedaan mendasar antara kebebasan tokoh dan kebebasan pembaca. Seorang pengarang boleh menciptakan tokoh yang tidak sepenuhnya merdeka, tetapi justru dari keterkungkungan itulah lahir pengalaman estetis yang kuat. Kafka, dalam surat-suratnya, menulis bahwa ia menulis karena “tak ada jalan lain untuk menjaga kewarasan.” Maka monofoni Kafka bukan pilihan estetik kosong. Ia adalah pengakuan bahwa absurditas dunia hanya bisa dirasakan dalam isolasi batin Joseph K.
Yang lebih ironis, banyak yang mengaku membela pluralitas justru menciptakan hierarki baru. Mereka ingin semua karya tunduk pada satu resep polifoni. Padahal, bila kita konsekuen dengan relativisme, tidak ada bentuk yang bisa mendominasi bentuk lain. Itulah paradoks kritik sastra mutakhir: memperjuangkan kebebasan dengan cara memaksa.
Saya percaya bahwa sastra Indonesia tidak perlu takut mengakui monofoni. Tidak perlu minder hanya karena pengarang memilih satu narator yang kuat. Karena justru dalam konsistensi itu kadang lahir pengalaman paling jujur. Lihat Pramoedya. Bumi Manusia sepenuhnya bercerita dari orbit Minke. Semua tokoh lain hanya memantulkan perjalanan kesadarannya. Tapi apakah itu membuatnya karya kecil? Sebaliknya, itulah yang membuatnya epik yang tak tergantikan.
Eka Kurniawan pun tidak malu menempatkan narator mahatahu dalam Cantik itu Luka. Narasi yang ironis dan omnipresent itu bukan kelemahan. Ia bagian dari strategi retoris untuk mengolok-olok tragedi kolonial. Sementara itu, Saman menemukan energinya dalam keberanian Ayu Utami mengiris tabu. Keberanian itu jauh lebih penting daripada debat apakah novel itu polifoni atau tidak.
Di dunia, di mana kritik sastra semakin dipengaruhi tren media sosial, kita harus berhati-hati pada simplifikasi. Dan sastra butuh pembacaan yang lebih lambat, lebih sabar, lebih rendah hati. Saya ingin menegaskan satu hal sebelum menutup, bahwa polifoni bukanlah puncak. Monofoni bukan dasar. Keduanya hanyalah pilihan. Yang membedakan karya besar dengan karya remeh bukan label bentuk, tapi keberanian pengarang menulis dari ruang batin yang paling gelap dan paling jujur.
Karena itu, dalam diskusi sastra apa pun, mari kita curiga pada kalimat yang terdengar terlalu mutlak. “Novel yang bagus harus polifonik atau monofonik.” Baiklah, saya memilih percaya bahwa novel yang bagus hanya butuh satu syarat—ia ditulis dengan kesungguhan. Selebihnya, biarlah bentuk tumbuh sesuai kebutuhan cerita.
Ketika kita mencoba memaksakan polifoni atas semua prosa, kita sesungguhnya hanya sedang menciptakan dogma baru. Dogma yang tak kalah membekukan dibanding dogma moral yang dulu kita perangi bersama. Karena setiap karya—monofonik, polifonik, multivokal—selalu membawa potensinya sendiri. Kadang satu suara yang konsisten lebih membekas daripada seribu suara yang pura-pura bebas.
Teori Bakhtin tentang polifoni memang memperkaya pemahaman kita terhadap struktur naratif. Ia memberi alat untuk membaca novel bukan sekadar sebagai kisah, tapi sebagai arena benturan kesadaran. Namun justru di sanalah masalahnya bermula. Ketika konsep analitis itu berubah menjadi ukuran evaluatif. Dalam lanskap kritik mutakhir—baik di Barat maupun Indonesia—polifoni kerap naik pangkat sebagai tolok ukur mutlak “kemajuan estetika”. Yang tidak plural dianggap regresif. Yang terpusat dianggap ideologis.
Tapi benarkah demikian? Bukankah Orwell mengendalikan 1984 dengan narasi tunggal justru untuk menyampaikan horor totalitarianisme secara efektif? Bukankah Chekhov mencapai ketegangan psikologis justru karena keheningan dan keterbatasan suara dalam ceritanya? Bukankah Hemingway memusatkan perspektif untuk menciptakan isolasi eksistensial yang tajam? Maka, bila kita mengamini bahwa setiap bentuk mengandung potensi uniknya sendiri, hierarki bentuk hanya akan mengaburkan keanekaragaman itu sendiri.
Esai ini tidak bermaksud menurunkan derajat polifoni, tetapi menantang anggapan bahwa hanya narasi plural yang berhak disebut modern, progresif, atau “baik”. Barangkali yang perlu kita pulihkan adalah kepercayaan bahwa nilai sastra tidak ditentukan oleh jumlah suara, melainkan oleh integritas pengucapan. Sebab baik dalam diam satu suara maupun dalam riuh percakapan, sastra tetaplah cara manusia menyatakan dirinya di hadapan dunia. Sastra, seperti hidup, tidak bisa diseragamkan. Maka mari kita rayakan kebebasan itu, tanpa takut mengakui monofoni yang jujur. Sebab pada akhirnya, yang tinggal hanya keberanian mendengarkan satu suara yang paling sunyi, yaitu suara hati pengarang sendiri.
Bakhtin, Mikhail. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Translated by Caryl Emerson, University of Minnesota Press, 1984.
Chekhov, Anton. Ward No. 6 and Other Stories. Translated by Constance Garnett, Dover Publications, 1997.
Dostoevsky, Fyodor. The Brothers Karamazov. Translated by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, Farrar, Straus and Giroux, 1990.
Dewan Kesenian Jakarta. “Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2018.” DKJ.or.id, 2 Mar. 2019, www.dkj.or.id/pertanggungjawaban-dewan-juri-sayembara-novel-dewan-kesenian-jakarta-2018/. Accessed 15 July 2025.
Hemingway, Ernest. Death in the Afternoon. Scribner, 1932.
———. The Old Man and the Sea. Scribner, 1952.
Joyce, James. Ulysses. Vintage, 1990.
Kafka, Franz. “Each of Us Has His Own Way of Emerging from the Underworld…”
WritingAnalytics.co, www.writinganalytics.co/quotes/655/. Accessed 15 July 2025.
Kurniawan, Eka. Cantik Itu Luka. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
McHale, Brian. Postmodernist Fiction. Methuen, 1987.
Orwell, George. 1984. Harvill Secker, 1949.
Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia. Hasta Mitra, 1980.
Sahal, Ahmad. “Pengantar.” Cerpen Pilihan Kompas Derabat 1999, edited by Redaksi Kompas,
Kompas, 1999, pp. vii–xiv.
Suwondo. Membaca Olenka dalam Perspektif Bakhtin. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2022.
Tolstoy, Leo. Anna Karenina. Translated by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky, Viking Penguin, 2000.
Utami, Ayu. Saman. Kepustakaan Populer Gramedia, 1998.
RS, Zen. “Novel jadi jelek kalau pengarangnya terkesan pamer pengetahuan. Novel yang bagus justru membiarkan tokohnya hidup sendiri, berbicara secara alami bukan dikendalikan pengarang.” Instagram, Dewan Kesenian Jakarta, 25 Mar. 2025, www.instagram.com/jakartscouncil/.

Ranang Aji SP
Ranang Aji SP adalah penulis fiksi dan nonfiksi kelahiran Klaten dan tinggal sementara di Magelang Jawa Tengah. Beberapa cerpennya diterbitkan oleh pelbagai media massa seperti Kompas dan Jawa Pos. Salah satu cerpennya berjudul "Malam Pertobatan" difilmkan oleh Falcon dan tayang perdana di festival film dunia Jakarta World Cinema 21-28 September 2024. Dua cerpennya diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dibukukan dalam antologi bersama oleh Dalang Publishing LLC USA. Ranang Aji SP juga menciptakan teknik "Fraksionasi" dalam fiksi. Sebuah teknik memecah kesatuan cerita menjadi fragmen-fragmen namun tetap terhubung dalam satu karakter. Contoh karya dengan teknik ini adalah "Catatan Seorang Veteran" (Koran Tempo, 2019), "Dendam yang Selesai sejak 1965" (Majalah Sastra Karas, 2023), dan "Sepuluh Kejadian" (Kompas, 2024). Ranang Aji SP juga menjadi salah satu nomine dalam Sayembara Kritik Sastra Badan Bahasa Kemendikbud 2020 dengan judul esai "Sepotong Senja untuk Pacarku: Antara Modernisme dan Pascamodernisme Jejak dan Terpengaruhannya. Buku terbarunya: Sejarah Cerita Pendek dan Perkembangannya (2025).