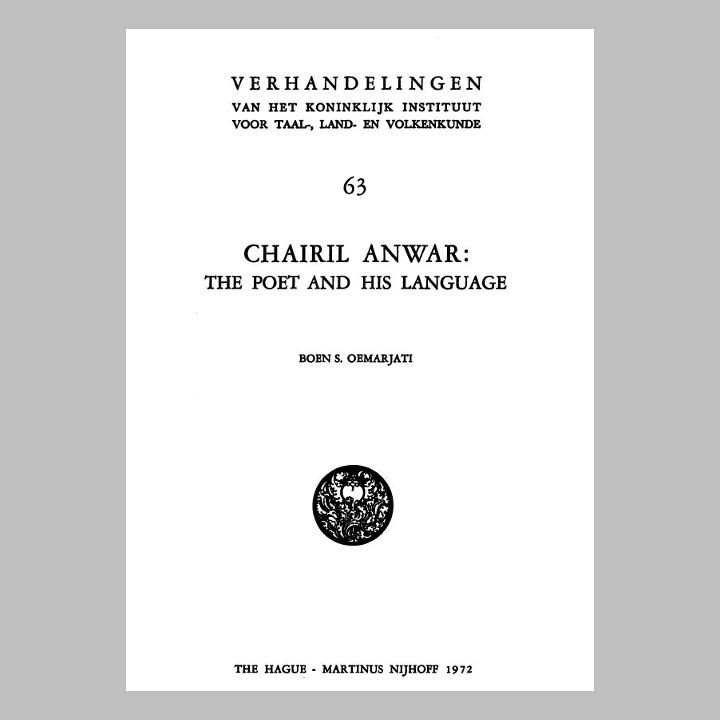Sebagai seseorang yang mengikuti perpuisian hari ini, saya sering dibayangi pertanyaan: apakah yang membuat sajak-sajak Chairil Anwar terkesan selalu ‘baru’ setiap kali dibaca? Apakah yang menjadikan puisinya seakan ditulis persis kemarin sore dan kita dari generasi kiwari tak pernah jemu menelisik karya-karyanya?
Sungguh menarik mencermati bahwa selama lebih dari tujuh puluh tahun semenjak penyair ini berpulang, kalangan sastra Indonesia masih membicarakan dan mendedahkan puisi-puisinya dalam berbagai ulasan. Saya kira catatan yang ditulis HB Jassin, Pamusuk Eneste, Arief Budiman, sampai yang terkini biografi kreatif besutan Hasan Aspahani—untuk menyebut beberapa referensi saja—merupakan pijakan penting untuk mengenal sosok Chairil. Kita bisa melihat betapa Chairil dapat ‘dibaca’ dengan beragam pendekatan, yakni konteks kekaryaan, lingkaran pergaulan kepenyairan, hingga historisitas hidupnya. Kita pun tidak lagi kesulitan melacak genealogi persajakan Chairil: siapa pendahulunya, generasi apa yang melahirkannya, dan hibriditas budaya macam apa yang memengaruhi puisi-puisinya.
Namun, semua pembacaan sejarah, sosiologis dan kesastraan itu, bagi saya, belum memberikan petunjuk jawaban atas pertanyaan awal kita. Asumsi saya: kesan kebaruan itu tidak muncul dari impresi tematik saja. Pasti ada sesuatu dari sisi kebahasaan, dari sisi bentuk, dari sisi cara dia mendayagunakan kata. Sudah tentu pertanyaan ini menggiring kita ke wilayah linguistik dan khususnya morfologi—suatu ranah keilmuan yang harus diakui justru dihindari oleh para penyair sebab seolah ada sekat bahwa penyair sebagai kreator tidak perlu bergelut dengan aspek-aspek teknis seperti ini. Tak ada perlunya pun untuk membaca kajian-kajian itu, yang terasa kering dan akademis, kurang merangsang imajinasi, dan dengan begitulah pembacaan dekat atas aspek kebahasaan senantiasa akan menjadi arsip.
Secara perlahan saya membaca disertasi Boen S. Oemarjati yang ditulis dalam bimbingan A. Teeuw, Chairil Anwar: The Poet and His Languange (1972). Ini adalah pembacaan intens atas tiga belas puisi Chairil, yakni Diponegoro, Kupu Malam dan Biniku, Kenangan, Hampa, Dimesjid, 1943, Isa, Kepada Pelukis Affandi, Sendja di Pelabuhan Kecil, Puntjak, Aku Berkisar Antara Mereka, Yang Terhempas dan Yang Putus, serta Derai-derai Cemara.
Menurut Boen, analisis linguistik yang dia lakukan tidak ditujukan untuk melihat satu per satu puisi ini, tetapi sedapat mungkin mencermatinya sebagai keseluruhan guna melihat sampai sejauh mana si penyair telah mendayagunakan perangkat puitikanya.
Yang menarik dari disertasi ini adalah bahwa selain menganalisis morfologi, struktur, dan perbandingan penggunaan kebahasaan dalam puisi-puisi Chairil dengan Bahasa Indonesia era 1940-an, Boen juga menyandingkan sajak asli dan karya terjemahan Burton Raffel, The Complete Poetry and Prose of Chairil Anwar (1970). Ini merupakan sebuah tinjauan penting karena puisi secara konkret dihadapkan dengan persoalan linguistik terapan, semisal bagaimana kita bisa merunut makna dari diksi yang serba ringkas, terbatas, kadang ambigu dan tidak jelas, kemudian mengalih-bahasakannya. Termasuk dalam cakupan analisis ini adalah sejauh mana kekeliruan interpretasi bisa diminimalisir dan karenanya analisis struktur bahasa, di samping pendalaman soal diksi-metafor, diperlukan sebagai pijakan dalam menentukan logika kreatif sang penyair agar hasil terjemahan cukup mendekati arti di wilayah bahasa-bahasa tujuannya.
Terlahir dari Bahasa serba Tertatih
Sebelum mengulas pembaruan linguistik yang dilakukan Chairil, agaknya kita perlu menyinggung konteks perkembangan Bahasa Indonesia dalam kurun 1930-1950an. Kita tidak menitikberatkan pada perubahan-perubahan ejaan, melainkan sisi konteks perannya semasa kolonial dan pendudukan Jepang.
Meskipun Sumpah Pemuda 1928 mengukuhkan Bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan, perlu diakui bahwa secara perangkat bahasa ini masihlah jauh dari sempurna. Namun, momentum ini boleh dikata mempercepat persebarannya: digunakan begitu masif lewat terbitan-terbitan media dan perbukuan Balai Pustaka dengan generasi Pujangga Baru sebagai pendorong perluasan kosabahasanya sejak 1933. Namun, itu adalah bahasa yang tertatih-tatih, yang berusaha memperbarui dirinya dari berabad-abad pemakaian lingua franca Melayu, dan dalam prosesnya terus-menerus ditantang justru oleh para penggunanya sendiri: antara kaidah gramatika Balai Pustaka dan keluwesan bacaan liar, termasuk posisinya di tengah keberagaman bahasa daerah yang berakar di wilayah geografis dan budaya Nusantara—seluruhnya seakan membuat ‘persatuan’ bahasa Indonesia jadi sulit diwujudkan.
Kalau ditengarai apa yang kemudian menumbuhkan bahasa ini, sebabnya tidak lain ialah jiwa zaman dan semangat kebangsaan yang kala itu merasuk ke setiap sanubari orang Indonesia. Seiring waktu, bahkan di masa kolonial dengan bahasa Belanda sebagai puncak stratanya, masyarakat mulai mengadaptasi bahasa Indonesia yang muda ini. Terseok-seok secara leksikal dan gramatika, kadang bercampur baur dengan bahasa daerah, para penulis dan jurnalis berusaha melakukan inovasi-inovasi—sebuah bekal kreatif yang kelak masih terlacak sampai puluhan tahun kemudian.
Semasa Jepang berkuasa, kaum terdidik dan awam kian intens menggunakan bahasa Indonesia. Persoalannya tak lain karena pelarangan bahasa Belanda serta sensor atas kritik politik dan kebudayaan. Namun, bahasa Indonesia tidak mengalami pembatasan, malah dibolehkan jadi medium ekspresi diri, kendati tentu pemakaiannya dibayang-bayangi polisi militer Kempeitai yang selalu awas menelisik benih-benih perlawanan di akar rumput. Walau begitu, masa-masa pendudukan Jepang juga perlu dilihat sebagai momentum persemaian bahasa Indonesia, dan mesti dicatat bahwa puisi pertama Chairil berjudul Nisan, ditulis pada tahun 1942, periode puncak kekuasaan Jepang di Nusantara dan menandakan kelahiran Chairil dalam dunia kesusastraan Indonesia.
Pembatasan kegiatan budaya dan aktivisme politik memicu kaum cendekia muda dalam mendayagunakan bahasa Indonesia sebagai medium tulis-menulis. Secara sadar atau tidak, merekalah yang secara organik berupaya memperbarui bahasa, termasuk di antaranya Idrus sang prosais yang menjadikan karyanya sebagai medium kritik nan merdeka. Bilamana semasa Balai Pustaka hampir semua prosa berkisah seputar adat dan modernitas, antara ketimuran dan budaya Barat, serta pertentangan antargenerasi, pengarang era 1940-an menitikberatkan karyanya sebagai pernyataan individu dalam situasi zaman penuh gejolak. Mereka pun mengelaborasi bentuk baru simbolisme demi berkelit dari sensor Jepang yang kemudian menjadi tipikal kesusastraan kala itu, sebagaimana ditunjukan El Hakim lewat Dewi Reni, Usmar Ismail dengan Tjitra dan Chairil Anwar pada puisi Diponegoro (Boen Oemarjati, 1972).
Boen Oemarjati menggarisbawahi bahwa di masa-masa ini Idrus mengenalkan apa yang disebutnya kesederhanaan baru, gaya penulisan prosa dengan gramatika minimum sebagai antitesa elaborasi bentuk à la Balai Pustaka yang baginya terlalu berlebihan. Idrus tidak menggarap bahasa dengan gramatika tradisional yang menyertakan kelengkapan subjek-verba-objek, ataupun penambahan serapan bahasa daerah dan asing khas pengarang terdahulu. Malahan, dia memakai bahasa Indonesia berkalimat ringkas dengan penekanan pada kata dasar tanpa imbuhan.
Kesederhanaan ini, tak pelak berpengaruh pula pada ekonomi bahasa dalam puisi, yang ditunjukkan Chairil lewat puisi-puisinya.
HB Jassin (Chairil Anwar: Pelopor Angkatan ’45, 1959) menuturkan bahwa Chairil bukanlah seorang yang lancar menulis sajak. Antara 1942 hingga 1949 dia hanya menulis 70 sajak asli, 4 sajak saduran, 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Jadi bila dijumlah, seluruhnya tak lebih dari 94 tulisan. Menurut Boen, ini menunjukan betapa pun Chairil sanggup menggunakan bahasa dengan merdeka, dia sebenarnya memandang bahasa Indonesia sebagai medium ungkap yang berbahaya justru karena kemudahannya membangun sajak[1]. Konsekuensinya, sebagaimana dituangkan dalam Hoppla! (1945), tebersit niatan Chairil untuk intens menggali kata, termasuk soal kata tidak mengabdi pada dua majikan—semacam kredo kepenyairan yang membimbingnya melahirkan puisi-puisinya.
Modifikasi dan Ambiguitas
Secara normatif, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari tiga elemen, yaitu Subjek/Pelaku – Predikat/Verba – Objek/Noun, atau sekurang-kurangnya dua elemen tanpa menyertakan Objek.
Boen Oemarjati mengidentifikasi bahwa Chairil melakukan modifikasi atas keduanya, dengan variasi penggunaan verba intrasitif (Vt) yang unik.
Variasi pertama dilakukan dengan skema ‘struktur pelaku terarah / agent-directed construction yang menyertakan prefiks me– penyusun verba intrasitif (meVt). Bila kontruksi normatif dicontohkan dengan Ali memukul Amat, maka modifikasi yang dilakukan Chairil justru dengan meniadakan elemen pelaku, mempertahankan meVt, dan menambah nomina. Perhatikan contoh larik pada puisi berjudul Kesabaran: Menunggu reda jang mesti tiba (berpola meVt-N1-N2), yang sama sekali tidak menyertakan pelaku dan mengesankan kuasan kata yang lebih lugas, meskipun secara tersirat kita masih dapat merujuk keberadaan pelaku sebagai sosok aku.
Pola meVt-N1-N2 tanpa ini sesungguhnya tidak dimungkinkan dalam Bahasa Indonesia umum. Meskipun begitu, Chairil tetap menggunakan pola ini dalam puisi-puisi lain, misalnya: Menembus sudah tjaja / Udara tebal kabut / Katja hitam lumut / Petjah pentjar sekarang (puisi Adjakan).
Ketidaksempurnaan bentuk ini kemudian membentuk suatu enigma yang membuat kata dan struktur itu tidak dapat tergantikan. Misalnya, jika gramatika kalimat lengkap memungkinkan kita mengubahnya menjadi susunan kalimat pasif, maka tidak demikian dengan baris puisi Chairil, umpamanya saja untuk baris yang disebutkan sebelumnya. Atau perhatikan baris:
aku mengembara serupa Ahasveros (puisi Tak Sepadan)
atau
kelam dan angin lalu mempesiang diriku (puisi Yang Terhempas dan Yang Putus)
keduanya ditulis dengan pola S-meVt-N, struktur yang nyaris sempurna, tetapi ternyata tidak bisa dipasifkan sebab N bukan terkategori objek atau penderita/patient.
Kalau pun ada yang dapat dipasifkan, semisal larik puisi Sendja di Pelabuhan Ketjil: gerimis mempercepat kelam menjadi kelam dipercepat gerimis, kita jelas telah kehilangan kekuatan nuansa. Artinya, Chairil secara sadar menggunakan prefiks me+verba transitif untuk menghasilkan efek fonetik sekaligus efek puitik. Begitu pula dengan pendekatan kesederhanan baru à la Idrus: diksi kata dasar yang mewakili aksi dia benturkan dengan rupa benda-benda sehingga semuanya justru membentuk metafora yang tegas, sama sekali tanpa bunga-bunga kiasan.
Selain penggunaan meVt secara unik, Chairil juga berkali-kali memakai pola imbuhan ke-an yang lazim menyertai adjektiva dan mengubahnya menjadi kategori nomina.
Menariknya, di beberapa puisi, bilamana diterjemahkan kepada bahasa Inggris, dia kemudian dapat menjelma verba intrasitif, sesuatu yang menunjukkan keambiguan pilihan kata, dengan pemisalan sebagai berikut:
/satu tak kehilangan lain di dalamnya./
‘the one won’t lose the other in it.’
(puisi Taman)
Ulang-alik antara adjektiva dan nomina ini juga terjadi dalam konteks sebaliknya. Seringkali Chairil malah membangun unsur sifat yang tersusun dari serangkaian kata benda dan membentuk nuansa metaforik, semisal di sunyi malam ganggang menari (puisi Cinta Buat Dien Tamaela). Ini menunjukan betapa Chairil, dengan perangkat bahasa dan puitika yang dipunya, begitu ingin melepaskan diri dari pengertian dan penggunaan bahasa pada umumnya.
Variasi lainnya menyangkut gramatika dua elemen, yakni Subjek dan Predikat. Dalam kasus Chairil, pola ini dapat saja berbentuk Nomina1 dan Nomina2, semisal ungkapan Aku saksi! Pola ini sering ditemukan; karena kecenderungan ekonomi diksi, lagi-lagi Chairil bersikeras menggunakan kata dasar yang dapat mengesankannya sebagai adjektiva, verba, atau nomina sekaligus, sebagaimana tampak dalam ungkapan barusan.
Perhatikan larik berikut:
Punah diatas menghamba
Binasa diatas ditinda
(puisi Diponegoro)
Ini adalah contoh cara Chairil membiaskan kategori kata yang semula lekat dengan pengertian sehari-hari: verba atau adjektiva menjadi nomina dan pada saat yang sama dapat dilihat tetap sebagai verba atau adjektiva itu sendiri. Pun begitu dengan kategori subordinat: mana yang termasuk penjelas atau penguatan di antara kedua larik tidaklah terlalu kentara.
Bagi pembaca puisi, ketidakjelasan ini memunculkan ambiguitas yang berpeluang memperkaya makna. Ambiguitas puisi Chairil juga dibangun dengan kesadaran lisensia poetika yang berseberangan dengan Bahasa Indonesia sehari-hari, semisal caranya menyisipkan kata ini dan itu di luar konteks kelaziman berbahasa maupun peniadaan kata hubung yang.
Namun, penulisan seperti ini jelas menjadi masalah pelik bagi penerjemah yang mesti jeli memerhatikan konteks keseluruhan puisi, termasuk kecenderungan penggunaan pola gramatika persajakan Chairil. Kekeliruan memilih kategori bagi sebuah diksi jelas berpotensi menghasilkan terjemahan yang jauh keliru.
Selain untuk menunjukkan letak kekhasan pendayagunaan bahasa, disertasi Boen juga mengajak pembacanya untuk melakukan analisis gramatikal, konteks dan historis terhadap kehadiran puisi-puisi Chairil sebagai bekal penerjemahan. Menurutnya, kecenderungan Chairil dalam membangun ambiguitas lewat pemenggalan diksi, modifikasi struktur kalimat, hingga faktor-faktor leksikal semisal homonimitas kata, masih mungkin disiasati dengan memetakan struktur baris sajak serta pendalaman informasi biografis, situasional, hingga pendalaman kesan citraan—kendati tentu sangat sulit menghasilkan terjemahan puisi dengan nuansa dan makna sebegitu persis bahasa asalinya.
Perlu dicatat juga bahwa betapa pun Chairil seakan leluasa melakukan modifikasi, dia sebenarnya tidak melampaui struktur berbahasa. Jika ditilik dari caranya melakukan inversi gramatikal, yang dalam Bahasa Indonesia umumnya meliputi subjek + verba, Chairil juga memenuhi kaidah ini dengan seringkali membentuk morfologi prefiks me-Vt (walau secara semantik kemudian menimbulkan pengertian berbeda). Di beberapa puisi terakhirnya, Chairil bahkan tidak lagi menggunakan meVt ini, tetapi secara langsung memangkasnya dengan mempertahankan kata dasarnya saja, seperti dalam larik: terkumpul di halte, kami tunggu trem dari kota (puisi Aku Berkisar Antara Mereka).
Sementara itu, karakteristik bahasa Indonesia masih memberikan ruang bagi patahan-patahan kalimat tanpa penjelas anak dan induk kalimat (subordinate dan coordination), apalagi jika tidak dibubuhkan kata penghubung di antaranya. Nalar puitik mengelaborasinya hingga di beberapa sisi membuat frasa-frasa yang ditulis Chairil dapat terasa terikat sekaligus bebas dari hubungan sebab-akibat peristiwa, sebagaimana contoh:
Ada djuga kelepak elang
menyinggung muram,
desir hari lari berenang
menemu budjuk pangkal akanan
Bait ini mengesankan hubungan subordinat dan koordinatif antara larik atau kalimat seperti membias. Ketiadaan kata hubung maupun keterangan penjelas membuat kita tidak menemukan rangkaian waktu mana yang berlangsung lebih dahulu—padahal mengidentifikasi waktu merupakan salah satu elemen penting dalam penerjemahan, terkhusus ke Bahasa Inggris dengan ukuran-ukuran waktu yang ketat itu. Ini sama sekali bukan kesalahan Chairil. Sebagaimana kita tahu, bahasa Indonesia semasa puisi Sendja di Pelabuhan Ketjil ini ditulis masihlah terus berinovasi; banyak kaidah itu belum sepenuhnya terbakukan.
Saya kira inilah keuntungan Chairil yang hidup dalam masa ‘pertumbuhan’ bahasa Indonesia. Berbekal pijakan berbahasa era Balai Pustaka dan Pujangga Baru (yang hanya sepuluh tahun terpaut dengan periode kepenyairannya) sekaligus keberanian untuk terus-menerus menggoyang penggunaan bahasa yang dikemukakan pengarang muda di masanya, Chairil dapat melakukan pembaruan-pembaruan, sesuatu yang ternyata membuat puisinya tampak selalu segar di tengah—barangkali—kejemuan cara kita berbahasa hari ini yang selalu diarahkan untuk serba ‘baik dan benar’ itu.
Pembacaan dekat yang dilakukan Boen Oemarjati ibarat membuka cakrawala kita bahwa Chairil dengan caranya sendiri telah membangun sebuah titian: antara yang tampak (yakni aspek kebahasaan) dengan yang tidak tampak (semangat pendayagunaan kreatifnya), antara gagasan dan medium ungkapnya, bahkan antara abstraksi dan objek-objek konkret yang menjadi tema sajak. Puisinya seakan terlahir dari lambaian tangan serba tak terduga, sekalipun sebenarnya mereka disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sadar atas kemungkinan-kemungkinan lain dalam berbahasa.
Ambiguitas yang dikemukakannya juga merupakan kerja sadar seperti yang muncul dalam perpuisian Jawa Klasik melalui keberanian mereduksi diksi selaras pilihan bentuk persajakan. Dengan begitu kebaruan kebahasaan yang dilakukan Chairil ini bukanlah dilandasi oleh suatu kecerdasan intuitif belaka, melainkan dirangsang oleh pencarian—dengan maksud yang terukur bahwa pesan linguistik yang tersaji bukan lagi untuk sekadar komunikasi praktis kreator-pembaca maupun tujuan intelektual, melainkan untuk memperkaya penyataan-pernyataan sang penyair.*
[1] Bahasa lndonesia adalah bahasa jang berbahaja sekali; ia mudah sekali menjadjak.’ (pernyataan lisan oleh R. Nieuwenhuys, dikutip oleh Boen Oemarjati, 1972)

Ni Made Purnama Sari
Ni Made Purnama Sari menamatkan studi antropologi di Universitas Udayana dan Magister Manajemen Pembangunan Sosial di FISIP Universitas Indonesia. Bukunya yang telah terbit adalah kumpulan puisi Bali Borneo (Penerbit HalamanMoeka, 2014), kumpulan puisi Kawitan (Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2016), novel Kalamata (Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), dan novel Yang Menari dalam Bayangan Inang Mati (Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2022). Karya puisinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Penghargaan yang telah diraihnya antara lain Buku Puisi Pilihan Anugerah Hari Puisi Indonesia dari Yayasan Sagang dan Indopos (2014), Pemenang Kedua Sayembara Manuskrip Buku Puisi Dewan Kesenian Jakarta (2015), Lima Besar Anugerah Kusala Sastra Khatulistiwa (2016), Nominasi Penghargaan Sastra Badan Bahasa (2023), dan Penghargaan Bali Jani Nugraha dari Pemerintah Provinsi Bali (2024). Kini mukim di Yogyakarta dan sehari-hari mengelola program di Bentara Budaya. Kadang-kadang melakukan pekerjaan sampingan penulisan dan penyelarasan buku maupun terlibat dalam kegiatan seni di berbagai kesempatan, baik sebagai narasumber, kurator, juri, moderator diskusi, atau sedikit mengisi pembacaan puisi.