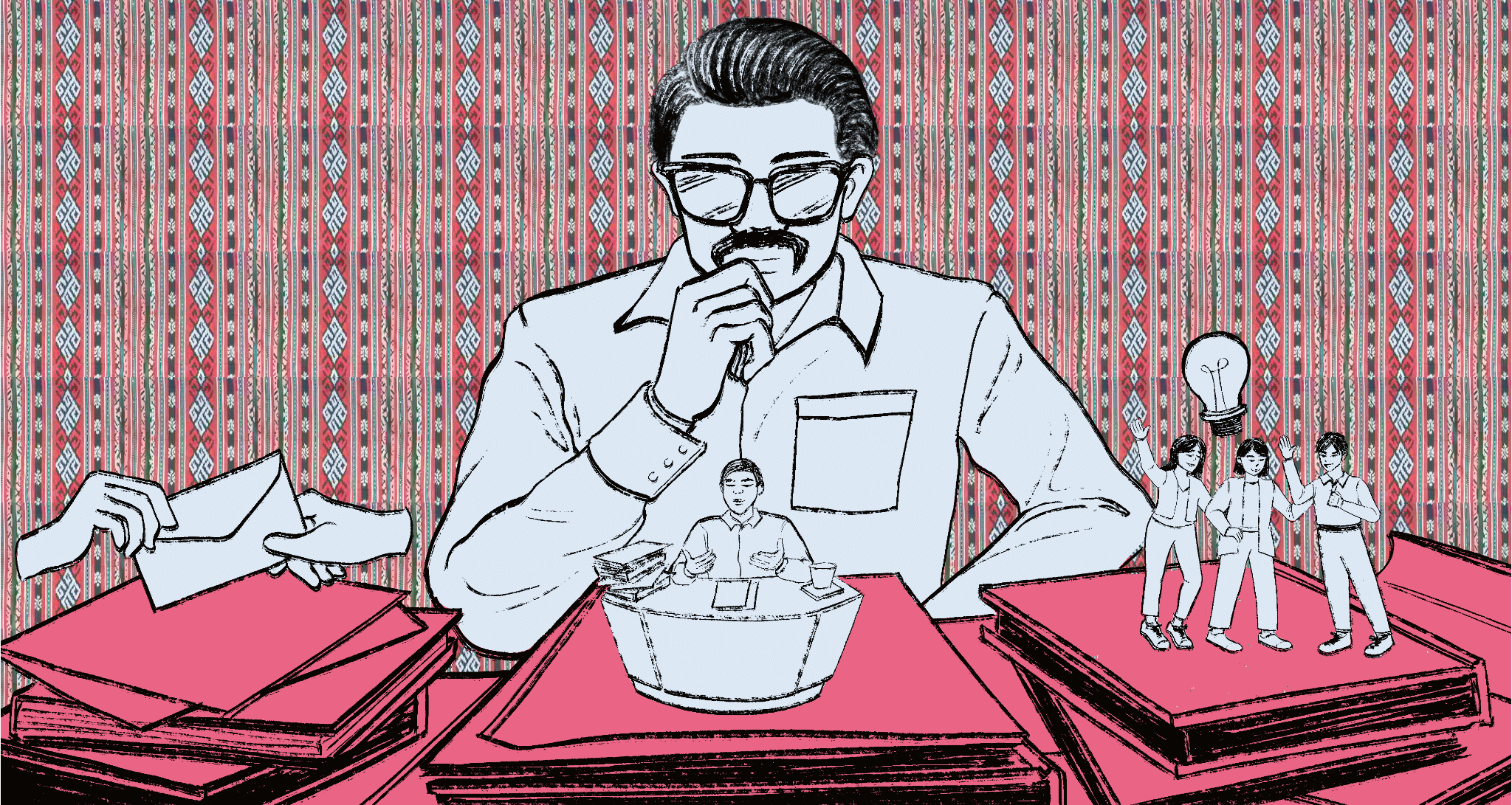Bayangkan seorang filsuf membongkar-bongkar keranda si mati. Ralph Waldo Emerson seharian menunggu hujan berhenti. Hatinya gelisah. Biarpun setelah membuka buku dan membaca surat pujukan Plutarch kepada istrinya (yang murung akibat kematian anak perempuan mereka), Emerson tidak merasa tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Ellen, ia mendengar suara mendiang istri pertamanya memanggil dari dalam kubur. Apabila hujan akhirnya reda, dan bulan perlahan-lahan muncul dari balik ranting, Emerson langsung memasukkan martil, beliung, penyodok, dan pencapak besi ke dalam karung goni lalu memacu langkah dari Boston ke pusara Ellen di Roxbury.
Emerson menikahi Ellen Louisa Tucker pada 1829 ketika Ellen berusia 18 tahun dan Emerson berusia 26 tahun. Ellen ingin menjadi penyair, sementara Emerson pendeta. Ketika Emerson mengenal istri pertamanya itu, Ellen sudah mengidap penyakit batuk kering. Kematian menghantui hubungan mereka dari semula. Dalam suratnya kepada Emerson, Ellen menulis, “Adapun tangan maut mampu menghancurkan seseorang, ada orang hanya merinding atau bahagia menghadapinya.”
Kenyataan romantik seperti ini tidak akan hadir dalam dunia Bukan Pasar Malam karangan Pramoedya Ananta Toer. Di situ kematian bukan sesuatu yang ngeri maupun bahagia; kematian adalah waktu. Bak kata seorang tokoh Tionghoa dalam novel itu: “Ya, mengapa hidup ini begitu cepat?” Waktu melahirkan kita; waktu menghubungkan kita; waktu juga akhirnya yang memisahkan kita.” Justru dari situ lahir ucapan paling penting dalam Bukan Pasar Malam:
Seorang. Seorang. Seorang. Dan seorang lagi lahir. Seorang lagi. Seorang lagi. Mengapa orang ini tak ramai-ramai lahir dan ramai-ramai mati? Aku ingin dunia ini Seperti Pasarmalam. (hlm. 95 )
Kedukaan ini hanya mungkin lahir dari jiwa seorang tua yang telah dihimpit waktu. Namun, bagaimana seorang kanak-kanak melihat kematian; bagaimana seorang kanak-kanak menanggapi waktu? Menurut E.M. Cioran, apabila membayangkan hari ia dilahirkan, “hatinya tersiksa dan merana.” Virginia Woolf mempunyai memori indah mengenai hari ketika ia dilahirkan di St. Ives (latar yang kemudian menjadi inspirasi kepada novel To the Lighthouse), telentang di dalam bilik asuhan, sambil mendengar ombak mengempas pikirannya: “Terlalu indah dan mustahil bagaimana saya bisa berada di sini; merasai kegembiraan yang tidak terhingga.” Dalam cerpen Shahnon Ahmad “Lagu Kitkitkit” seorang kanak-kanak bernama Montel melonjak-lonjak riang, “seriang maut” saat tetamu datang menziarahi arwah si ibu. Kalau dalam novel klasik Shahnon Ranjau Sepanjang Jalan, alam bersama maut hadir menewaskan Jeha dan Lahuma; sementara dalam cerpen itu maut menjadi teman Montel yang belum mengerti apa-apa mengenai hidup dan mati. Tapi sejauh manakah kita memahami arti hidup dan mati? Barangkali selagi adanya langit dan bumi, sastrawan akan terus-menerus menulis dan menghadapi persoalan tanpa jawaban ini.
Buat generasi pelipur lara terawal, persoalan hidup dan mati adalah lebih mudah karena segalanya sudah diatur dan ditentukan oleh alam dan dewa-dewa kayangan. Hanya apabila manusia mulai melihat dirinya sebagai subjek yang terpisah dari dunia, maka ia mulai melihat ke dalam diri; ia mulai mendengar suara yang berbisik dan pikiran yang menggila (bak kata Harold Bloom, ia terlampau mendengar suara hatinya); ia menjadi Macbeth yang dihantui oleh bayang-bayangnya sendiri. Di rantau Nusantara, Munsyi Abdullah adalah pengarang terawal yang mencatat ketakutan menghadapi kematian dalam pengembaraannya di tengah laut dari Melaka ke Kelantan. Walaupun Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan bukan sebuah novel, kita melihat buat pertama kali realitas peperangan dan penderitaan rakyat jelata akibat perang saudara di kalangan kaum kerabat istana Kelantan. Abdullah mengutuk dan mempersoalkan mereka yang menyerahkan diri bulat-bulat kepada takdir dan kekuasaan. Ia menjadi titik permulaan kepada kemunculan novel sebagai medium tempat pengarang (dan pembaca) mulai mempersoalkan keberadaannya sebagai manusia di tengah dunia.
Sejarawan dan sarjana sastra akan mengatakan novel Malaysia dan Indonesia bermula dengan kemunculan mesin percetakan sekitar abad ke-17. Namun, pandangan ini sama sekali keliru. Malah A. Wahab Ali, dalam bukunya Kemunculan Novel dalam Sastra Moden: Satu Kajian Perbandingan, membuat kesilapan besar dengan menyatakan bahawa novel adalah “satu bentuk kesusasteraan moden di Eropah,” dan ia mengulangi dosa sejarawan Eropa seperti Ian Watt yang meletakkan novel Inggris abad ke-18 sebagai titik tolak. Bagaimana dengan karya agung Murasaki Shikibu Tales of Genji yang ditulis 600 tahun lebih awal daripada novel Daniel Defoe Robinson Crusoe? Bahkan di Eropa sendiri, novel Miguel de Cervantes Don Quixote, yang ditulis 100 tahun lebih awal, terasa lebih dekat dengan novel moden hari ini jika dibandingkan dengan Robinson Crusoe. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyandarkan pendapat pada sejarah kesusastraan untuk memahami hubungan di antara novel Malaysia dan Indonesia.
Ajip Rosidi dalam bukunya Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir? menyebut Munsyi Abdullah sebagai tokoh yang sedikit banyak mencorak perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Namun, selepas Abdullah, hubungan Indonesia dengan sastra di Semenanjung terputus. “Kita hampir buta, sampai kemana sudah perkembangan kesusastraan Melayu setelah Abdullah sekarang.” Ternyata apa yang Ajip katakan pada 1955 kekal relevan hingga hari ini. Kita bukan saja buta, kita bahkan tidak menyadari keberadaan masing-masing. Walaupun pengarang dan pembaca Malaysia dari dulu senantiasa merayakan karya sastra dari Indonesia, pengaruh itu terbatas kepada genre puisi. Kita tidak melihat pengaruh besar fiksi Indonesia kepada fiki Malaysia. Tidak ada seorang Iwan Simatupang atau seorang Putu Wijaya dalam sastra Malaysia. Seperti tidak ada seorang Shahnon Ahmad atau seorang Arena Wati dalam sastra Indonesia. Pada abad kedua puluh, novelis Malaysia berlomba-lomba untuk menghasilkan novel epik masyarakat; sementara novelis Indonesia lebih tertumpu pada budaya kedesaan dan hal-hal eksistensi kemanusiaan.
Hanya selepas 1998 , setelah jatuhnya Orde Baru, kita melihat novel Indonesia perlahan-lahan bangkit dan mengembangkan sayap meninggalkan Pulau Buru dan Dukuh Paruk. Perkembangan Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) selepas 2000 mencerminkan evolusi novel Indonesia yang semakin mendunia, semakin berani, dan semakin berkiblatkan personalitas dan suara hati novelis berbanding desakan dan kehendak nurani masyarakat. Sebelum 2000, tidak mungkin akan lahirnya novel seperti 24 Jam Bersama Gaspar, Semua Ikan di Langit, dan Semusim, dan Semusim Lagi. Jika kejatuhan Orde Baru membebaskan novel Indonesia, Era Reformasi setelah 1990-an di Malaysia menjadi titik tolak kepada kejatuhan novel epik dan berakhirnya dominasi dua tiang besar novel Malaysia yaitu Shahnon Ahmad dan A. Samad Said. Kehadiran S. Othman Kelantan, Arena Wati, Azizi Hj. Abdullah, dan Anwar Ridhwan tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mereka. Selepas Hujan Pagi dan Tunggul-tunggul Gerigis, belum ada novel epik penting yang lahir dalam sastra Malaysia. Oleh karena itu, jika kita hendak mencari titik pertemuan di antara novel Malaysia dan Indonesia dari segi silang budaya dan tradisi, maka kita tidak akan menemukannya. Kita perlu kembali kepada tujuan awal cerita (dan novel) ditulis, yaitu melengahkan waktu dan menunda kematian.
Tiada contoh lebih jelas daripada Hikayat Seribu Satu Malam; permulaan kepada segala permulaan; cerita kepada segala penceritaan. Atau dalam kata-kata Robert Irwin: “Sebuah cerita, adalah ibarat ombak, ia menelan cerita yang selanjutnya.” Selama seribu satu malam Shahrazad bercerita untuk menghalang dirinya daripada dibunuh oleh Sultan Shahriyar. Seperti serial drama opera sabun, cerita Shahrazad selalu tergantung; berarti malam esok Shahrazad akan bersenggama dulu dengan Sultan Shahriyar sebelum menyambung cerita. Justru, cerita bukan saja menangguhkan kematian, ia menjadi alasan untuk melanjutkan kemanisan asmara. Bentuk penceritaan ini mempunyai persamaan dengan karya klasik Giovanni Boccaccio The Decameron yang dikarang pada abad ke-14. Ia adalah kitaran seratus cerita yang diceritakan oleh sepuluh orang pemuda dalam masa sepuluh hari. Boccaccio menyebut karyanya sebagai commedia yang bermaksud “sebarang drama atau puisi naratif di mana watak utamanya berjaya mengelak malapetaka dan menemui pengakhiran yang bahagia.”
Unsur cerita lisan atau pelipur lara ini muncul dalam novel Felix K. Nesi Orang-Orang Oetimu yang memenangi Sayembara Menulis Novel DKJ 2018. Ia diwakili oleh watak Am Siki yang dikatakan pernah “membunuh lebih daripada sepuluh tentera Jepang” dan “membakar habis satu kamp kerja paksa.” Kerap kali novel yang mengangkat latar desa atau pasar sebagai fokus utama akan menggunakan pendekatan mitos dan folklor ini. Walaupun imajinasi dan sensualitas Felix tidak sampai ke tahap Eka Kurniawan dalam Cantik Itu Luka, ia tetap memanfaatkan suara penceritaan yang bergerak ke mana-mana demi menanam dalam pikiran pembaca citra Oetimu sebagai wilayah yang keramat dan terasing. Am Siki asalnya seorang pahlawan hebat; tetapi setelah diburu oleh tentera Jepang, ia berpindah dari satu tempat ke satu tempat sehingga ia memilih untuk menetap di Oetimu setelah Indonesia merdeka. Di Oetimu, Am Siki mengumpulkan daun lontar, dan menjadi pelipur lara ketika musim hujan. “Semua anak di kampung itu selalu datang, sebab yang tidak datang akan disengat kalajengking. Tempias hujan membuat kalajengking keluar dari dinding-dinding rumah dan menghukum anak-anak yang tidak mendengarkan dongeng.” Tapi ketika anak-anak larut dalam kisah dongeng, ibu-bapak di rumah sibuk “membikin anak lagi.” Ya, sekali lagi, kita melihat cerita hadir untuk menunda kematian di samping membuka ruang untuk bermadu kasih.
Dalam bukunya berjudul Dying for Time, Martin Hägglund menyatakan bahwa keinginan hanya wujud dalam “penangguhan waktu” karena tanpa penangguhan itu, tidak akan ada ruang dan waktu untuk dikejar atau dinikmati. Hägglund kembali kepada dialog Socrates dalam Symposium untuk menggariskan dorongan sejati keinginan manusia. Kita mendambakan sesuatu bukan karena ia bersifat sementara; tetapi kita mengejar tujuan abadi “yang tidak hadir sepenuhnya maupun berlalu pergi.” Ini bukan bermaksud manusia tidak ingin mati; tetapi disebabkan ia menjadi saksi akan kematian, maka ia ingin terus bertahan sebagai manusia dan menjadi bagian dari dunia yang sementara ini. Hägglund menyebut kondisi ini sebagai kronofobia: ketakutan pada waktu yang mendorong manusia untuk “melabur dalam kehidupan yang pasti musnah.”
Adakah watak fiksi mengetahui ia akan mati atau hidup abadi? Persoalan ini agak aneh dan ironis karena jika kita mengambil contoh watak tragis seperti Ned Stark dalam Game of Thrones, atau Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah, mereka mati dalam garis waktu penceritaan; tetapi selagi kisah mereka terus dibaca, selama itu mereka akan mati dan hidup kembali. Namun, watak fiksi tidak mempunyai pentas drama untuk bersuara. Tidak ada penonton untuk melihat dan mendengarnya berbisik dan bermonolog. Maka mereka menggelintar dalam sebuah cerita, mencari tokoh lain yang sudi mendengar.
Dalam novel Orang-Orang Oetimu, tokoh Sersan Ipi mengalami trauma seksual sama seperti Sultan Shahriyar mengalami trauma saat melihat istrinya meniduri hamba berkulit hitam. Kasus Sersan Ipi lebih parah, kemaluannya dicabul oleh seorang dukun ketika dia masih kanak-kanak. Akibatnya Sersan Ipi tumbuh besar tanpa disunat dan ia tidak dapat menikmati kepuasan hubungan kelamin. Ini berubah apabila ia menemui seorang gadis bernama Silvy. Seperti Shahrazad, Silvy adalah gadis pintar dan menawan; maka melalui Silvy, Sersan Ipi menemui pencerita dan pendengarnya; melalui Silvy juga Sersan Ipi akhirnya mendapat kepuasan batin yang penuh.
Wilayah Oetimu mempunyai persamaan dengan Kepulauan Ogonshoto ciptaan Anwar Ridhwan dalam novel Naratif Ogonshoto: kedua-duanya terpelosok di sudut dunia yang asing; dan kedua-duanya tempat ini senantiasa dibayangi oleh tirani pemerintah, tekanan sejarah, dan ancaman kehancuran alam. Ogonshoto terdiri atas tiga pulau: Gora-Gora, Rai-Rapa, dan Futu-Ata. Setiap pulau mempunyai gunung berapi yang menjadi amaran kepada kemusnahan yang bisa berlaku kapan saja. Ogonshoto juga menghadapi ancaman gempa bumi dan ribut topan. Namun, musuh terbesar Ogonshoto bukan angin, laut dan gunung, melainkan bayang dan permainan kuasa Presiden. Anwar membagi novelnya kepada 10 bagian (atau cerpen) yang memaparkan Ogonshoto dari sudut penceritaan yang berbeda-beda. Walaupun watak Presiden tidak hadir dalam kesemua bagian ini, ancaman kekuasaannya senantiasa dirasakan. Di sinilah terletak perbedaan utama dunia Oetimu dengan Ogonshoto.
Dalam dunia Oetimu, kronofobia diatasi atau diisi dengan cinta, seks, dan ketuhanan. Dalam dunia Ogonshoto, politik menerjang masuk ke dalam segala aspek kehidupan, nyata atau tersembunyi; manusia Ogonshoto tidak punya waktu untuk bercinta dan memuaskan nafsu batin. Permainan kuasa Presiden hanya boleh dilawan dengan mencipta permainan dalam permainan. Seperti ketika seorang antagonis Presiden dalam bagian “Hering,” menciptakan permainan berburu binatang. Ini adalah permainan menentang permainan. Ada juga yang mencoba masuk ke dalam permainan Presiden dengan harapan ia akan selamat dan mencapai kebahagiaan abadi di Ogonshoto. Kita melihat dalam cerita “Mainan” seorang pemuda dari Banaba ditemukan terdampar separuh mati di pantai Gora-Gora. Ia kemudian dijadikan anak angkat oleh Presiden dan untuk sementara pemuda itu mengecap kehidupan serba-mewah. Ia juga mulai berlatih berburu tupai kerawak dengan harapan kemahiran dan binatang buruannya akan mendapat perhatian Presiden ketika acara berburu binatang yang berlangsung di Ogonshoto setiap kali tamatnya gerhana matahari. Namun, apa yang berlaku kemudian adalah sebaliknya. Bukan tupai kerawak yang menjadi binatang buruan, melainkan pemuda Banaba itu sendiri. Dia mencoba memengaruhi peraturan permainan tanpa memahami bahwa yang berkuasa dan bisa mengubah peraturan di Ogonshoto hanya sang Presiden.
Mengapa dia menjadi mangsa permainan ini? Fikir pemuda Banaba itu. Kalau betul dia telah menjadi mainan Presiden, tanpa setahunya, dia sudah diuji dengan tiga das tembakan yang mencederakan. Tiga das tembakan; itulah batas akhir permainan… Tetapi hutan di pinggang gunung ini baru saja menyaksikan, peraturan permainan tidak dipatuhi. Kecuali dirinya yang putus lidah dan kudung kedua-dua tangan, tidak seorang pun di hutan ini yang mengendahkan peraturan permainan. Dia bukan saja menjadi mainan Presiden seorang, tetapi turut menjadi bahan lapahan tentera elitnya. (hlm 110)
Sejarah novel ternyata bukan sejarah pemodernan; bukan sejarah sains dan teknologi; bukan sejarah adat dan budaya; sejarah novel adalah pertentangan waktu yang berulang. Dalam dunia jin, gergasi dan permadani terbang, Shahrazad mempunyai kekuasaan untuk menunda hukuman mati Sultan. Namun, novel hadir untuk mengingatkan kita realitas sebenarnya bahwa kuasa peraturan permainan tidak berada di tangan pencerita maupun pembaca.
Seperti seorang Emerson yang menjarah kubur mendiang istrinya, kita menatap wajah kematian untuk mengingatkan diri bahwa ada kebahagiaan lebih abadi yang menanti, dan ia lebih dekat daripada yang kita sangka.

Wan Nor Azriq
Wan Nor Azriq adalah novelis kelahiran Alor Setar Kedah, Malaysia. Novel pertamanya D.U.B.L.I.N. memenangkan Malaysian Institution of Books and Translation-BH-PENA Literary Prize (2014). Karya-karyanya adalah Boneka Rusia Guido, Di Kala Bulan Bermain Biola, Astronomi Bilik Mainan, Mana Dadu Darjeeling, dan lain-lain.