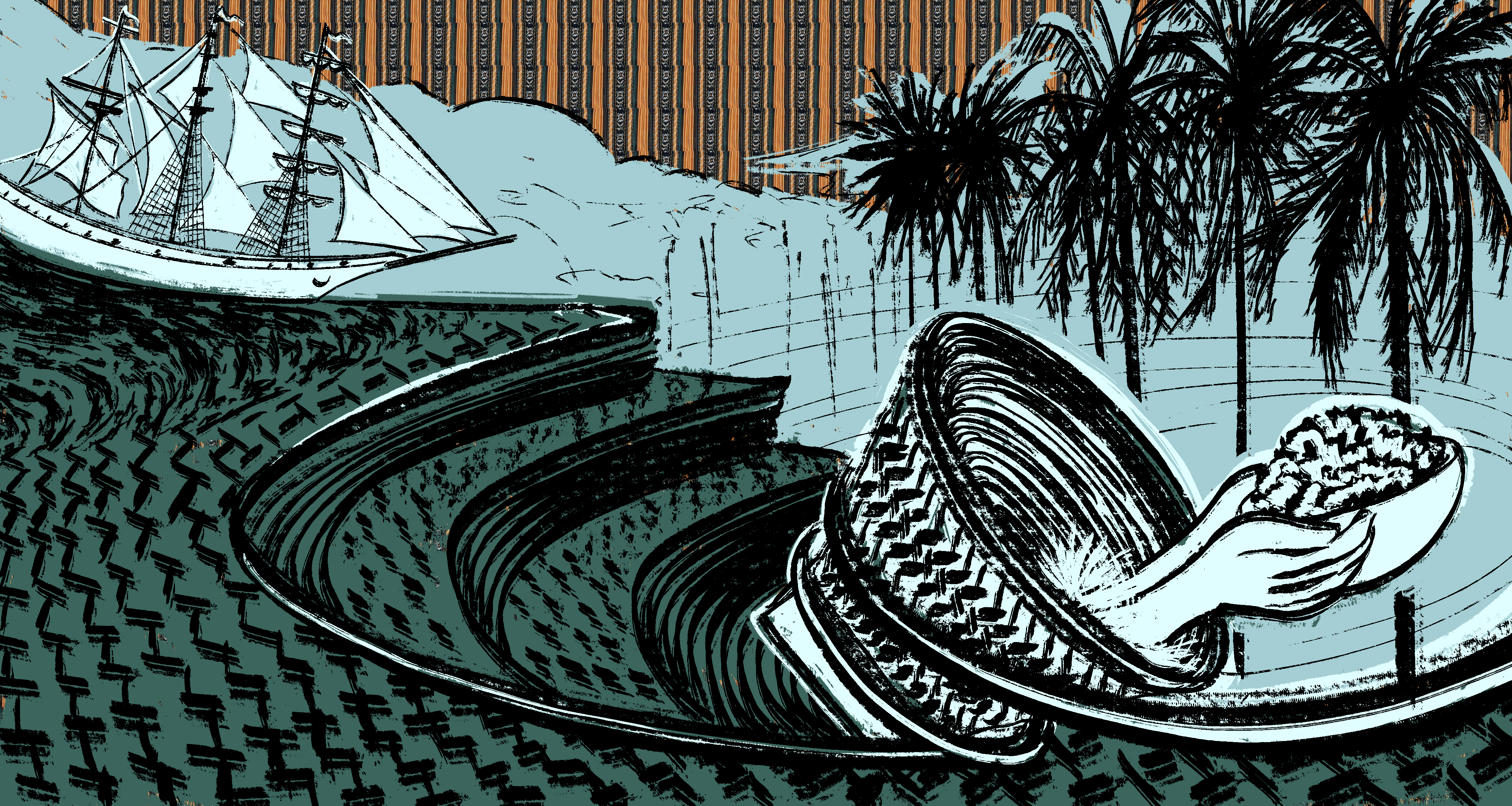Babi-Babi dan Anjing-Anjing Nidu
Catatan atas Novel Burung Kayu
“Penulis novel melakukan riset pustaka dan lapangan terkait suatu masyarakat
yang hendak ia tulis. Hasil riset itu kemudian menjadi bahan atau titik tolak penulis
untuk dikembangkan menjadi narasi fiksional.” (Teroka Press)
“Sebuah novel etnografi yang cemerlang dari jemari seorang sasareu membaca
kehidupan orang Mentawai Siberut, khususnya Sarereiket (Penghuni Das Rereiket)”
(Dr. Maskota Delfi, Antropolog, Dosen Universitas Andalas)
“Wahai nenek moyang yang telah lama mati, kepadamu kami persembahkan
buah kelapa, iba, kuping kiri seekor babi, dan jiwa buruk yang hidup di hutan-hutan.”
(Niduparas Erlang, Burung Kayu)
BURUNG Kayu, novel Niduparas Erlang alias Endin Saparudin yang memenangi penghargaan Kusala Khatulistiwa 2020, dibuka dengan adegan seorang calon sikerei[1] membawakan tarian Muturuk dalam kondisi kerasukan pada prosesi pengukuhannya[2] yang serta-merta mengingatkan saya kepada ritual tatung[3] dalam tradisi masyarakat Cina-Hakka tempat saya tumbuh. Ada sejumlah persamaan thungse (pelaku tatung) dengan sikerei, setidaknya dari gambaran Nidu dalam novelnya. Pertama, keduanya sama-sama menjadi perantara antara dunia nyata (fana) dan dunia supranatural (alam roh), antara manusia (ngin, sirimanu) dan Tuhan (Tian, Ulaumanua).
Para sikerei tua tahu bahwa roh-roh sikerei dari berbagai masa tengah memberkati sikerei muda yang kini melompat ke dalam api dan terus saja menari. Kakinya yang tadi tak henti mengentak-ngentak lantai, kini mengentak-ngentak bara api yang berkobar, menerbangkan lelatu yang pecah mekar sebelum padam. Kakinya tak lepuh dibakar api. Ia dingin di dalam api. Sementara matanya, mendelik berkilat-kilat, lalu memejam seolah memasuki dunia para leluhur, memasuki Uma Besar yang begitu memesona penuh warna penuh bunga-bunga, sembari terus saja menarikan tarian manyang melayang dan menyambar. (Erlang, 2)
Apabila dalam kebudayaan suku Mentawai—terutama dalam konteks Arat Sabulungan[4]—para sikerei adalah orang yang dikultuskan dan dipercaya sebagai penghubung puak dengan roh para leluhur, roh-roh baik dari dalam hutan, roh sungai, roh dedaunan, roh laut, roh batu, roh hewan buruan dan peliharaan; dalam kebudayaan Cina-Hakka—khususnya di kalangan penganut Shenisme—para thungse adalah perantara para dewa Cina (shen) di kahyangan maupun roh-roh suci (xian) dengan manusia. Hanya melalui tubuh para thungse inilah para dewa dapat berkomunikasi dengan manusia di dunia fana. Baik sikerei dalam kebudayaan Mentawai maupun thungse dalam kebudayaan Cina-Hakka ini juga sama-sama merupakan orang-orang pilihan. Artinya di sini, tidak seorang pun bisa menjadi sikerei atau thungse atas kemauan sendiri, melainkan semata-mata karena mereka telah dipilih oleh roh-roh leluhur/para dewa. Sebab itulah, diyakini pula bahwa segala “kesaktian” yang mereka miliki (misalnya kebal api, kemampuan berinteraksi dengan roh dan mengobati penyakit) adalah anugerah yang tidak dapat dipelajari oleh siapa pun.
Adapun tanda-tanda seseorang terpilih sebagai sikerei dan thungse juga memiliki kemiripan, yakni jatuh sakit. Bahkan dalam banyak kasus thungse—sebagaimana yang terjadi di kampung halaman saya pulau Bangka—mereka yang dipanggil oleh para dewa untuk menjadi perantara seringkali mengalami kerasukan mendadak pada tempat dan waktu secara acak. Mereka baru akan tenang, tidak lagi tiba-tiba kerasukan, kejang, dan sembuh dari sakit apabila para dewa sudah berkenan memenuhi takdir mereka sebagai thungse—yang harus dikukuhkan lewat sebuah upacara yang disebut khoi kong (membuka cakra) oleh thungse lebih tua dan berpengalaman.
Hal ini persis seperti yang dialami oleh tokoh Legeumanai dalam novel Burung Kayu. Sebagaimana dikisahkan oleh Nidu, kendati telah lama mengabaikan Arat Sabulungan agama adat leluhurnya dan berpindah-pindah agama sebanyak tiga kali sampai akhirnya memilih Islam sebagai agama di KTP-nya serta mengaku sebagai Saiminang (orang Minang) di tanah seberang, tetap saja Legeumanai mendapatkan “mimpi tentang sikerei yang terus menari di atas seunggun api.” Mimpi yang terus datang berulang-ulang menganggu tidurnya, membuat ia cemas dan akhirnya terserang demam tinggi tak tersembuhkan. “Demam yang telah membuat tubuhnya begitu lemah, dadanya sesak, kepalanya berdenyar, sehingga ia mengira telah terkena guna-guna. Apalagi, dokter yang memeriksanya tak menemukan gejala apa-apa dan obat yang ditelannya tak mempan menghalau penyakitnya.” (Erlang, 147)
Di tengah gigil demam itu, ia mesti menerima pula kabar bahwa Taksilitoni ibunya sudah berhari-hari terbaring tidak sadarkan diri sehingga Legeumanai harus mudik ke barasi. Karena sakit ibu-anak itu tidak kunjung berhasil diobati oleh para sikerei dan dokter puskesmas di barasi, maka Saengrekerei sang ayah sambung sekaligus pamannya pun akhirnya membawa keduanya kembali ke uma asal mereka di pedalaman lembah dengan harapan para sikerei di sana mampu menyembuhkan mereka.
Para sikerei yang telah berkali-kali menggelar ritual umagri dan pebeteijat (pembersihan badan dan penyembuhan) serta meminumkan racikan dedaunan mengandung roh-baik kepada ibunya dan kepada dirinya itu kemudian menganggap Legeumanai mendapatkan panggilan leluhur untuk menjadi seorang sikerei. Ini lantaran dalam demamnya yang semakin parah, Legeumanai kerap menggumamkan tentang Uma Besar, tentang dunia roh para leluhur, dan tentang dunia-sebelah-kiri. Panggilan ini dalam keyakinan mereka—seperti yang diungkapkan Saengrekerei—adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.[5]
Legeumanai menoleh ke belakang, tersenyum gamang kepada Saengrekerei yang tengah mengendalikan tuas motor tempel itu. Saengrekerei menatapnya dengan tajam, seolah hendak meyakinkan bahwa menjadi sikerei adalah kejadian tak terhindarkan; ia berkah sekaligus kutukan sebab begitu banyak keikei, begitu banyak pantang-larang, yang mesti dijalani Legeumanai. (Erlang, 48)
Suara sipaumat-nya, guru sikerei yang membimbingnya menuju Uma Besar para leluhur, menuju Sabulungan, mendenging lagi dalam kepala Legeumanai, “Leluhur telah memilihmu, Legeumanai. Leluhur telah memilihmu.”
“Leluhur telah memilihmu,” kata dua sikerei lain yang juga turut dalam upaya menyembuhkan ibu dan dirinya, seolah terulang penuh penekanan di dalam pendengaran Legeumanai. (Erlang, 149)
Menjadi seorang sikerei—dukun adat—untuk puaknya, bagi seorang Legeumanai yang telah sembilan tahun meninggalkan tradisi-budaya asalnya dan menjalani “kehidupan modern” di Tanah Tepi, di Padang (empat setengah tahun kuliah dan hampir lima tahun bekerja di kantor pemerintah) tentunya bukanlah perkara mudah. Karena, seperti yang dituturkan oleh sang narator mahatahu (omniscient narrator): Bukankah ia (Legeumanai), juga anak-anak muda lain yang mengenyam pendidikan lebih lanjut dan memilih tinggal di kota-kota, tak lagi tahu bagaimana cara berburu atau mengolah sagu, atau sekadar memanggil ayam-ayam yang hendak diberi makan? Bukankah ia juga telah melupakan rasa okbuk, subbet, dan kapurut dan menggantikan makanan-makanan khas puaknya di rimba pulau Siberut itu dengan makanan orang Padang seperti nasi, rendang, dan gulai serta mengubah gaya bahasa serta menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan lama sukunya?[6]
Bahkan lebih jauh ia pernah mencoba menolak para roh dan jiwa dan bajou segala-yang-ada-dalam-semesta (yang dalam kepercayaan sukunya mesti dipikat agar betah atau dihalau agar menjauh), karena itu semua—menurut seorang kawannya yang Sipuisilam (Islam)—“cuma hantu-hantu.”[7] Itu sebabnya Legeumanai pun sempat memandang dirinya sendiri serupa Silango, salah seorang leluhurnya yang terus saja pergi, menjauh, dan terus menjauh. Atau, mengibaratkan kepergiannya sebagai kejatuhan sebutir kelapa tua di hulu sungai yang hanyut terseret arus hingga ke hilir, ke muara, ke laut, dan mendamparkannya di Tanah Tepi.
Meskipun begitu, dirinya ternyata lebih mirip kata peribahasa Saiminang, “Satinggi-tinggi tabang bangau, baliaknyo ka kubangan juo.” Para roh leluhur tetap tidak berkenan meninggalkannya, dan memanggilnya pulang lewat mimpi dan demam tidak berkesudahan. Karena itu, perjalanannya kembali ke barasi, terlebih ke uma leluhur di tengah rimba, tidak lain adalah perjalanan kembali ke jati dirinya sebagai putra Bagaiogok, putra suku-sura’-boblo, seraya pada saat yang sama mesti berdamai dengan masa silam leluhurnya yang penuh dendam sekaligus juga mendamaikan dua dunianya yang paradoksal.
Maka, kita pun menemukan sosok Legeumanai yang tidak lagi hendak “mengingkari kediriannya sebagai seorang yang terlahir di sebuah uma, disambut dengan punen (ritual pesta) kelahiran, dipotongkan seekor babi paling besar.”
Tapi kini, seusai penobatannya sebagai sikerei yang mampu menari di atas unggunan api, Legeumanai tak hendak mengubah agamaya lagi. Ia Sipuisilam, tapi ia akan selamanya menggelar pesta-pesta, puliaijat-puliaijat, ritual-ritual penyembuhan, menjalani kekei atau pantang-larang, dan akan menerima otcai iba saina’ yang mananam. Ia Sipuisilam, tapi tubuh dan jiwanya menghendaki daging babi yang mananam—yang lezat tak tertanggungkan. (Erlang, 171)
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu bakal kita bicarakan nanti. Namun, yang jelas, konflik identitas di pulau Siberut yang melahirkan krisis identitas pada diri Legeumanai (juga tokoh-tokoh lainnya) inilah yang melatari sekaligus menjadi nyawa novel Burung Kayu. Di sana, kita bukan saja menemukan perseteruan antar-uma atau lebih tepatnya kelompok kekerabatan (kin group) di Mentawai yang telah berlangsung berabab-abad secara alami, melainkan juga yang timbul belakangan akibat kebijakan pemerintah untuk “memajukan-menyejahterakan” masyarakat adat yang dianggap sebagai masyarakat tertinggal. Dari sinilah kemudian, muncul berbagai ketegangan horisontal maupun vertikal baru yang mewujud sebagai kekerasan sosial.
Ya, Burung Kayu boleh dibilang sebagai novel yang menghidupkan dan dihidupkan oleh konflik identitas dan perseteruan antarsuku. Sebelum masuknya campur tangan Pemerintah atas nama pembangunan, kesejarahteraan, penertiban dan sebagainya yang cenderung intimidatif, konflik horizontal tampaknya memang telah lama menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial di pulau Siberut, Mentawai, yang menjadi latar tempat pengkisahan. Dalam novel ini konflik tersebut terwujud sebagai perseteruan yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dari teteu kepada cucu atau dari ayah kepada anak lewat penuturan titiboat berulang-ulang. Hal ini persis seperti yang dikemukakan oleh Juniator Tulius, antropolog asal Mentawai, dalam disertasinya di Leiden University, Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts Over Land in Mentawai – Indonesia. (Selanjutnya disingkat Family Stories):
Anggota-anggota kelompok kekerabatan yang lebih tua mewariskan cerita keluarga kepada generasi muda. Sejumlah anak muda yang telah mendengarkan cerita-cerita tersebut suatu hari nanti akan mengambil alih tugas para pendongeng yang lebih tua. Kemudian giliran generasi muda itu untuk menceritakan kisah yang sama kepada generasi mendatang. Lantaran kemampuan mereka dalam berbicara dan mengisahkan cerita keluarga, orang-orang ini kerap dihormati dan dikagumi oleh para anggota keluarga lainnya. Karena bakat dan posisinya, sejumlah individu memiliki peluang besar untuk menuturkan cerita keluarga. Di Mentawai, para pendongeng yang terampil dan berbakat juga memiliki status khusus dalam kelompok kekerabatannya, yang disebut rimata (pemimpin ritual) atau sikebbukat uma (penatua kelompok kerabat). Orang-orang yang jumlahnya sedikit inilah yang menjadi individu terdepan dalam acara-acara sosial dan ritual. Laki-laki lebih sering dipilih menjadi penutur cerita keluarga dibandingkan perempuan. (Tulius, 275)
Dalam Burung Kayu—seperti yang dinarasikan oleh omniscient narrator maupun yang dikisahkan oleh karakter Saengrekerei—permusuhan antara uma Legeumanai, yakni suku-sura’-boblo dan suku-tunggul-kelapa merupakan sebuah perseteruan warisan yang berakar jauh ke masa silam dalam sejarah keluarga, yakni sejak pembunuhan pertama dilakukan oleh leluhur mereka Baumanai.
Ada pun asal muasal permusuhan itu berawal dari babi sigelag yang digunakan oleh keluarga Babuisiboje untuk mengawinkan anak lelakinya dengan adik perempuan Baumanai yang ketika itu masih disebut suku-sura’-sabbeu. Namun, babi sigelag besar itu terlepas dari kurungannya. Karena tidak kunjung berhasil ditemukan kembali sampai malam, Baumanai mengira babi itu telah kembali ke uma keluarga Babuisiboje. Sehingga keesokan harinya ia pun pergi mengunjungi Babuisiboje dan menanyakan apakah babi yang telah diberikan kepada keluarga mereka itu kembali lagi ke uma Babuisiboje. Babuisiboje mengatakan tidak melihatnya, padahal babi sigelag itu telah ditombak dan dimakan oleh keluarganya. Baumanai yang mengetahui kecurangan Babuisiboje ini dari kabar yang disampaikan oleh adik perempuannya yang dinikahkan dengan anak lelaki keluarga Babuisiboje kemudian menuntut Babuisiboje untuk membayar tulou saina’ lewat tiga orang sipasaili (juru runding) agar tidak ada lagi perselisihan. Namun, permintaan ganti rugi tersebut ditolak oleh Babuisiboje.
Singkat cerita, pengelakan dan penolakan Babuisiboje ini pun membuat marah Baumanai. Pada hari keempat akhirnya kesabarannya habis, sehingga ia mengajak Pabelemanai adiknya untuk mengasah parang dan mata tombak. Lalu terjadilah pembunuhan terhadap dua anggota keluarga Baumanai. Akibatnya, perang antara suku-tunggul-kepala dan suku-sura’-boblo tidak terelakkan lagi. Namun, sebelum pertumpahan darah kembali terjadi, Baumanai dan Pabelemanai melarikan diri ke leleu Sigarena, sehingga Babuisiboje tidak bisa membalaskan dendamnya dan terus mewariskan kisah pembunuhan kedua kerabatnya itu kepada keturunan-keturunan mereka.
Karena itu, kata sang teteu kepada Saengrekerei: “Maka kau mesti mengingat ini, Saengrekerei, bahwa suku-suku yang berasal dari suku-tunggul-kelapa itu, sampai kapan pun adalah musuh bagi suku-suku yang berasal dari suku-sura’-boblo, khususnya bagi anak-keturunan Baumanai.”[8] Itulah kenapa permusuhan kedua uma bisa terus berlanjut sampai terjadilah peristiwa pako’ berburu yang dipicu oleh perbuatan Saengrekerei mengurung seorang gadis dari keluarga suku-tunggul-kelapa yang ia sukai di rusuk-nya dan membiarkan kaum sesuku gadis itu di seberang sungai mencari-cari dalam cemas dan kecewa.
Martabat dan harga diri kedua kelompok kekerabatan pun kemudian dipertaruhkan ketika sikkok jelita yang tidak menyukainya itu berhasil kabur dan mengadu kepada keluarganya, sehingga ayah si gadis menuntut tulou kepada uma Saengrekerei—yang tentu saja enggan membayar denda apa pun sebab hal itu bakal membuat ia diperolok teman-teman dan dicemooh saudara-saudaranya.
Maka, demi menghindari tulou malu dan menunjukkan bahwa uma-nya adalah uma yang patuh disegani di seantero lembah itu, Saengrekerei menantang pako’ kepada uma seberang sungai. Pako’ berburu. Pako’ yang akan membuktikan kehebatan masing-masing uma sekaligus mempermalukan siapa pun yang kalah. (Erlang, 26)
Mulanya Saengrekerei dan saudara-saudaranya bertingkah sombong lantaran merasa telah menang dan tidak mungkin terkalahkan setelah mereka berhasil membawa pulang seekor joja dan dua anak babi hutan buruan. Karena itu mereka segera menggelar pesta, memukul tuddukat (kentongan), menari dan menyanyi sembari mengejek Uma seberang sungai. Namun, siapa nyana, uma di seberang sungai itu malah berhasil memanah tiga ekor babi hutan jantan besar lalu membalas mereka dengan memukul tudukkat, gong, dan membawakan nyanyian-nyanyian lebih kencang yang sarat ejekan dan penghinaan.
Akibatnya tidak ada jalan lain untuk menebus rasa malu itu selain menenggerkan seekor burung kayu (yang menjadi judul novel ini) di pucuk pohon katuka untuk membela kehormatan kelompok kekerabatan.
Sungguh, bunyi tuddukat dan gong dan lagu bernada sombong sekaligus mengejek itu, terasa benar menggedor-mengentak gendang telinga dan gendang dada Aman Legeumanai. Membikin kepalanya berdenyar. Bunyi itu, bunyi pertaruhan-pertarungan harga diri dan wibawa sebuah uma; harga kaum sesuku yang mesti dibela, dibanggakan, dan diselamatkannya dari segala perlakuan yang memalukan. Apalagi, dipermalukan oleh uma yang—menurut penuturan teteu-nya pada malam-malam panjang yang mencucuk tulang—telah menjadi musuh lama bagi uma-nya, bagi sukunya. Maka, apa pun yang akan terjadi, uma-nya tak boleh menanggung malu, apalagi dipermalukan. Taaakkk… (Erlang, 16)
Inilah awal malapetaka itu, penyebab kematian Bagaiogok alias Aman Legeumanai, kakak kandung Saengrekerei. Sebab dialah yang paling dipercaya oleh segenap penghuni uma (para taluba, eira, kamaman, bajak, dan teteu-nya) untuk menenggerkan burung-enggang-kayu di puncak pohon katuka—agar kelak, semua uma tetangga tahu bahwa hanya uma merekalah yang paling perbawa, paling magege, di antara uma-uma lain di seantero lembah.[9] Hal ini lantaran Aman Legeumanai dianggap sebagai lelaki yang paling perkasa berkat sembilan belas ti’ti’ durukat (tato) rusa dan joja yang terajah di tubuhnya.
Seakan tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan muka uma akibat perbuatan Saengkerei adiknya itu. Kendati di hati kecil Aman Legeumanai, sebetulnya ia lebih mendambakan perdamaian dan berpikir “barangkali pada generasinya kini, kedua uma yang bermusuhan bisa menjalani paabat (ritual berdamai), sebagaimana pernah dilakukan uma-nya beberapa tahun lalu dengan uma lain dari lembah lain di aliran sungai lain.” Sebab, “Bukankah akan lebih menyenangkan jika bersama-sama menyembelih banyak babi banyak ayam, lalu makan bersama dan menari bersama, dan melupakan segala pertentangan-permusuhan dan dendam warisan?” (Erlang, 18)
Namun, perdamaian tampaknya bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu, narator pun lantas mengibaratkan permusuhan turun-temurun ini dengan tanaman yang terus bertunas. Dan salah satu medium untuk mewariskan dendam itu—sekali lagi—adalah lewat titiboat. Itu sebabnya, meskipun memendam keinginan untuk berdamai dengan uma seberang, ketika mengenang salah seorang bajak-nya yang mati secara curang dan mengingat kemenangan uma-nya di masa lalu, “meski hanya melalui sebuah kisah”, dada Aman Legeumana jadi sebak, air mukanya mengeras, dan darahnya membuncah-meruah.
Di sinilah, berdasarkan hasil riset lapangan Nidu seolah hendak “mengingatkan” kita betapa kisah (cerita lisan) seyogianya berperan besar dalam kehidupan sosial suatu masyarakat—yang dalam hal ini khususnya masyarakat Mentawai yang menjadi subjek penelitiannya—bahkan dapat menjelma jadi sesuatu yang berbahaya. Katanya lewat suara narator:
Ah, lidah yang berkisah memang lebih menusuk-merasuk dibanding anak panah beracun yang dilepas-lesakkan sekuat roh; lebih tajam dari mata parang yang diayun-entakkan pada batang-batang sagu yang ditumbangkan. Daya rusak lidah yang berkisah—jika memang dimaksudkan demikian—membadai di tengah samudra, menyeret dan mengempaskan dan membenturkan apa saja ke tebing-tebing terjal yang mustahil didaki. Sebagaimana tebing di Simatalu, tempat asal segala uma, yang terempas-terbentur gelombang samudra. Tebing yang hanya ditempuh dalam kisahan tentang perempuan yang bunting oleh angin dan terusir bersama seekor anjing. (Erlang, 19)
Namun benarkah demikian? Benarkah kisahan memang kerapkali cukup berandil dalam sebuah konflik antar-kelompok kekerabatan?
Cerita Keluarga di Mentawai
Kebudayaan Mentawai—seperti yang dikutip Teroka Press dari sukumentawai.org—memang merupakan kebudayaan yang kaya akan tradisi mendongeng.[10] Bahkan begitu kuatnya mengakar dalam kebudayaan Mentawai, tradisi berkisah ini boleh dikatakan sebagai bagian dari pusat kehidupan masyarakat Mentawai, yang secara serius memengaruhi nyaris seluruh aspek: sejarah, adat-istiadat, silsilah dan hubungan kekerabatan, batas wilayah, struktur sosial, dan berbagai dinamika keseharian. Terutama dalam hal ini jenis titiboat yang dikategorikan sebagai cerita keluarga (family stories).
Cerita keluarga merupakan salah satu bentuk narasi lisan yang menjadi pembawa utama kebudayaan Mentawai. Orang Mentawai tidak mengamalkan tradisi tertulis apa pun. Mereka mempertahankan nilai-nilai budayanya dalam bentuk narasi lisan. Masyarakat Mentawai menceritakan kisah-kisah tertentu dan meneruskan kisah-kisah tersebut dalam keluarga mereka dari generasi ke generasi. Beberapa narasi lisan berisi informasi umum dan dimiliki seluruh masyarakat Mentawai. (Tulius, 18)
Kendati sebagian besar tradisi lisan Mentawai yang berbentuk cerita umumnya disebut sebagai titiboat, tetapi—seperti yang diungkapkan oleh Juniator Tulius—cerita-cerita tersebut tidaklah dapat dikelompokkan ke dalam satu kategori. Dijelaskan Tulius, bahwa cerita yang mengisahkan tentang asal-usul tumbuhan, hewan, manusia, dan cara kerja fenomena alam biasanya disebut pumumuan, yang terbentuk dari akar kata mumu (secara harfiah berarti “matang” atau “dewasa” dan secara kiasan berarti “tua”). Cerita dalam pumumuan ini adalah narasi tentang hal-hal besar yang terjadi di masa lalu, yang menjelaskan bagaimana segala sesuatunya dimulai, misalnya asal usul manusia pertama di Mentawai. Sehingga dengan demikian, pumumuan dapat digolongkan sebagai cerita mitos.
Ada lagi cerita jenis lain yang disebut pungunguan, yang berasal dari kata dasar ngungu, yang secara harafiah berarti “mulut” dan secara kiasan berarti narasi lisan. Kisah-kisah ini menyerupai legenda, dongeng, dan fabel,[11] yang berfungsi menyampaikan moral tentang budaya dan tradisi, tentang bagaimana seharusnya kita belajar hidup bermasyarakat.
Tentu saja selain yang berbentuk cerita, tradisi lisan Mentawai masih memiliki jenis-jenis sastra lain, misalnya yang berbentuk mantra dalam bahasa ritual dan lagu. Mantra-mantra ini ada yang digunakan sebagai doa dalam upacara dan ada pula yang dinyanyikan. Pada beberapa kesempatan, kata-kata ritual dibawakan sebagai doa dan kemudian dinyanyikan. Pada kesempatan lain, kata-kata ritual hanya dibawakan sebagai doa dan tidak dinyanyikan. Untuk menghindari kebingungan, masyarakat Mentawai kemudian memberi nama pada lagu-lagu tersebut.
Nama sebuah lagu menunjukkan jenis lagunya, yang dibedakan menjadi dua kategori utama: lagu ritual dan lagu biasa. Lagu ritual yang disebut urai kerei (lagu perdukunan), biasanya dinyanyikan oleh dukun (tai kerei). Seorang dukun sering menggunakan nyanyian dalam ritual sebagai cara untuk berkomunikasi dengan roh. Urai kerei dapat dibagi lagi menurut fungsinya. Ada kumpulan lagu untuk membujuk roh (naknak simagre) agar bergabung dengan keluarga dalam suatu ritual. Ada kumpulan lagu untuk menyelaraskan kembali hubungan jasmani dan rohani (urai pameru), dan sebagainya. Kebanyakan nyanyian perdukunan diturunkan dari dukun senior ke dukun junior dan transmisi ini disebut panguli.[12]
Dalam Burung Kayu, lagu-lagu urai kerei inilah yang dinyanyikan oleh Legeumanai dalam keadaan setengah kesurupan di dalam laju sampan menuju uma asal mereka. Yakni, lagu-lagu yang semakin lama semakin tidak dikenalinya. Bukan lagi lagu yang pernah ia nyanyikan di gereja, di dalam perkumpulan Orang Muda Katolik, atau di sekolah pada saat upacara bendera. Lagu-lagu yang kemudian terdengar begitu asing oleh telinganya sendiri, juga oleh telinga Saengrekerei sang ayah.[13] Bacalah deskripsi lebih rinci di bawah ini:
Legeumanai meragu. Adakah ia pernah mengenal lagu-lagu itu? Ia mencoba melafalkannya sekali lagi, menyenandungkannya lagi, dan mengingat-ingat dari mana ia mendapatkan lagu-lagu itu? Ei, bukan, itu bukan lagu para ipar dan menantu perempuan Silango; bukan lagu puja-pujian kepada Tuhan atau kepada orang-orang suci; bukan lagu wajib nasional; bukan lagu tentang tanah rantau atau kisah-cinta uni-uda yang saling merindukan; bukan lagu yang perah didengarnya di mana pun. Liriknya tak dapat ia mengerti. Dialeknya belum pernah ia pelajari. Dan bahasanya, seperti dituturkan para leluhur, seperti lagu mantra dalam ritual-ritual para sikerei. Tapi, mengapa lagu itu terajahkan begitu saja di pangkali lidahnya? Legeumanai tak tahu. Ia gamang. Dan merasa semakin demam. (Erlang, 156)
Masih menurut hasil penelitian Juniator Tulius, cerita keluarga (gobbui) karena itu memiliki ragam fungsi yang bernilai tinggi sebagai narasi sejarah lisan. Pertama, cerita keluarga ini berfungsi sebagai salah satu penanda identitas kelompok kekerabatan untuk membedakan satu suku dengan suku lainnya. Sehingga suatu suku mengetahui bagaimana mereka berada dalam sebuah kelompok kekerabatan dan siapa nenek moyang mereka. Di Mentawai, para pendongeng ini mengomunikasikan pemahaman mereka tentang kejadian di masa lalu dengan gerak tubuh tertentu, ekspresi wajah, dan perubahan nada suara, yang menunjukkan ketegangan, kemarahan, kesedihan atau kebahagiaan; mereka berupaya mengungkapkan perasaan dan pikiran nenek moyang seolah-olah merekalah nenek moyang itu sendiri. Cerita keluarga ini tak hanya memberikan sumber pengetahuan yang kaya, namun juga mengungkapkan identitas komunal suatu kelompok.
Itu sebabnya berbagai pengetahuan tentang suku dalam cerita, seperti lokasi dan nama tempat, nama individu, dan kronologi peristiwa merupakan unsur-unsur penting yang diakui benar oleh masyarakat Mentawai.
Apakah cerita keluarga cenderung menyajikan sejarah permusuhan antar-kelompok kekerabatan? Tentu saja tidak. Dalam fungsinya sebagai penanda identitas, seyogianya cerita-cerita ini bersama para pengisahnya juga menyimpan ikhtiar untuk mempertemukan-menyatukan kembali yang tercerai-berai. Dari cerita keluarga-lah, orang-orang kemudian menjadi tahu soal pohon silsilah mereka yang bercabang-cabang, suku mana saja yang masih bersanak-kerabat dengan suku mereka dan tak pernah merajut sejarah silang sengketa.
Sejumlah cerita keluarga milik kelompok-kelompok kekerabatan individu juga menyebutkan asal usul nenek moyang mereka yang lebih jauh. Beberapa kelompok kekerabatan memiliki asal usul nenek moyang yang sama, merujuk pada sebuah lembah tertentu di mana nenek moyang mereka mulai tinggal dan di mana anggota kelompok kekerabatannya saat ini percaya bahwa di sanalah tanah leluhur mereka berada. Cerita keluarga terdiri dari ciri-ciri kelompok kekerabatan. (Tulius, 274)
Beberapa yang lain menganggap hubungan silsilah yang terdapat di antara kelompok kekerabatan terkait sebagai poin penting dalam cerita keluarga; cerita-cerita tersebut mungkin dapat membantu mereka menemukan kerabat yang tinggal di tempat lain di Kepulauan Mentawai. (Tulius, 275)
Cerita-cerita yang dituturkan oleh Saengrekerei kepada Legeumanai dalam Burung Kayu tatkala sang keponakan hendak berangkat melanjutkan pendidikan ke Tanah Tepi merupakan contoh gamblang bagaimana melalui cerita keluarga, Saengrekerei mencoba memaparkan hubungan di antara keluarga-keluarga suku-sura’-sabeu, dengan nama-nama individu dan wilayah cukup rinci, yang telah tercerai satu sama lain lantaran migrasi nenek moyang mereka. Sebagai akibat dari migrasi ini, terciptalah suku-suku berkerabat dengan nama kekerabatan berbeda yang menetap di tempat-tempat terpisah.
Sebelum kau pergi ke Tanah Tepi nanti, Legeumanai, cobalah temui mereka. Keluarga kita dalam kelompok kerabat yang disebut suku-sura’-sabeu, sebelumnya berasal dari uma Mongan Simalegi itu. (Erlang, 134-135)
Kedua, sebagai narasi sejarah penting, cerita keluarga—sebagaimana dikatakan Nidu lewat karakter Saengkerei—juga mengamanatkan soal perbatasan-perbatasan tanah yang ditemukan dan diwarisi bersama (hlm 122-123). Atau dengan kata lain, ia sering digunakan sebagai bukti klaim atas sebidang tanah tertentu. Sehingga dengan demikian, dalam cerita keluarga ini juga terkandung nilai-nilai ekonomis dan politis, bahkan berperan sebagai semacam hukum agraria yang tak tertulis. Hal ini bisa terjadi lantaran—seperti kata Tulius—tak ada bukti tertulis mengenai klaim-klaim tanah leluhur tersebut; sebab orang Mentawai tidak mempunyai ortografi atau bahasa tulisan tertentu, tak memiliki tradisi menulis dan hanya mempunyai bahasa lisan saja.[14]
Sehingga untuk membuktikan keterkaitannya dengan tanah leluhurnya, para anggota kelompok kekerabatan saat ini mencoba mengingat kembali apa yang pernah diceritakan nenek moyang mereka tentang kelompok kekerabatan tetangga ketika nenek moyang mereka masih tinggal di tempat sebelumnya, dan mengingat gambaran alam di sekitar tanah leluhur tempat tinggal nenek moyang mereka itu.[15]
Maka tidaklah mengherankan apabila masyarakat Mentawai kemudian menjaga cerita keluarga mereka sama seperti masyarakat lain menghargai cerita tertulis.
Terakhir, selain berguna sebagai “catatan” sejarah—yang terdiri dari kesepakatan sosial penting, percakapan penting, dan peristiwa penting dalam kehidupan nenek moyang—cerita keluarga juga berperan sebagai pelajaran bagi generasi muda. Orang-orang muda dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam berperilaku sosial.
Babi-babi Nidu: Penulisan ulang atas titiboat
Sayangnya, dari sekian banyak ulasan atas novel Burung Kayu, baik berupa tinjauan buku, makalah akademik, maupun kritik sastra lepas di berbagai media dan jurnal (paling tidak yang berhasil saya lacak), tidak ada satu pun tulisan yang mengupas perihal titiboat berupa cerita keluarga ini. Padahal cerita keluarga yang diangkat oleh Nidu tersebut selain cukup dominan dalam narasi Burung Kayu, nota bene merupakan titik tolak Nidu dalam membangun keseluruhan kisahnya.
Sebagaimana halnya yang tampak pada kehidupan nyata orang-orang Mentawai dalam tesis Juniator Tulius, posisi cerita keluarga ini juga terbilang amat signifikan dalam Burung Kayu, baik dalam menentukan alur cerita novel dan konflik di dalamnya maupun jalan pikiran dan jalan hidup para tokoh seperti Bagaiogok (Aman Legeumanai), Taksilitoni (Bai Legeumanai), Saengrekerei, Legeumanai, dan lain-lain tokoh. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh cerita keluarga dan tidak bisa dilepaskan dari cerita keluarga sebagai elemen kunci identitas yang berkait-kelindan dengan Arat Sabulungan.
Selain tampak jelas dari bagaimana para karakter memahami hubungan kekerabatan dan perseteruan antar uma, pentingnya titiboat cerita keluarga ini juga terlihat dari upaya Saengrekerei untuk terus memelihara kisah-kisah itu dengan meneruskannya kepada Legeumanai. Ikhtiar mewariskan cerita keluarga inilah pula yang terlintas di benak Aman Legeumanai pada saat-saat terakhir hidupnya ketika ia sedang berada di puncak pohon katuka dan melihat keceriaan anaknya (Legeumanai kecil) dari ketinggian dengan perasaan bangga.
Ah, kelak akan ia ceritakan kepada Legeumanai kecil tentang para leluhurnya yang pemberani dan selalu menjaga marwah-wibawa uma, marwah-wibawa kaum sesuku. Dan tentu juga titiboat tentang tanah, lembah, hutan yang dirambah, pantang-larang, tulou, silsilah, dan kemudian uma-uma atau suku-suku berkerabat dan yang bermusuhan—sebagaimana kisah-kisah yamg kadang mengesankan, kadang memilukan, kadang membanggakan, yang didapatnya saban malam dari teteu-nya dulu. (Erlang, 59)
Bahkan cerita keluarga ini juga yang membuat janda Taksilitoni enggan meninggalkan uma mendiang suaminya untuk pulang ke uma orangtuanya seperti yang diharuskan oleh tradisi. Semua itu demi anak lelakinya, demi Legeumanai yang akan mewarisi segala yang dimiliki mae (ayah)-nya dan kelak akan membalaskan kekalahan uma mereka. Sehingga ia pun rela menikahi Saengrekerei adik iparnya sendiri agar dapat tetap bertahan di uma Bagaiogok. Perhatikan suara hati Taksilitoni dalam berat duka yang saya kutip di bawah ini:
Melalui titiboat-titiboat yang akan dituturkan bajak-bajak-nya pada malam-malam yang damai, ia percaya, kelak Legeumanai akan mewarisi batang hingga ranting ranji dari uma-nya sendiri, sekaligus mewarisi silsilah permusuhan dengan uma-uma lainnya. Sebab, mengurai-mengurut asal-usul uma, tak mungkin terhindar dari kisah mengenai pertengkaran dan perpecahan, kekecewaan dan kepergian, ketakcukupan dan keterpisahan. Sebagaimana kisah antara kakak-beradik dan buah sipeu dalam kisahan lampau yang pernah didengarnya di uma orang tuanya. Perpecahan yang hanya dihubungkan kembali melalui para perempuan, melalui perkawinan. (Erlang, 68)
Suara batin Taksilitoni soal mengurut asal-usul uma yang tidak mungkin terhindar dari kisah konflik dan perpecahan kekerabatan ini tentunya juga dapat kita temukan dalam penjelasan Tulius dalam “Family Stories”, yang saya terjemahkan sebagai berikut:
Dalam proses perluasan silsilah, beberapa keluarga tetap tinggal di tempat pemukiman pertama sementara yang lain mencari tempat tinggal lain. Keluarga-keluarga di tempat asal atau pemukiman pertama terkadang membentuk kelompok kekerabatan baru. Sementara itu, keluarga migran yang pindah ke tempat baru jarang sekali kembali ke tempat asalnya, apalagi jika keputusan mereka untuk berangkat dilatarbelakangi oleh konflik yang krusial dan sensitif seperti penghinaan terhadap anggota keluarga tertentu. Ketika keluarga-keluarga yang bermigrasi memutuskan untuk menempuh arah yang berbeda, terkadang mereka memutuskan untuk berpisah lagi meskipun mereka telah membentuk kelompok kekerabatan baru. Belakangan, di tempat baru, keluarga-keluarga ini membentuk kelompok kekerabatan baru lagi.[16]
Dalam disertasi doktornya, Tulius setidaknya memberikan tiga buah contoh cerita keluarga yang masing-masing terdiri dari tiga versi, yaitu The Mango Story (Cerita Mangga), The Pig Story (Cerita Babi), dan The Wild Boar Story (Cerita Babi Hutan)—yang diperolehnya dari para narasumber berbeda-beda yang berasal dari uma berbeda-beda pula selama masa penelitian lapangan di Kepulauan Mentawai.
Ketiga cerita keluarga asli Mentawai paling terkemuka ini pulalah yang dipungut oleh Niduparas Erlang untuk Burung Kayu, di mana The Pig Story (atau kisah tentang babi sigelag) ditempatkannya pada porsi yang paling besar dan dijadikannya sebagai titik tolak bagi pengisahan novel—muara dari segala cerita silang sengketa antara suku-sura’-boblo dan suku-tunggul-kelapa yang mengakibatkan kematian Aman Legeumanai dan membuat Saengrekerei memutuskan untuk membawa keluarganya pindah ke barasi bikinan pemerintah.
Alasan Nidu menggunakan Cerita Babi ini sebagai “fondasi” novel tampaknya sama dengan alasan Tilius memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi tentang migrasi awal nenek moyang Mentawai dan menggambarkan perluasan kelompok kekerabatan Mentawai. Sebab dibandingkan dengan Cerita Mangga maupun Cerita Babi Hutan yang juga sama-sama mengisahkan perpindahan beberapa kelompok kerabat Mentawai, Cerita Babi adalah kisah yang paling kompleks. Cerita ini juga menggambarkan proses pemisahan: keluarga-keluarga dari kelompok kekerabatan tertentu terpecah menjadi beberapa kelompok kekerabatan baru. Selain itu, ia juga memperlihatkan salah satu aspek budaya Mentawai, yaitu peternakan. Apalagi hewan peliharaan seperti babi memilki tempat penting dalam budaya Mentawai, yang bakal menunjukkan betapa sejahtera dan dihormatinya orang tersebut.
Ketiga versi Cerita Babi yang dicatat oleh Tulius dalam Family Stories berdurasi cukup panjang (meskipun durasi berkisah setiap pendongengnya beragam), sehingga agak sulit bagi saya untuk mengutipnya secara utuh dalam tulisan ini. Namun, dari hasil pembacaan saya, baik atas ketiga versi Cerita Babi itu secara langsung maupun dari interpretasi Tulius, secara garis besar tidaklah terdapat banyak perbedaan dari ketiganya kecuali menyangkut hal-hal yang bersifat lebih terperinci.
Hal ini, menurut Tulius, lantaran masyarakat Mentawai sebetulnya tidak mudah menoleransi adanya versi lain dari cerita keluarga mereka. Karenanya, terdapat aturan dan cara yang dapat menjadi pedoman bagi para pendongeng untuk mengisahkan cerita keluarga-nya dengan baik. Seperti, mereka akan memilih kesempatan tertentu untuk bercerita, juga memilih para tetua tertentu untuk memainkan peran sebagai pendongeng terkemuka dalam keluarga mereka. Para tetua ini akan menjaga cerita keluarga mereka secara hati-hati dengan menyampaikannya akurat mungkin kepada generasi muda, sebagian besar kepada mereka yang dianggap memiliki kualitas dan bakat dalam berbicara, mendengarkan, dan menghafal.[17] Dengan cara inilah, cerita keluarga membawa masa lalu suatu kelompok kekerabatan ke masa kini—demi memelihara identitas kekerabatan maupun untuk menjaga klaim atas tanah.
Salah satu kategori peristiwa masa lalu yang masih mempengaruhi kehidupan kelompok kekerabatan saat ini adalah konflik pertanahan. Konflik pertanahan tak hanya terjadi pada masa lalu, namun juga terjadi pada masa kini. Jika kita melihat luas Kepulauan Mentawai dan jumlah penduduk yang tinggal di pulau-pulau tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lahan di Mentawai masih melimpah. Jumlahnya mencapai 13 orang per kilometer persegi lahan. Karena itu, kita takkan menemukan konflik serius mengenai kepemilikan atau penggunaan lahan. Ketika konflik pertanahan terjadi, cerita keluarga berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan.(Tulius, 17)
Perhatikan kutipan narasi tentang perselisihan antara Aman Maria dari suku-batang-langsat dan Aman Takgougou dari suku-titik-air akibat perebutan leleu (wilayah hutan yang belum dikelola akan tetapi sudah pernah diberi batas) berikut ini:
Nen! Beberapa waktu lalu, kedua suku itu memang terlibat dalam perebutan leleu Palekuteteket yang banyak ditumbuhi durian, nangka, rambutan, langsat, sagu, rotan, yang menjulang tinggi di belakang barasi. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan Aman Maria dan Aman Takgougou memulai perselisihan, pertikaian, dan perebutan leleu Palekuteteket itu. Hanya saja, dari keduanya terlalu sering terdengar dengung ancaman dan cercaan dibarengi ejekan-ejekan yang memekakkan telinga warga barasi. Lalu, keduanya mendatangkan para kerabat yang mereka anggap paling menguasai titiboat, cerita-keluarga dan sejarah-kepemilikan-tanah, yang menguarkan kisah-kisah dari para leluhurnya. (Erlang, 106)
Dalam cerita keluarga inilah setidaknya tersimpan tiga perkara terpenting dari sebuah kelompok kekerabatan, yakni nenek moyang kelompok tersebut, tanah leluhur yang mereka klaim, dan hubungan kekeluargaan mereka dengan kelompok-kelompok lain yang kini tinggal di tempat terpisah di Kepulauan Mentawai.
Jika kelompok-kelompok kekerabatan ini berasal dari keluarga leluhur yang sama, maka kelompok-kelompok tersebut biasanya menuturkan cerita keluarga yang sama tentang leluhur mereka. Namun begitu, toh ragam perbedaan versi dan potensi perubahan tetaplah menjadi sebuah keniscayaan yang terjadi dalam pengisahan cerita keluarga secara berulang-ulang dan turun-temurun oleh berbagai pendongeng dari beragam kelompok kekerabatan yang terpisah, yang juga dipengaruhi oleh bakat-kemahiran berkisah dan daya ingat sang pendongeng:
Dalam sebuah kelompok kekerabatan, beberapa orang mempunyai bakat alami dalam bercerita, sementara orang lain perlu mendengarkan cerita yang sama beberapa kali sebelum dapat mengingat kembali keseluruhan cerita. Mereka harus berlatih berulang-ulang hingga terampil bercerita. Hal ini menandakan bahwa tak semua anggota suatu kelompok kekerabatan mempunyai kemampuan yang sama dalam mengisahkan cerita keluarga. Pendongeng yang berbeda mungkin menceritakan versi cerita yang berbeda. Munculnya versi yang berbeda tidak terlalu menjadi masalah bagi masyarakat Mentawai selama cerita keluarga tersebut tidak menimbulkan kontroversi di kalangan pendengar. Penting bagi pendengar untuk mengetahui tema-tema besar sebuah cerita agar mereka dapat meneruskan cerita tersebut kepada generasi berikutnya dengan baik. Untuk melakukan hal tersebut, para tetua membutuhkan generasi muda yang dapat mengingat berbagai hal dengan baik. (Tulius, 209)
Namun, lain perkaranya dengan kasus Cerita Mangga (Sipeu). Di antara ketiga cerita keluarga terpenting Mentawai, Cerita Mangga tampaknya merupakan cerita yang paling longgar, yang perbedaan versinya lebih mencolok, utamanya sebagai subjek awal konflik keluarga, tetapi tidak menjadikannya sebuah persoalan berarti. Bahkan kisah ini juga diceritakan oleh dua atau lebih kelompok kekerabatan berbeda yang tak memiliki hubungan kekerabatan akibat pengadopsian.[18]
Meskipun berbagai versi Cerita Mangga semuanya memiliki unsur serupa, yakni para pendongeng memberitakan suatu tempat asal dari mana nenek moyang mereka berangkat, tidak ada satu pun versi cerita yang secara eksplisit menghubungkan pergerakan migrasi dengan klaim atas bidang tanah tertentu. Para pendongeng hanya menceritakan bahwa nenek moyang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal inilah yang menjadikan Cerita Mangga berbeda dengan kebanyakan cerita keluarga yang cenderung menekankan kepemilikan atas bidang tanah tertentu, dan menunjukkan Cerita Mangga sepertinya lebih fokus kepada konflik dan migrasi.
Boleh jadi ini karena Cerita Mangga merupakan cerita keluarga yang lebih tua sehingga kepemilikannya (ownership of family stories) tidak lagi cukup jelas. Seperti yang ditulis Tulius: “Setiap kelompok menceritakan versi Cerita Mangga di mana keluarga tersebut awalnya tinggal di lembah Simatalu dan berangkat dari sana. Namun, kelompok kekerabatan ini tak menyarankan adanya hubungan dengan kelompok kekerabatan lain yang juga pernah saya dengar Cerita Mangga-nya. Pendongeng kelompok kekerabatan Siribetug yang menceritakan Cerita 7 tidak menyebut kelompok kekerabatan Satairarak sebagai kerabatnya, begitu pula pendongeng Satairarak yang menceritakan Cerita 9 tidak menyebut kelompok kekerabatan Siribetug sebagai kerabatnya.”[19]
Ada sejumlah kemungkinan mengapa sebuah cerita bisa diadopsi oleh kelompok kekerabatan lain yang bukan anggota cerita tersebut, antara lain melalui pernikahan seperti kasus Taksilitoni (Bai Legeumanai) dalam Burung Kayu, pengangkatan anak (sinappit) dari suku lain, dan persahabatan (siripo) yang erat antar-uma. Akibatnya, beberapa unsur penting dari cerita tersebut berubah ketika diceritakan oleh kelompok kekerabatan yang bukan anggota cerita. Hal ini tergambar dalam Cerita Mangga yang dituturkan oleh Taikatubutoinan; ia mengakui bahwa cerita tersebut bukanlah miliknya atau sukunya.
Sang pendongeng menceritakan unsur-unsur dasar alur Cerita Mangga sedemikian rupa sehingga pendengar dapat dengan mudah mengenali bahwa Cerita Mangga yang dituturkannya adalah versi Cerita Mangga di tempat lain. Namun ia tidak mengisahkan elemen-elemen penting yang menjadi ciri identitas sebuah kelompok kekerabatan yang menjadi bagian dari Cerita Mangga tersebut. Dalam kasus seperti ini, yakni apabila sebuah cerita keluarga diceritakan oleh pendongeng yang bukan pemilik cerita, maka cerita tersebut tidak lagi berfungsi sebagai catatan sejarah, karena sang pendongeng tidaklah mengetahui pokok-pokok mana yang penting bagi si pemilik cerita.
Bahkan dalam kajiannya atas cerita keluarga, Tulius juga menemukan versi Cerita Babi Hutan yang bukan dituturkan oleh kelompok kekerabatan yang menjadi pewaris orisinal cerita tersebut, yakni yang dituturkan oleh pendongeng dari suku Sakuddei bernama Aman Dumatkerei di desa hulu Sagulubbe bagian barat daya Siberut, yang direkam oleh Professor Reimar Schefold dalam penelitian lapangannya pada 1967. Hal ini lantaran sang pendongeng merupakan anggota kelompok kekerabatan bernama Satoleuru yang pernah mendiami lembah Rereiket, tempat tinggal suku Sakuddei sebelum pindah dan menetap di hulu sungai Sagulubbe.
Akibatnya menurut Tulius, sang Pendongeng Sakuddei tidak peduli dengan isi sebenarnya dari Cerita Babi Hutan tersebut, dan tak menyebutkan tempat asal dirinya maupun nama nenek moyangnya yang terkena dampak insiden babi hutan itu. Ia hanyalah mengisahkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama cerita agar anggota keluarganya tak mengejeknya. Meskipun tempat-tempat tokoh itu bermigrasi disebutkan, cerita versi Pendongeng Sakuddei ini tidak lagi berfungsi sebagai catatan sejarah, karena berbagai tambahan yang dimaksudkan sebagai penghiburan telah mengubah tujuan cerita. Di tangan Pendongeng Sakuddei, Cerita Babi Hutan itu berubah menjadi sekadar kisah menghibur yang bisa ditertawakan oleh para pendengarnya. Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan suatu cerita keluarga dapat mengubah cerita tersebut, atau dengan bebas memodifikasinya untuk kepentingan hiburan atau tujuan lain, sehingga membuat cerita itu tak lagi berfungsi sebagai sumber informasi tentang suatu suku.[20]
Apa yang dilakukan oleh Pendongeng Sakuddei ini boleh jadi hampir mirip dengan posisi Nidu sebagai seorang pencerita baru, yakni mengisahkannya ulang sembari mencoba memberinya tafsir yang lebih segar dan menyesuaikannya dengan konteks kekinian demi kepentingan cerita yang luas. Sehingga seperti Sakuddei, Nidu seyogianya pun bisa mengaku bahwa, “Kisah ini milik kelompok yang disebut Satoleuru, menceritakan tentang nenek moyang mereka.”[21]
Namun, dalam novelnya itu Nidu tidak memberi kita catatan apa pun mengenai narasumber maupun daftar pustaka yang menjadi rujukan cerita-cerita keluarga yang ia pungut. Apakah dengan demikian, Nidu dapat dianggap sebagai seorang pencuri kisah atau dituduh sebagai plagiator atas cerita keluarga dalam tradisi lisan masyarakat Mentawai?
Tentu tidak. Sekalipun dalam kasus penulisan ulang atas titiboat ini, Nidu tidaklah melakukan perombakan yang berarti terhadap isi ketiga cerita keluarga yang ia ambil, kecuali sekadar mengganti nama-nama. Contohnya dalam penulisan kembali Cerita Babi. Cerita ini aslinya melibatkan dua keluarga bertetangga, yakni Emeiboblo dari uma Samongilailai dan keluarga Sapokka di Simatalu. Namun oleh Nidu, kedua nama tersebut digantinya menjadi Baumanai dan Babuisiboje sembari tetap mempertahankan nama tempat Simatalu.
Cerita Babi yang digunakan oleh Nidu ini paling mirip dengan versi Cerita Babi yang disampaikan kepada Tulius pada 2004 oleh Aman Maom (bernama muda: Terig Kerei), seorang sikerei dari suku Salamao anggota kelompok kekerabatan Samongilailai yang tinggal di desa Taileleu bagian barat daya Siberut. Berikut ini saya kutipkan dan terjemahkan penggalan Cerita Babi versi Aman Maom:
Kami pindah dari Simatalu karena terlibat perselisihan dengan kelompok kekerabatan bernama Sapokka. Perselisihannya adalah tentang babi. Nenek moyangku menceritakan sebuah kisah yang harus selalu kami ingat. Ceritanya adalah sebagai berikut. Nenek moyang kami tinggal di Simatalu, dan Sapokka menjadi salah satu tetangga nenek moyang kami. Salah satu putra Sapokka menikah dengan salah satu putri nenek moyang kami. Emeiboblo adalah nenek moyang kami yang terkemuka tatiaoa penyerangan itu terjadi. Sapokka menawarinya seekor babi sebagai mahar. Oleh karena itu, nenek moyang kami sangat menghormati Sapokka.
Suatu hari, Sapokka menombak babi yang diberikannya sebagai mas kawin nenek moyang kami. Usai menombak babi itu, keluarga Sapokka mengabaikan fakta bahwa menantu mereka berasal dari Samongilailai. Ia sepertinya mengenali babi itu dan ia menanyakan hal tersebut, tetapi mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, ayahnya, Emeiboblo, datang mengunjungi Sapokka, “Mungkin, kau sudah melihat babiku, saudara iparku tersayang (kaddei). Aku telah kehilangan babi itu beberapa hari terakhir ini. Aku kira babi itu telah kembali kepada kalian, karena ia berasal dari sini. Karena itu, aku datang untuk menanyakan apakah kau melihatnya di sini akhir-akhir ini.” Sapokka menyangkalnya, “Tidak, kami tak melihat satu pun babi yang kami berikan kepadamu.” Tentu saja Sapokka sengaja berbohong kepada Emeiboblo. Putri Emeiboblo mendengar percakapan mereka.
Setelah itu, ia pergi mengunjungi rumah ayahnya dan mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang babi yang dimakan oleh keluarga Sapokka beberapa hari terakhir. Setelah mendengar cerita putrinya, Emeiboblo memutuskan untuk meminta denda dari Sapokka. Emeiboblo mencari beberapa orang sebagai mediator (sipasaili atau sipasuili) untuk merundingkan perselisihan yang timbul antara dirinya dan Sapokka. Para perunding pun tiba di rumah Sapokka, “Kami datang untuk mewakili Emeiboblo, yang babinya telah ditombak dan dimakan oleh kalian. Emeiboblo sudah tahu bahwa babi miliknya telah ditombak karena putrinya telah menceritakan hal itu kepadanya. Karena itu, kami sekarang datang untuk meminta kalian membayar denda atas penombakan babi (tulou saina). Kau harus membayar seekor babi kepada Emeiboblo agar bisa berbaikan lagi dengannya.” Setelah mendengar tuduhan itu, Sapokka berkata, “Jadi, itulah alasan kalian datang ke sini. Emeiboblo mengetahui tentang babinya dari putrinya. Karena anak perempuannya itu melaporkan kami kepada ayahnya, kami tidak akan membayar denda. Kami mengakui bahwa kami menombak babi itu untuk tujuan khusus, tapi kami takkan membayar dendanya.” Para mediator kembali ke Emeiboblo dan melaporkan apa yang dikatakan Sapokka. Namun, Emeiboblo berusaha untuk tetap tenang. Ia menunda pembahasan kasus itu, ia menunda, menunda, menunda demi mencari cara lain untuk mendesak Sapokka mengganti babi yang ditombak itu. Emeiboblo butuh waktu untuk berpikir tetapi itu tidaklah cukup lama. Setelah menunggu beberapa hari, Emeiboblo mengasah parang dan tombaknya. Ia tidak membawa busur (rourou) dan anak panah beracun (silogui) ketika berkunjung ke rumah keluarga Sapokka. Ia mencoba untuk tidak menarik perhatian Sapokka.
Di rumah, anggota keluarga Sapokka sedang memasak pisang. Emeiboblo melontarkan pertanyaan kepada mereka saat ia duduk di sebelah mereka, “Kenapa kalian tak memenuhi permintaan perunding yang aku kirim untuk bicara dengan kalian, bahwa kalian harus membayarku seekor babi sebagai pengganti apa yang kalian tombak?” Keluarga Sapokka sengaja menjawab permintaan Emeiboblo dengan jawaban menantang, “Kami tidak mau membayarnya karena kami tak mau melakukannya. Kalau kau ingin mendapatkannya kau harus melakukannya dengan parang dan tombak yang berkilau tajam.” Seraya beranjak berdiri, Emeiboblo berkata, “Aku akan melakukan apa yang kau inginkan.” Dan pada saat berikutnya ia melemparkan tombaknya menikam orang yang menjawabnya tersebut, yang sedang memasak pisang, lalu mengayunkan parangnya ke satu orang lagi yang duduk di sebelahnya. Keluarga Sapokka yang tersisa lari berhamburan keluar rumah. Kemudian Emeiboblo kembali ke rumahnya. [22]
Hal yang serupa dilakukan pula Nidu untuk Cerita Babi Hutan yang dikisahkannya lewat mulut Saengrekerei. Di sini juga hampir tidak ada perubahan berarti pada cerita tentang Silango (berarti “orang pingsan”) yang dikisahkannya ulang pada halaman 158-164, yakni tentang seorang kepala keluarga yang menemukan tujuh atau delapan ekor babi hutan pingsan di bawah pohon laggure yang buahnya beracun sehingga siapa pun yang memakannya bakal pingsan atau mati. Babi hutan-babi hutan itu pingsan karena telah memakan buah laggure. Dalam cerita ini, Nidu cuma mengubah nama asli Silango saja, dari Sikoibatei yang berarti “pemakan hati hewan” menjadi Sikoibat. Perhatikan kutipan di bawah ini yang merupakan Cerita Babi Hutan versi penuturan Lemanus Saleleusi dari wilayah Paipajet, Siberut:
Nama akrab nenek moyang kita adalah Silango [yang artinya “si pingsan”]. Tetapi nama aslinya adalah Sikoibatei [pemakan hati hewan]. Ia berdiam di suatu tempat di tepi sungai Simatalu. Nenek moyang kami disebut Silango karena siberi [insiden babi hutan]. Cerita keseluruhannya adalah sebagai berikut. Suatu hari, Silango atau Koibatei [kependekan dari Sikoibatei] pergi berburu binatang di hutan. Ketika sedang berburu, ia menemukan beberapa ekor babi hutan tergeletak tak sadarkan diri di tanah di bawah pohon laggure. Pohonnya berbuah, dan buah laggure memiliki zat beracun yang dapat menyebabkan orang yang memakannya pingsan tak sadarkan diri atau bahkan mati.[23]
Selebihnya antara cerita Nidu dan cerita Saleleusi ini nyaris tidak terdapat perbedaan. Yakni bahwa dalam suka citanya menemukan babi hutan-babi hutan itu tak berdaya, Silango merasa tidak perlu menombak atau mengikat babi-babi liar tersebut, dan hanya memanggul pulang seekor saja.
Namun, alih-alih membawa babi hutan itu ke rumah komunal (uma), ia malah menempatkannya di dekat rumpun bambu yang terletak di dekat rumahnya (sapou). Hal itu dilakukannnya karena hendak memberi kejutan kepada kerabatnya. Kemudian katanya kepada istrinya, “Tolonglah pergi mengumpulkan bambu dengan saudara ipar (eira) kita untuk memasak. Saudara-saudara laki-laki kita akan mengumpulkan babi hutan di hutan.” Namun, lantaran hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, para kerabat lelakinya tak bisa segera berangkat untuk mengambil babi hutan pingsan itu. Mereka baru bisa pergi setelah hujan reda. Sesampai mereka di pohon laggure yang dimaksud, celeng-celeng itu sudah tak ada lagi. Rupanya babi-babi liar itu terbangun oleh guyuran hujan dan melarikan diri. Alhasil orang-orang itu pun pulang dengan tangan kosong.
Cerita Babi Hutan ini cukup panjang. Intinya, seperti yang dikisahkan kembali oleh Nidu dalam Burung Kayu, untuk mengobati kekecewaan sanak saudaranya, Sikoibat lantas menyembelih babi-babi peliharaannya sendiri sebagai pengganti dan mengadakan pesta. Selepas makan, para ipar perempuan dan menantunya lalu menyanyikan sebuah lagu untuk meninabobokan anak-anak dengan lirik yang membuat Sikoibat amat gusar, “Karena silango, kami baru saja makan daging babi ayah kami”. Lagu itu diulang terus-menerus setiap hari. Kendati Sikoibat kemudian benar-benar berhasil menangkap seekor babi hutan dengan perangkap, tetapi para perempuan di uma itu kembali menyanyikan sebuah lagu yang terasa mengolok-oloknya: “Kami baru saja merayakan pesta, kami berpesta karena silango.”
Berkali-kali ia berhasil menjebak babi hutan, tapi para perempuan tetap saja bernyanyi tentang dirinya, dan menjulukinya Silango atau orang yang pingsan. Akibat tidak bisa menahan sakit hati, suatu hari Sikoibat pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari uma dan tinggal di Simalegi. Ia enggan kembali lagi ke uma-nya walaupun saudara-saudaranya mencarinya dan memintanya untuk pulang. Ia justru pergi semakin jauh.
Novel Residensi: Sebuah Kerja Etnografis
Ritual tatung yang sempat saya singgung pada awal tulisan ini adalah bagian dari budaya asli saya, yang “hidup” di lingkungan terdekat saya dan dilakoni oleh keluarga besar saya sejak saya kecil. Namun, tentunya tidak demikian dengan Nidu terkait lokalitas Mentawai yang diangkatnya dalam Burung Kayu. Nidu adalah penulis berdarah Sunda-Banten yang lahir di Serang dan dibesarkan di wilayah Banten. Karena itu, menulis cerita yang mengambil latar tempat di Mentawai, tentang orang-orang dan kebudayaan Mentawai, baginya adalah menulis tentang sesuatu yang asing. Dengan kata lain, ia adalah seorang sasareu (orang luar) yang mencoba menulis tentang orang lain (the other). Untuk itulah ia membutuhkan riset, baik lewat kajian pustaka maupun penelitian lapangan, melalui wawancara maupun pergaulan dengan orang-orang Mentawai yang menjadi pokok pengisahannya.
Tentu tidak masalah jika seorang penulis hanya melakukan studi pustaka saja alias menulis berdasarkan hasil riset orang lain. Atau, mencoba menggali data melalui berbagai obrolan jarak jauh dengan sejumlah narasumber dari daerah yang bakal ia jadikan sebagai setting lokasi cerita, seperti misalnya yang dilakukan oleh Aveus Har selaku penulis berlatar Jawa ketika menggarap novelnya Tak Ada Embusan Angin yang mengambil latar di Aceh.[24] Kita juga bisa merujuk kepada karya novelis Cina-Amerika Maxine Hong Kingston (湯婷婷) seperti The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts (1976) dan China Men (1980). Kedua novel semi-autobiografis yang mengisahkan sebagian kehidupan keluarganya di Cina Daratan ini ditulis Kingston hanya berdasarkan cerita-cerita lisan para wanita dalam keluarganya saja.[25]
Bahkan di ranah cerita silat Tanah Air, kita juga mengenal seorang Asmaraman S. Kho Ping Hoo yang sedikitnya telah menulis 120 judul cerita dan sebagian besar mengambil latar di Cina Daratan, kendati ia belum pernah menginjakkan kakinya di Cina sebelum tahun 2000-an.[26] Berbekal tontonan film-film kungfu Hongkong dan Taiwan, tampaknya juga berbekal bacaan atas cerita-cerita silat Cina terjemahan, ia mampu menghasilkan karya-karya cerita wuxia yang memukau begitu banyak pembaca pada era kejayaannya hingga saat ini.[27]
Namun, mengandalkan studi pustaka saja bakal memiliki banyak kelemahan. Di samping harus mendalami lebih banyak sumber referensi, bukanlah soal mudah bagi seorang penulis untuk mengembangkan “imajinasi hipotesis” karena tidak bisa merasakan secara langsung atmosfer (kondisi dan suasana) latar tempat yang mesti ia bangun ulang ataupun bersentuhan secara intens dengan masyarakat setempat untuk memahami lebih dalam emosi dan cara berpikir mereka.
Keberhasilan Maxine Hong Kingston menulis Cina yang belum pernah ia kunjungi kala itu (walau tidak lepas dari berbagai kritik tajam para kritikus sastra Inggris asal Cina), adalah lantaran ia dilahirkan dan dibesarkan di Stockton, California, oleh sepasang orang tua Cina totok—imigran asal Kanton (Guangdong) yang selalu gagap ketika mencoba menjadi warga negara Amerika Serikat tetapi mengenang Cina dengan penuh kerinduan.
Ya, kesadaran tentang tidak memadainya studi pustaka inilah yang membuat Nidu memutuskan untuk melakukan penelitian lapangan di pulau Siberut, Mentawai, ketika kesempatan untuk itu terbuka baginya berkat Program Residensi Komite Buku Nasional (KBN).[28] Selama dua bulan (September-November 2018) ia kemudian tinggal dan bergaul bersama masyarakat Sarereiket di lembah sungai Rekeiket. Ada pun ketertarikan Nidu terhadap tradisi lisan dan masyarakat adat Mentawai ini bermula ketika ia membaca kajian tentang Mentawai karya Profesor Reimar Schefold, “Aku dan Orang Sakuddei: Mainan Bagi Roh”. Apalagi Nidu sendiri memang memiliki latar belakang pendidikan yang menunjangnya untuk melakukan riset, yakni Pascasarjana Kajian Tradisi Lisan di Universitas Indonesia. Bahkan lebih jauh, menurut Nidu, rencana tesisnya pun sebetulnya sempat ditujukan untuk menggali khazanah tradisi lisan orang Mentawai. Hanya saja ada berbagai kendala yang kemudian membuatnya tak jadi melanjutkan tesis tersebut. [29]
Karena itu, Burung Kayu bisa dikatakan sebagai sebuah novel riset, yang ditulis berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada (studi pustaka), juga fakta lapangan di Mentawai. Apakah dengan demikian, ia dapat dikategorikan sebagai novel etnografis seperti yang disebut-sebut dalam sejumlah tulisan? Sayangnya, kebanyakan tulisan yang saya maksud ini tidak menjelaskan definisi dari novel etnografis itu, bahkan tidak menyinggung sedikit pun apa yang disebut sebagai etnografi.
Maka, penting di sini bagi kita untuk memeriksa apa itu etnografi dan apa pula itu novel etnografis, sehingga dengan begitu kita bisa menyatakan bahwa Nidu memang seorang novelis etnografer yang, meminjam Maskota Delfi, menyajikan opini dan imajinasinya berdasarkan pengalaman observasi dan wawancara mendalam dengan subjek yang ditulisnya.[30]
Etnografi, menurut Wikipedia, adalah “a branch of anthropology and the systematic study of individual cultures. Ethnography explores cultural phenomena from the point of view of the subject of the study. Ethnography is also a type of social research that involves examining the behavior of the participants in a given social situation and understanding the group member’s own interpretation of such behavior.” Ilmu ini bermula dari antropologi sosial dan budaya pada awal abad ke-20, kemudian menyebar ke disiplin ilmu sosial lainnya, termasuk sosiologi.[31] Sementara itu menurut Britannica.com, etnografi merupakan “descriptive studi of a particular human society or the process of making such a studi.” Di mana etnografi kontemporer hampir seluruhnya didasarkan pada kerja lapangan yang menuntut pendalaman menyeluruh para antropolog atas kebudayaaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang menjadi subjek studinya. [32]
Oleh sebab itu, sebagai suatu bentuk penelitian, etnografi amat bergantung pada observasi partisipan, yakni peneliti yang berpartisipasi dalam suatu latar atau dengan orang-orang yang diteliti, setidaknya dalam peran marjinal tertentu, dan berusaha untuk mendokumentasikan secara rinci pola-pola interaksi sosial dan perspektif orang-orang yang diteliti itu untuk memahami konteks lokal mereka.
Secara tradisional, etnografer memusatkan perhatian pada suatu komunitas; memilih informan yang berpengetahuan luas dan mengetahui aktivitas komunitas dengan baik. Informan ini biasanya diminta untuk mengidentifikasi informan lain yang mewakili masyarakat, sering menggunakan pengambilan sampel snowball atau chain. Etnografi sangat bergantung kepada pengalaman pribadi dan keintiman. Partisipasi, bukan sekadar observasi, adalah salah satu kunci proses ini. Berbagai metode pengumpulan data dapat digunakan untuk memfasilitasi hubungan yang memungkinkan gambaran yang lebih personal dan mendalam tentang informan dan komunitas mereka. Ini dapat mencakup observasi partisipan, catatan lapangan, wawancara dan survei, serta berbagai metode visual.
Apa itu observasi partisipan? Observasi partisipan adalah salah satu jenis metode pengumpulan data yang dilakukan oleh para praktisi-cendekiawan yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif dan etnografi. Metode jenis ini digunakan di banyak disiplin ilmu, khususnya antropologi (termasuk antropologi budaya dan etnologi), sosiologi (termasuk sosiologi budaya dan kriminologi budaya), studi komunikasi, geografi manusia, dan psikologi sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keakraban yang dekat dan intim dengan sekelompok individu tertentu (seperti kelompok agama, pekerjaan, kelompok pemuda, atau masyarakat tertentu) dan praktik-praktik mereka—melalui keterlibatan intensif dengan orang-orang dalam lingkungan budaya mereka, biasanya dalam jangka waktu yang lama. [33]
Inilah juga yang dilakukan oleh Nidu sebagai seorang peneliti Tradisi Lisan Mentawai. Katanya dalam sebuah wawancara tertulis yang diunggahnya kembali di akun Facebook-nya:
Dalam kasus saya (tentu akan berbeda dengan kasus yang terjadi dalam penelitian lain dan oleh peneliti lain), yang mesti saya hindari, di antaranya: menghindari merasa lebih pintar ketimbang informan yang saya wawancarai, menghindari kekeliruan dalam memahami apa-apa yang saya dapatkan baik melalui riset pustaka maupun riset lapangan, menghindari berbagai tabu yang berlaku dalam masyarakat yang sedang saya teliti, dan sebagainya. Sementara yang harus saya lakukan adalah berupaya terus-menerus untuk memahami cara berpikir, berekspresi, dan sebagainya dari masyarakat yang sedang saya teliti, mencatat dan merekam semua hal untuk membantu saya menuliskannya kelak, dan berulang kali melakukan konfirmasi baik kepada peneliti sebelumnya maupun kepada informan-informan saya. Sederhananya, saya perlu terus-menerus belajar dari masyarakat yang sedang saya teliti itu, terus-menerus berupaya memahami berbagai hal yang saya dapatkan dari hasil belajar itu.[34]
Karena itulah, dalam kasus pengambilan cerita keluarga di atas, Nidu tidaklah mencoba mengubah isi cerita, tetapi hanya mengadopsinya untuk dikisahkan kembali dalam perspektif terbatas yang lebih segar, yang di satu sisi mengolahnya menjadi (bagian dari) sebuah karya sastra yang lebih menarik untuk dibaca dan di sisi lain mencoba mempertahankannya sebagai sebuah kajian etnografi. Hal ini persis seperti yang diungkapkan oleh Vito Laterza dalam artikelnya, “The Ethnographic Novel: Another Literary Skeleton in the Anthropological Closet?” di Suomen Antropologi,· Januari 2007:
Ketertarikan para antropolog terhadap artefak sastra memiliki sejarah yang panjang. Sejak lahirnya disiplin ilmu ini, sejumlah besar orang telah menerbitkan karya sastra bersamaan dengan karya etnografi mereka (Schmidt 1984). Banyak yang terlibat dalam penulisan cerita pendek atau novel yang dimaksudkan untuk menyampaikan gambaran tentang cara hidup subjek etnografi mereka (Langness & Frank 1978). Bagi yang lain, kisah-kisah novelistik merupakan format yang cocok untuk mengekspresikan komponen pribadi dari pengalaman kerja lapangan yang biasanya ditekankan dalam etnografi konvensional mereka (Tedlock 1991).[35]
Namun, akankah format novel ini memang dapat memberikan nilai tambah bagi usaha etnografi? Bagaimana dengan kontradiksi antara sifat fiksi novel dan prinsip kebenaran yang semestinya memandu karya etnografer?
Dalam definisi umum, novel lebih disiratkan sebagai karya imajinasi pengarangnya, karena itu perbedaan antara fakta dan fiksi pun kemudian mengemuka jadi persoalan di sini. Misalnya pendapat bahwa bahwa novelis cenderung tidak berkomitmen pada penyediaan representasi yang jujur, sehingga masalah komitmen terhadap prinsip kebenaran adalah pertanyaan penting yang harus diajukan untuk novel etnografis[36]—juga ethnofiction.
Tantangan para etnografer lainnya ketika menuliskan hasil penelitian dalam bentuk novel adalah novel biasanya amat menekankan karakter. Fokus pada karakter ini berpotensi memaksa novelis-etnografer untuk melakukan bias budaya mengenai isu-isu penting seperti konstitusi subjek dan hubungan antara individu dan masyakarat. Selain itu, apabila intropeksi langsung digunakan untuk menyuarakan pikiran karakter informan, hal ini bakal menciptakan tantangan lain atas “nilai kebenaran novel” dari sang novelis-etnografer. Jelaslah bahwa seorang etnografer tidak dapat membaca pikiran orang lain. Lalu bagaimana ia akan menampilkan suara batin para karakter?[37]
Penggunaan karakter ini meskipun memungkinkan seorang etnografer untuk mengekspresikan berbagai pendapatnya lewat suara para tokoh, hal ini mungkin menjadi hambatan ketika muncul kebutuhan untuk membangun otoritas etnografis. Bagaimana sang etnografer memposisikan dirinya dalam teks? Ada yang berargumentasi bahwa jika etnografer muncul dalam teks sebagai seorang tokoh, maka terdapat risiko untuk menghasilkan keterangan “pengakuan” yang lain. Terakhir, ada yang berpendapat bahwa estetika genre novel tidak memberikan ruang bagi produksi teoretis yang ketat. Plot dan cerita bisa jadi merupakan alat yang baik untuk menyajikan data empiris, tetapi tentunya tak dapat dijadikan argumentasi teoritis.
Namun, menurut Laterza, pertentangan antara fiksi dan fakta tidaklah harus meruncing dalam kasus ini. Sebab, bukankah fiksi populer pun dapat dipelajari sebagai bentuk etnografi lantaran seringkali berisi deskripsi etnografi rinci dan pernyataan analitis tentang realitas sosial? Lagipula, definisi klasik novel sebagai semata-mata karya fiksi tidaklah memperhitungkan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada paruh kedua abad ke-20, contohnya ketika apa yang disebut sebagai “novel nonfiksi” telah menjadi subgenre yang sah dari novel.
Kehadiran karakter ini, bagi Laterza, malah dapat dimanfaatkan untuk melayani berbagai tujuan etnografis khusus. Potret sastra yang menitikberatkan pada postur tubuh, aspek fisik, busana, dan ciri-ciri perilaku yang khas justru dapat meningkatkan efek realistis etnografi. Dengan demikian, pembaca akan lebih mudah memahami argumen teoretis yang disajikan apabila argumen tersebut dituangkan ke dalam cerita yang melibatkan karakter yang menyerupai individu dalam kehidupan nyata. Sehingga para karakter memungkinkan etnografer mengungkap pandangan tertentu tentang subjektivitas dan intersubjektivitas dalam masyarakat yang diteliti.
Kehadiran karakter ini juga membantu etnografer menghindari tampilnya subjek-subjek tidak manusiawi (de-humanised subjects), yang kerap direpresentasikan sebagai objek pengetahuan yang kering dan tipe abstrak dalam laporan-laporan etnografi. Sehingga dalam novel etnografis, para partisipan riset pun dapat hadir sebagai manusia, dengan segala emosi dan kontradiksi, sebagai agen aktif dan diri yang berbicara (speaking self). Lalu yang terpenting, representasi para partisipan riset sebagai karakter utuh yang disertai laporan narasi personal mereka melalui direct speech dan dialog juga memungkinkan ekspresi berbagai suara (the expression of multiple voices).[38] Dengan begitu, terbangunlah sebuah novel etnografis yang secara eksplisit berkomitmen pada representasi jujur dari peristiwa, karakter, dan lingkungan sosial.
Itu sebabnya tidaklah semua novel yang mengangkat sebuah lokalitas tertentu—utamanya dalam hal ini wilayah-wilayah yang dianggap belum dikenal luas bahkan dipandang terbelakang, atau memiliki budaya yang dipandang eksotik dari kacamata orang asing—yang ditulis oleh pengarang-insider maupun penulis dari luar lokalitas tersebut, dengan gampangnya dapat dilabeli sebagai novel etnografis. Meskipun saya khawatir justru pelabelan secara serampangan terhadap novel-novel berlatar lokalitas tertentu inilah yang kerap terjadi dalam sastra (berbahasa) Indonesia, mengingat minimnya penjelasan tentang apa itu novel etnografis dalam berbagai review dan kajian yang telah saya singgung di atas.
Bayangkan saja, jika semua novel berlatar kedaerahan dapat begitu gampang dilabeli sebagai novel etnografis, betapa banyaknya novel etnografis yang kita miliki! Lantaran sebagai sebuah negara kepulauan yang demikian luas dan terdiri dari beragam suku, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang begitu majemuk dengan beratus-ratus mungkin beribu-ribu bahasa dari Sabang sampai Merauke. Juga betapa konyolnya jika yang pantas dilabeli sebagai novel etnografis itu hanyalah karya-karya berlatar daerah-daerah terpencil; sementara sebuah novel yang melukiskan secara terperinci dan jernih tentang masyarakat Kota Gede di Yogya atau komunitas Betawi di Jakarta misalnya, serta-merta dianggap bukan novel etnografis kendati riset untuk penulisan novel itu telah sungguh-sungguh mempraktikkan observasi partisipan sebagai metode penggalian data.
Oleh karena itu, saya kira Burung Kayu dapat kita kategorikan sebagai novel etnografis bukan lantaran Nidu mengangkat kehidupan masyarakat Mentawai—sebuah wilayah di pesisir barat Sumatra yang dianggap masih tertinggal dan memiliki kebudayaan unik dari kacamata pusat (Padang maupun Jakarta)! Bukan pula lantaran belum banyak novel, baik novel populer maupun karya sastra, berlatar Mentawai yang ditulis.[39] Tetapi karena kerja etnografer yang mencoba menampilkan representasi jujur dari peristiwa, karakter, dan lingkungan sosial tadi memang ditempuh oleh Nidu sebagai seorang pengarang-peneliti dari luar ketika menuliskan novelnya.
Hal ini berbeda dengan novel Orang-orang Oetimu karya Felix K. Nesi yang diklaim secara sembrono oleh Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakara 2018 (A.S. Laksana, Nukila Amal, Martin Suryajaya) sebagai “sebuah contoh fiksi etnografis” dalam pertanggungjawabannya yang tidak menyertai penjelasan apa pun itu.[40] Padahal, sebagai metode penelitian, etnografi sesungguhnya merupakan kajian mengenai the other—yang lazimnya digunakan untuk meneliti kebudayaan, adat-istiadat, dan kepercayaan yang “lain” dari sang etnografer. Hal mana yang berarti si penulis bukanlah salah satu anggota masyarakat dari daerah yang ditulisnya. Jika si penulis adalah native dari daerah tersebut, produk yang dihasilkannya hanyalah sebuah warna lokal, bukan produk etnografi.[41]
Lantas, apakah Orang-orang Oetimu dapat disebut sebagai sebuah novel autoethnography atau “etnografi orang dalam” (insider ethnography)[42]? Untuk ini tentu saja mesti kita periksa dulu sedalam apa Felix melakukan riset atas lokalitasnya sendiri, serta dalam narasinya apakah ia lebih cenderung membiarkan subjek berbicara sendiri atau justru hendak mewakili suara mereka—sekalipun sejujur-jujur dan sejernih-jernihnya?
Seorang etnografer akan sedapat mungkin mendekati bagaimana alam pikiran masyarakat yang ditelitinya. Penceritaan-penceritaan ulang atas cerita keluarga Mentawai yang cenderung apa adanya, penyajian yang transparan atas konflik-konflik horisontal alami antara kelompok kerabatan di Mentawai dan resistensi mereka terhadap ragam kebijakan pemerintah, potret yang jernih dari kehidupan sosial keseharian—termasuk praktik adat dan ritual, penggunaan kosakata lokal yang berhamburan di sepanjang novel tanpa diberi catatan kaki, serta pemaparan langsung atas pandangan-pemikiran warga lokal adalah contoh bagaimana Nidu “berusaha” membiarkan para partisipan di lapangan penelitiannya berbicara sebagai subjek—bukan semata-mata objek kajian. Sehingga, Burung Kayu dalam hal ini “mestinya” hadir sebagai sebentuk wadah bagi masyarakat Mentawai itu sendiri berbicara tentang diri mereka, bukan dibicarakan oleh sasareu (orang luar).
Karena itu di sini, novel etnografis seyogianya harus berlaku seperti karya ilmiah tradisional tetapi dengan memberikan empati yang lebih kentara, tatkala subjektivitas peneliti-pengarang menjembatani kesenjangan antara realitas sebagaimana adanya dan realitas yang direpresentasikan dengan menghidupkan para partisipan riset sebagai karakter fiksi. Seperti yang dikatakan Jenny Ingridsdotter dan Kim Silow Kallenberg:
Dalam kasus fiksi etnografi, ia merupakan cerminan kehidupan yang muncul dari konteks empiris. Kita sebagai manusia ada di dalam tubuh dan emosi kita, sama seperti dalam kepala kita—dan hal ini, tentu saja, berlaku baik untuk pembaca maupun peneliti. Saat kita membayangkan kehidupan orang lain, kita berusaha menjadi orang tersebut, agar mampu menggambarkan sepenuhnya pilihan hidup dan perasaan orang tersebut. Fiksi etnografi dapat berfungsi sebagai motode untuk memproses pengalaman afektif dan untuk menangkap dimensi etnografi yang sulit dipahami dalam karya ilmiah tradisional. [43]
Nidu bisa saja menerbitkan hasil kerja etnografinya (kajian pustaka dan penelitian lapangan) dalam bentuk makalah jika ia mau. Namun ia memilih menuliskannya dalam format novel yang tidak lain merupakan bentuk kreatif di mana para etnografer beralih dari genre ilmiah tradisional ke cara baru dalam memublikasikan riset. Di sinilah novel etnografis dapat didefinisikan sebagai metode penulisan yang menggabungkan kreativitas dan imajinasi dengan fakta dan deksripsi empiris. Seperti yang diungkapkan Sarah Pink:
Kita telah mencatat bahwa ada sensasi, atau bahasa tubuh, yang tidak selalu mungkin bisa disampaikan dalam teks ilmiah, namun tetap memengaruhi analisis. Ini mungkin cara seseorang menghindar ketika mengucapkan sesuatu, atau perasaan yang diungkapkan melalui mata. Ini adalah sensasi yang dikomunikasikan dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Ini adalah pengetahuan yang terkandung di dalamnya, yang karena sifatnya, tidak dapat dapat diungkapkan sebagai bagian dari argumen ilmiah, meskipun hal itu memengaruhi cara pengambilan kesimpulan. Melalui penulisan fiksi etnografi, pengetahuan indrawi ini dapat diungkapkan secara ekplisit, memperlihatkan bagaimana peneliti mengalami dan menafsirkan bagian-bagian bidang empiris. Dengan demikian juga berkontribusi terhadap transparansi dan keakuratan produksi ilmiah. Etnografi bergantung pada praktik imajinasi dan dalam menulis fiksi etnografi alur pemikiran ini diambil selangkah lebih jauh.[44]
Maka, meskipun dalam narasi Burung Kayu Nidu menulis ulang cerita keluarga Mentawai secara ada apanya seperti yang ia terima dari narasumber sekaligus menghidupkan pemikiran-pandangan para partisipan risetnya, ia tak bisa dituduh melakukan plagiasi terhadap para narasumber atau partisipan. Ia juga tidak bisa dituduh bersikap misoginis terkait narasi-narasi Burung Kayu yang mencoba menggambarkan secara akurat kedudukan sosial kaum perempuan di lapangan penelitiannya, hanya karena ia “[…] berupaya terus-menerus untuk memahami cara berpikir, berekspresi, dan sebagainya dari masyarakat yang sedang saya teliti, mencatat dan merekam semua hal.”[45]
Misalnya, ketika ia menggambarkan kondisi kaum perempuan Mentawai yang hingga kini masih terus hidup dalam lingkungan patriarkis—mereka tak pernah memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, rumah tangga maupun sosial. Contoh-contoh dari hal ini antara lain dapat kita temukan dalam kasus penculikan seorang gadis oleh lelaki yang dianggap lazim, perempuan yang selalu mendapat tugas memasak, janda yang akan kehilangan hak waris dan hak asuh setelah ditinggal mati oleh suami, perempuan yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak pernah diajak berunding, dan sebagainya. Semua itu bukanlah “apa yang dikhayalkan atau dibuat-buat” oleh pengarang, melainkan memang merupakan himpunan fakta yang benar-benar ia peroleh dari lapangan penelitian.
Karenanya, lewat pandangan-pemikiran karakter Bai Legeumanai (Taksilitoni), Nidu pun berujar getir tentang nasib kaum perempuan: “Betapa berat duka perempuan-janda. Bahkan, anak lelakinya pun akan direnggut-diceraikan darinya.”[46]
Akibatnya dalam hal ini, Taksilitoni tidak lain tak bukan adalah korban budaya patriarki sekaligus karakter yang sadar akan kesetaraan gender sekalipun tetap tetap sungkan untuk bersuara langsung. Perhatikan dua kutipan berikut ini:
Bai Legeumanai bermenung dan barangkali merasa beruntung. Ia tahu bahwa tak banyak yang berubah bagi perempuan-perempuan di dusunnya, sejak tinggal di uma keluarga suami di hulu sampai menetap di barasi. Segala keputusan tetap mesti dirundingkan oleh para lelaki. Hanya oleh para lelaki. Sementara para perempuan, hanya boleh mengikuti segala keputusan keluarga suami. Namun, ia merasa cukup beruntung untuk tetap bertahan di barasi setelah kekacauan antara suku-kembang-bambu dan suku-rumpun-tebu bertahun lalu, adalah karena keteguhan Bai Legeumanai yang tak mau kembali ke uma di hulu. (Erlang, 97)
Ia sadar bahwa dunia di sekelilingnya telah berubah, meskipun perempuan-perempuan di dusunnya tak mampu menjadi perempuan-perempuan yang boleh mengambil keputusan sendiri, sebagaimana Istri Guru Baha’i atau Bu Dokter yang murah senyum ini. (Erlang, 101)
Satu-satunya “perlawanan halus” yang pernah dilakukan oleh Taksilitoni adalah ketika ia memutuskan untuk tetap bertahan di uma mendiang suaminya dengan cara mengawini Saengrekerei sang adik ipar yang masih lajang demi kepemilikan anak dan harta peninggalan suaminya. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan membiarkan adik iparnya menyelinap masuk ke dalam kelambunya juga memperhatikan sepasang buah dadanya yang telah ber-ti’ti’ durakat (bertato) dengan birahi, karakter Taksilitoni dapat dianggap telah dijadikan oleh Nidu sebagai seorang seorang janda (silumang) penggoda—sebuah stigma buruk yang kerap dialamatkan kepada perempuan menjanda di Indonesia?
Barangkali saja. Adanya anggapan seperti itu bukanlah hal mengherankan bagi saya, sebagaimana anggapan bahwa sikap “narator (yang di situ tampaknya tidak dibedakan dari pengarang) novel ini telah melanggengkan citra mistisisme atau citra klenik penghayat kepercayaan” yang saya temukan dalam sebuah makalah akademis.[47]
Saya rasa tidaklah sulit bagi Nidu untuk mencantumkan para narasumber atau partipasan risetnya yang telah berjasa dalam novel ini. Jika Burung Kayu merupakan sebuah makalah ilmiah, ia pasti sudah melakukannya. Namun, novel tidaklah memiliki persyaratan ketat seperti makalah ilmiah yang selalu dituntut untuk mencantumkan referensi. Tidak ada keharusan untuk menyertakan daftar narasumber maupun daftar pustaka dalam novel dan jenis karya sastra lainnya, sekalipun itu karya-karya yang tergolong intertekstual. Pengecualiannya hanyalah jika si pengarang sendiri memang menginginkan hal tersebut dengan alasan tertentu, entah karena menganggap bahwa pencantuman tersebut penting bagi teks karyanya atau sebagai caranya menghormati narasumber. Dengan begitu, saya kira, cukuplah bagi Nidu sekadar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa bagi kerja penelitian dan proses kreatifnya pada tiga halaman terakhir novel (177-180).
Novel etnografis seharusnya adalah karya yang berupaya membuat subjek penelitian berkisah sendiri (baca: merepresentasikan dirinya sendiri) untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga sang pengarang-periset cenderung bertindak sebagai seorang perantara (bukan wakil) lewat kerja riset dan kemahirannya menulis. Karena itu sang pengarang-periset pun sebisa mungkin tidak memberikan suara-pemikirannya atas ragam konteks-kasus dalam narasi untuk menghindari bias representasi, kecuali jika hal itu memang benar-benar dibutuhkan.
Sebagai karya yang ditulis oleh sasareu (orang luar) tentang the other, ia tidak boleh sampai terjebak menjadi karya yang cenderung memanfaatkan (dan mengeksploitasi) sebuah lokalitas beserta segenap kehidupan sosial-budayanya bagi kepentingan politis sang pengarang-periset seraya pada saat bersamaan terpukau-takjub—sebagaimana yang kerap kita temukan dalam kajian sastra pascakolonial, misalnya novel-novel Barat tentang Timur yang secara kentara menjalankan fungsi politis dan colonial discourse-nya dengan “membenarkan” representasi terdistorsi atas subjek-subjek terjajah yang diciptakan oleh pihak luar. Sebab novel etnografis—seperti halnya karya-karya penelitian ilmiah—seyogianya harus ditulis untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Anjing-anjing Nidu: Sebuah resistensi terhadap kebijakan pemerintah
Membiarkan data empiris bersuara inilah pula yang tampak dalam cerita-cerita konflik vertikal antara masyarakat Mentawai dan pemerintah dengan beragam kebijakannya yang tendensius. Semua ini, sekali lagi, bukanlah “karang-karangan” Nidu semata, melainkan memang merupakan fakta yang terjadi di lapangan, yang dengan mudahnya dapat kita temukan dalam berbagai pemberitaan di media atau laporan-laporan penelitian.
Karena itu, dalam hal ini Nidu bisa dikatakan bertindak seperti seorang jurnalis yang mencatat sekaligus menyampaikan apa yang ia temui di medan, sembari membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat Mentawai sebagai subjek untuk mengungkapkan sudut pandang mereka.
“Dalam menulis novel Burung Kayu saya berupaya tidak sekadar berkisah “tentang” Mentawai, melainkan berkisah “di dalam” masyarakat Mentawai, khususnya masyarakat di Lembah Sungai Rereiket. Saya tidak tahu apakah upaya itu berhasil atau tidak. Biarlah pembaca Burung Kayu yang menilainya.”[48]
Apakah “pemberitaan” atau “laporan” Nidu ini dapat dikatakan sebagai pemberitaan yang seimbang? Saya kira tidak. Meskipun tidak sepenuhnya dan tidak secara frontal, Nidu jelas tampak lebih condong berpihak kepada masyarakat Mentawai yang menjadi subjek penelitiannya. Itu sebabnya kita pun bersua dengan dua ekor anjing peliharaan Saengrekerei dan Taksilitoni yang diberi nama Pemerintah dan Sistem:
Sisa-sisa iba dan kapurut dibiarkan bergeletakan pada lulak dan lantai kayu, untuk dibersihkan seekor anjing berbulu cokelat bernama Sistem. Ei, Saengrekerei-lah yang menamai anjing itu Sistem, sebagaimana teteu Taksilitoni menamai anjingnya yang telah lama mati sebagai Pemerintah. Tapi Saengrekerei tak tahu, sejak kapan nama-nama dari luar semesta mereka menjadi nama-nama bagi anjing-anjing pemburu yang hanya diberi makanan sisa dan sesekali bisa dipukul kepalanya itu. Saengrekerei hanya tahu bahwa nama-nama bisa berasal dari apa saja dan dari mana saja. Tak terkecuali nama-nama baru, seperti Pemerintah dan Sistem, yang bunyinya mungkin terdengar merdu, menyenangkan, atau sama sekali sekadar cemoohan. (Erlang, 76-77)
Lalu, apakah pemberian nama Pemerintah dan Sistem ini kepada anjing ini memang semata-mata lantaran “bunyinya mungkin terdengar merdu” atau lebih mengarah kepada cemooh bahwa pemerintah dengan sistem yang mereka paksakan kepada masyarakat Mentawai tak ubahnya seperti “anjing”—binatang yang umumnya di Indonesia kerapkali dipakai untuk mencaci-maki? Tidak ada penjelasan yang cukup di sini mengapa Saengrekerei menamai anjingnya Sistem. Apakah di matanya sistem yang dibuat oleh pemerintah itu memang demikian tak manusiawi, sementara ia sendiri akhirnya menjadi bagian dari sistem itu, yakni diangkat menjadi Pak Desa (kepala desa)?
Upaya pemerintah untuk “memajukan-menyejahterakan” masyarakat di Kepulauan Mentawai yang selalu dirujuk sebagai suku terasing, terbelakang, bahkan primitif ini memang menjadi salah satu konflik utama dalam Burung Kayu yang memengaruhi jalan hidup tokoh-tokohnya—tatkala resistensi dan penerimaan orang-orang Mentawai terhadap perubahan akibat perintah dan anjuran pemerintah itu saling beririsan.
Seperti yang dikemukakan oleh Ade Irwandi dan Kris Irwandi Saleleubaja dengan mengutip sejumlah sumber, pelabelan negatif terhadap suku Mentawai oleh pemerintah ini didasari oleh kegiatan orang Mentawai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti meramu dan berburu yang dipandang sebagai kegiatan masyarakat yang belum maju. Karena itu, kepulauan Mentawai pun menjadi salah satu target program pembangunan dan “misi pemberadaban” pemerintah—yang kedengaran seperti civilising mission ala kolonial—sejak zaman Orde Lama yang berlanjut ke masa Orde Baru hingga sekarang. Akibatnya, masyarakat Mentawai di Pagai, Sipora, dan Siberut kehilangan ciri khas budaya tradisionalnya. Di Siberut, hal serupa juga terjadi. Bahkan pada 1970-an, orang Mentawai “dipaksa” untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dan menghentikan semua ritual yang terkait dengan Arat Sabulungan. Dalam aspek pembangunan birokrasi dan pemerintah daerah, orang Mentawai juga diintervensi dengan konsep desa. Bahkan, sebelumnya karena dianggap suku terasing, orang Mentawai harus dikumpulkan (baca: dimukimkan) dengan konsep PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) dan resettlement atau barasi di wilayah pesisir.[49]
Bukan hanya itu, mereka juga merasa terkekang dengan beragam peraturan baru yang diterapkan oleh pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh polisi, dinas sosial, dan kepala desa. Selain dilarang ber-kabit dan ber-laha yang dipandang primitif oleh pemerintah, mereka juga dilarang memelihara babi yang telah menjadi tradisi turun-temurun dan terkait erat dengan kepercayaan leluhur mereka. Simaklah kutipan di bawah ini.
“Mau makan apa kalian di barasi? tanya sikebbukat uma. “Pemerintah melarang memelihara babi.”
“Pemerintah melarang memelihara babi,” saudara-saudaranya yang lain menggemakan.
“Pohon sagu kalian di sini. Durian dan langsat ada di sini. Ladang gette ada di sini. Kelapa ada di sini. Babi dan ayam ada di sini.” (Erlang, 7)
Bahkan aparatur kepolisian juga melarang mereka untuk menato tubuh mereka:
Basah meruyak di tubuh Aman Legeumanai yang telanjang. Mengilaukan sembilan belas tato rusa dan joja yang masih tegas terajah di pangkal lengan dan perutnya; pertanda ia pernah memburu dan memenggal sembilan belas kepala rusa dan joja di masa lampau. Sementara tato di dada, di lengan, di tangan, di jari, di pipi, di dagu, di punggung, di paha, dan di kakinya—garis-garis hitam melengkung bersilangan yang didapatnya sejak masa remaja—masih menjadi bagian dari keseluruhan hidupnya. Tato yang kerap ia banggakan kepada para “tetangga” uma yang kini tak lagi berani bertato, sejak polisi melakukan razia di lembah-lembah, di tepi hilir dan muara, dan melarang warisan kakek-nenek moyang mereka. Polisi yang terus saja mengawasi pemindahan uma-uma ke dusun-dusun baru bikinan pemerintah, ke barasi-barasi yang terus merangsek sampai ke lembah di antara hulu dan hilir sungai-sungai besar. (Erlang, 21)
Alhasil, program-program pemerintah atas nama pembangunan dan pemberadaban itu pun menciptakan konflik-konflik baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. “Katanya pemerintah mau memajukan kita, mau menyejahterakan kita, kenapa semuanya dilarang?” demikian gugat seorang warga yang tinggal di barasi (hlm. 92).
Dalam Burung Kayu, rencana pemerintah memindahkan masyarakat dari uma di pendalaman ke barasi-barasi bikinan pemerintah contohnya, “malah membuat kaum sesuku terpecah dalam cekcok tak terhindarkan” dalam rapat-rapat (alei, paruru’) keluarga se-uma yang membahas berbagai persoalan, mulai dari pembagian warisan hingga kabar burung tentang proyek pembangunan pemerintah yang terus meluas. Sehingga sebagian dari mereka memilih untuk bertahan di uma, di lembah dingin-lembap itu, dengan tetap memelihara babi dan merawat daun-daun penghidupan yang telah mereka warisi dari para leluhur sejak beribu tahun; sementara sebagian lainnya memilih tawaran-tawaran dan pembaruan-pembaruan yang datang dari dunia luar, dari sasareu, yang mungkin menguntungkan.[50]
Ya, salah satu orang yang memutuskan untuk menanggalkan kabit dan laha dan pindah ke barasi adalah Saengrekerei bersama iparnya Taksilitoni yang telah ia peristri dan Legeumanai kecil, keponakan yang telah menjadi anaknya sendiri. Keputusan itu cukup dipengaruhi oleh rasa bersalahnya karena merasa menjadi penyebab kematian sang kakak. Namun, ternyata perpindahan mereka ke barasi dengan harapan memperoleh kesejahteraan yang dijanjikan oleh pemerintah justru membuat “mereka benar-benar tercerabut dari uma yang melindungi.” Tak ada lagi yang menjadi milik saudara se-uma. Tak ada lagi rimata yang akan memimpin upacara-upacara, puliaijat-puliaijat, dan pesat-pesta. [51]
Akibatnya tidak ada jalan lain bagi mereka yang memilih hidup di barasi selain terpaksa mematuhi dan mengikuti setiap anjuran pemerintah dan belajar beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya mereka harus belajar hidup bersama dengan orang-orang yang tak sesuku, sebab sebagian besar penghuni barasi tak lagi memiliki saudara sesuku se-uma. Sehingga—seperti yang disuarakan oleh Saengrekerei lewat penuturan narator—untuk mengeratkan pertemanan, mereka kerap berkumpul di sapou (rumah) kepala dusun yang dipilih dan ditetapkan bukan melalui paruru’, melainkan ditunjuk oleh sekelompok polisi (hlm. 72). Di samping itu mereka dianjurkan (tepatnya dipaksa) pula untuk mengganti sagu makanan pokok mereka dengan beras.
Bahkan pada 2012, khususnya di Siberut Selatan, dilakukan upaya pembukaan lahan persawahan 600 hektar dengan tujuan mengubah budaya pangan hasil hutan. Hal ini didasari pada program “Peningkatan Keamanan Pangan Nasional” di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Pagai Selatan, Pagai Utara, Sikakap, Sipora Selatan, Sipora Utara, dan Siberut Selatan dengan tujuan untuk mengintensifikasi pertanian. Padahal dalam kebudayaan Mentawai, sagu adalah tanaman yang bernilai tinggi sebagai pangan maupun bagian tidak terpisahkan dari Arat Sabulungan. Apalagi tanah Mentawai sebetulnya tidak cocok ditanami dengan padi. [52]
Seiring dengan itu, hutan-hutan di Mentawai pun dijadikan sebagai ladang penghasil uang bagi perusahaan HPH dan HTI sejak tahun 1970an. Seperti yang dikatakan oleh Ade Irwandi dan Kris Irwandi Saleleubaja:
Memang sudah lama Mentawai menjadi sasaran banyak “panah” yang diarahkan melalui banyak program dan perizinan perusahaan, terutama kayu. Tanpa disadari, pembuat program pembangunan tidak pernah bertanya apakah orang Mentawai membutuhkan itu semua? Orang Mentawai tidak bisa mengelak dari berbagai program intervensi. Imbasnya ialah membuat nilai-nilai sosial budaya hancur berantakan diterkam zaman (baca: periode kekuasaan). [53]
Konflik pertahanan dan hutan ini terus meruncing antara masyarakat yang tinggal di barasi maupun uma dengan pemerintah dan perusahaan HPH-HTI, sehingga terjadilah apa yang tak terduga oleh polisi, pemerintah dan para pengusaha hutan, yakni bersatunya suku-suku Mentawai yang selama ini bahkan saling bermusuhan, untuk melindungi tanah dan hutan mereka. Beramai-ramai mereka membakar tiga alat berat—backhoe, excavator, dan bulldozer—milik salah satu perusahaan kayu pemegang konsensi hutan yang didatangkan dari Padang.[54]
Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun, seperti disampaikan oleh narator, tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali memulai atau menggalang massa dari sejumlah desa. Polisi selama ini hanya mengenal mereka sebagai orang-orang yang lebih mementingkan martabat kaum se-uma dan tidak pernah memperkirakan bahwa mereka bakal bergerak dan bertindak bersama-sama untuk merusak, membakar, bahkan mengancam akan melakukan pembunuhan apabila perusahaan kayu masih bernyali mendatangkan alat perusak hutan tempat tinggal Taikaleleu. Tidak heran jika pihak kepolisian pun mengalami “kesulitan mengurai-mengusut kasus dan menemukan dalang kerusuhan,” seolah pembakaran ketiga alat berat itu berlangsung tanpa perencanaan. Simaklah aksi masyarakat Mentawai bersatu secara spontan untuk mempertahankan hutan mereka yang dideskripsikan dengan sinematik oleh narator berikut ini:
Nen! Beberapa saat sebelum kejadian, warga dari beberapa barasi di lembah dan aliran sungai yang berlainan, datang begitu saja sembari menjinjing parang, tombak, busur, dan anak panah, sebagaimana mereka hendak pergi berburu babi atau joja di kelembatan hutan. Mereka mengayuh sampan dari satu aliran sungai ke aliran sungai lain, bertemu di satu percabangan sungai atau di pesisir pantai. Sebagian berjalan sepanjang hari menembus hutan, mendaki perbukitan, menyusuri bantaran sungai, melewati rawa-rawa ladang sagu, dan bertemu di satu percabangan jalan. Semuanya bergerak menuju lokasi pendirian perusahaan kayu. (Erlang, 116)
Bahkan sebagai orang dalam, sebagai seorang kepala desa, Saengrekerei sendiri pun digambarkan terheran-heran kala mendengar bahwa beberapa orang dari beberapa suku yang mewarisi konflik dan permusuhan, mewarisi dendam turunan, bisa bertemu begitu saja pada saat kejadian—bukannya saling menghindari satu sama lain, sebagaimana kebiasaan para kerabat se-uma menghindari para kerabat uma lain yang merupakan musuh lama dan belum sempat menjalani paabat (ritual perdamaian). Ia tak mengira pula kalau sebagian warganya akan bernyali menentang kebijakan pemerintah dan melakukan perlawanan kepada pemegang hak konsensi hutan. Karena itu Saengrekerei menerawang dan membatin dengan gamang:
“Ah, adakah mereka telah diikat kepentingan yang sama: menyelamatkan hutan dan penggundulan, menuntut ganti rugi atas ladang dan hutan yang akan dimanfaatkan perusahaan? Atau barangkali, Saengrekerei menduga-duga, orang-orang itu tak benar-benar diikat visi tentang penyelamatan hutan sebagaimana digaungkan para aktivis lingkungan yang belakangan banyak bercokol di desa-desa dan melakukan advokasi kepada warga. Barangkali orang-orang itu hanya ingin menyelamatkan ladang sagu, hutan, dan tanah warisan leluhur mereka sendiri yang terancam dihabisi atau beralih fungsi menjadi hutan industri. (Erlang, 117-118)
Boleh jadi, apa yang dipikirkan karakter Saengrekerei ini tidak keliru. Sebab bertahun-tahun lamanya campur tangan pemerintah “agar penduduk Mentawai maju dan dapat mengejar ketertinggalannya” itu bukan hanya membuat kebudayaan dan identitas mereka kian terkikis, tetapi juga mengancam penghidupan mereka secara nyata; atas nama pembangunan kerapkali mereka ditipu dan dieksploitasi karena dianggap bodoh bahkan masih primitif. Penipuan tanah masyarakat oleh pemerintah ini di antaranya, seperti dikisahkan dalam Burung Kayu, melibatkan Dinas Sosial dengan dalih untuk melakukan perluasan dusun dan mendirikan barasi baru hingga sosialisasi pembentukan Taman Nasional yang luasnya lebih dari separuh pulau. Perhatikan kesaksian seorang kepala desa lain kepada Saengrekerei berikut ini:
“Sebagai kepala desa, saya mendukung saja program pemerintah. Saya pun menemui dan meminta tiga suku lain untuk mendukung program itu. Lalu kami sama-sama menandatangani surat penyerahan tanah seluas 36 hektar kepada Dinas Sosial. Itu tanah milik empat suku, termasuk suku saya. Tapi sebulan kemudian, saya menerima dokumen serah terima tanah kepada Dinas Sosial seluas 360 hektar. Saya terkejut. Saya tak tahu kenapa jadi seluas itu.
“Kabar itu segera saja meluas dan menjadi pembicaraan suku-suku lain. Terutama suku-suku yang tanahnya tercakup dalam dokumen 360 hektar tanah yang diklaim Dinas Sosial. Orang-orang di desa saya marah. Lima belas suku yang merasa tidak pernah menyerahkan tanahnya, menunduh saya dan tiga suku lain—yang menandatangani surat penyerahan sebelumnya—telah menjual tanah mereka kepada pemerintah. Tentu saja itu tidak benar. Kami hanya menyerahkan 36 hektar, bukan 360 hektar.” (Erlang, 90)
Si kepala desa malang itu kemudian meminta bantuan kepada para aktivis lingkungan hidup, orang lembaga bantuan hukum, dan pemuda-pemudi yang sedang berkuliah di Tanah Tepi. Namun mereka malah dipukuli dan diancam. Akhirnya ia dan para warga menuntut Dinas Sosial ke pengadilan dengan bantuan LBH. Apa hasilnya?
“Selama hampir setahun, kami sidang dan sidang dan sidang di pengadilan. Setelah sembilan kali sidang, akhirnya pengadilan mengeluarkan putusan. Isinya menyatakan bahwa 360 hektar adalah tanah milik 15 suku, bukan hanya milik empat suku yang menandatangani surat penyerahan tanah itu.” (Erlang, 92)
Apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap masyarakat lokal Mentawai ini tentu saja serta-merta mengingatkan kita kepada cara-cara picik yang dilakukan oleh kolonialis Barat untuk menguasai tanah jajahan beserta penduduknya, yakni—seperti yang digambarkan dengan tepat oleh Daniel Defoe lewat novelnya yang terkemuka Robinson Crusoe—menganggap bahwa penduduk lokal pribumi adalah orang-orang belum beradab atau subjek inferior terbelakang (barbar, tidak rasional, penuh takhayul, dan tak mampu merepresentasikan dirinya sendiri); yang harus diselamatkan dengan memperkenalkan kepada mereka cara hidup, bahasa, dan agama yang benar. Lalu bersamaan dengan itu, Crusoe pun mengklaim pulau “kosong” (tapi berpenghuni) tempatnya terdampar itu sebagai penemuannya dan miliknya.[55] Perhatikan narasi dalam Burung Kayu berikut ini:
Saengkrekerei menenggak kopinya dan masih menahan diri untuk berkomentar di tengah kecemasan warganya. Sebagai pemimpin desa yang membawahi beberapa dusun, perpanjangan tangan pemerintah tapi sekaligus perwakilan orang-orang desanya, ia mencoba menangkap apa-apa yang menjadi kecemasan warga barasi. Apalagi, sudah berkali-kali ia diajak dan terlibat dalam sosialisasi pembentukan Taman Nasional yang luasnya lebih dari separuh pulau ini, sebagaimana selembar peta yang pernah ditunjukkan kepadanya. Seolah-olah pulau ini tak berpenghuni atau hanya berisi hutan dan binatang belaka; seolah hutan dan tanah itu tak pemiliknya. (Erlang, 89, huruf tebal oleh Sunlie Thomas Alexander)
Para pembaca Burung Kayu tentu tahu bahwa perlawanan para penduduk lokal Mentawai tersebut akhirnya nyaris sia-sia. Tidak berapa lama setelah pembakaran tiga alat berat itu, beberapa orang dijemput paksa oleh polisi dan diinterogasi di Pos Jaga di Muara. Mereka ditanyai dan ditanyai, lalu didesak polisi untuk mengakui semua tuduhan. Yang tidak mau mengaku, dihantam dengan popor senapan. Hingga akhirnya dalam keadaan tak berdaya, beberapa orang yang terlibat dalam aksi pembakaran itu malah menjual tanah milik sukunya kepada perusahaan kayu tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Saengrekerei sendiri merasa kecolongan dan tak bisa berbuat apa-apa, lagipula selama tiga minggu sebelum kejadian itu ia sedang sibuk melobi orang Dinas Pendidikan agar anaknya Legeumanai beroleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Padang. “Bukankah pendidikan Legeumanai di sebuah universitas di Padang—yang tak lain tak bukan adalah pemilik perusahaan yang mengirimkan tiga alat berat yang telah terbakar—jauh lebih penting dari berbagai keributan di desanya?” demikian tanyanya dalam hati.[56]
Ketakberdayaan masyarakat lokal Mentawai ini juga terlihat secara kentara ketika pemerintah memaksakan agama yang resmi diakui negara kepada mereka—seolah-olah agama asli mereka yang mereka warisi secara turun-temurun dari leluhur mereka adalah ajaran sesat dan agama yang tidak layak untuk dianut!
Semua itu sudah dimulai sejak 1954, ketika pemerintah memprakarsai Rapat Tiga Agama (Protestan, Islam dan Sistem Kepercayaan Tradisional) di Kepulauan Mentawai yang diselenggarakan oleh perwakilan pemerintah, militer dan polisi. Hasilnya adalah Arat Sabulungan tidak dianggap oleh pihak berwenang sebagai keyakinan yang tepat bagi orang-orang yang ingin maju dalam modernitas.[57] Sebagai gantinya, mereka diharuskan memilih salah satu dari lima agama resmi yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha (yang dalam praktiknya cuma Islam, Protestan, dan Katolik saja) dalam waktu tiga bulan setelah pertemuan. Melalui Surat Keputusan Nomor 167/PROMOSI/1954, pemerintah kemudian juga melakukan pengawasan, investigasi dan larangan pada semua bentuk keyakinan yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pemerintah.
Awalnya implementasi dari kebijakan terhadap masyarakat Mentawai ini dimaksudkan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat. Namun, yang terjadi di lapangan pada tahun 1970-an adalah kebijakan tersebut digunakan oleh Pemerintah Sumatra Barat dengan bantuan aparat kepolisian untuk memaksa penduduk Mentawai meninggalkan uma mereka dan melarang mereka mempraktikkan ritual adat serta mulai menghancurkan budaya material Mentawai. Dengan melakukan ini, Pemda Sumatra Barat berharap gambaran “primitif” masyarakat Mentawai dapat dihapuskan dan “budaya baru Indonesia” dapat diterima. Oleh karena itu, pemerintah bersama militer dan polisi setempat secara bertahap memaksa penduduk untuk tinggal di desa-desa yang didirikan pemerintah. Dengan cara ini, struktur sosial masyarakat Mentawai dihancurkan dan diganti dengan struktur sosial baru yang dibuat oleh badan pemerintah daerah dan organisasi keagamaan yang sudah mapan.[58]
Seperti yang diungkapkan oleh seorang sikerei di daerah Matota bernama Suarno Saurei: “Pada 1972, polisi berdatangan membawa senjata api dan masuk ke dalam pemukiman secara paksa, membakar berbagai peralatan ritual yang tersimpan di dalam uma. Ia dan puluhan warga Matotoan dipaksa pergi ke Muara Siberut untuk diberikan pekerjaan paksa, seperti menebang pohon dan membersihkan jalanan. Adanya larangan serta ancaman menjadikan pelaksanaan ritual Arat Sabulungan semakin bersifat tertutup dan bersifat rahasia pada saat itu.”[59]
Kisah serupa juga dituturkan oleh Batista Teu Lakka (78 tahun) dari suku Sabulukkungan. Ia masih ingat betul saat ditangkap oleh polisi karena menjadi sikerei. Ia ditodong dengan senjata, kabit-nya dilucuti dan ia digelandang ke kantor polisi tanpa perlawanan. “Pemerintah memberikan mandat pada polisi untuk memusnahkan kami,” katanya. [60]
Dalam Burung Kayu, peristiwa inilah yang diungkapkan oleh narator lewat ingatan Aman Legeumanai:
Aman Legeumanai masih mengingat kisah-kisah yang diceritakan teteu-nya dengan jelas-tegas. Betapa di suatu waktu, para sikerei—tak terkecuali kakeknya itu sendiri—pernah dikejar dan dihancurkan. Bakkat katsaila dibakar dan dileburkan, dan agama-agama pendatang dipaksakan. Juga kisah-kisah lain yang diceritakan teteu-nya: tentang tanah, lembah, hutan yang dirambah, pantang-larang, tulou, silsilah. Kisah-kisah yang selalu menautkan uma-uma atau suku-suku yang berkerabat dan yang bermusuhan.
Kami ketakutan. Sebagian memilih berdamai dan menerima dipindahkan ke barasi. Sebagian, sedikit sekali, memilih bertahan dan pergi lebih jauh ke dalam hutan, ke hulu-hulu sungai, ke lembah-lembah yang sukar dijangkau polisi. Tapi kami bertahan. Meskipun kami juga mendengar kisah-kisah, bahwa beberapa orang yang masih memakai kabit dan memanjangkan rambut, dijemur dan dipaksa mencabuti rumput di lapangan depan Pos Jaga di Muara.
Kisahan itu masih terajah tegas dan tajam dalam ingatan Aman Legeumanai; setegas dan setajam mata jarum sipatiti yang merajah tubuhnya pertama kali. (Erlang, 21-22)
Ketidakberdayaan inilah yang membuat masyarakat Mentawai sebagai penganut Arat Sabulungan kemudian melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri: menerima sekaligus menolak agama-agama asing itu pada saat yang bersamaan—berdasarkan pertimbangan untung-rugi—sehingga terkesan berolok-olok.
Tidak heran, seperti yang digambarkan oleh Nidu, kita pun menemukan orang-orang yang bergonta-ganti agama seminggu sekali, orang-orang yang mengaku Islam tetapi makan babi, atau yang membuang salib ke sungai lantaran Tuhan baru ternyata tidak berhasil menyembuhkan anak mereka yang terkena kisei uma.
“Minggu kemarin kau ke mana?” tanya si lelaki juling kepada si suku-titik-air. “Sepertinya kami tak melihatmu di gereja?”
“Saya pindah ke hari Jumat”
“Hari Jumat?” tanya yang lain berbarengan.
“Saya Sipuisilam sekarang.”
“Eiii, Sipuisilam…. Tak boleh makan babi.”
“Tak. Tapi seminggu sekali saya akan dikasih beras, mi instan, ikan kaleng, juga dikasih kain, kelambu, baju, dan ini…,” si suku-titik-air mengeluarkan kopiah hitam dari balik kemaja dan memakainya di kepala.
“Eiii… Maeru’, maeru’. Tapi masih lebih bagus luat sikerei.”
“Tapi kalau ada punen, ada pesta, diberi otcai, saya tak bisa kalau tak makan babi.”
(Niduparas Erlang, 94)
Bagi orang Mentawai, Arat Sabulungan sebagai agama asli mereka tetaplah tidak tergantikan. Setidaknya dari kutipan di atas, kita bisa melihat bagaimana mereka dapat bergonta-ganti agama dari luar yang dipaksakan oleh pemerintah dengan luwes tidak ubahnya seperti berganti pakaian. Namun, apabila sudah terkait dengan Arat Sabulungan, seperti yang dikatakan oleh si suku-titik-air di atas: “Saya tak bisa kalau tak makan babi.”
Sikap ambivalen yang sama ini pulalah yang diperlihatkan oleh Legeumanai muda si pegawai kantor pemerintah yang telah menamatkan pendidikan tinggi di Padang: Ia Sipuisilam, tapi tubuh dan jiwanya menghendaki daging babi yang mananam—yang lezat tak tertanggungkan (hlm. 171). Sikap Legeumanai dalam beragama ini (beserta pengakuannya sebagai Saiminang dan gelar sarjana yang berhasil diraihnya di seberang) pun mengingatkan saya kepada istilah mimikri yang diperkenalkan oleh Homi K. Bhabha, yaitu proses ketika subjek terjajah direproduksi sebagai produk yang almost the same, but not quite—yang mengandung unsur meniru sekaligus mengejek.[61]
Mimikri inilah yang kemudian melahirkan identitas hibrid dalam masyarakat terjajah, yang kemudian dinamai Bhabha sebagai unhomely, yakni orang-orang yang bebas hadir melalui pencaplokan identitas lain sebagai tubuh sementara, yang bisa ditanggalkan kapan saja untuk menjadi nomad dalam tubuh yang lain.[62] Dalam Burung Kayu, sikap beragama yang dianut oleh masyarakat Mentawai ini kiranya merupakan sebuah negosiasi yang tepat terhadap tekanan pemerintah, bukan sebuah penistaan terhadap agama-agama. Perhatikan kata-kata Saengrekerei di bawah ini yang selalu diingat oleh Legeumanai:
“Anggap saja pemberian saraina,” kata ayahnya suatu ketika, “Dan kita mesti menerimanya. Kita pernah mengenal Baha’i, agama persaudaraan. Itu baik. Tapi kita pernah juga jadi Protestan. Itu juga baik. Lalu kita pindah ke Katolik yang lebih berkenan menampung peninggalan-peninggal leluhur kita. Itu juga baik. Arat Sabulungan ataupun arat Katolik dan arat Isilam, tak mesti kita pertentangkan.”
“Kita,” kata Saengrekerei lagi, “mesti menerima apa-apa yang menguntungkan bagi hidup dan kehidupan. Jiwa-jiwa kita mesti dibahagiakan. Dengan punen. Dengan lia. Dengan Tuhan. Dengan kemajuan zaman. Dengan apa saja yang menyebabkan kita tidak merugi.” (Erlang, 168)
Maka, kita pun menemukan sosok Legeumanai yang namanya terus diubah-ditambah seiring pergantian agama-agamanya di KTP: “Legeumanai Sura’-Sabbeu, Agustinus Legeumanai Sura’-Sabbeu, Ahmad Legeumanai tanpa Sura’-Sabbeu.” Selepas pengukuhannya menjadi sikerei, ia kembali menyandang nama Legeumanai Sura’-Sabbeu. Walau mungkin ia akan tetap dipanggil Ahmad jika melancong ke Padang dan bertemu kawannya yang Sipuisilam, atau tetap dipanggil Agustinus jika bertemu kawannya dalam perkumpulan Orang Muda Katolik di asramanya dulu.
Sikap demikian yang diperlihatkan oleh masyarakat Mentawai ini juga bukanlah “karang-karangan” Nidu, tetapi sungguh merupakan realitas yang ia temukan di lapangan riset. Karena itu, dalam esainya “Mengapa Tubuh Saya Menolak Makan Babi” di alif.id, Nidu menulis:
Demi memahami keterkaitan antara babi dan agama atau kebudayaan itu, maka saya melakukan wawancara secara intensif dan mendalam dengan beberapa informan yang telah saya identifikasi dan tentukan. Dan hasil dari wawancara itu, saya mendapati jawaban-jawaban yang menarik sekaligus mencengangkan, yang kemudian saya rangkum dalam beberapa kalimat pernyataan, sebagai berikut.
“Agama kami (memang) Islam, tapi tubuh kami Mentawai. Dan orang Mentawai memakan babi. Tubuh kami suka daging babi. Dalam pesta-pesta harus ada babi. Jadi, tubuh kamilah yang menginginkan dan memakan babi, bukan agama kami.”[63]
Tidak tergantikannya Arat Sabulungan ini kita dapati pula dari pandangan orang Mentawai terhadap pengobatan modern (Medis Barat) yang selalu mereka bandingkan dengan pengobatan yang dilakukan oleh para sikerei, ketika kebanyakan penduduk belum bisa sepenuhnya percaya pada dokter dan Puskesmas.
Bai Legeumanai dan Istri Guru Baha’i berpandangan. Mereka tahu, beberapa orang yang dibawa ke Puskesmas dalam kondisi kelewat kritis, memang tak tertolong. Orang-orang itu mati meski telah diobati. Sebagaimana kabar yang beredar dari dusun ke dusun, Puskesmas bukan lagi tempat bagi orang sakit disembuhkan, tapi sekadar tempat bagi orang sakit menjemput maut. Dan siapa pun tahu, pitto dari tubuh orang-orang yang mati di Puskesmas, tak pernah diusir oleh para perawat atau dokter. Mereka tak pernah meminta sikerei untuk mengusir roh jahat dari sana. (Erlang, 96)
Namun sebagaimana sikap luwes yang mereka tunjukkan dalam menerima kehadiran agama dari luar, toh lambat-laun pandangan sebagian penduduk Mentawai terhadap dokter dan puskesmas ini juga semakin melunak. Bai Legeumanai adalah salah satunya, yang diam-diam “membayangkan kerja sama antara dunia medis dan dunia roh yang mungkin bisa ditempuh tanpa mencederai keyakinan para penghuni lembah”. Ia membayangkan seorang sikerei yang mendampingi dan menyerahkan si sakit untuk diperiksa dan diobati oleh dokter atau perawat setelah mengusir roh-roh jahat atau pitto yang bersemayam di Puskesmas. “Benda-benda baru yang berdatangan dari luar bisa diperkenalkan kepada benda-benda lama agar bajou-bajou yang dimiliki benda-benda itu tak saling mencelakai. Obat-obatan bisa diperkenalkan kepada dedaunan-baik. Peralatan medis di Puskesmas bisa dipertemukan dengan jejeneng dan lagu-mantra para sikerei. (Erlang, 102)
Perubahan sikap mereka secara perlahan ini terjadi pula ketika mereka berhadapan dengan para sasareu dan situri bule yang masuk ke wilayah Mentawai. Mereka telah menyadari bahwa orang-orang luar itu ingin mencari keuntungan dengan menjadikan mereka yang dipandang masyarakat tertinggal sebagai objek dan tontonan eksoktik. Karena itu, seperti kata seorang warga dari suku-daun-keladi, “Tak apa menjadi objek hiburan, asal kita tidak marugi”.
“Asal kita tidak marugi,” timpal yang lain, seperti biasa, disusul tawa membahana.
“Kalau sasareu mau ambil foto kita, mereka harus bayar.”
“Harus bayar.”
“Kalau sasareu mau lihat tarian kita , mereka harus bayar.”
“Harus bayar.”
“Kalau sasareu mau lihat kita pakai kabit, mereka harus bayar.”
“Harus bayar.”
“Kalau sasareu mau lihat puliaijat-puliaijat kita, mereka harus bayar.”
“Harus bayar.”
(Erlang, 166-167)
Begitulah. Maka, pada penghujung novel, kita pun diajak untuk menyaksikan tarian Muturuk yang tidak lagi sakral dan tanpa ekstase di atas panggung festival, yang dibawakan oleh sikerei-sikerei belia tetapi palsu dengan iring-iringan lagu pop dari recorder, dengan kabit dan tato-tato tiruan dari tinta spidol hitam yang diguratkan oleh para guru di sekolah. Itulah Muturuk yang lain: Muturuk yang semata-mata dipersembahkan kepada para penonton dan dewan juri, bukan kepada roh-roh nenek moyang.
Lantas bagaimana dengan masalah kosakata bahasa Mentawai yang berhamburan di sekujur narasi dan dialog novel ini tanpa diberi glosarium? Saya kira itu tidak jadi soal. Dalam novel-novel Salman Rushdie, contohnya dalam The Satanic Verses yang kontroversial itu, kita juga bakal mendapatkan betapa banyaknya kosakata bahasa Urdu, Hindi, serta ungkapan-ungkapan Hinglish khas Mumbai yang dimasukkan oleh Rushdie tanpa disertai penjelasan apa pun. Sehingga Paul Brians, seorang Emeritus Professor of English dari Washington State University, kemudian menerbitkan sebuah catatan khusus untuk kosakata-kosakata tersebut beserta berbagai perihal lainnya yang diberi judul “Notes for Salman Rushdie: The Satanic Verses”.[64]
Kekurangan dari novel etnografis seperti Burung Kayu ini adalah sempitnya ruang bagi pengarang-periset untuk melakukan rekonstruksi dan mengembangkan sudut pandangnya sendiri secara bebas, demi menghindari bias representasi bahkan tudingan rasis!
Ah, sebagai penutup, saya ingin mengutip suara Nidu yang “terdengar” sayup-sayup lewat pikiran karakter Leugemanai pada halaman 167: Alei, betapa hidup sudah begitu sentosa, begitu cukup dengan segala yang disediakan semesta, […] Tapi mengapa program-program pemerintah-pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan-kemajuan-pendidikan-pelayanan mesti juga menggusur hutan-hutan sembari mengejek mencela gaya hidup di uma-uma?”
BAHAN BACAAN:
Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.
Bhabha. Homi K. “The World and the Home” dalam Social Text, 10 (31-2), 1992, 141-153.
Brians, Paul. “Notes for Salman Rushdie: The Satanic Verses”, dalam http://public.wsu.edu/~brians/anglophone/satanic_verses/copyright.html, diakses 2014.
Defoe, Daniel. Robinson Crusoe, terj. Peusy Sharmaya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
Dewan Kesenian Jakarta. “Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2018”, dalam https://dkj.or.id/berita/pertanggungjawaban-dewan-juri-sayembaara-novel-dewan-kesenian-jakarta-2018/, diakses 07/12/2023.
Dewan Kesenian Jakarta. “Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2019”, dalam https://dkj.or.id/tak-berkategori/pertanggungjawaban-dewan-juri-sayembara-novel-dewan-kesenian-jakarta-2019/, diakses 22/11/2023.
Dude. “Novel Etnogafi Sebagai Kritik Budaya” dalam https://gudeg.net/read/3608/novel-etnografi-sebagai-kritik-budaya.html, diakses 08/12/2023.
Erlang, Niduparas. 2020. Burung Kayu. Padang-Jakarta: CV. Teroka Gaya Baru.
Erlang, Niduparas. “Mengapa Tubuh Saya Menolak Makan Babi” dalam https://alif.id/read/niduparas-erlang/mengapa-tubuh-saya-menolak-makan-babi-b215701p/, diakses 29/12/2023.
Erlang, Niduparas. “Perihal Bahasa Mentawai dalam Novel Burung Kayu yang Sering Dipertanyakan Pembaca (dari Grup Apresiasi Sastra) dalam https://m.facebook.com/story.php?story_fid=pfbid0jsknMvp69YTMbA6AvfmrNN19ET7giTnzeFKKdo8mmLf5DszFasaHHiQKaN5UlrYml&id+1376345033&mibextid=9R9pXO, diakses 10/12/2023.
Ingridsdotter, Jenny & Kallenberg, Kim Silow. “Ethnography and the Arts: Examining Social Complexities through Ethnographic Fictions” dalam Etnofoor, Stories, volume 30, issue 1, 2018.
Irwandi, Ade & Saleleubaja, Kris Irwandi. “Dari Sagu ke Beras: Perubahan Kehidupan sosial Budaya Orang Mentawai” dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 47 No. 2 Tahun 2021.
Laterza, Vito. “The Ethnographic Novel: Another Literary Skeleton in the Anthropological Closet?” dalam Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 32 (2), January 2007.
Kumparan. “Tatung, Manusia Pilihan yang Rela Dimasuki Roh Dewa demi Tradisi”, dalam https://m.kumpuran.com/kumparantravel/tatung-manusia-pilihan-yang-rela-dimasuki-roh-dewa-demi-tradisi-1shoxf0G6qh, diakses 25/11/2023.
Pinasti, M.Si., V. Indah Sri. 2007. Etnografi Indonesia: Data Etnografi dalam Penelitian Suku Bangsa di Indonesia (Diktat). Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sosiologi.
Redaksi. ““Burung Kayu”, Novel Etnografis Karya Niduparas Berlatar Mentawai”, dalam https://alif.id/read/redaksi/burung-kayu-novel-etnografis-karya-niduparas-yang-berlatar-mentawai-b231189p/, diakses 06/12/2023.
Redaksi, “Penulis Banten Raih Kusala Sastra Khatulistiwa 2020” dalam https://www.bantennews.co.id/penulis-banten-raih-kusala-sastra-khatulistiwa-2020/, diakses 22/11/2023.
Rivaldy, Padel Muhamad Rallie Rivaldy. “Visi Pengarang dan Narator Berafiliasi dalam Burung Kayu karya Niduparas Erlang” dalam http://ejournal.uki.ac.id/index.php/dia/article/view/4749, diakses 21/11/2023.
Sitinjak, Marlen. “Arti Tatung / Asal Usul Tatung / Sejarah Tatung atau Lokthug Pada Perayaan Cap Go Meh Singkawang, dalam https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/13/arti-tatung-asal-usul-tatung-sejarah-tatung-atau-lokthung-pada-perayaan-cap-go-meh-singkawang, diakses 25/11/2023.
Sonia. “Novel Burung Kayu: Meneroka Sastra Lisan Mentawai”, dalam https://padangkita.com/novel-burung-kayu-meneroka-sastra-lisan-mentawai/, diakses 06/12/2023.
Suprapto, Yitno. “Cerita Kala Kepercayaan Adat Orang Mentawai Dilarang, dan Pindah dari Hutan (Bagian 1)” dalam https://www.mongabay.co.id/2018/01.28/cerita-kala-kepercayaan-adat-orang-mentawai-dilarang-dan-pindah-paksa-dari-hutan-bagian-1/, diakses 24/11/2023.
Sya’rani M., Atika (Ed.). 1985. Kamus Mentawai-Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departeman Pendidikan dan Kebudayaan.
The Editors of Encylopedia Britanica. “ethnography”, dalam https://www.britannica.com/science/ethnography, diakses 10/12/2023.
Tulius, Juniator. 2012. Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts Over Land in Mentawai – Indonesia (PhD thesis). Leiden: Leiden University, ISBN: 978-94-6203-160-9.
Utami, Rini. “”Kho Ping Hoo” akhirnya tiba di tanah leluhurnya” dalam https://m.antaranews.com/berita/409520/kho-ping-hoo-akhirnya-tiba-di-tanah-leluhurnya, diakses 11/12/2023.
Wahyuni, Dwi, dkk. “Resistensi Arat Sabulungan terhadap Modernisasi: Analisis Kritis atas Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang” dalam Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2023. URL: http://dx.doi.org/10.15575/jt.v6i1.25670, diakses 22/11/2023.
Windiyarti, Dara. “Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang: Representasi Budaya Masyarakat Tradisional Suku Mentawai yang Terkoyak” dalam Sirok Bastra, Vol. 9 No. 2, Desember 2021: 167-184.
Siritoitet, Martison. “Kisah Kuno Untuk Masa Depan Kita” dalam http://www.sukumentawai.org/id/2019/08/kisah-kuno-untuk-masa-depan-kita, diakses 26/11/2023.
Wikipedia. “Autoethnography” dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Authoethnography, diakses 08/12/2023.
Wikipedia. “China Men” dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/China_Men, diakses 11/12/2023.
Wikipedia. “Ethnography”, dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ethnography, diakses 08/12/2023.
Wikipedia. “Ethnofiction”, dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ethnofiction, diakses 08/12/2023.
Wikipedia. “Kho Ping Hoo” dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kho_Ping_Hoo, diakses 11/12/2023.
Wikipedia. “Participant observation” dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Participant_observation, diakses 10/12/2023.
Wikipedia. “Sikerei”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sikerei, diakses 22/11/2023.
—-
[1] Sikerei adalah dukun yang memiliki pengetahuan, keahlianserta keterampilan dalam pengobatan, yang dapat berhubungan dengan roh-roh dan jiwa orang-orang di alam nyata maupun di alam gaib. Karena itu, sikerei memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat Mentawai. Di samping menjadi tokoh pengobatan dan spiritual, sikerei juga menjadi pemimpin ritual dalam setiap upacara adat atau pesta di uma. Lihat Dara Windiyarti, “Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang: Representasi Budaya Masyarakat Tradisional Suku Mentawai yang Terkoyak” dalam Sirok Bastra, Vol. 9 No. 2, Desember 2021: 167-184.
[2] Menurut Wikipedia, upacara untuk mengangkat seseorang menjadi sikerei ini disebut sebagai Tadek. Seluruh rangkaian upacara Tadek ini dipersiapkan oleh keluarga calon sikerei, termasuk pembiayaan upacara. Upacara Tadek ini adalah pemberitahuan adanya sikerei baru sekaligus untuk menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang sikerei, seseorang harus belajar kepada sikerei senior terlebih dahulu. Istilah Tadek ini tidak disebutkan oleh Niduparas Erlang dalam novelnya Burung Kayu. Lihat Wikipedia, “Sikerei”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sikerei, diakses 22/11/2023.
[3] Tatung (ejaan Hakka: Ta Thung; 打童, Pinyin: Da Tóng) adalah ritual memanggil dewa merasuki tubuh para perantara yang disebut Thung Se (Tóng Zǐ [童子]) dalam masyarakat Cina-Hakka penganut Shenisme (ajaran Tri Darma: Kongfuchu, Buddha, Taoisme). Di Cina Daratan dan Taiwan, Tatung (sebuah istilah yang di Indonesia lazim digunakan di Kalimantan Barat, khususnya Singkawang) lebih dikenal dengan istilah Thiau Thung ( 跳童[Tiào Tóng]). Sedangkan di Pulau Bangka, kampung halaman saya, ritual ini lebih kerap disebut Lok Thung (落童). Untuk mengenal ritual Tatung lebih jauh, silakan membaca cerpen-cerpen saya, antara lain “Jelaga Hio” (Sunlie Thomas Alexander, Malam Buta Yin, Yogyakarta: Gama Media, 2009, hlm. 52-64), “Lok Thung” (Sunlie Thomas Alexander, Istri Muda Dewa Dapur, Yogyakarta: Ladang Pustaka & Terusan Tua, 2012, hlm. 77-88), “Thung Se” (Sunlie Thomas Alexander, Makam Seekor Kuda, Yogyakarta: Indie Book Corner, 2018, hlm. 125-139) dan “Kakekku yang Lain” / “My Maternal Grandfather” (Sunlie Thomas Alexander, My Birthplace and Other Stories, Jakarta: The Lontar Foundation, 2019, hlm. 81-97 dan 3-18). Sementara artikel dalam bahasa Indonesia yang menurut saya cukup representatif mengenai ritual Cina ini antara lain dapat dibaca di Marlen Sitinjak, “Arti Tatung / Asal Usul Tatung / Sejarah Tatung atau Lokthung Pada Perayaan Cap Go Meh Singkawang”, dalam https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/13/arti-tatung-asal-usul-tatung-sejarah-tatung-atau-lokthung-pada-perayaan-cap-go-meh-singkawang (diakses 25/11/2023) dan Kumparan, “Tatung, Manusia Pilihan yang Rela Dimasuki Roh Dewa demi Tradisi”, dalam https://m.kumpuran.com/kumparantravel/tatung-manusia-pilihan-yang-rela-dimasuki-roh-dewa-demi-tradisi-1shoxf0G6qh (diakses 25/11/2023).
[4] Menurut antropolog Mentawai Juniator Tulius, Arat Sabulungan adalah nama sistem kepercayaan tradisional Mentawai yang dikenal saat ini. Dahulu suku Mentawai tidak memiliki istilah khusus untuk sistem kepercayaan mereka. Gereja dan pemerintah setempat menciptakan istilah ini untuk membedakan antara Arat Puaranan (salah satu atau semua agama di dunia) dan Arat Sabulungan (kepercayaan tradisional). Dengan melakukan hal ini, pemerintah dan gereja lokal bisa lebih mudah melarang warga Mentawai mempraktikkan Arat Sabulungan. Istilah ini terbentuk dari kata sa dan bulungan. Sa adalah kesatuan jamak dari sesuatu, sementara akar kata bulungan adalah bulu, yang artinya “persembahan”. Bulungan dipahami sebagai sekelompok makhluk halus yang tidak dikenal. Dengan demikian, Sabulungan adalah sekelompok makhluk halus yang kepadanya diberikan persembahan khusus (buluat). Jadi, Arat Sabulungan adalah kepercayaan yang berpusat pada keberadaan makhluk halus. Dipercayai melalui berbagai ritual yang berbeda, manusia dapat melakukan kontak dengan makhluk halus. Karena itu menurut Tulius, para sarjana Indonesia yang mempelajari budaya Mentawai telah memberikan definisi yang keliru tentang Sabulungan. Mereka mengartikan bulungan seolah-olah didasarkan pada akar kata bulug yang berarti “daun”. Itu sebabnya mereka berasumsi bahwa Sabulungan adalah sistem kepercayaan yang didasarkan pada kekuatan daun yang menjadi perantara hubungan sakral antara masyarakat Mentawai dan makhluk gaib (lihat Sihombing, 1979; Rudito, 1993; 1999). Dalam pandangan para sarjana ini, masyarakat Mentawai lebih percaya kepada jenis dedaunan tertentu dibandingkan dengan roh. Lihat Juniator Tulius, Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts Over Land in Mentawai – Indonesia (Leiden: Leiden University, 2012), 69.
[5] Niduparas Erlang, Burung Kayu (Padang-Jakarta: CV. Teroka Gaya Baru, 2020), 148.
[6] Ibid, hlm. 146.
[7] Ibid, hlm. 143-144.
[8] Ibid, hlm. 35.
[9] Ibid, 15-16.
[10] Seperti yang dikutip oleh akun instagram Teroka Press dari sukumentawai.org: “Budaya Mentawai kaya akan tradisi mendongeng, dari kisah-kisah tentang asal-usul sikerei, lagu-lagu roh tanaman obat Mentawai, tulisan suci upacara dibacakan dalam bahasa-bahasa lama Siberut, dan diskusi tengah malam memetakan wilayah, sumber daya dan sejarah keluarga, di antara banyak lainnya. Itulah cara orang Mentawai bertemu dan berinteraksi dalam harmoni sejati. Namun sekarang telah berubah.” Selengkapnya lihat Martison Siritoitet, “Kisah Kuno Untuk Masa Depan Kita”, dalam http://www.sukumentawai.org/id/2019/08/kisah-kuno-untuk-masa-depan-kita, diakses 26/11/2023.
[11] Masyarakat Mentawai juga memiliki cerita tentang kera, buaya, kura-kura, burung, ular, babi, rusa, dan kadal yang menggambarkan siapa mereka dan bagaimana mereka hidup. Cerita seperti ini juga disebut pungunguan. Masyarakat Mentawai memanfaatkan ciri-ciri hewan untuk mengajari masyarakat tentang perilaku hewan tersebut dan menggunakannya sebagai contoh bagi manusia. Cerita Pungunguan mungkin lucu, heroik, atau mendidik. Contoh cerita seperti ini dapat ditemukan dalam naskah Karl Simanjuntak yang tidak diterbitkan (1914), berjudul Pungunguanda Sakalagan. Sebagian besar cerita dalam naskah ini bercerita tentang keberanian dan mencakup cerita tentang tokoh legendaris Pagetasabbau. Cerita tentang Pagetasabbau juga menggambarkan kedekatan seorang paman (Pagetasabbau) dengan kedua keponakannya. Cerita pungunguan tersebut menyampaikan moral tentang budaya dan tradisi, tentang bagaimana seharusnya masyarakat belajar hidup bermasyarakat. Juniator Tulius, Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflicts Over Land in Mentawai – Indonesia, 198.
[12] Menurut Tulius, lagu-lagu biasa (nonritual) disebut sebagai urai simata’ atau leleiyo (lagu rakyat biasa) yang umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti urai soubaga (sorrowful songs), urai belet baga (sad songs), urai goat baga (lonesome songs), urai angkat baga (happy songs), and urai nuntut baga (love songs). Ibid, 200.
[13] Niduparas Erlang, 155.
[14] Juniator Tulius, 67.
[15] Ibid, 273-274. Terjemahan oleh Sunlie Thomas Alexander.
[16] Ibid, 276. Terjemahan oleh Sunlie Thomas Alexander.
[17] In order to remember the content of a family story, there are rules and methods to guide storytellers to tell their family story properly. They choose particular occasions to tell the stories. Certain elders are chosen to play the important role as the prominent storyteller of their family stories. These elders maintain their family stories carefully by accurately transmitting the essential content of the stories through the generations, mostly to those who are perceived by the elders to have a certain quality and talent in speaking, listening and memorizing what they have heard. For a kin group it is crucial to maintain the stories accurately and as completely as possible, because family stories establish the identity of the kin group. Mentawaians do not tolerate the existence of a new version of their family story. Ibid, 201.
[18] Versi cerita kelompok yang satu menunjukkan bahwa konflik awal disebabkan oleh kesalahan sang kakak, sedangkan versi kelompok yang lain menekankan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh sang adik. Dalam Cerita Mangga versi lain, kita membaca bahwa ibu dari keluarga tersebut melakukan kesalahan dengan menganggap menantu perempuannya tidak bersalah. Perbedaan-perbedaan ini menandakan kurangnya keterhubungan di antara kelompok-kelompok tersebut. Ibid.
[19] Ibid, 211.
[20] Ibid, 214-215.
[21] Ibid.
[22] Ibid, 140-141. Terjemahan oleh Sunlie Thomas Alexander.
[23] Ibid, 171. Terjemahan oleh Sunlie Thoms Alexander.
[24] Aveus Har pernah menuliskan secara ringkas proses kreatifnya menggarap novel Tak Ada Embusan Angin (salah satu dari “lima naskah yang menarik perhatian juri” dalam Sayembara Novel DKJ 2023) di akun Facebook-nya, 12 Agustus 2023, yakni bagaimana ia mencoba mengali referensi/melakukan riset untuk bahan novel tersebut melalui obrolan dengan sejumlah temannya yang berasal Aceh. Berikut penggalan tulisan di akun Facebook-nya tersebut: “Mula-mula saya mengobrol dengan Nanda Winar Sagita, menjajaki kemungkinan menulis sebuah cerita dengan latar Aceh. Berselang waktu, beliau sibuk dengan urusan pribadi, dan saya mencari-cari siapa gerangan kawan Aceh yang bisa saya ajak bicara. Saya menghubungin S Gegge Mappangewa, dan menanyakan nomor kontak FLP Wilayah Aceh. Dari sini pengembaraan saya bermula. Berbicara dengan orang satu dan dialihkan ke orang lain dan dialihkan ke lain lagi, demikian sampai saya bertemu dua orang yang tidak mau disebut namanya—cukup inisial yang saya sebut pada ucapan terima kasih di buku. Maneh Maulu hidup di kepala saya dari obrolan-obrolan itu. Saya juga sempat berbincang panjang dengan Pidar Lingi, yang dengan senang hati dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya meskipun zona waktu kami berbeda—dia di Polandia saat itu, kalau tak salah ingat. Saya tahu, saya tidak mungkin bisa menceritakan Maneh Maulu sebaik jika kisah itu diceritakan oleh orang Aceh, tetapi saya telah berusaha menjadi Maneh Maulu dengan segenap emosi dan pikiran saya.” Lihat https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0yxf4kHwcfNaTefEZTtzBa5pnGncaBuuKf228611BbaeFKDCVmv6Cj5RgnfFa58KWI&id=100000174022521&mibextid=9R9pXO, diakses 11/12/2023.
[25] Seperti yang dikutip Wikipedia dari sejumlah sumber: Kingston wrote The Woman Warrior and China Men as one and would like them to be read together; she decided to publish them separately in fear that some of the men’s stories might weaken the feminist perspective of the women’s stories. The collection becomes what A. Robert Lee calls a “narrative genealogy” of Chinese Settlement in the United States. To tell their stories, many of which Kingston heard only through the talk-story of the women in her family, she mixes the know history of her family with hypothetical imaginings and with the legal history of Chinese America” (huruf tebal oleh saya). Lihat https://en.m.wikipedia.org/wiki/China_Men, diakses 11/12/2023.
[26] Rini Utami, “”Kho Ping Hoo” akhirnya tiba di tanah leluhurnya” (14 Desember 2013), dalam https://m.antaranews.com/berita/409520/kho-ping-hoo-akhirnya-tiba-di-tanah-leluhurnya, diakses 11/12/2023.
[27] Menurut Wikipedia, karena tidak bisa berbahasa Mandarin (baca-tulis), Kho Ping Hoo tidak memiliki akses ke sumber-sumber sejarah negeri Tiongkok yang berbahasa Tionghoa, sehingga banyak fakta historis dan geografis Tiongkok dalam cerita-ceritanya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lihat https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kho_Ping_Hoo, diakses 11/12/2023.
[28] Seperti yang dikutip oleh Padangkita.com, menurut Nidu: “Sudah lama saya tertarik dengan masyarakat Mentawai beserta segala adat istiadat dan persoalannya, baik sebagai akademisi tradisi lisan maupun sebagai penulis fiksi. Berbagai referensi bacaan terkait itu saya kumpulkan bertahun-tahun. Namun, jalan untuk menuliskannya dalam bentuk fiksi baru terbuka pada 2018 lalu. Saya memperoleh kesempatan residensi dari Kominte Buku Nasional dan memilih Mentawai sebagai tujuan. Di sana saya bermukim selama dua bulan, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Mentawai.” Lihat https://padangkita.com/novel-burung-kayu-meneroka-sastra-lisan-mentawai/, diakses 06/12/2023.
[29] Wahyuni, Dwi, dkk. “Resistensi Arat Sabulungan terhadap Modernisasi: Analisis Kritis atas Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang” dalam Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2023. URL: http://dx.doi.org/10.15575/jt.v6i1.25670, diakses 22/11/2023.
[30] Redaksi. ““Burung Kayu”, Novel Etnografis Karya Niduparas Berlatar Mentawai”, dalam https://alif.id/read/redaksi/burung-kayu-novel-etnografis-karya-niduparas-yang-berlatar-mentawai-b231189p/, diakses 06/12/20203/
[31] Lihat Wikipedia, “Ethnography”, dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ethnography, diakses 08/12/2023. Masih menurut Wikipedia pada laman yang sama: “Para etnografer umumnya menggunakan metode kualitatif, kendati mereka juga dapat menggunakan data kuantitatif. Etnografi umumnya merupakan studi holistik dan mencakup sejarah singkat, serta analisis medan, iklim, dan habitat. Meskipun secara tradisional, etnografi mengandalkan kehadiran fisik peneliti dalam suatu latar, ada pula penelitian menggunakan label yang mengandalkan wawancara atau dokumen. Hal ini terutama ketika seorang peneliti ingin menyelidiki peristiwa di masa lalu. Ada juga sejumlah virtual atau online ethnography, yang terkadang disebut sebagai ‘netnography’ atau ‘cyber-ethnography’.”
[32] Lihat The Editors of Encylopedia Britanica, “ethnography”, dalam https://www.britannica.com/science/ethnography, diakses 10/12/2023.
[33] Wikipedia, “Participant observation”, dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Participant_observation, diakses 10/12/2023.
[34]Niduparas Erlang, “Perihal Bahasa Mentawai dalam Novel Burung Kayu yang Sering Dipertanyakan Pembaca (dari Grup Apresiasi Sastra) dalam https//:m.facebook.com/story.php?story_fid=pfbid0jsknMvp69YTMbA6AvfmrNN19ET7giTnzeFKKdo8mmLf5DszFasaHHiQKaN5UlrYml&id+1376345033&mibextid=9R9pXO, diakses 10/12/2023.
[35] Vito Laterza, “The Ethnographic Novel: Another Literary Skeleton in the Anthropological Closet?” dalam Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 32 (2), January 2007.
[36] Kaburnya batasan antara fiksi dan sains bukanlah perkara baru di kalangan peneliti etnografi. Dalam pengantar buku Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (Clifford and Marcus 1986), James Clifford menulis tentang bagaimana para antropolog terkenal di awal tahun 1900-an seperti Bronislaw Malinowski, Margaret Mead, Edward Sapir dan Ruth Benedict memahami diri mereka sebagai penliti sekaligus penulis dalam rasa yang lebih artistik (Clifford 1986:3). Hal ini menunjukkan bahwa genre campuran dan cara penulisan alternatif mempunyai tradisi panjang dalam etnologi dan antropologi. Jenny Ingridsdotter & Kim Silow Kallenberg, “Ethnography and the Arts: Examining Social Complexities through Ethnographic Fictions” dalam Etnofoor, Stories, volume 30, issue 1, 2018, 58.
[37] Dalam wawancara dengan Damien Stankiewcz, antropolog dan penulis Amitav Ghosh mengatakan bahwa bagian tersulit dalam membuat deksripsi etnografis adalah Anda tidak bisa memahami isi kepala orang (Stankiewicz 2012: 539). Kita tidak bisa mengamati pikiran orang. Namun, menurut Ghosh, hal ini membuka peluang (kemungkinan) kepenulisan fiksi karena genre fiksi itu sendiri didasarkan pada keinginan untuk melihat dunia melalui sudut pandang orang lain. Ibid, 57-75.
[38] Vito Laterza, “The Ethnographic Novel: Another Literary Skeleton in the Anthropological Closet?”, 131.
[39] Menurut penyair dan arsiparis Dewan Kesenian Jakarta, Esha Tegar Putra, seperti yang dikutip oleh Padangkita.com: “Sejauh yang terlacak, baru ada tiga fiksi yang fokus bercerita tentang Mentawai. A. Damhoeri, salah seorang sastrawan Balai Pustaka, pernah menulis dua fiksi tentang Mentawai, yaitu Depok Anak Pagai yang terbit pertama kali pada 1939 serta Ratu Pulau Mentawai yang pernah terbit secara bersambung di majalah Dunia Islam & Panji Islam pada 1940. Selain ini pernah ada juga roman berjudul Darah Mentawai karya Hassan Noel ‘Arifin yang terbit di majalah Loekisan Soesana edisi Juli-Agustus 1946.” Lihat Sonia, “Novel Burung Kayu: Meneroka Sastra Lisan Mentawai” dalam https://padangkita.com/novel-burung-kayu-meneroka-sastra-lisan-mentawai/, diakes 09/12/2023.
[40] Dalam “Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2018” tertulis antara lain: “[…] Penulisnya (baca: Felix K. Nesi) mampu menggambarkan budaya, suasana kehidupan, karakter orang timur [sic!] dengan sangat kental dan akurat: sebuah contoh fiksi etnografis yang digarap dengan baik”. Lihat https://dkj.or.id/berita/pertanggungjawaban-dewan-juri-sayembara-novel-dewan-kesenian-jakarta-2018/, diakses 07/12/2023.
[41] Lihat Dude, “Novel Etnogafi Sebagai Kritik Budaya” dalam https://gudeg.net/read/3608/novel-etnografi-sebagai-kritik-budaya.html, diakses 08/12/2023. Bandingkan dengan informasi tentang karakteristik novel Burung Kayu sebagai novel etnografis yang diberikan oleh Teroka Press dalam https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KmKVWnAvnQFBNWSSt17mNsTwSCfRDNArZm8PJUbf89GJjaFAzVrr19MqwBa1ruLPI&id=107491990771262&mibextid=9R9pxO, diakses 11/012/2023.
[42] Wikipedia, “Autoethnography”, dalam https://en.m.wikipedia.org/wiki/Authoethnography, diakses 08/12/2023.
[43] Jenny Ingridsdotter & Kim Silow Kallenberg, “Ethnography and the Arts: Examining Social Complexities through Ethnographic Fictions”. Terjemahan oleh saya.
[44] Ibid. Terjemahan oleh Sunlie Thomas Alexander.
[45] Lihat catatan kaki 35.
[46] Niduparas Erlang, 68.
[47] Lihat Padel Muhamad Rallie Rivaldy, “Visi Pengarang dan Narator Berafiliasi dalam Burung Kayu karya Niduparas Erlang” dalam http://ejournal.uki.ac.id/index.php/dia/article/view/4749, diakses 21/11/2023.
[48] Redaksi, “Penulis Banten Raih Kusala Sastra Khatulistiwa 2020” dalam https://www.bantennews.co.id/penulis-banten-raih-kusala-sastra-khatulistiwa-2020/, diakses 22/11/2023.
[49] Ade Irwandi & Kris Irwandi Saleleubaja, “Dari Sagu ke Beras: Perubahan Kehidupan sosial Budaya Orang Mentawai” dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 47 No. 2 Tahun 2021.
[50] Niduparas Erlang, 6-7.
[51] Ibid, 71.
[52] Ade Irwandi & Kris Irwandi Saleleubaja, “Dari Sagu ke Beras: Perubahan Kehidupan sosial Budaya Orang Mentawai”.
[53] Ibid.
[54] Niduparas Erlang, 115.
[55] Lihat Daniel Defoe, Robinson Crusoe, terjemahan Peusy Sharmaya (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010).
[56] Niduparas Erlang, 119.
[57] Wahyuni, Dwi, dkk. “Resistensi Arat Sabulungan terhadap Modernisasi: Analisis Kritis atas Novel Burung Kayu Karya Niduparas Erlang”.
[58] Juniator Tulius, 72-73.
[59] Wahyuni, Dwi, dkk.
[60] Selengkapnya lihat Yitno Suprapto, “Cerita Kala Kepercayaan Adat Orang Mentawai Dilarang, dan Pindah dari Hutan (Bagian 1)”, dalam https://www.mongabay.co.id/2018/01.28/cerita-kala-kepercayaan-adat-orang-mentawai-dilarang-dan-pindah-paksa-dari-hutan-bagian-1/, diakses 24/11/2023.
[61] Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 1994), 86
[62] Homi K. Bhabha, “The World and the Home”, Social Text, 10 (31-2), 1992, 141-153, 144.
[63] Niduparas Erlang, “Mengapa Tubuh Saya Menolak Makan Babi”, dalam https://alif.id/read/niduparas-erlang/mengapa-tubuh-saya-menolak-makan-babi-b215701p/, diakses 29/12/2023.
[64] Lihat Paul Brians, “Notes for Salman Rushdie: The Satanic Verses”, dalam http://public.wsu.edu/~brians/anglophone/satanic_verses/copyright.html, diakses 2014.

Sunlie Thomas Alexander
Sunlie Thomas Alexander lahir di Belinyu, Bangka, 7 Juni 1977. Menyelesaikan pendidikan Teologi dan Filsafat di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia telah menerbitkan sejumlah buku cerpen, puisi, dan esai seperti Malam Buta Yin (cerpen, 2009), Istri Muda Dewa Dapur (cerpen, 2012), Sisik Ular Tangga (puisi, 2014), Makam Seekor Kuda (cerpen, 2018), Dari Belinyu ke Jalan Lain ke Rumbuk Randu (kritik sastra, 2020), dan Seperti Karya Sastra, Hidup Bukanlah Racauan (esai, 2021). Karya-karyanya yang terbit dalam terjemahan, antara lain Youling Chuan (cerpen dan puisi, dalam bahasa Mandarin, 2016) dan My Birthplace and Other Stories (cerpen, dalam bahasa Inggris, 2019).