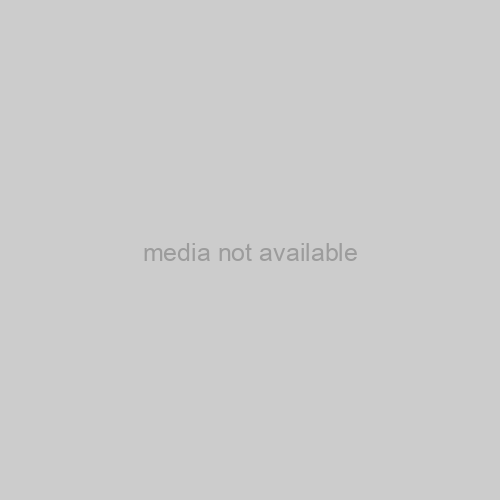Selama beberapa dekade terakhir, kritik sastra feminis telah memainkan peran penting dalam membuka lapisan-lapisan tersembunyi dalam teks sastra. Khususnya, dalam mengungkap bagaimana struktur naratif yang tampak netral sesungguhnya menyimpan jejak penindasan dan perlawanan gender. Salah satu pendekatan yang menonjol dalam arus ini adalah penggunaan metafora palimpsest—sebagaimana dikembangkan Sandra M. Gilbert dan Susan Gubar dalam The Madwoman in the Attic (1979)—yang menggambarkan strategi estetik para penulis perempuan pada abad ke-19. Menurut kedua kritikus, karya-karya penulis perempuan tersebut merupakan teks yang dalam desain permukaannya tampak patuh pada norma sastra patriarki, tetapi diam-diam menyembunyikan kontra-narasi yang subversif. Namun, karena pada saat yang sama, karya-karya mereka berwatak palimpsestic (menyembunyikan atau mengaburkan tingkat makna yang lebih dalam dari yang tampak di permukaannya), karya-karya mereka pun acap dianggap kurang bisa diakses dan diterima secara sosial. Di titik inilah, kritik sastra feminis lalu menugasi diri mereka untuk menyingkap makna atau kebenaran yang diyakini tersembunyi di balik desain permukaan teks palimpsestic semacam itu.
Tak berlebihan saya kira, jika kritik sastra yang diberati oleh tujuan dan agenda ideologis semacam itu, disebut sebagai kritik sastra yang tergoda untuk menjadi sejenis detektif. Ia berupaya membongkar makna yang tersembunyi, seolah-olah teks sekadar kamuflase. Metafora palimpsest yang dipopulerkan kritikus seperti Gilbert dan Gubar persis telah disinggung, cukup membuktikan adanya godaan tersebut. Namun, di situlah persisnya, menganga liang jebakan. Tafsir lalu mengira ada kebenaran tunggal di balik lapisan formal. Maka, meskipun terbilang visioner, pendekatan yang menekankan pelapisan sebagai strategi kamuflase dan penindasan ganda itu pun menuai kritik karena cenderung reduksionis.
Itulah mengapa, lantaran resah dengan pembacaan yang cenderung mereduksi kualitas literer teks semacam itu, Toril Moi mengingatkan bahwa tafsir demikian itu berisiko menjadikan makna sebagai kebenaran tunggal yang tersembunyi di bawah jangat formal suatu teks—yang oleh Julia Kristeva sebut lapisan feno-teks—sehingga memaksa teks tunduk pada hierarki tafsir tertentu. Hal ini juga menjadi problematik terutama karena bahkan istilah Palimpsest yang merujuk pada karya Hilda Doolittle (H. D.) sebagai sumber metafora untuk menggambarkan struktur teks yang berlapis lagi tumpang tindih itu sendiri, rupanya justru membantah “logika pelapisan-represi” yang mereka yakini.[1]
Pembacaan reduksionis semacam itu misalnya dapat kita temui pada kritik yang ditulis oleh Endiq Anang P. (selanjutnya disebut “Endiq”), berjudul Membedah Kaki Kelima Nirwan (Membongkar Ideologi Nirwan Dewanto dalam Buli-Buli Lima Kaki).[2] Bagi saya, pembacaan Endiq kurang tepat karena pada puisi-puisi Nirwan, yang kita temui tak jarang bukanlah makna tersembunyi yang menunggu disingkapkan, melainkan apa yang Sarah Dillon uraikan sebagai “involusi makna yang saling melintasi, mengaburkan, dan tak pernah mencapai satu pusat tetap nan stabil.”[3] Di titik inilah persoalan kemudian timbul. Ketika sastra dinilai lebih karena apa yang ia katakan alih-alih bagaimana ia mengatakannya, maka yang sedang berlangsung barangkali bukanlah kritik sastra, melainkan sejenis apologetik budaya.
Penting untuk dicatat terlebih dahulu, esai ini ditulis bukan dengan maksud untuk mengharamkan pendekatan politis atau ideologis dalam wujud apa pun seperti yang diterapkan oleh Endiq. Secara visi, yang demikian itu bisa jadi baik belaka. Akan tetapi, kritik sastra bukanlah sebentuk aktivisme. Oleh sebab itu, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa tafsir ideologis seperti diterapkan Endiq dalam kritiknya—betapa pun itu penting—disadari atau tidak akan rawan menghasilkan pembacaan yang berisiko memperkuda otonomi semantik puisi itu sendiri—khususnya, puisi-puisi yang memiliki relasi bentuk dan isi tidak linear persis pada puisi-puisi Nirwan. Alhasil, kritik pun menjadi tafsir yang tampak memaksakan kebenaran hipotesisnya sendiri, atau, jika meminjam ungkapan Georges Didi- Huberman: “menutup mata terhadap kejutan yang ditawarkan oleh tatapan.”[4]
Sebagai konsekuensi terbalik dari kecondongan kritik-tradisional karya penulis perempuan dengan (melulu) mengandalkan pembacaan feminisme, pembacaan terhadap karya penulis laki-laki pun kerap kali dijalankan dengan pendekatan yang sama. Dalam pembacaan Endiq atas sejumlah puisi Nirwan, si kritikus tampak memancarkan ego gelap pribadinya lantaran kecondongan dalam bertungkus-lumus menelusur jejak representasi tubuh, liyan, dan ideologi dalam puisi sehingga yang tampil adalah pola yang sama dari umumnya pembacaan ideologis, yakni sebuah pembacaan yang terlampau sibuk dengan persoalan isi dan politik representasi, sambil mengabaikan dinamika formal nan kompleks dari puisi itu sendiri.
Kritik yang diberati pretensi ideologis demikian, sering menyimpulkan hasil analisis dengan keyakinan tunggal, menganggap teks sebagai wadah penipuan yang menyimpan suatu “kebenaran tersembunyi”, dan tugas kritik adalah menguaknya seolah itu satu-satunya lapisan makna yang niscaya. Alhasil, kritik Endiq tampak disusun lebih sebagai bukti bagi ideologi patriarkal yang sekonyong-konyong ditautkan dengan diri si penyair—yang diyakini, bersembunyi di balik larik-larik puitik Nirwan. Ini misalnya tampak pada bagaimana kritikus mempersamakan “aku-lirik” sebagai “diri-biografis” atau “aku-biologis” si penyair, mengabaikan, misalnya, dedication line di bawah judul puisi “Sapi Lada Hitam” yang dicungkilinya. Dalam salah satu bahasan di bawah subtajuk “Perempuan yang Dijebak Nirwan pada Labirin”, kritikus juga membaca sejumlah puisi Nirwan sebagai teks yang secara laten mengonstruksi dominasi maskulin, dan secara sadar menjebak sosok perempuan ke dalam perangkap simbolik yang merepresentasikan kekuasaan patriarkal; memosisikan tubuh perempuan mutlak sebagai situs perebutan kuasa, dan penyair sebagai subjek laki-laki yang menyusunnya dalam posisi subordinat.
Tafsir seperti itu memang memiliki nilai politis. Dan ia, barangkali, juga dihasilkan dari kesadaran akan urgensi tujuannya. Namun, justru karena pretensi nilai dan tujuan itulah ia menjadi reduktif ketika diterapkan pada puisi modern—yang tak selalu bergerak linear dalam hubungan reflektif antara “diri-penyair” dan “aku-puisi”. Saya kira, bahasa puisi modern lebih kerap tampil sebagai yang eksentrik, subversif, dan lihai berkilah dari pemaknaan ideologis tunggal. Tak jarang, ia merupakan perwujudan estetika kebebasan dari, misalnya, tradisi, kelas, gender, bahkan juga diri penyairnya sendiri.
Maka, tafsir ideologis itu akhirnya mengabaikan bagaimana puisi Nirwan kental oleh pemiuhan. Bagaimana Nirwan, misalnya, tampak berikhtiar meradikalkan bentuk, membangun metafora dari metafora, menjauhkan perbandingan dari asosiasinya, detail citra yang rizomatik, sehingga bahasa puisinya terasa menepis berbagai tujuan penjelasan; membuat puisi menjadi sejenis derau, gangguan, atau apa pun yang mengacu pada penolakan terhadap segala upaya pemaknaan tunggal. Dengan corak puisi yang demikian, kita sebetulnya patut curiga bahwa, bukan tidak mungkin si penyair tidak sedang menulis tentang perempuan, tetapi menulis bagaimana perempuan selama ini telah ditulis, katakanlah, oleh tragedi, agama, seni rupa, atau barangkali oleh puisi-puisi pendahulunya.
Bentuk penilaian sebagaimana kita dapati pada kritik yang ditulis oleh Endiq agaknya juga luput menimbang bahwa meski puisi kerap tampil sebagai suara seorang “aku” yang berdiri di hadapan sebuah lanskap—entah nyata atau bayang belaka—dan menyampaikan wicara seakan-akan suara itu berasal dari pengalaman langsung si penyair, semeyakinkan apa pun kesan biografis tersebut, tetap saja puisi—khususnya puisi modern—tak bisa didudukkan secara paksa sebagai cermin diri si penyair. Sebab, ia adalah hasil dari pergulatan si penyair dengan konvensi yang melingkupinya, di mana pengalaman biografis itu diolah ketimbang sekadar disalin secara verbatim. Diri biografis itu diserap, ditransformasikan, lalu diberi ruang untuk berkembang menjadi tema yang tak selalu berkait langsung dengan kenyataan, melainkan dengan kemungkinan-kemungkinan makna yang ditawarkan oleh bahasa puisi itu sendiri. Demikianlah, puisi akhirnya tak hanya tampil sebagai yang in praesentia melainkan juga yang in absentia.
Selain itu, menafsir “aku-lirik” sebagai “aku-penyair” akan berisiko fatal jatuh menjadi falasi autobiografis. Dalam konteks kritik sastra yang menggunakan pendekatan feminisme, falasi autobiografis misalnya terpancar dari keyakinan bahwa tulisan perempuan entah bagaimana dipandang lebih dekat dengan pengalaman pribadi dibandingkan tulisan laki-laki. Oleh sebab itu, ketika misalnya puisi penyair perempuan dalam fenoteksnya menampilkan citra atau imaji yang menyugestikan domestikasi, ekspresi tersebut niscaya diposisikan sebagai suara pilu si penyair perempuan itu sendiri—atau setidaknya, perpanjangan dramatis dari ketidaksadarannya. Hal demikian itu bukanlah fenomena anyar dalam kritik sastra. Ia sering menjadi kelumrahan, bahkan dalam taraf yang telah mentradisi. Namun, tentu tidak semua yang telah mentradisi lantas benar belaka, dan justru sebab itulah ia menjadi perlu dipersoalkan.
Penting pula untuk dicatat, falasi otobiografis juga tak luput terjadi pada teks laki-laki. Sebagai permisalan, ketika Chairil Anwar secara formal menggunakan diksi betina atau wanita alih-alih perempuan, pemilihan diksi tersebut kerap dianggap mutlak sebagai pancaran personalitas Chairil, atau sekurang-kurangnya perpanjangan dari ketidaksadarannya—sesuatu yang akhirnya kian menabalkan mitos biografis Chairil sebagai Sang Binatang Jalang. Itulah mengapa barangkali, Cep Subhan KM dalam esai berjudul Citra Subjek Feminin dalam Puisi Chairil Anwar: Sebuah Konsekuensi Lain Pembacaan Biografis menyebut: “Mengatakan bahwa Chairil Anwar adalah penyair sadar-gender seperti para feminis pada tahun 2022 semata karena dia banyak menggunakan diksi perempuan dan tidak menggunakan diksi wanita dalam puisi-puisinya sama tidak relevannya dengan mengatakan bahwa dia penyair misoginis semata karena dia menggunakan diksi betina untuk subjek feminin.”[5] Bukankah ini juga yang kita dapati dari pembacaan Endiq atas puisi-puisi Nirwan?
Dalam tafsirnya, Endiq misalnya menulis: “Entah laki-laki itu bernama Minotaur, Theseus, atau Nirwan, misalnya, ia akan sama saja: mengandalkan buli-buli demi memikat perempuan. Begitu pentingnya buli-buli maka benda ini perlu dirawat agar selalu perkasa sehingga patukannya mematikan (hlm. 36)”; “Hingga semakin benderanglah gagasan yang ada di balik ragam pilihan kata Nirwan atas nama buli-buli, yaitu alat untuk menaklukkan sang objek [perempuan]: taji, gading, belalai, linggis, hingga pisau. Sila dibayangkan bagaimana lingga perempuan di-taji, di-linggis, atau ditikam dengan pisau oleh si pemangsa, seraya ia menyanyikan kidung pujian demi menutupi maksud hati sebenarnya . . . Begitulah perempuan dalam perspektif Nirwan yang mesti berlaku serba sempurna, anggun, dan indah karena ia akan tampil di depan bangsawan (sang tuan; laki-laki) (hlm. 38-39)”; atau “Lantas, ia pun menghilang: “sang puan dukacita tak terlihat lagi”. Mungkin saja, ia kembali diperangkap dalam labirin agar “taji”, “gading”, “belalai” dan “linggis” Nirwan tak kehilangan taklukan . . . Kita tentu tahu “film pendek tanpa alur” adalah film porno. Dengan kata lain, si aku tengah men-taji, me-linggis si perempuan tanpa melibatkan perasaan (hlm. 44)”.
Segala tafsir Endiq ini menunjukkan indikasi adanya falasi otobiografis, di mana penanda-penanda seperti Minotaur, buli-buli, taji, gading, belalai, linggis, atau pisau dilihat semata-mata sebagai simbol kejantanan yang dilekatkan pada identitas personal-biologis si penyair. Kritik biografis semacam ini, bagaimanapun, gagal memperhatikan kompleksitas bentuk teks. Di penutup kritiknya, Endiq bahkan dengan cukup percaya diri merasa telah berhasil menyingkap apa yang ada di balik puisi-puisi Nirwan dengan mengatakan: “Ah, Nirwan. Demi tulisan ini, maaf jika terpaksa kubedah kaki kelimamu: si buli-buli itu.”
Barangkali juga penting untuk mengingat ulang metakritik Toril Moi atas pembacaan beberapa kritikus feminis semisal Elaine Showalter terhadap esai dan fiksi karya Virginia Woolf. Dalam pengantar Sexual/Textual Politics itu, Moi mengingatkan bahwa tampak betapa problematiknya pendekatan yang sekadar mengukur representasi dalam teks sastra terhadap kriteria ideologis-politis normatif. Moi mencatat bagaimana Virginia Woolf dikecam oleh kritikus feminis seperti Showalter karena tak menulis seperti yang mereka harapkan. Alhasil, Woolf dinilai terlalu simbolik, terlalu “tidak langsung”, dan terlalu bergulat dengan bentuk. Berseberangan dengan pandangan kritikus feminis seperti Showalter, yang menganggap bahwa segala hal yang menimbulkan ketidakjelasan sehingga teks tampak selalu meloloskan diri dari sudut pandang kritikus untuk dijabarkan dalam satu sudut pandang pemersatu, adalah wujud dari penolakan terhadap pemikiran feminis yang otentik, yakni “yang marah dan terasing”. Lebih dari itu, Showalter juga menilai bahwa karya Woolf tak berkomitmen, bahkan gagal sebagai karya feminis. Maka, dengan tegas Moi menolak penilaian reduksionis semacam itu, dan menekankan bahwa eksperimen dalam pengolahan bahasa adalah juga inti dari karya feminis sejati.[6]
Membaca Moi sambil berhadap-hadapan dengan penilaian Endiq atas puisi-puisi Nirwan tak pelak membuat saya bertanya-tanya: mungkinkah Nirwan—seperti Woolf—sebetulnya bukan sedang menjebak perempuan, seperti dituduhkan Endiq dalam kritiknya, melainkan justru menjebak pembaca yang masih percaya bahwa puisi mesti transparan secara ideologis? Bahwa makna niscaya bergerak secara linear? Apakah puisi Nirwan semata-mata menjebak perempuan sebagai objek dalam kerangkeng mitologis maskulin seperti dituduhkan oleh Endiq dalam kritik yang pada 2013 pernah didaulat sebagai Juara 2 Sayembara Kritik Sastra Dewan Jakarta (DKJ) itu? Atau justru puisi-puisi Nirwan menantang pembaca memeriksa batas bahasa dalam membayangkan, meniru, bahkan mengacaukan struktur tersebut?
Saya bayangkan, berhadapan dengan puisi seperti “Sapi Lada Hitam” atau “Kobra”, atau puisi Nirwan lain di Buli-Buli Lima Kaki (Gramedia Pustaka Utama, 2010) adalah berhadapan dengan situs ketidakstabilan. Membaca teks yang merupakan wujud dari “situs ketidakstabilan” sama artinya berperkara dengan teks yang unsur-unsur pembangun keseluruhannya disusun justru secara sumbang. Alhasil, berhadapan dengan teks semacam itu akan sama halnya dengan keniscayaan untuk berkonfrontasi, bukan hanya dengan cara penyampaian yang dioperasikan oleh penyair, melainkan juga dengan cara pembacaan terhadap bagaimana teks pelik itu beroperasi.
Makna di dalam puisi yang bergerak secara tak linear seperti pada “Sapi Lada Hitam” bukan serupa umbi tambun yang dapat kita ambil dengan mencangkul permukaan tanah yang menimbunnya. Ia lebih tampil menyerupai lapisan-lapisan kain penutup tubuh Drupadi dalam lakon wayang “Pandhawa Dadu” di mana saat Dursasana melucuti selapis demi selapis kain yang menutupi lekuk tubuh sang Panchali, setiap kali itu pula lapis-lapis kain itu tak habis-habisnya dilucuti. Tentu saja, menjadi Dursasana lebih melelahkan dan penuh ketidakpastian jika dibanding menggali umbi siap panen di ladang belakang rumah.
Dalam konteks pembacaan terhadap puisi yang tampil dalam wujud seperti itu, penyair tidak hanya bermaksud mengajak pembaca bersoal-jawab tentang apa yang dikatakan dan bagaimana sebuah puisi mengatakannya, tetapi juga tentang bagaimana keduanya kerap terlibat dalam sebuah konfrontasi— oleh sebab ketidaklinearan kedua unsur tersebut. Dalam ungkapan yang sama, ini berarti si penyair bermaksud menggiring pembaca kembali kepada “teks” itu sendiri. Bagaimana teks itu, misalnya, tampil mengemuka sekaligus menyembunyikan dirinya; mengundang sekaligus menantang kita untuk tidak sekadar melihat-nya, tetapi, lebih dari itu, memandang-nya.
Pembaca puisi “Sapi Lada Hitam” yang tak terburu membuhul makna kiranya akan menyadari bahwa “Sapi Lada Hitam”—termasuk puisi “Kobra” dan puisi-puisi lain Nirwan Dewanto semisal “Jangkar Perunggu”, yang dengan segala keterbatasan dan keterpaksaan, tidak bisa saya bahas seluruhnya—adalah sebuah hiperteks dari berbagai hipoteks yang bertindihan satu dengan yang lain; lapisan-lapisan yang tidak muncul secara eksplisit tetapi bekerja sebagai palimpsestuousness—struktur yang ditampakkan oleh teks karena proses penumpukan. Mengingat bahwa teks-teks yang terukir pada palimpsest tidak memiliki hubungan yang niscaya satu sama lain karena satu teks tidak diturunkan dari yang lain, dan pada saat yang sama, “yang satu” tidak berfungsi sebagai asal-muasal dari “yang lain”, maka pemfigurasi teks—dalam hal ini adalah Nirwan—sebagai palimpsest[7] tidak menggambarkan hubungan eksplisit antara suatu teks dengan sumber-sumbernya. Ia bukan serupa metafora asal-usul, keterpengaruhan, afiliasi, atau intertekstualitas sebagaimana umum dipahami.
Ditributkan kepada Francis Bacon, “Sapi Lada Hitam” memang dibuka dengan suara yang menggoda, tetapi taksa. “Tenanglah. Ia sudah kulumpuhkan dan kubawa hanya untukmu,” tulis penyairnya, dan siapa pun rawan terhasut untuk memaknainya sebagai ujaran yang merepresentasikan suara si subjek pemangsa atau penakluk. Namun, patut digarisbawahi: siapa “aku”, “ia”, dan “kau” di sana abu-abu belaka. Penyair tak menjelaskan, lebih-lebih menegaskannya. Alih-alih mencerahkan, tiga larik sesudah larik terkutip itu justru semakin mengentalkan ketidakpastian: “Bertahun-tahun kau menghunus pisau dan menyembunyikan/ diri darinya, aku tahu. Kau tak akan lagi melihat wujudnya yang biasa menggiriskanmu. Kupanggul ia kini. Sebab ia/ ternyata tak lebih perkasa ketimbang aku.” Identitas si “ia” baru muncul—itu pun secara sayup-sayup—pada dua kalimat setelahnya: “Telah kulepas/ tanduknya, tanduk yang kapan-kapan akan kukenakan untuk mempesonamu juga. Buli-buli yang menegang selalu di antara/ kedua pahanya akan kutanam untuk diriku sendiri, untuk terus mendatangkan serbuk jantan bagiku.”
Pembacaan Endiq terhadap “Sapi Lada Hitam” secara eksplisit memanggil figur Minotaur—makhluk separuh manusia separuh banteng yang dikurung dalam labirin oleh Raja Minos. Endiq lalu mengaitkan “ia” pada puisi Nirwan sebagai “lelaki” karena mungkin diatributi dengan “tanduk” sehingga cocok menjadi tinanda dari Minotaur, si manusia setengah banteng. Meski kita tahu, dalam puisi Nirwan, si “ia” dengan tanduk yang dilepas oleh si “aku” itu lebih relevan dengan “sapi”—sejalan judul puisi. Apa pun itu, si “aku” ditafsir Endiq sebagai juga laki-laki. Penautan ini, barangkali, dilandaskan pada larik: “Buli-buli yang menegang selalu di antara/ kedua pahanya akan kutanam untuk diriku sendiri, untuk terus mendatangkan serbuk jantan bagiku.” Meskipun taut-menaut identitas itu terasa pas belaka, ia akan segera menjadi problematik sebab larik tersebut justru menegaskan bahwa sebelum si “aku” memasang “Buli-buli yang menegang selalu di antara/ kedua paha” si “ia”, si “aku” belum juga jelas identitasnya. Apakah laki-laki, apakah perempuan, atau malah bukan kedua-duanya (?). Apakah dengan demikian, sebelum menanam “buli-buli” untuk dirinya sendiri, si “aku” adalah subjek beridentitas netral?
Tubuh sapi jantan yang telah dilumpuhkan itu kemudian dinarasikan dicabuti tanduknya oleh si “aku”; dihadiahkan kepada perempuan kekasihnya yang, dalam tafsir si kritikus, ditautkan secara linear dengan “Eriadne”, putri Raja Kreta dalam mitologi Minotaur. Berdasarkan acuan mitologi Minotaur tersebut, taut-menaut identitas secara linear itu dapat diringkas menjadi: (1) “aku” yang adalah tinanda “Theseus” = representasi subjek “laki-laki”, (2) “ia” yang adalah tinanda Minotaur, subjek yang dibunuh Theseus = representasi subjek “laki-laki”, dan (3) “kau” yang adalah tinanda Eriadne = representasi subjek “perempuan”. Representasi ini mungkin meyakinkan, sekurang-kurangnya, sebelum kita segera tahu bahwa yang meyakinkan tidaklah selalu tepat.
Ada juga pernyataan yang terus terang membuat saya cukup terusik, yang mana si kritikus menulis: “Begitu pun, perempuan dalam puisi “Sapi Lada Hitam” yang hidup di dunia urban. Ia takut pada Minotaur, tapi selalu merindukan buli-bulinya (kelaminnya) yang perkasa.” Pernyataan ini, bagi saya, justru membuat pembacaan dengan menerapkan pendekatan feminisme yang sudah dibangun secara visioner oleh si kritikus, jadi tak ubahnya banteng yang ia cabuti sendiri tajam tanduknya. Seolah-olah kritikus menilai bahwa setiap dari perempuan di dunia urban tidak hanya lemah, tetapi juga menyediakan dirinya untuk selalu dilemahkan an sich.
Jika mencermati bentuk formal “Sapi Lada Hitam”, puisi ini tampak juga analog dengan apa yang disebut Benstock sebagai palimpsest kompleks. Artinya, keseluruhan berbagai elemen—kita mungkin dapat menyebutnya hipoteks—eksis dalam suatu relasi palimpsestuous, yakni relasi di mana “setiap elemen dari pasangan oposisi didefinisikan oleh yang lain dan ditempati oleh yang lain”.[8] Koeksistensi semua elemen tersebut dibangun penyair secara disharmonis, katakanlah dengan membangun citra atau imaji yang ganjil dan karenanya menepis hasrat mimetik atau representasi. Alhasil, ia menuntut model pembacaan yang tidak mereduksi teks ke salah satu dari elemen penyusunnya.
Dalam pada itu, Diana Collecott merumuskan bentuk pembacaan terhadap teks bercorak demikian sejalan dengan gagasan Michael Riffaterre tentang “pembaca yang terinformasi”, yakni “pembaca yang membuat hubungan antara teks, interpretan, dan interteks”.[9] Bagi Collecott, pembacaan palimpsest tidak mengikuti makna literal dari bahasa Yunani-nya, yakni menggosok halus permukaan karena makna ini mengonotasikan kecenderungan pembacaan yang identik dengan praktik dekode biografis atau interpretasi reduktif. Sebaliknya, ia menyebut pembacaan palimpsest sebagai “prosedur yang tak terelakkan bersifat tentatif” yang “melibatkan pembacaan melalui lapisan-lapisan makna, yang hidup berdampingan dengan makna-makna ganda, dan kesiapsiagaan terhadap permainan makna antara teks tertentu dan interteksnya.”[10]
Maka, jika “Sapi Lada Hitam” kita baca menggunakan pembacaan palimpsestuous yang tak berupaya mengungkap makna tersembunyi atau yang tertekan/ditekan misalnya oleh simbolisasi penyair, melainkan menelusuri di dalam struktur, lapisan-lapisan teks yang saling mengunci sekaligus membuka di dalamnya, dapatlah kita katakan bahwa puisi Nirwan disusun oleh lapisan-lapisan wacana yang dijalin centang-perenang, serta apa yang juga disebut oleh Sarah Dillon sebagai “hiasan-ganjil” (queer frills)—aspek yang kemudian membuat makna puisi bergerak secara tidak linear itu. Konsep tentang queer frill yang disebut Dillon ini, tak pelak mengingatkan saya pada konsep Pan yang digagas oleh Georges Didi-Huberman.
Dalam Confronting Images, persisnya pada“Appendix: The Detail and the Pan”, Didi-Huberman mendefinisikan Pan sebagai “sebuah simtom di dalam gambar”. Inti dari konsep Pan yang ditawarkan Didi-Huberman saya kira merujuk pada pengalaman estetis yang melibatkan sejumlah detail (atau unsur kecil yang mungkin acap diabaikan) yang saling terhubung satu sama lain dalam sebuah gambar atau karya seni; di mana keterhubungan unsur-unsur kecil tersebut, menjadi semacam jaringan yang membentuk sebuah keutuhan gambar yang lebih besar—dan keluar dari sistem logika representasi mimetik. Analog dengan konsep Pan Huberman, queer frill adalah juga sejumlah detail yang mengundang efek “gangguan”, sebuah “derau”, atau “iritasi” yang disengaja, sehingga linearitas makna yang lahir dari representasi mimetik pun tergoyahkan. Sebelum beranjak ke sana, pertama-tama marilah kita sodorkan satu pertanyaan sederhana: Mengapa nama Francis Bacon ditaruh Nirwan di bawah judul puisinya?
Tentu saja peletakan nama Francis Bacon di bawah judul puisi itu tidak dilakukan Nirwan dengan tanpa tujuan. Sebab, pada puisi Nirwan yang lain, “Asep Rusdiana kepada Euis Sabariah”, nama yang sama disebut kembali di dalam larik, disandingkan dengan nama “Nasirun” dan diksi “rupa” (“Tanyalah ke Bacon dan Nasirun bagaimana rupaku kini./ Barangkali rupa yang tuntas ditikami seligi.”). Hal ini menjadi penting kita sorot, selain karena nama itu ditaruh sebagai dedication line, ia sekaligus menjadi penegasan bahwa nama yang ditaruh Nirwan di bawah judul puisinya, kemungkinan besar menunjuk pada Francis Bacon seorang pelukis kelahiran Irlandia—alih-alih misalnya, Francis Bacon seorang filsuf dan negarawan Inggris, sekaligus Bapak Empirisme. Meski tidak menutup kemungkinan satu nama itu bisa kita rujukkan pada kedua sosok itu sekaligus.
Jika benar nama itu merujuk pada Francis Bacon si pelukis, maka penting bagi kita untuk menarik benang penghubung bagaimana konsepsi seni Bacon dengan bentuk puisi Nirwan. Terutama, pada bagaimana misalnya Bacon kerap menghadirkan figur manusia di atas kanvasnya, bukan sebagai individu dengan diri yang utuh, melainkan daging yang terberai. Pada lukisan berjudul Portrait of George Dyer Crouching misalnya, George Dyer—kekasih Bacon (Bacon adalah seorang homoseksual)—tidak ditampilkan sebagai George Dyer si pribadi, melainkan sebagai sosok yang sudah terdistorsi. Figur yang telah terdistorsi itu, ditampilkan sedang berjongkok di atas sebuah papan loncat, sementara ruang di mana ia seharusnya melompat atau menyelam, terdiri dari sofa bundar sempurna.
Kita lantas tahu bahwa yang tampil dalam kanvas Bacon itu adalah ketidakstabilan penanda-tinanda. Itulah mengapa barangkali, Ernst van Alphen pun memandang lukisan-lukisan Bacon sebagai cara tubuh kehilangan pusat identitasnya—termasuk dalam hal ini, Portrait of George Dyer Crouching. Van Alphen menegaskan bahwa sebagaimana banyak lukisan Bacon lainnya, lukisan itu pun mengandung tanda-tanda yang maknanya saling bertentangan. Bahkan secara keseluruhan, tanda-tanda tersebut tidak membentuk ruang homogen yang dapat menyuguhkan bentuk dan identitas pada subjek di dalamnya.[11] Alhasil, yang hadir dalam Portrait of George Dyer Crouching bukanlah individu dengan diri yang utuh, melainkan daging yang telah tercerai dan tubuh yang tersiksa oleh ketakmenentuannya sendiri. Sosok Dyer itu tak hanya terdistorsi, tetapi juga rapuh. Tubuhnya melipat ke dalam dirinya sendiri, sehingga kemiripan dengan figur manusia pun hilang. Identitasnya lenyap, dan hanya meninggalkan sisa-sisa daging dan gestur keterhimpitan.
Apa yang ditawarkan oleh Bacon melalui lukisannya itu—jika kita merujuk van Alphen—sebetulnya ialah tawaran alternatif atau respons kritis terhadap konsepsi tentang representasi. Representasi, dalam hal ini, sudah bukan lagi dilihat sebagai reproduksi, melainkan prokreasi. Bagi van Alphen, karya Bacon menunjukkan ketegangan antara dua teori estetika, yang dapat dicirikan dalam istilah Peircean, yakni teori reproduksi yang didasarkan pada keutamaan ikonikitas di satu pihak, dan teori prokreasi yang didasarkan pada keutamaan indeksikalitas di pihak yang lain. Spesifiknya, van Alphen menyebut bahwa secara diskursif, karya Bacon mengusulkan teori estetika prokreasi melalui indeksikalitas sebagai jawaban atas efek pengasingan dari teori estetika reproduksi melalui ikonikitas. Walhasil, bayangan sosok-sosok dalam karya Bacon bukanlah ikon, melainkan indeks dari tubuh mereka—yang, seringkali ditampilkan secara provokatif.[12]
Puisi “Sapi Lada Hitam” karya Nirwan Dewanto pun, barangkali dapat dibaca dalam garis ketegangan yang serupa. Tubuh yang “kehilangan identitas”-nya—apa yang van Alphen sebut sebagai “loss of self” itu—dihadirkan di tengah citraan-citraan yang meningkahi representasi mimetik, tetapi serentak dengan itu, ia sekaligus menjadi indeks-indeks dari tubuh itu sendiri. Nirwan misalnya menuliskan tubuh bukan sebagai subjek yang utuh, melainkan sebagai potongan, santapan, dan daging yang diolah sebagai hidangan.
Sebagaimana tubuh George Dyer dalam kanvas Bacon yang melipat diri, terdistorsi, dan tak lagi menampilkan personalitas-nya, tubuh dalam puisi Nirwan pun impersonal. Ia tak hadir sebagai sosok yang stabil. Dengan begitu, “Sapi Lada Hitam” sekaligus memperlihatkan bagaimana bahasa puitisnya bekerja seperti kuas Bacon yang meremukkan subjek hingga tak lagi dapat dikenali. Daging yang dimasak dengan lada hitam agak berlimpah dalam puisi itu barangkali adalah metafora tentang tubuh yang ditanggalkan dari identitasnya—tubuh yang diperas hingga tinggal rasa getir dan jejak rempahnya belaka. Nirwan, dengan cara ini, mengulang strategi yang dibaca van Alphen pada Bacon, yaitu menghapus diri (loss of self) si subjek agar yang tampil justru materialitas tubuh itu sendiri. Pada puisi Nirwan, materialitas itu ialah materialitas bahasa.
Namun, jika Francis Bacon di bawah judul puisi itu kita geser untuk merujuk pada Bacon si filsuf empiris, “Sapi Lada Hitam” kemungkinan ditulis Nirwan dalam hubungannya dengan prinsip vexation of art,[13] tidak saja karena nama itu ditaruh di bawah judul, tetapi juga sebab kita memang menyaksikan relevansi antara konsep tersebut dengan bagaimana hal-ihwal di puisi ini bekerja. Bahwa puisi “Sapi Lada Hitam” mungkin ditulis Nirwan dengan visi untuk mengusik kemapanan cara seseorang—bahkan termasuk penyairnya sendiri—tidak hanya dalam menulis, tetapi juga membaca puisi—sebagaimana alam yang ditarik-paksa keluar dari ke-alami-annya dalam gagasan vexation of art. Visi ini, barangkali hanya akan mungkin jika variasi puisi diubah bentuknya secara radikal, yakni dengan jalan menyiksa bentuk, katakanlah dengan mendesak formal bahasa ke titik paling ekstrem sehingga ia menjelma bentuk baru yang selain-lainnya. Dengan cara ini jugalah puisi mungkin dimaksudkan sebagai “gangguan” terhadap tradisi penulisan sekaligus pembacaan puisi itu sendiri.
Meski barangkali kita menangkap adanya jarak yang cukup lebar di sini, konsep metode eksperimentasi Bacon itu pun masih memiliki irisan dengan wilayah seni. Svetlana Alpers misalnya, dengan terang menyebut bahwa judul buku The Vexations of Art: Velázquez and Others yang ia tulis, dipinjam dari istilah Bacon tersebut—yang kemudian, ia transposisikan ke wilayah seni rupa. Kendati yang dimaksud Bacon dalam gagasannya itu bukanlah seni lukis, tetapi di mata Alpers, istilah yang merujuk pada metode eksperimen ilmiah itu tetap relevan, karena praktik melukis itu sendiri sejatinya juga bersifat “mengganggu” atau “menggelisahkan.” Bahwa ada restlessness dalam relasi pelukis dengan dunianya, baik dalam proses penciptaan, maupun dalam pandangan seseorang terhadap hasil penciptaan itu sendiri.[14]
Sebagai contoh, dalam tafsirnya terhadap Las Hilanderas karya Diego Velázquez—dengan memakai gagasan tersebut—Alpers menjelaskan bahwa Las Hilanderas bukan sekadar kisah mitologi Minerva dan Arachne, melainkan juga sebuah salinan kompleks (salinan dari salinan) yang menganyam ulang karya Rubens dan Titian—dua nama pelukis generasi sebelum Velázquez. Las Hilanderas karya Velázquez memanglah simpul dari jaringan panjang penyalinan dan tafsir ulang. Lukisan ini berangkat dari kisah Ovid tentang persaingan Minerva dan Arachne, yang kemudian divisualkan oleh Titian dalam The Rape of Europa, lalu disalin dan diolah kembali oleh Rubens dalam Minerva and Arachne. Velázquez, dalam Las Hilanderas, menempatkan adegan mitologis Rubens-Titian tersebut sebagai semacam latar belakang lukisannya. Dalam lukisan karyanya, Velázquez mengacu karya Rubens secara implisit sebagai latar belakang ruangan, di mana tampak adegan Minerva dan Arachne sedang berhadap-hadapan, seolah di dalam lukisan Velázquez, terdapat lukisan yang lain. Sementara itu, versi The Rape of Europa karya Titian dimunculkan Velázquez sebagai tenunan atau permadani yang juga tampak di latar belakang lukisannya. Pada saat yang sama, di ruang depan, ditampilkanlah oleh Velázquez sekumpulan perempuan penenun.
Dengan strategi anyam-menganyam itulah, Velázquez bukan saja menyulam kembali karya terdahulu, melainkan juga membalik hierarki seni: yang agung dan mitologis ditarik ke belakang, sedangkan yang sehari-hari didorong ke depan. Jauh berbeda dengan dua pendahulunya (Rubens dan Titian), Velázquez tidak lagi menempatkan energi erotis dalam sebuah drama pertunjukan di sebentang kanvasnya. Sebaliknya, dia menempatkannya dalam tujuan tubuh wanita, yakni tubuh yang berpakaian (tidak seperti figur-figur mitologis yang kerap tampil bugil), juga tubuh yang sedang bekerja. Bagi Alpers, hal ini merupakan transformasi luar biasa; bagaimana seni yang dihasilkan dari salinan dan tafsir ulang terhadap seni tampak memberikan jalan bagi kehidupan yang umum, bahkan lumrah.[15] Velázquez, dalam tafsir ini, seperti sengaja “menyiksa” seni dengan jalan memaksa lukisan keluar dari alamnya yang agung, menuju dunia kerja yang profan. Vexation, dengan demikian, menjadi strategi estetik di mana seni ditarik ke luar dari kodratnya sendiri untuk memperlihatkan sesuatu yang ganjil, bahkan ambigu.
Sampai di sini, puisi “Sapi Lada Hitam” akhirnya malah mengandung resonansi dari dua Bacon sekaligus. Puisi ini, di satu layer, menjadi wujud dari seni yang “disiksa (vexed)” agar lepas dari kemapanan konvensinya sebagaimana kita baca pada tinjauan Alpers terhadap sapuan kuas Velázquez. Namun, di sisi yang lain, ia juga metafora dari tubuh yang “kehilangan diri” (loss of self) di tengah citraan-citraan yang silang-sengkarut, tumpang-tindih, seperti kita temui dalam amatan van Alphen terhadap Portrait of George Dyer Crouching karya Bacon. Di tangan Nirwan, daging, tubuh, dan kekerasan dimasukkan ke dalam cawan kata-kata—seperti Velázquez menenun ulang mitos, tetapi bedanya, Nirwan menenun ulang ikon dan metafora—sehingga menghasilkan puisi yang, alih-alih tinggal dalam “alam” puisi liris konvensional, justru mendesak puisi itu sendiri ke wilayah yang tak stabil, penuh eksperimen, membuat bahasa tersiksa agar menyingkap lapisan lain kemungkinan pemaknaan.
Namun demikian, persis saya katakan, sebuah metode pembacaan palimpsestuous tetaplah sebuah pembacaan yang akan selalu tentatif. Dan yang tentatif itu hanya akan terjadi apabila sebuah puisi tidak dibaca dengan terburu-buru menyimpul makna, melainkan dengan—meminjam ungkapan Nirwan—menyayat “…pelan-/ pelan, agak dalam di bawah kulit, agar arus darah tak meledak/ lepas ke udara”; sebuah ungkapan yang secara alegoris menjadi satire terhadap tradisi membaca puisi dengan menganggap teks sebagai dekode biografis sehingga kritik, yang berupaya mengemukakan apa yang tersembunyi di balik sandi-sandi atau unit-simbol itu, kerap terjerembab ke dalam interpretasi yang reduktif.
Pasalnya, upaya menyibak satu lapis “Sapi Lada Hitam” dengan menautkannya pada dua resonansi Baconian di atas pun tidak serta-merta presisi. Sebab, larik-larik “Sayat pelan-/ pelan, agak dalam di bawah kulit, agar arus darah tak meledak/ lepas ke udara” itu pun bahkan mengandung struktur relasi yang menyimpan dan menyembunyikan lapisan-lapisan teks secara involutif.” Watak inilah yang kemudian mengonsekuensikan situasi palimpsestuousness atau “atmosfer yang lahir dari teks yang memiliki watak palimpsestuous” di mana kita mesti menyadari bahwa terdapat lapisan-lapisan lain yang hidup di dalam teks yang sedang kita baca. Bahwa teks yang terlihat tunggal pun ternyata disusun dari banyak suara, banyak waktu, banyak memori, misalnya.
Atmosfer yang lahir dari tumpukan lapisan tersebut akan meniscayakan konsekuensi lain, yakni keterlibatan “simultaneity of intimacy and separation” atau “kehadiran bersama makna yang tumpang-tindih dan saling menembus, tetapi tidak sepenuhnya menyatu”.[16] Alhasil, larik-larik “Sayat pelan-/ pelan, agak dalam di bawah kulit, agar arus darah tak meledak/ lepas ke udara” sekaligus juga mengalusikan bagaimana Francis Bacon (filsuf empiris)—dengan “vexation of art”-nya—rupanya bernasib tak jauh berbeda dengan puisi atau seni itu sendiri. Bahwa keduanya acap dibaca dengan tergesa, dipotong bagian-bagiannya dengan perasaan gusar dan kasar. Singkatnya, keduanya kerap ditafsir sepihak seturut ideologi yang dianut baik oleh para pemuja maupun pencibirnya.
Sebagai permisalan, selama tak kurang dari empat abad metode eksperimental Bacon dengan konsep vexation of art-nya itu sempat mendulang pujian. Namun, begitu memasuki abad ke-20, pendekatan tersebut dikritik karena mengandaikan implikasi instrumental, ekologi, dan anti-feminisme. Dan bagaimanakah dengan puisi? Tidakkah keduanya kerap juga bernasib sama? Sementara itu, jika kita menarik tafsir kembali pada hubungannya dengan Francis Bacon si pelukis, tampaklah pada “Sapi Lada Hitam” bagaimana bahasa tidak hanya dipaksa Nirwan untuk keluar dari “alam” lirisnya yang lempang, tetapi juga bagaimana subjek puitisnya didistorsi, hingga yang tersisa adalah citra-citra yang disusun, justru untuk mencabik diri puisi itu sendiri. Jika demikian, dapatkah “Sapi Lada Hitam”, kita katakan sebagai puisi yang menanggung kehilangan “identitas-puitis”-nya, demi menemukan kemungkinan lain dari bahasa?
Kita sebetulnya tidak pernah betul-betul tahu, tetapi juga tidak pernah betul-betul tak tahu. Yang kita mungkin ketahui, puisi Nirwan sebagaimana “buli-buli”. Artinya, oleh karena dorongan ideologis seorang kritikus atau pembaca umumnya, ia sontak ditafsir dalam skema pembacaan garis lurus sebagai simbol yang merepresentasikan sebuah “penis”. Saya kira, “buli-buli” pada “Sapi Lada Hitam” adalah sebuah palimpsest, yang merupakan konsepsi metaforis dan sekaligus menjadi metafora itu sendiri. Sebagai sebuah palimpsest, “buli-buli” mengonotasikan ketidakmungkinan pembacaan dengan hanya menggosok halus permukaan literalnya belaka. Ketidakmungkinan menafsir makna linear (yang dimetaforkan sebagai menggosok halus permukaan palimpsest) dari “buli-buli” ini terjadi sebagai konsekuensi dari adanya queer frill, hiasan-hiasan ganjil yang diatributkan penyair sebagai citra-citra yang mendestabilisasi linearitas makna representatif dari “buli-buli”. Dengan ungkapan lain, queer frill tersebut adalah sebuah dissemblance (ketidakserupaan atau keterpisahan) yang merobohkan gerak lurus representasi, katakankanlah, yang dijembatani oleh hubungan penanda dan tinanda.
“Buli-buli” dalam citra-citra yang dibangun Nirwan memang mudah terbaca sebagai pusat simbolik dari tubuh jantan di dalam puisi. Maka, bukan sesuatu yang mencengangkan bila pembacaan ideologis terhasut menafsirkannya sebagai organ genital laki-laki, terutama karena larik seperti “Buli-buli yang menegang selalu di antara/ kedua pahanya akan kutanam untuk diriku sendiri, untuk terus mendatangkan serbuk jantan bagiku” secara tersirat menyugestikan sekaligus mendukung tafsir tersebut. Akan tetapi, “buli-buli” di sana pun tampil sebagai objek yang tidak hanya erotik, tetapi juga asing, ambigu, bahkan transformatif. Kata “buli-buli” sendiri bahkan terkesan seolah dicomot dari ruang imajinasi kuna sebuah museum artefak lampau.
Pemilihan diksi “buli-buli”—apalagi dengan atribut “lima kaki”—dalam hemat saya, sudah merupakan bentuk queer frill tersendiri. Ia memancarkan citra keganjilan. Ia menandai, memiuh, dan menumpuk ulang makna maskulinitas. Secara leksikal, misalnya, “buli-buli” adalah sejenis guci bundar tanpa leher dengan kaki rendah yang umum dipakai sebagai wadah air. Pada saat yang sama, “buli-buli” secara leksikal juga dapat merujuk pada “kandung kemih”: sebuah organ yang, sejatinya netral (tidak erotik), dan nyaris tak pernah muncul dalam perbincangan tubuh-seksual. Alih-alih menyebut secara langsung bagian tubuh laki-laki, Nirwan justru memilih diksi “buli-buli” yang tidak hanya terasa arkaik dan ambigu, tetapi juga mengandung resonansi figuratif. Alhasil, sejak pemilihannya, “buli-buli” telah menjadi diksi yang menciptakan “gangguan” terhadap skema representasi-mimetik.
Kita boleh menduga, pemilihan diksi tersebut mungkin memang bertujuan untuk menciptakan efek frilled, sebuah penyimpangan gaya yang justru membuka lapisan-lapisan makna potensialnya. Letaknya yang digambarkan “di antara kedua paha” membuat pembaca otomatis menautkannya dengan penis. Namun, serentak dengan itu, bentuk, fungsi, dan citra-citra yang diatributkan kepadanya justru men-dissemblance-kan makna “penis” itu sendiri (“….. Kini kau akan melihatnya/ seperti seonggok kain belaka. Tapi awaslah, kalau kautiup ia,/ akan mekar luas ia seperti angkasa raya, sehingga ruangmu/ akan termakan olehnya). Efek frilled yang dihasilkan dari operasi palimpsestuous pada teks Nirwan tersebut membuat sesuatu yang seharusnya tampak jelas jadi meleset dari identitas tunggalnya. Maka, “buli-buli” di sana, mungkin bukan hanya simbol dari phallus, melainkan juga sebuah organ yang sudah diseret jauh keluar dari tubuh mimetiknya. Ia tidak hanya dipindahkan, bahkan ditanam oleh si “aku” yang adalah “laki-laki” (subjek maskulin)—ini jika memang masih ingin memaksakan “aku” sebagai tinanda dari Theseus dan personalitas dari penyair—untuk “mendatangkan serbuk jantan.”
Di sini kita akhirnya menyaksikan bahwa pemindahan tersebut bukan sekadar reposisi kuasa, melainkan juga reposisi fungsi, katakanlah dari reposisi fungsi penetratif menjadi produktif, kuasa maskulin menjadi inkubatif, tubuh menuju liyan. Maka “buli-buli” itu bukan sekadar diobjektifikasi, melainkan juga disubjektifikasi ulang oleh penyair. Kekuasaan maskulin seakan juga dipiuh ke dalam sistem yang feminin bahkan maternal, di mana “buli-buli” akhirnya menjadi semacam “rahim laki-laki”, bukan dalam arti biologis-nya, melainkan ruang tubuh yang tidak hanya menerima, melainkan juga menumbuhkan dan menggandakan jantanitas milik tubuh lain.
Di atas, saya menyebut queer frill sebagai “gangguan” karena apa yang ditampilkan Nirwan melalui “buli-buli” beserta segenap citra-citra ganjil yang diatributkan padanya persis telah disinggung, mengingatkan saya pada konsep “Montase” yang disebut oleh Didi-Huberman sebagai “gambar yang berpikir”. Montase, bagi Didi-Huberman, adalah bentuk teladan dari sebuah intervensi. Sebab, montase berwatak anti-mimetik sehingga itu berarti ia menolak formulasi idealistis tentang representasi. Lebih dari itu, montase juga bersifat diskontinu, dan diskontinuitas ini akhirnya memungkinkan montase dapat mengguncang, merestrukturisasi, merangkai ulang, bahkan menembus struktur pengetahuan yang ada, menolak untuk membiarkan apa pun duduk nyaman di atas kursi kestabilan.[17]
Segala macam intervensi atau gangguan itu merupakan efek epistemologis dari “montase”. Darinyalah seseorang bertanya-tanya bukan tentang apa yang ia pandang dari sebuah puisi, melainkan tentang bagaimana, katakanlah, citra puitik itu melihat dirinya, dan sebaliknya, dirinya melihat citraan dalam puisi yang ia baca. Dus, montase tak lain merupakan perangkat epistemologis di mana imajinasi adalah motor penggeraknya, dan sebaliknya, montase sekaligus menjadi motor penggerak yang membangkitkan imajinasi itu sendiri. Pasalnya, berbeda dengan pengetahuan yang sudah ditentukan sebelumnya, imajinasi lebih bersifat aktif. Ia melintasi, dan anti-representasional. Itulah mengapa Didi-Huberman menyebut bahwa imajinasi bukanlah refleksi pasif yang terikat pada peniruan dan kenangan. Justru sebaliknya, imajinasi terkait dengan produksi dan pembentukan pengetahuan. Imajinasi juga bukan penarikan diri ke ilusi refleksi tunggal, melainkan konstruksi dan montase berbagai bentuk yang ditempatkan dalam kesesuaian satu sama lain.[18]
Sebagai permisalan, barangkali penting juga kita sorot frasa “serbuk jantan” dan bagaimana ia tidak saja mempertebal ironi tetapi juga menghasilkan semacam retakan semantis. Dalam nomenklatur botani, kita tahu, “serbuk jantan” mengacu pada polen, material reproduksi tumbuhan. Dari acuan literal ini, segaris pertanyaan (harusnya) segera muncul di pikiran kita: Mengapa tubuh laki-laki jantan dibahasakan penyair justru dengan diksi vegetal alih-alih zoologis? Bukankah yang vegetal lebih identik dengan yang feminin?
Pembacaan palimpsestuous yang selalu mengandaikan tafsir tentatif barangkali hanya dapat berasumsi bahwa penyair mungkin bermaksud menyilangkan medan semantik kata, yakni antara yang zoologis dan yang vegetal—dan lebih jauh lagi, mengintervensi struktur biner maskulin-feminin. “Buli-buli”, jika kata ini memang hendak kita baca sebagai simbolisasi “penis” yang identik dengan aktivitas penetrasi sehingga acap ditautkan sebagai simbol dominasi maskulin, kini justru dicitrakan sebagai penghasil “serbuk jantan” yang akan “ditanam” di tubuh si “aku”—yang juga subjek “laki-laki”. Konsekuensi makna yang dihasilkan dari pola yang melenceng ini adalah “buli-buli” menjelma situs yang tak stabil, yang penuh retakan sekaligus kemungkinan. Maka, “buli-buli” bisa tetap menyimbolkan maskulinitas di satu pihak, tetapi juga femininitas di pihak yang lain.
Serentak dengan itu, jika mencermati bagaimana “buli-buli” dicitrakan, kita tahu bahwa ia telah dibongkar dari sistem heteronormatif-nya, dan dioperasikan dalam logika hasrat yang cenderung menyimpang sehingga ia malah bisa bukan maskulin sekaligus feminin. Oleh karena itu, ia tidak hanya menjadi derau yang mengintervensi formulasi idealistis tentang representasi, tetapi bahkan hendak meruntuhkan formulasi idealistis representasi mimetik itu sendiri. Posisi kuasa dan identitas memang tidak berarti hilang, tetapi ia justru menjadi tumpah-tindih, saling menggandakan, bahkan saling menghapus sebagiannya. Alhasil, “buli-buli” pun menjadi metafora yang malah membelah dikotomi antara maskulin dan feminin, dominasi dan pengorbanan, phallus dan juga uterus, akibat digabung-kacaukannya struktur biner ke dalam citra-citra yang ganjil, yang ambigu, dan karena itu, mengganggu.
Gangguan-gangguan yang lahir dari efek frilled itu akan terus berulang hadir tiap kali kita menjumpai citra-citra ganjil Nirwan yang ditimpakan pada “buli-buli”, atau pada objek apa pun di puisi-puisinya, sebagai lapisan-lapisan yang terus timpa-menimpa. Sampai di titik ini, kita mestinya mulai curiga bahwa “buli-buli” sama sekali bukan simbol organ genital “penis”, bukan pula penanda yang merepresentasikan aktivitas penetrasi dan mewacanakan dominasi patriarki, tetapi barangkali sebuah palimpsest, metafora yang memetaforkan prinsip epistemologis (epistemological principle) Nirwan Dewanto dalam kerja kepenyairannya itu sendiri.
Masih pada larik yang lain “Sapi Lada Hitam” misalnya, Nirwan membangun citra “buli-buli” yang baru, tercerai dari citraan yang telah ia bangun sebelumnya. Nirwan menulis: “Pastilah kau/ akan mencari-cari buli-buli yang termasyhur itu di antara/ kedua pahanya! Buli-buli yang selalu kaulukis dengan warna/ emas dalam mimpimu, agar ia lekas memasukimu dari celahmu/ yang mana saja, agar kau tak lagi merasa terancam olehnya.” Yang saya lucuti di sini, barulah beberapa lapis-detail dari buli-buli di Buli-Buli Lima Kaki, belum mencakup keseluruhannya. Apapun itu, yang saya ingin tegaskan adalah: bentuk teks seperti puisi Nirwan, pada akhirnya mengandaikan bahwa upaya kategorisasi terbatas selalu sudah tidak mungkin diterapkan terhadapnya. Sebab, ia selalu menawarkan lebih banyak infinitas dari yang mungkin bisa kita tangani. Kecuali, jika kita menempuh jalan paling pintasnya, yakni tafsir ideologi [ ]
[1] Istilah “logika pelapisan represi” tersebut, saya rumuskan dari kritik Sarah Dillon terhadap “metafora palimpsest” yang dipopulerkan oleh Sandra M. Gilbert dan Susan Gubar (dalam The Madwoman in the Attic, 1979) sebagai gambaran bagi strategi para penulis perempuan abad ke-19. Seperti dikemukakan Sarah Dillon, metafora itu justru terbantahkan oleh sumber metafora palimpsest yang mereka acu, yakni prosa karya H. D. Dillon memandang, pada prosa tersebut, lapisan-lapisan teks hadir dan saling bertumpang-tindih secara kompleks, sehingga malah mengandaikan ketidakmemadaian kritik feminis tradisional dalam menyingkap kebenaran tunggal/sejati, yang mereka yakini ada di balik lapisan-lapisan tersebut. Selengkapnya baca dalam Sarah Dillon, “Chapter 7: Queering the Palimpsest: H. D.”, dalam The Palimpsest: Literature, Criticism, Theory (Bloomsburry Publishing, 2014), hlm. 102-103.
[2] Endiq Anang P., “Membedah Kaki Kelima Nirwan (Membongkar Ideologi Nirwan Dewanto dalam Buli-Buli Lima Kaki)”, dalam Memasak Nasi Goreng Tanpa Nasi: Antologi Esai Pemenang Sayembara Kritik Sastra DKJ 2013 (Dewan Kesenian Jakarta, 2024).
[3] Sarah Dillon, “Introduction”, dalam The Palimpsest: Literature, Criticism, Theory (Bloomsburry Publishing, 2014), hlm. 4.
[4] Georges Didi-Huberman, Fra Angelico: Dissemblance & Figuration, translated by Jane Marie Todd (University Of Chicago Press, 1995).
[5] Cep Subhan KM. 2022. “Citra Subjek Feminin dalam Puisi Chairil Anwar: Sebuah Konsekuensi Lain Pembacaan Biografis”. https://tengara.id/esai/citra-subjek-feminin-dalam-puisi-chairil-anwar/. Diakses 11 Juli 2025. 14.19 WIB.
[6] Selengkapnya baca Toril Moi, “Introduction: Who’s Afraid Virginia Woolf? Feminis Reading of Woolf” dalam Sexual/ Textual Politics (Routledge, 1995), hlm. 1-5.
[7] Dalam konteks naskah, palimpsest adalah perkamen (atau bahan tulis lain) yang tulisannya telah dihapus atau dikikis untuk digunakan kembali, tetapi jejak tulisan aslinya masih dapat terlihat.
[8] Sarah Dillon, The Palimpsest: Literature, Criticism, Theory (Bloomsburry Publishing, 2014), hlm. 107.
[9] Mengenai “pembaca yang terinformasi” ini, dapat dibaca dalam Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry (Indiana University Press, 1978), hlm. 164.
[10] Diana Collecott, H. D. and Sapphic Modernism, 1910–1950 (Cambridge University Press, 1999), hlm. 2.
[11] Ernst van Alphen, Francis Bacon and the Loss of Self (Reaktion Books, 1998), hlm. 148.
[12] Ibid, hlm. 88-89.
[13] Bahwa “alam dalam keadaan bebas”—dalam gagasan ini—berbeda dengan “alam yang berada di bawah tekanan (vexed), yakni ketika dipaksa keluar dari keadaan alaminya, diperas, dan dibentuk oleh campur tangan manusia. Hakikat sesuatu, bagi Bacon, justru lebih mudah terungkap ketika alam “disiksa” atau “dipaksa” oleh eksperimentasi, dibandingkan ketika ia dibiarkan bebas belaka (Carolyn Merchant. 2013. Francis Bacon And The ‘Vexations Of Art’: Experimentation As Intervention. The British Journal For The History Of Science, 46(4), 551-599).
[14] Svetlana Alpers, The Vexations of Art: Velázquez and Others (Yale University Press, 2007), hlm. 5.
[15] Ibid, hlm. 210.
[16] Sarah Dillon, The Palimpsest: Literature, Criticism, Theory (Bloomsburry Publishing, 2014), hlm. 3.
[17] Chari Larsson, Didi-Huberman and the Image (Manchester University Press, 2020), hlm. 149.
[18] Georges Didi-Huberman, Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz, diterjemahkan oleh Shane B. Lillis (University of Chicago Press, 2008), hlm. 120.

Yohan Fikri
Yohan Fikri dilahirkan di Ponorogo pada 1 November 1998. Belajar di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang. Menulis puisi, prosa (esai), dan kritik sastra. Tulisan-tulisannya tersebar di sejumlah media, seperti Kalam, Kompas, Tempo, Jawa Pos, Bacapetra, Basabasi, dll. Pernah juga ia memenangi sejumlah kompetisi penulisan sastra, di antaranya adalah Sayembara Puisi Festival Sastra Yogyakarta (FSY) 2024 dan Lomba Cipta Puisi Tingkat Asia Tenggara, Pekan Bahasa dan Sastra, Universitas Sebelas Maret (2021). Telah menerbitkan dua buku puisi, yakni Tanbihat Sebuah Perjalanan (2022) dan Anjing-Anjing Lepas Amarah (2025). Saat ini, ia menjadi tenaga pengajar di SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) dan kolumnis tetap di sivitaskotheka.org. Dapat disapa melalui instagramnya: @yohan_fvckry.