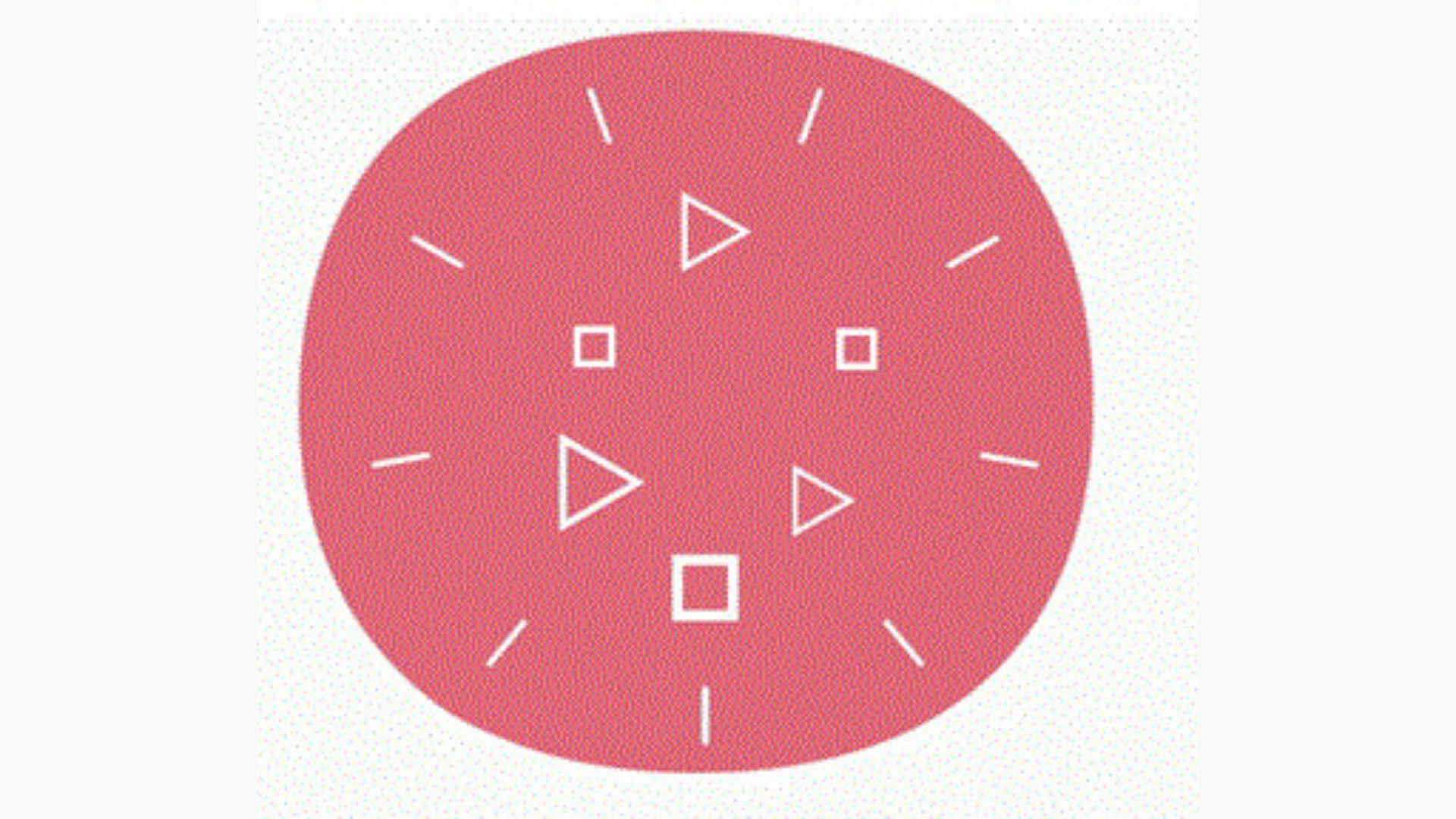Sebuah bom baru saja dijatuhkan sebelum matahari berkilau di Kabaundungo. Membinasakan setengah penduduk sekaligus membiarkan hidup sisanya dalam teror, ketakutan, dan kungkungan hidup. Asap hitam membumbung tinggi ke langit fajar yang masih mengandung bintang. Tidak hanya sekali Kabaundungo meledak. Dari arah sawah, kaki bukit, ladang-ladang, perkebunan teh, bahkan di antara rumah-rumah warga ledakan itu saling sahut-menyahut. Rumah-rumah itu goncang, terbakar, kemudian runtuh dan sebagian menimbun penghuninya. Ledakan itu menyisakan kepulan asap hitam berbau mesiu, debu, dan pengap yang melesat ke seluruh Kabaundungo. Saat ini hanya satu hal yang bisa dipikirkan oleh mereka yang tersisa; cara untuk bertahan hidup.
Ketika ledakan itu terjadi, aku telah tertangkap. Seseorang sedang menindih tubuhku di tempat aku bersembunyi di dalam semak belukar yang gelap. Aku merasa orang itu tidak sendirian. Berdua, bertiga, berlima, atau lebih, aku tidak tahu. Sepertinya aku telah diawasi oleh orang-orang asing itu jauh sebelum berada di dalam semak belukar ini. Apakah mereka perampok, pembunuh bayaran, atau jangan-jangan orang-orang jahat yang diisukan sudah menjarah Pasar Raya tempo hari?
Aku mencoba mengangkat tubuhku, tetapi sekuat apa pun aku mencoba orang yang menindihku semakin membenamkanku ke dalam tanah yang basah. Kupikir dengan berusaha membalikkan badan, aku bisa menyingkirkan orang yang ada di atas punggungku sambil mengetahui siapa orang-orang itu. Ketika rencana itu kulakukan dan terasa hampir berhasil, kepalaku dihantam benda tumpul yang sangat keras dan dengan cepat mereka mengikat kedua kaki serta tanganku seperti seekor kambing yang hendak dikurbankan.
“Bawa dia ke tempat pengamanan, setelah itu kita akan bergabung dengan yang lain untuk mengamankan Kabaundungo,” ucap salah seorang dari mereka.
Saat itulah aku tahu pasti siapa orang-orang itu. Mereka bukan perampok, pembunuh, atau para penjarah. Mereka pasti sekelompok tentara kiriman pemerintah pusat yang mendarat di Pantai Padang beberapa hari yang lalu. Desas-desus tentang kedatangan mereka rupanya benar. Tapi, apa maksud mereka dengan mencoba mengamankan Kabaundungo? Setahuku tidak ada seorang pun di Kabaundungo yang terlibat PRRI. Itu hanya kampung petani, peternak, dan pedagang pasar.
Sebelum aku mencoba mengatakan hal itu pada mereka, rambutku dijambak sekuat tenaga, membuat wajahku terangkat dari tanah. Ketika itulah aku menatap wajah seseorang yang tersembunyi dibalik balutan kain menyerupai topeng wajah. Kemudian tentara pusat berwajah kain itu munyumpal mulut dan mataku, menghantamkan kembali tubuhku ke dasar tanah dan seketika itu juga aku diseret ke luar dari semak-semak.
Aku hanya bisa menduga kalau rencana kami untuk berpatroli mengamankan kampung telah gagal. Apalagi setelah serangkaian kejadian berbahaya di luar kampung yang membuat teror dan kabar buruk semakin kuat berhembus ke Kabaundungo. Desas-desus yang paling membuat heboh adalah tentang penangkapan seluruh anggota Masyumi di setiap kota dan kabupaten. Bahkan orang-orang yang berhubungan dengan partai itu walau hanya sekali saja juga ikut ditangkap. Karena itu, penduduk kampung yang pernah dibantu oleh Masyumi memilih untuk mengasingkan diri di dalam rumah atau menyingkir ke luar daerah. Dan bisa saja karena perubahan sikap penduduk kampung yang berubah tiba-tiba, ada pihak yang memanfaatkannya secara sengaja lalu menjatuhkan kabar kalau Kabaundungo telah ikut membela PRRI.
Sepanjang perjalanan aku diseret dengan tubuhku yang terlentang menghadap langit. Punggungku sangat pedih, panas, dan tercabik-cabik. Sepanjang perjalanan itu, aku tidak bisa melihat apa pun selain temaram langit malam yang samar-samar menembusi kain yang menutup mataku. Aku tidak tahu hendak dibawa ke mana. Dari kejauhan, aku mendengar ledakan-ledakan silih berganti menggetarkan bumi. Seperti letupan-letupan balon yang tertusuk peniti, bunyi yang memecahkan udara itu pasti mengagetkan siapa pun yang mendengarnya. Tapi mungkin saja ada sebagian orang yang tidak terkagetkan dengan ledakan sekeras itu. Seolah-olah tahu bahwa semua itu akan terjadi, atau sudah terbiasa dengannya. Mungkin saja, tidak ada yang tahu.
Beberapa minggu yang lalu sebuah desas-desus telah berkembang di Kabaundungo. Ada seorang mata-mata di kampung dan kemungkinan besar dialah dalang dari penjarahan yang terjadi di Pasar Raya. Tapi selama desas-desus itu berkembang, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan ada mata-mata di Kabaundungo. Sebelum kejadian itu, semua orang yang tinggal di Kabaundungo masih tetap sama, ada yang pergi tetapi tidak ada yang datang. Satu-satunya kedatangan di Kabaundungo hanyalah kelahiran empat bayi dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Dan bagi orang waras, tidak mungkin bayi itu seorang mata-mata.
Aku mendengar suara mesin mendekat. Dari kebisingan itu, sayup-sayup aku menangkap suara sekelompok orang yang tampaknya sedang berkerumun membicarakan sesuatu. Mungkin karena kedatanganku yang sangat mencolok, mereka seketika berhenti bersuara. Salah seorang dari tentara pusat yang menculikku memulai percakapan dengan mereka, orang-orang asing yang pastinya juga sekelompok tentara dari pusat. Hanya sedikit yang bisa kutangkap dari percakapan itu.
“Dinaikkan saja ke atas truk … sebentar lagi kita akan berangkat.”
Hanya satu ucapan singkat itu yang dapat kudengar jelas. Selebihnya hanya seperti gumaman yang aku tidak tahu apa maksudnya. Setelah mereka berhenti bicara, aku dipaksa berdiri, lalu diperintah mendekati sumber suara yang sedari tadi menderum. Dari bunyinya aku tahu kalau itu semacam truk atau bus. Dan dari asap terhempas ke arahku, tercium bau solar yang terbakar dan menyesakkan dada.
Ketika sampai di tempat yang mereka inginkan, aku dipapah menaiki sebuah kotak semacam tangga bantuan. Kemudian dalam satu kali dorongan kuat, aku sudah menapaki lantai truk yang jauh lebih tinggi dari tanah. Setelah keheningan datang menyelimuti lantai truk yang dingin itu, aku merasakan kehadiran orang lain. Bukan hanya diriku dan tentara pusat yang ada di dalam sana. Samar-samar aku mendengar suara yang mendengus, napas yang tertahan, dan gesekan kaki yang berusaha menjauh dari tempatku terduduk. Dari celah kain yang menutup mataku, tidak ada sedikitpun cahaya yang bisa membantuku melihat keadaan sekitar. Aku mencoba menenangkan diri, menyimak kembali segala sesuatu yang bisa aku dengar. Suara orang tertawa, gemerisik dedaunan yang tersapu angin malam, deruman mesin truk yang sedari tadi sibuk menyala, lalu suara erangan yang terbekap menyeru lembut di hampir semua sudut lantai truk. Memang benar, bukan hanya aku dan tentara-tentara pusat yang ada di dalam truk itu. Tetapi, ada sekelompok orang yang juga bernasib sama sepertiku di dalamnya.
Dan tidak lama setelah kedatanganku, truk itu mulai berjalan perlahan, membawaku bersama orang-orang yang ada di dalamnya ke suatu tempat yang mereka inginkan. Tempat yang sebelumnya mereka sebut sebagai tempat pengamanan sementara.
Aku masih belum diperbolehkan melihat apa pun. Dan tiba-tiba terlintas dibenakku di mana tepatnya tempat pengamanan sementara itu. Truk yang membawaku masih terus berjalan menjauhi jembatan gantung. Kalau aku membayangkan arah laju truk ini, tergambar di pikiranku jalan luas yang membentang dari jembatan gantung menuju pertigaan di depan Pasar Raya dan Terminal Bayuang Bukik. Aku menduga kalau tempat pengamanan itu pasti berada jauh dari Kabaundungo. Mungkin tempat itu ada di Padang atau Bukittinggi dan bisa saja lebih jauh dari kedua tempat itu.
Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatiranku saat ini adalah Amak. Apakah Amak baik-baik saja? Mungkin Amak sedang mengkhawatirkanku saat ini. Walau Amak jarang menampakkan wajah penuh kecemasan, aku selalu tahu bahwa Amak banyak mengandung cemas dan harap pada diriku. Bisa saja setelah ledakan itu, Amak mencariku di setiap sudut kampung. Menanyai siapa saja yang mungkin melihatku tertangkap atau diseret di sepanjang jalan. Sungguh aku tidak menduga kalau hal semacam ini akan terjadi padaku. Dan juga aku tidak menyangka kalau tentara pusat akan menyerang Kabaundungo saat itu juga.
Kemarin sore setelah selesai rapat pemuda, aku melihat Amak sedang duduk mencabuti rumput liar di halaman rumah. Ketika aku hampir mendekati tempat Amak terduduk, aku sengaja terbatuk dari kejauhan agar Amak tahu kepulanganku. Amak mengarahkan wajahnya padaku. Dari sana tampak sosoknya yang begitu akrab. Dengan raut wajah tenang dan bersahaja, sepasang mata dan segaris senyum yang lembut menyambut kedatanganku. Tidak pernah sekali pun Amak mengubah sikapnya itu padaku. Dirinya selalu berwajah tenang, lembut, dan penuh senyum saat mengetahui diriku ada di dekatnya. Walau pernah suatu kali aku tidak sengaja menemukan Amak sedang mengantungkan ekspresinya dalam kemurungan yang dalam. Kala itu hujan sore mulai berganti dengan gerimis, menyisakan dingin dan kelembapan yang mengapung di sepenjuru Kabaundungo. Dari bibir jendela, aku melihat Amak sedang duduk termenung memperhatikan sesuatu di kejauhan. Saat itu aku baru saja selesai mengurus pekerjaan di ladang. Aku tidak tahu apa yang sedang diperhatikan Amak waktu itu. Dari arah tatapannya, Amak memandang jauh ke arah bukit Kabaurabah. Apakah ada sesuatu yang menarik kesadarannya ke sana?
Itulah untuk pertama kalinya aku melihat Amak memasang wajah yang begitu sendu dan penuh keinginan akan sesuatu. Dari tempatku berdiri, aku seolah bisa merasakan apa yang sedang dipikirkan oleh Amak. Namun, di satu sisi aku juga tidak bisa begitu yakin dengan hal yang aku duga sebagai hal benar-benar dirasakannya. Aku hanya bisa menduga dan tidak pernah berani menanyakannya. Bagiku Amak adalah wanita penuh kedalaman emosi. Sulit untuk mengetahui relung hati seorang ibu bagiku. Dan aku juga tahu kalau Amak telah banyak menyimpan rasa seorang diri. Seolah-olah dia berkata kalau dirinya sudah cukup merasakan semua itu. Dan mungkin karena hujan begitu melenakan hari itu, ketersembunyian yang selama ini Amak jaga terbuka dengan sendirinya.
Aku terduduk di sebelahnya, mencabuti rumbut liat satu-persatu dengan kedua tangan. Memilintir rumput liar yang mekar sebesar sekepalan tangan, kemudian memutarnya berlawanan arah terbit matahari sambil menariknya pelan menjauh dari permukaan tanah. Mengingat kejadian Amak yang melamun waktu itu membuatku sulit untuk memulai pembicaraan. Ada rasa penasaran yang mengganjal dalam hatiku. Ingin sekali aku menanyakan kenapa Amak bersikap seperti itu. Tetapi aku juga kesulitan menanyakan hal itu pada Amak. Aku khawatir rasa penasaranku akan membuat kebahagiaan Amak menghilang. Lalu dalam satu kali hentakan seolah mengingat sesuatu, aku mulai membuka pembicaraan. Seperti kebiasaan anak laki-laki pada umumnya, dan aku juga sering melihat Lisman melakukannya, aku terlebih dahulu membuka percakapan dengan sebuah basa-basi.
“Mak, mungkin panen singkong kita tahun ini akan lebih banyak dari yang sebelumnya.”
Aku lihat Amak mengangguk lalu berkata,“Amak pikir juga begitu.”
“Mak, menurut Anjako, apa sebaiknya sebagian singkong kita olah lalu kita jual? Lumayan kan Mak kita bisa dapat uang.” usulku. Aku sengaja mengungkit hal ini kepada Amak. Selama ini hasil panen singkong selalu dijual Amak dalam bentuk mentah. Amak tidak pernah menjual olahan singkong di Pasar Raya. Seingatku Amak berasalan kalau orang lebih banyak mencari singkong mentah karena bisa dibuat sesuai kesenangan hati mereka. Tapi bagiku, orang-orang juga pasti menginginkan jajanan pasar yang sulit mereka buat pada waktu sibuk mereka. Karena itu sebagian dari pembeli yang pernah kutemui di Pasar Raya pasti menyempatkan diri memakan jajanan kecil selain menyarap sarapan pagi dan makan siang di kedai-kedai makan.
Dalam keadaan yang menebak-nebak, aku mendengar Amak menyetujui usulanku itu. Aku sedikit kaget dengan kesetujuan Amak yang begitu cepat. Kukira saat itu Amak akan menolak saranku dengan alasan yang penuh pertimbangan seperti sebelumnya. Setelahnya Amak bertanya tentang jajanan apa yang sebaiknya kami jual di Pasar Raya.
“Di pasar sudah banyak keripik Sanjai. Bagaimana kalau kita buat Kacimuih saja, Mak?”
Mendengar usulku Amak terdiam seperti menimbang berat baik dan buruknya sampai akhirnya berkata, “boleh.”
Ketika itu aku sadar bahwa Amak sedang memperhatikanku. Mungkin Amak sedang menduga-duga waktu yang telah kami lalui bersama. Begitu cepatnya diriku tumbuh bersama Amak. Dan begitu larutnya masa yang telah menambah sedikit demi sedikit usia Amak. Waktu itu Amak menghadapkan arah duduknya kepadaku. Memandang wajahku lekat-lekat dalam pandangan yang begitu panjang. Dari kandungan tatapannya masih terpancar ketenangan yang tidak menampakkan kepecahan riak seperti getar kekhawatiran. Ketika itu aku merasakan bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengatakan niatku yang sebenarnya pada Amak.
“Mak, Anjako izin meminta diri untuk menjaga kampung,” kata Anjako tenang. “Kabaundungo sudah tidak terlalu aman seperti sebelumnya, dan belakangan ini banyak sekali kejadian aneh yang muncul di sekeliling kampung. Para pemuda khawatir kalau hal-hal berbahaya akan segera mendatangi Kabaundungo setelahnya.”
Pada akhirnya aku membiarkan Amak mendengar kabar itu. Kabar yang seharusnya tidak baik diiringkan dengan keinginanku membujuk Amak membuat makanan kesukaan almarhum Abak. Tapi apa boleh buat, aku memang harus mengatakan hal itu pada Amak. Cepat atau lambat Amak pasti akan mengetahuinya juga.
Setelah mendengarkan permintaanku Amak terdiam. Tatapannya padaku masih tetap sama, tenang tanpa riak kekhawatiran. Amak mengulurkan tangannya ke kepalan tanganku yang terpangku di hadapannya, kemudian menyapukan tangannya itu ke kepalaku, dan membelai lembut permukaan rambut hitamku yang berposisi lebih tinggi dari batas ketinggian duduknya. Waktu itu aku melihat Amak menganggukkan kepala. Lalu Amak berkata pendek seperti berpesan.
“Pergilah. Tapi jangan kembali kalau kau hendak jadi mayat!”
Pada akhinya aku akan menjadi anak yang tidak akan berbakti pada Amak. Aku tidak segera pulang seperti apa yang telah kujanjikan padanya. Aku dibawa menjauh dari Kabaundungo entah ke tempat apa. Mungkin saat ini Amak sedang mengkhawatirkanku. Dan kalau aku tidak kunjung kembali mungkin Amak akan menduga kalau aku telah bernasih sama seperti Abak. Ingin sekali aku mengabarkan keadaanku pada Amak melalui langit fajar yang ada di atasku. Mungkin dari sana langit akan memberitahu Amak kalau aku baik-baik saja. Melalui ambang jendela yang selalu dijadikannya sebagai tempat melabuhkan nasib, Amak akan menerima kabarku itu melalui hujan pagi, siang, sore, atau malam.
Ketika aku hampir larut dalam pikiranku, truk yang membawaku berhenti. Terdengar suara berat merayap ke dalam telingaku ketika pintu kursi penumpang dibuka. Dari luar sana seseorang melantangkan suaranya ke arahku dan yang lainnya. Layaknya seorang pengembala domba, tentara itu menyeru kepadaku dan sekelompok orang yang bersamaku, berkata kalau kami akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Namun, tentara pusat itu tidak menjelaskan apa yang dia maksud dari ‘tempat ini’. Kalau aku mencoba membayangkan kembali arah jalan truk yang membawaku pergi, sepertinya aku masih berada di Nagari Bayuang Bukik. Truk itu belum melewati pertigaan yang ada di depan Pasar Raya dan Terminal Bayuang Bukik. Jika kami berada di luar Nagari Bayuang Bukik, seharusnya kami berbelok ke arah timur. Hanya itu satu-satunya jalan keluar dari kanagarian. Namun, alih-alih berbelok truk itu berhenti. Mereka menuruniku, membawaku masuk ke dalam suatu tempat, lalu membuka ikatan mataku setelah kegelapan semakin pekat. Di situ aku melihat tiga orang tentara sedang berdiri tegap membelakangi cahaya di ambang pintu. Wajah mereka masih bertopengkan kain hitam sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Setelah melihat keadaan sekeliling seolah memeriksa detak kehidupan yang ada dalam diriku dan orang-orang yang ada di sekitarku, mereka akhirnya pergi. Menutup pintu dari luar dan menguncinya dalam tiga kali putaran. Saat itu aku yakin bahwa diriku akan menghabiskan waktu yang sangat lama di sana agar bisa kembali pulang.
Saat tertidur aku kembali melihat diriku yang masih berumur sepuluh tahun. Ketika itu aku, Lisman dan Riaman sedang mengistirahatkan lelah di atas saung di tengah sawah. Di tengah lamunannya, Lisman berkata kalau dia ingin menjadi seorang guru. Aku mendengarkan semua alasannya saat itu. Kekaguman, panutan, tampak bersinar, cerdas, dan ramah. Itulah alasan yang menjadikan Lisman ingin menjadi seorang guru. Walaupun hari ini kami telah berpeluh keringat karena membantu orangtuanya menanam bibit padi, di hadapanku Lisman serasa masih memancarkan semangat bergelora seolah sedang menyantap sekumpulan nasi kapau bermenu lengkap yang mengeyangkan badan. Wajahnya begitu semringah, dia memejamkan kedua mata seraya membayangkan dirinya di masa depan sedang mengajar di depan kelas. Mungkin karena gambaran dirinya yang tampak begitu mengagumkan, tangan kanannya menunjuk-nunjuk ke udara seolah tertunjuk ke papan tulis dengan mulut tersenyum penuh kegembiraan.
Mendengar cita-cita Lisman, aku ikut membayangkan diriku menjadi seorang guru. Berdiri di depan kelas, meminta anak-anak seusiaku ikut mengeja huruf, angka, dan kata yang tertulis di papan tulis. Bayang-bayang itu begitu indah di mataku. Seandainya aku menjadi guru, pastilah aku akan menjadi seperti Buya Aswan. Orang terpandai di Kabaundungo. Tidak ada satu pun pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Buya Aswan. Walau aku tidak tahu apa yang dipertanyakan orang-orang pada Buya Aswan, di mataku yang masih berusia sepuluh tahun Buya Aswan tampak bersinar dengan wajah yang berseri-seri dan indah dipandang mata. Terkadang saat kelas kosong, tanpa sadar aku seringkali membayangkan diriku sebagai Buya Aswan dan bahkan bermain peran seperti dirinya saat menjawab pertanyaan orang-orang.
Ketika aku sedang asik membayangkan diri sebagai Buya Aswan, tiba-tiba aku merasakan kegelian di ujung kakiku yang kujulurkan ke kolong saung. Saat itu aku menegur Lisman agar berhenti mengangguku. Aku tidak ingin dia membuyarkan gambaran masa depanku yang sekarang terlihat jelas di dalam mataku. Tapi Lisman masih saja mengganggu. Dia terus saja mengusik dan tidak mengindahkan perkataanku. Karenanya aku menjadi kesal. Tapi saat aku hendak melihat dirinya yang ada di bawah kolong saung, aku terlebih dahulu menatap Lisman yang sedang tertidur pulas di samping Riaman. Ketika aku melihat Lisman yang sedang tertidur di sana, tubuhku menjadi kaku. Siapa yang sedang membelai ujung jemari kakiku saat itu? pikirku. Saat itu hilang sudah semua bayangan indah tentang diriku yang sedang menjadi Buya Aswan. Kala itu yang tertinggal hanyalah perasaan takut. Dengan memaksakan diri, aku mengangkat kakiku yang ke atas lalu dalam tubuh yang terduduk lemas di pinggiran saung, aku menatap ujung jemari kaki yang terangkat. Di sana aku melihat seekor ular sawah berwarna cokelat sedang melilit telapak kaki kiriku.
Sontak saja aku berteriak. Mengagetkan Lisman dan Riaman dari tidurnya. Ketika mereka melihat ular yang ada di telapak kakiku, Lisman ikut berteriak. Tanpa tahu apa yang harus aku lakukan, akhirnya aku menangis. Riaman yang saat itu masih setengah sadar keluar turun dari saung. Dia mencari sesuatu di sekeliling saung dan setelah lama mencari hal yang dia inginkan di bawah sana, Riaman kembali ke menaiki saung perlahan-lahan.
“Tenang. Jangan bergerak. Ular sawah tidak bahaya. Kau jangan khawatir,” kata Riaman padaku.
Saat itu kata-kata Riaman tidak begitu terpikirkan olehku. Aku hanya bisa melihat dirinya yang sedang merangkak perlahan sambil membawa dua ranting pohon berwarna abu-abu kelam di tangannya. Saat dia berhenti mendekat ke arahku, aku menangis lebih keras. Saat itu ketakutanku membuncah. Apalagi saat mengetahui Riaman yang berhenti bergerak dan membuat diriku menduga-duga kalau dia akan segera meninggalkanku dipatok ular sawah. Ketika bayangan ketakutan itu mulai memenuhi isi kepalaku yang masih berusia sepuluh tahun, aku berkata keras pada Riaman. “Aku mau pulang. Aku mau sama Amak.”
Melihat kecengenganku itu, Riaman menggangguk lalu berkata kalau aku harus kembali menurunkan kakiku ke kolong saung. Dia kembali berujar kalau ular itu tidak berbahaya. Dia tidak akan menggigitmu, ucapnya. Menuruti perkataannya, aku perlahan-lahan menurunkan kaki ke bawah ke arah yang dia tunjuk dengan ranting kayu. Dalam aba-aba yang tenang, Riaman berkata berhenti saat kakiku berada dalam posisi melandai rendah ke kolong saung. Lalu tanpa tahu detail kelanjutannya, aku merasakan permukaan ranting pohon yang kasar dan gemeliat ular di kakiku. Dan dalam sekejap, aku tidak merasakan keduanya.
Sambil menangis aku bertanya, “apa ular itu sudah pergi?”
Sambil tersenyum Riaman menjawab kalau ular itu sudah pergi. Setelahnya dia mengusap air mataku dan berkata kalau aku begitu cengeng. Tidak berselang lama, aku mendengar suara kedua orangtua Lisman dari kejauhan. Mereka menanyakan apa yang sedang terjadi. Melihat sosok orangtuanya, Lisman berlari ke arah mereka. Ketika itu aku masih menangis sambil membayangkan kalau kedua kakiku hilang dimakan ular. Melihat diriku yang masih berurai air mata, Riaman kembali mengusap pipiku yang basah dengan telapak tangannya. Dia berkata kalau kakiku baik-baik saja. Katanya kakiku masih bisa dipakai untuk mengejar belalang. Kemudian Riaman mengucapkan sepatah kata yang membuatku mulai berhenti menangis. Seucap kata yang membuat diriku begitu senang karena memiliki kawan seperti dia.
“Tenang Anjako. Aku akan menjaga kau dan Lisman. Jangan khawatir.”