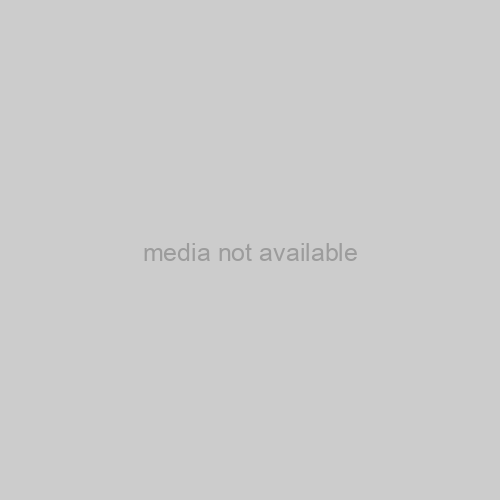“…Traduttore, traditore…”*)
[…Penerjemah, pengkhianat…]
Akhir-akhir ini saya terobsesi menggumuli sajak dalam bahasa Mandarin, bukan karena saya mahir, tetapi karena saya tahu saya tidak akan pernah benar-benar bisa memahaminya.
1
Saya membaca puisi-puisi Asia Timur, utamanya Mandarin, dengan langkah tertatih-tatih, seperti seorang asing yang mengetuk banyak pintu sebelum benar-benar memasuki rumah yang dia cari. Bahasa Mandarin bukan milik saya. Ia ada di kejauhan, di luar batas pengalaman linguistik saya, tetapi ironisnya, saya mencapainya melalui jalan memutar yang panjang. Saya lahir dan besar dengan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang merembes dalam tutur sehari-hari, menjadi lapisan tipis yang membentuk sensibilitas makna. Kemudian berpikir dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, tempat gagasan-gagasan dari berbagai bahasa dikristalisasi dalam sintaks yang telah dibentuk oleh pengaruh kolonial. Lalu mencari makna dalam teks Mandarin yang diterjemahkan melalui medium asing, utamanya Bahasa Inggris.
Dengan kata lain, saya menekuri puisi Mandarin dalam bahasa Inggris, melalui pemikiran bahasa Indonesia, dengan bayangan bahasa Jawa yang masih mengintai di belakang kepala saya.
Saya melewati tiga gerbang bahasa, tiga filter yang semakin menjauhkan saya dari sisi kemagisannya, sebelum saya tiba di teks asli, yang pada akhirnya tetap tidak saya pahami sepenuhnya. Ketika saya sampai ke teks asli, saya tiba dengan penuh luka: saya “membaca” huruf-huruf Mandarin yang saya tidak benar-benar pahami, meraba bunyi-bunyinya yang asing, mencoba mengaitkannya dengan versi yang telah diterjemahkan. Dan setiap kali saya membaca versi terjemahannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dibawa ke bahasa lain.
Ini semacam paradoks. Saya membaca puisi Mandarin, tetapi sebenarnya tidak membaca puisi itu, hanya menelusuri jejak samar yang ditinggalkannya dalam terjemahan. Dan di titik ini, saya selalu merasa iri.
Saya iri karena saya hanya bisa membaca 杜甫 sebagai Du Fu, tidak sebagai 杜甫, tidak sebagai dirinya yang meletup dalam sonoritas Han, tidak sebagai ketukan suara yang seharusnya melompat dari lidah penyairnya sendiri. Saya hanya bisa menduga apa yang hilang dalam kerja sunyi penerjemah, dalam kebohongan estetika yang disebut translasi.
Saya iri pada mereka yang bisa membaca puisi dalam bahasa aslinya, merasakan seluruh bebannya dalam setiap goresan aksara. Iri pada mereka yang tidak perlu bertanya-tanya: “Apa yang hilang?” Karena saya tahu, ada sesuatu yang pasti hilang dalam perjalanan dari satu bahasa ke bahasa lain. Sebuah ritme, sebuah resonansi fonetik, sebuah lanskap semiotik yang tak bisa direplikasi. Dalam setiap penerjemahan, ada yang terhapus, ada yang berubah, ada yang menjadi sesuatu yang lain.
Saya cemburu kepada mereka yang bisa mengecap lapisan-lapisan makna yang mengendap di setiap karakter Hanzi. Sebab, kata yang tampaknya sederhana dalam Mandarin sering kali berisi gugusan makna yang tidak bisa begitu saja diterjemahkan.
Ambil contoh kata “青” (qīng). Dalam banyak terjemahan ke bahasa Barat, kata ini sering dipaksakan menjadi “biru,” “hijau,” atau “cyan.” Padahal dalam Mandarin klasik, “青” merujuk pada spektrum warna yang mengandung elemen kehidupan, transisi, dan waktu. Ia adalah warna langit subuh yang belum benar-benar biru, tetapi juga belum hijau. Ia adalah warna dedaunan muda yang masih segar, tetapi juga warna kulit buah pir mentah yang belum matang. Ketika diterjemahkan, kata ini kehilangan spektrumnya. Kata yang kaya menjadi kering, yang luas menjadi sempit. Maka, dalam penerjemahan, selalu ada luka kecil, selalu ada sesuatu yang hilang—betapa pun cermat seorang penerjemah mencoba menambalnya.
2
Mitos Menara Babel dalam Kejadian 11:1-9 menceritakan bagaimana manusia, yang dulunya berbicara dalam satu bahasa, dihukum dengan perpecahan linguistik karena kesombongannya yang ingin mencapai langit. Tuhan merusak bahasa mereka agar mereka tak lagi bisa saling memahami dan, sejak itu, penerjemahan menjadi sejenis dosa asal. Kita terpaksa hidup dalam bahasa-bahasa yang terbatas dan para penerjemah adalah nabi-nabi yang mencoba menyatukan kembali fragmen-fragmen yang berserakan itu, tetapi mereka selalu gagal. Di titik ini, penerjemah hadir sebagai seseorang yang mencoba mati-matian membangun jembatan dari serpihan-serpihan Menara Babel yang berserakan.
Penerjemah memiliki peran sentral dalam penyebaran pengetahuan dan umumnya dipandang sebagai juru kunci peradaban. Di dunia Timur, para penerjemah kuno sering kali bukan hanya orang-orang yang terampil berbahasa, tetapi juga filsuf dan mistikus. Kumarajiva, misalnya, bukan sekadar seorang penerjemah, tetapi juga seorang bhikkhu besar yang mengalihwahanakan Buddhisme Mahayana ke dalam bahasa Mandarin. Ada pula Yan Fu yang menerjemahkan banyak teks filsafat barat, seperti Evolution and Ethics, dan menghidupkan ulang istilahnya agar diterima dalam masyarakat Tiongkok yang menghidupi Konfusianisme.
Lalu hadirlah penerjemah karya sastra, terutama puisi.
Seorang penerjemah puisi bukan hanya pengalih bahasa. Dia adalah seorang penyair, penerjemah dan exorcist dalam satu tubuh. Tugasnya adalah mengusir hantu bahasa asli dan menjelmakan jiwa puisi dalam tubuh yang baru. Tugasnya lebih berat dari seorang penyair biasa, dia harus menciptakan ulang sesuatu yang sudah diciptakan sekaligus menerjemahkan dunia yang terkandung di dalamnya.
Dia juga harus memutuskan bahan apa yang harus dikorbankan agar jembatan itu tidak runtuh.
Saya ingin mengambil contoh konkret: puisi Vagabond karya Bai Qiu, seorang penyair obskur asal Taiwan. Dalam bahasa Mandarin, puisi ini berbentuk seperti pohon, dengan baris-barisnya yang turun vertikal, menciptakan citraan visual yang sejalan dengan temanya:
一棵丝杉
丝杉
在
地
平
线
上
Yī kē sīshān
Sīshān
Zài dìpíngxiàn shàng
Dan dalam terjemahannya ke dalam bahasa Inggris, kita melihat sesuatu yang lain:
a silk fir
silk fir
on the horizon
Di sini, terjadi sesuatu yang subtil tetapi mendasar: pergeseran struktur yang mengubah lanskap puisi. Dalam bahasa Mandarin, pengulangan 丝杉 (sī shān, “pohon fir sutra”) menciptakan resonansi fonetik yang bergema. Ada sesuatu yang mistis dalam repetisi ini, sebuah ritme yang menyerupai mantra. Dalam bahasa Inggris, efek ini melemah. “Silk fir” tidak memiliki keseimbangan fonetik yang sama, dan meskipun tipografi vertikal tetap dipertahankan, ia tidak memiliki “gravitasi” semiotik yang sama.
Contoh lainnya adalah kata “bulan” dalam bahasa Mandarin (月, yuè) yang bukan hanya merujuk pada benda langit yang menggantung di malam hari, tetapi juga simbol waktu, perubahan musim, dan melankolia yang terperangkap dalam baris-baris puisi klasik. Bagaimana menerjemahkan ini ke dalam bahasa lain tanpa mereduksi resonansi budaya yang menyertainya?
Lihatlah bait terkenal dalam puisi Li Bai:
床前明月光
疑是地上霜
举头望明月
低头思故乡
chuáng qián míng yuè guāng
yí shì dì shàng shuāng
jǔ tóu wàng míng yuè
dī tóu sī gùxiāng
Terjemahan yang saya temukan adalah:
Cahaya bulan menyinari di depan tempat tidurku,
Kukira itu embun beku di tanah,
Kudongakkan kepala menatap bulan terang,
Kuturunkan kepala, teringat kampung halaman.
Atau:
Rembulan penuh menyinari di lantai depan ranjang
Membuat orang menyangka yang penuh di lantai itu embun beku musim gugur
Sambil mendongak kepala, memandang rembulan
Ketika menunduk, kampung halaman terbayang-bayang
Tapi apakah ini benar-benar sebuah “terjemahan”?
Di sini, kita kehilangan bunyi yang mendesing pelan dalam konsonan Mandarin, kehilangan pengulangan míng yuè (明月) yang dalam fonetik aslinya memberi kesan terang yang menetes perlahan. Kita kehilangan muatan emosional nostalgik dari frasa gùxiāng (故乡), kata yang dalam bahasa aslinya membawa luka lebih dalam daripada sekadar ingatan akan tempat tinggal yang jauh.
Akhirnya, penerjemahan adalah sebuah reduksi. Sebuah amputasi.
Hal yang sama terjadi pada haiku jepang. Bagaimana kita menikmati haiku di luar bahasa Jepang? Bagaimana kita memahami esensi 5-7-5 dalam ritme bahasa lain? Sebuah haiku terkenal dari Bashō yang berbunyi:
古池や
蛙飛びこむ
水の音
Furuike ya
Kawazu tobikomu
Mizu no oto
Diterjemahkan menjadi:
Kolam tua
seekor katak melompat
suara air
Dan dalam bahasa Inggris:
An old pond—
a frog leaps in,
water’s sound.
Tetapi sesuatu hilang di sini.
Dalam bahasa Jepang, “や“ (ya) adalah kireji yang berfungsi seperti jeda dramatis, semacam tarikan napas sebelum peristiwa terjadi. Dalam bahasa Inggris atau Indonesia, tidak ada padanan langsung untuk efek ini. Kita bisa menambahkan tanda koma atau garis panjang, tetapi itu tidak bisa menyamai efek dalam bahasa aslinya. Lebih jauh, dalam bahasa Jepang, haiku juga bekerja dengan kontras yang subtil. Kata “古“ (furu, “tua”) berhadapan dengan “飛びこむ“ (tobikomu, “melompat masuk”), yang menciptakan tensi antara keheningan abadi dan gerakan yang tiba-tiba. Dalam terjemahan, kontras ini melemah.
Dalam bahasa Jepang, haiku juga memiliki dinamika suara yang tidak bisa ditiru dalam bahasa lain. Matsuo Bashō, misalnya, menulis menggunakan bahasa yang memiliki struktur sangat berbeda dari bahasa-bahasa Barat atau bahkan bahasa rumpun Melayu-Polinesia seperti Indonesia. Ritme dalam bahasa aslinya bersifat organik, sementara dalam terjemahan, ia menjadi semacam konstruksi ulang yang selalu terasa kurang.
Lihat bagaimana Harold G. Henderson menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris:
“An old silent pond…
A frog jumps into the pond,
Splash! Silence again.”
Dia mencoba menangkap suasana dengan menambahkan kata “silent” dan “splash“, tetapi apakah ini masih Bashō? Ataukah ini Bashō versi Henderson? Di sinilah penerjemah terjebak. Dia bukan hanya berhadapan dengan bahasa, tetapi dengan epistemologi yang berbeda. Jepang memiliki konsep wabi-sabi, keindahan yang ditemukan dalam ketidaksempurnaan dan kefanaan. Mandarin klasik penuh dengan alusi budaya, simbolisme kontekstual yang hanya dapat dipahami jika seseorang telah hidup dalam bahasa itu.
Akhirnya, meskipun saya bisa membaca puisi itu dalam bahasa asli, saya tahu bahwa saya kehilangan sesuatu. Namun, ketika saya membaca terjemahan, saya juga sadar bahwa saya mendapatkan sesuatu yang lain.
Maka, bagaimana cara kita menikmati haiku di luar bahasa Jepang?
Jawaban yang paling mungkin adalah: dengan menerima bahwa terjemahan selalu cacat. Bahwa setiap haiku yang diterjemahkan adalah semacam reruntuhan dari yang asli
Lalu bagaimana dengan Ezra Pound?
Sebagai seorang modernis Barat, Pound terkenal karena menerjemahkan (atau lebih tepatnya: mengadaptasi) puisi Tiongkok klasik. Dalam kumpulannya Cathay (1915), dia menciptakan ulang puisi-puisi Mandarin dalam idiom bahasa Inggris modern. Pound mengambil puisi “臨江仙“ (Lín Jiāng Xiān) karya Li Bai dan membentuknya kembali dengan irama dan estetika bahasa Inggris. Kritik terhadap Pound selalu sama: dia mengkhianati teks asli. Akan tetapi di satu sisi, Pound paham bahwa puisi bukan hanya masalah akurasi linguistik. Dia paham bahwa puisi adalah permainan ritme, nuansa, dan keterasingan.
Ezra Pound dalam Cathay (1915) memberi kita pelajaran tentang terjemahan yang bukan hanya “pindahan”, melainkan juga sebuah “penciptaan ulang.” Puisi-puisi Cina yang dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris tidak selalu akurat secara harfiah, tetapi dia menangkap jiwa yang berdenyut di balik teks aslinya.
Ini adalah potongan dari The River-Merchant’s Wife: A Letter, yang merupakan interpretasi dari Changgan Xing karya Li Bai. Dalam versi Pound:
At fourteen I married My Lord, you.
I never laughed, being bashful.
Lowering my head, I looked at the wall.
Called to, a thousand times, I never looked back.
Bandingkan dengan teks aslinya:
十四为君妇,羞颜未尝开。
低头向暗壁,千唤不一回。
Shísì wéi jūn fù, // xiū yán wèi cháng kāi.
Dītóu xiàng àn bì, // qiān huàn bù yī huí.
Puisi asli Mandarin jauh lebih ringkas dan ekonomis, tetapi Pound membebaskannya dalam semangat bahasa Inggris. Apakah ini pengkhianatan? Atau justru inilah penerjemahan yang sesungguhnya?
Dia tidak menyalin bahasa Mandarin dengan baik, tetapi dia menangkap suasana yang bahkan penerjemah akademis sering gagal pahami.
Jika Pound adalah nabi, maka dia adalah nabi yang menggubah wahyunya sendiri.
3
Salah satu tragedi dalam penerjemahan adalah kerap kali hilangnya jiwa teks.
Penerjemah mengemban tugas para rasul; membawa firman dari satu peradaban ke peradaban lain, tetapi dengan risiko kehilangan mukjizatnya di sepanjang jalan.
Karena apa yang hilang dalam terjemahan bukan sekadar makna. Lebih dari itu: ritme, resonansi, dan sesuatu yang tak bernama dalam susunan fonetik sebuah bahasa yang tak bisa dibiakkan ke dalam bahasa lain. Robert Frost pernah berkata, “Poetry is what gets lost in translation,” dan dia barangkali sedang mengutuki seorang penerjemah yang berusaha menyalibkan puisinya ke dalam bentuk lain.
Karena bahasa adalah cara dunia bekerja, cara realitas diatur, cara tubuh kita memahami kehadiran dan ketiadaan. Dan tiap-tiap bahasa punya sistemnya masing-masing, yang muhal untuk dialihragakan secara utuh.
Ketika kita berkata saudade dalam bahasa Portugis, itu tidak sama dengan kata rindu dalam bahasa kita. Sebab, rindu dalam bahasa Indonesia tetap memiliki objek. Sedangkan saudade adalah rasa kehilangan yang tak terjangkau, sesuatu yang mengiris tetapi juga manis dalam kehilangan itu sendiri.
Apa yang dilakukan penerjemah ketika menemukan kata yang tidak memiliki ekuivalen? Kata yang hidup di dalam Weltanschauung tersendiri, yang berakar dari sejarah dan ritus yang tak dimiliki bahasa lain?
Yan Fu menciptakan prinsip-prinsip dalam penerjemahan yang meliputi: xin (信), da (達), ya (雅). Kesetiaan, Kejelasan, dan Keindahan. Tiga prinsip ini bertentangan satu sama lain, karena kesetiaan sering kali membunuh kejelasan, dan kejelasan sering kali membunuh keindahan. Akan tetapi seorang penerjemah harus mencari keseimbangan di antaranya.
Penerjemah, betapapun setianya, harus memilih antara ketepatan dan keindahan, antara makna harfiah dan makna yang dirasakan. Dan sering kali, dia gagal dalam keduanya.
Tentu saja, di medan penerjemahan puisi, ada dua aliran yang saling berseteru: mereka yang percaya pada kesetiaan dan mereka yang berpihak pada kebebasan. Apakah seorang penerjemah harus patuh pada struktur asli puisi itu, ataukah dia berhak mempermainkan teks demi menangkap esensinya?
Kelompok pertama menganggap penerjemahan sebagai bentuk filologi yang ketat, di mana struktur, rima, dan metafora harus dipertahankan sedapat mungkin. Namun, ada juga mereka yang percaya bahwa penerjemahan puisi harus bebas dari dogma. Seorang penerjemah tidak hanya membawa makna, tetapi juga menciptakan makna baru dalam bahasanya sendiri.
Dalam banyak kasus, aliran kedua membuat batas antara penerjemah dan penyair menjadi begitu kabur hingga keduanya seolah melebur. Tengoklah terjemahan-terjemahan Chairil atas puisi-puisi Barat, seperti Rilke. Dia tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga menyerap puisi itu ke dalam idiomnya sendiri, menjadikannya lebih mirip Chairil daripada Rilke.
Ernste Stunde – Rainer Maria Rilke
Wer jetzt weint irgendwo in der Welt,
ohne Grund weint in der Welt,
weint über mich.
Wer jetzt lacht irgendwo in der Nacht,
ohne Grund lacht in der Nacht,
lacht mich aus.
Wer jetzt geht irgendwo in der Welt,
ohne Grund geht in der Welt,
geht zu mir.
Wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt,
ohne Grund stirbt in der Welt:
sieht mich an.
Jenak Berbenar —Terjemahan Chairil Anwar
Yang kini entah di mana di dunia nangis,
tidak berpijakan di dunia nangis,
nangiskan aku.
Yang kini entah di mana tertawa dalam malam,
tidak berpijakan tertawa dalam malam,
mentertawakan aku.
Yang kini entah di mana di dunia berjalan,
tidak berpijakan di dunia berjalan,
datang padaku.
Yang kini entah di mana di dunia mati,
tidak berpijakan di dunia mati,
pandang aku.
Maka di sini muncul anak pertanyaan: dalam setiap penerjemahan puisi, siapakah yang lebih dominan, sang penyair asli atau sang penerjemah?
4
Ada puisi yang benar-benar tak bisa diterjemahkan, karena ia lahir dari penghancuran bahasa. Lantas bagaimana cara menerjemahkan puisi yang lahir dari kehancuran sebuah bahasa itu sendiri?
Lihat puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri dalam bahasa Indonesia. Dalam “O, Amuk, Kapak,” kata-kata bukan sekadar kendaraan makna, melainkan entitas mandiri:
O
dukaku dukakau dukarisau dukakalian dukangiau
resahku resahkau resahrisau resahbalau resahkalian
raguku ragukau raguguru ragutahu ragukalian
mauku maukau mautahu mausampai maukalian maukenal maugapai
siasiaku siasiakau siasiasia siabalau siarisau siakalian siasiasia
waswasku waswaskau waswaskalian waswaswaswaswaswaswaswas
duhaiku duhaikau duhairindu duhaingilu duhaikalian duhaisangsai
oku okau okosong orindu okalian obolong orisau oKau O….
Bagaimana ini diterjemahkan? Dalam bahasa Inggris, mungkin:
My grief, your grief, our grief, grief-unrest, grief-madness
My restlessness, your restlessness, restless-sorrow, restless-chaos, restless-all
My doubt, your doubt, doubt-master, doubt-knower, doubt-all
My desire, your desire, desire-know, desire-arrive, desire-all, desire-recognize, desire-reach
My futility, your futility, futility-futility, futility-chaos, futility-madness, futility-all, futility-futility
My anxiety, your anxiety, our anxiety, anxiety-anxiety-anxiety-anxiety-anxiety-anxiety-anxiety-anxiety
My sorrow, your sorrow, sorrow-longing, sorrow-pain, sorrow-all, sorrow-despair
My void, your void, void-empty, void-longing, void-all, void-hollow, void-sorrow, void-You, O…
Tetapi dalam alih bahasa itu, (lagi-lagi) ada sesuatu yang hilang. Ritme khas bahasa Melayu, permainan bunyi, efek mantra yang tersirat dalam pilihan katanya. Penerjemah yang baik akan menyadari bahwa menerjemahkan Sutardji bukan soal mencari padanan kata, melainkan menciptakan ulang kesaktiannya dalam bahasa lain.
5
Jika kita percaya pada Barthes, maka teks selalu mati begitu ia lepas dari pengarangnya. Setiap pembaca adalah seorang algojo. Dan barangkali penerjemah adalah Frankenstein yang menghidupkan kembali teks itu dalam tubuh lain.
Penerjemah puisi bisa disamakan dengan Viktor Frankenstein. Dia mengalihkan bahasa, membedah teks itu, membunuh struktur aslinya, lalu menyusunnya kembali dalam bentuk yang berbeda. Dia seorang yang membongkar makam, mengangkat mayat puisi dari tanah aslinya, memindahkannya ke dunia lain, tetapi tahu bahwa kehadiran roh tak akan pernah bisa diangkut bersama tubuhnya.
Apakah terjemahan itu dosa? Ataukah ia adalah satu-satunya cara bagi kita untuk mengintip sedikit ke dalam dunia lain?
Atau mungkin kita harus berhenti menganggap puisi sebagai artefak statis yang harus dibawa utuh ke dalam bahasa lain. Mungkin, seperti organisme yang mengalami evolusi, puisi harus diizinkan untuk berubah, untuk hidup dalam bentuk-bentuk baru yang tak pernah dibayangkan oleh penyair aslinya.
Maka, penerjemah bukan pengkhianat, melainkan seorang alkemis yang mengubah teks menjadi bentuk lain, sama berharganya, meski tak pernah sama persis. Jika kita menerima bahwa sebuah puisi adalah pengalaman yang terus bergerak, maka setiap penerjemahan adalah sekadar kelahiran ulang, bukan kematian.
6
Penerjemah puisi adalah seorang rasul yang meragukan wahyunya sendiri. Dia membawa pesan dari satu dunia ke dunia lain, tetapi dia tahu bahwa pesan itu, bagaimanapun juga, telah terdistorsi. Dia tidak pernah bisa membawa Tuhan itu sendiri, hanya bayangannya. Dia tahu bahwa pekerjaannya mustahil. Dia tahu bahwa tidak ada padanan yang sempurna. Dia tahu bahwa setiap kata yang dia pilih adalah kompromi
Penerjemahan, khususnya puisi, pada akhirnya, meskipun bisa dianggap sebagai kerja yang sia-sia, tetapi ia juga tetap menjadi kerja yang harus dilakukan. Sebab di dalam kegagalan itulah tersimpan kemungkinan perjumpaan, antara dunia-dunia yang tak pernah sepenuhnya saling memahami.
Penerjemah, idealnya, cukup rendah hati untuk mengakui bahwa dia hanya bisa mendekati makna, tetapi juga cukup berani untuk menciptakan ulang makna itu dalam bentuk yang baru. Dia harus menerima bahwa setiap kata yang dipindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain pasti akan mengalami kehilangan, dan dalam kehilangan itu ada kemungkinan lain yang muncul, sebuah kemungkinan yang tidak ada dalam bahasa aslinya.
Lalu, sebagai pembaca?
Mungkin tugas kita sebagai pembaca bukanlah berusaha menembus batas bahasa, melainkan merayakan batas itu sendiri. Kita tidak membaca untuk memahami sepenuhnya, tetapi untuk menikmati kegagalan pemahaman itu. Seperti menatap bulan yang dipantulkan di permukaan air, kita tahu itu bukan bulan yang sesungguhnya, tetapi apakah itu membuatnya kurang indah?
Karena pada akhirnya, kita semua hidup dalam terjemahan.
Kita membaca puisi-puisi yang tak lagi sama dengan aslinya. Kita membaca novel-novel yang telah kehilangan irama dan idiom yang hanya bisa dipahami dalam konteks budaya sumbernya. Kita menikmati filsafat yang telah melewati filter bahasa lain, kehilangan nuansa yang mungkin akan mengubah pemaknaannya.
Dan kita menerima semua ini, karena kita tak punya pilihan lain.
Namun, barangkali, di tengah semua kehilangan ini, ada sesuatu yang tetap bisa dirasakan: bahwa bahasa, seberapa pun terbatasnya dalam menerjemahkan, tetap mampu menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari kata-kata.
Maka, membaca terjemahan adalah membaca dengan kesadaran bahwa kita selalu kehilangan sesuatu. Penerjemah, bagaimanapun, tetaplah peziarah yang mengembara di antara bahasa-bahasa, mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, meskipun dia tahu bahwa sebagian besar akan tetap tertinggal di sisi lain gerbang bahasa.
Traduttore, traditore.
Namun, tanpa pengkhianatan itu, kita tak akan pernah tahu betapa kayanya dunia di luar kata-kata kita sendiri.
*) Ungkapan Italia “Traduttore, traditore” (penerjemah adalah pengkhianat) lahir ketika The Divine Comedy karya Dante Alighieri mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, banyak orang Italia menganggap terjemahan tersebut gagal menangkap kompleksitas alegori, musikalitas, dan nuansa filosofis yang melekat dalam versi aslinya serta dianggap telah mereduksi keagungan Dante.

Muhammad Haidar
Muhammad Haidar adalah mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya angkatan 2023 yang aktif di pers mahasiswa. Ia adalah pembaca awam sastra Asia Timur, dan tengah mencoba meraba kemungkinan-kemungkinan yang lahir dari pertemuan antara bahasa asing, puisi, dan rasa asing itu sendiri.