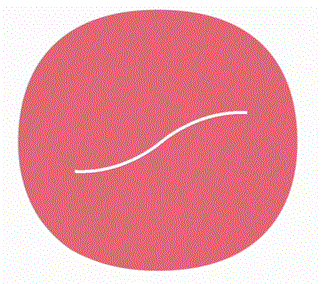Untuk Zen, Martin, Mimi, Vivi & Hasan—
Ketika tengara.id diluncurkan (dalam konperensi pers), ia dikatakan sebagai situs kritik sastra. Setidaknya begitulah menurut Avianti Armand & Hasan Aspahani. Hasan malah menyebut contoh tulisan-tulisan Subagio Sastrowardoyo di Budaja Djaja. Waduh, dalam hati saya berkata: siapa yang akan nulis kritik sastra macam begitu sekarang ini? Siapa yang bisa, siapa yang mau, siapa yang punya waktu? Kalaupun ada orangnya, maka itu jumlah, saya duga, tak akan lebih dari sepuluh. Dan mereka yang segelintir itu pun harus dipaksa-paksa nulis juga. Atau, sampeyan harus memancing “siapa saja” di dunia luas yang serba-lisan dan serba-jempol di media sosial untuk menuliskannya. Jadi, jalan tengara.id sungguh curam, berliku, dan panjang sekali.
Tapi, kalau saya baca editorial yang sangat berbau ikonoklasme (yang dari baunya akan segera ketahuan bahwa itu ditulis oleh Martin Suryajaya), maka saya tahu bahwa ternyata “kritik sastra” itu bisa apa saja. Ini adalah kritik sastra yang tidak perlu didasarkan pada close reading; bahkan “membaca adalah tidak sungguh-sungguh membaca”. Sangat heroik. Bahkan dinyatakan bahwa tengara.id adalah “ruang inklusif untuk mempercakapkan segala gelagat sastra Indonesia hari ini.” Kalau saya boleh jahil, maka saya akan bilang bahwa tengara.id akan juga bisa menampung tulisan-tulisan tentang gosip sastra, bahkan tentang sandal seorang penyair pun bisa, asalkan itu mengandung “sesuatu”. Maka, “kritik sastra” pun bisa segala-galanya. Ikonoklasme total.
Tapi, masak iya sih, Dewan Kesenian Jakarta mau menjalankan ikonoklasme? (Kata Kiai Togog, ikonoklasme hanya pantas dijalankan oleh mereka yang tidak mendapatkan dana dari pemerintah.)
Jadi tengara.id mau yang close reading atau mau yang distant reading? Atau kedua-duanya? Artinya, Komite Sastra (Hasan, Avianti) cenderung kepada kritik sastra yang “klasik”, sedangkan Redaktur tengara.id mau yang ikonoklastik? Dan berdamai di jalan tengah?
Kalaupun Redaktur tengara.id cenderung yang ikonoklastik, maka spesifikasi tulisan yang boleh dimuat itu seperti apa? Apa betul segala “gelagat sastra” bisa ditulis? Dan ditulis dengan cara apa, sepanjang apa? Dengan cara mbeling, bolehkah? (Ada juga sedikit tendensi ke situ, misalnya di wawancara dengan Sabda Armandio)? Bisakah tulisan yang sepanjang hanya 1.000 kata, bahkan 500 kata, dimuat? Mohon kejelasan untuk soal ini. (Sebagai contoh: jurnal Poetry, memuat kritik puisi yang bisa sependek itu.)
Waktu peluncuran kemarin, sebenarnya saya mendorong supaya tengara.id itu jadi situs, bukan penerbitan berkala. Paling tidak, ada aspeknya yang dinamislah, unggahan yang bisa tayang sewaktu-waktu, tidak menunggu periode terbit yang baru. Surat ke redaksi (tentu yang betul-betul layak), komentar, kontra-kritik, hak jawab (dari apa yang jadi sasaran kritik sastra atau “kritik sastra” yang termuat), dan sejenisnya, itu harus segera dimuat, tidak bisa ditunda, tidak bisa nunggu penerbitan edisi yang baru. Ini zaman internet, puan-tuan sekalian, yang menurut “editorial” sampeyan sudah “mengubah struktur kesadaran sastrawan”. Jadi, sampeyan semua, ya, harus konsisten dengan bunyi editorial itu. Maka, saya menghasut supaya tengara.id hidup di dunia digital, bukan melanjutkan dunia cetakan. Minimal menggabungkan sifat periodical dengan blogging (seperti London Review of Books, Paris Review, dan sejenisnya).
Demikianlah uar-uaran saya, yang dalam hal ini termasuk ke dalam “rakyat sastra”. Tapi saya, selaku tukang sastra, juga termasuk ke dalam golongan aurochs (Bos primigenius), lembu purba, spesies yang hidup di zaman Pleistosen. Saya pikir tengara.id lebih cocok hidup untuk zaman Holosen bahkan Antroposen, zaman terbaik bagi “generasi tanpa semboyan & tanpa kekhasan”. Kecuali kalau anda sekalian mau hidupkan lagi golongan aurochs dengan teknik reversed cross-fertilization.
Terima kasih.
21 Agustus 2021

Nirwan Dewanto
Nirwan Dewanto adalah penyair, esais, dan kurator. Buku-bukunya adalah, antara lain, Buli-Buli Lima Kaki (puisi), Satu Setengah Mata-Mata (esai), Buku Jingga (fiksi), Kaki Kata (esai), dan Museum of Pure Desire (puisi dalam terjemahan Inggris).