Pengantar: Situs web tengara.id tentu lahir dari sikap bahwa kritik sastra diperlukan. Bisa dipersoalkan, sejauh mana kritik diperlukan, diperlukan siapa, dan kenapa. Di sini saya bukan hendak menjawab itu; saya berpendapat, lebih baik menengok dan memeriksa letak kritik dalam kancah karya sastra.
Kritik terjadi sesudah pengalaman dengan sebuah karya sastra.
Kata “pengalaman” ingin saya beri tekanan di sini. Pertemuan paling awal kita—persisnya pertemuan primordial—dengan karya sastra, bukan sebuah pertemuan kognitif. Dalam pertemuan primordial itu “saya” [pembaca, atau kritikus] masuk “mengalami” sebuah karya. Mengalami, tanpa kehendak untuk mengerti dengan mengurai dan merumuskannya. Dalam sikap itu tersirat pengakuan bahwa, “a poem should not mean, but be”, seperti dikatakan Penyair Archibald MacLeish dalam Ars Poetica.
Lagu Gadis Itali
(pantun berkait)
Buat Silvana Maccari
Kerling danau di pagi hari
Lonceng gereja bukit Itali
Jika musimmu tiba nanti
Jemputlah abang di teluk Napoli
Kerling danau di pagi hari
Lonceng gereja bukit Itali
Sedari abang lalu pergi
Adik rindu setiap hari
Kerling danau di pagi hari
Lonceng gereja bukit Itali
Andai abang tak kembali
Adik menunggu sampai mati
Batu tandus di kebun anggur
Pasir teduh di bawah nyiur
Abang lenyap hatiku hancur
Mengejar bayang di salju gugur
Bunyi dan repetisi dalam sajak karya Sitor Situmorang ini “membius” kita. Kesadaran kita tak bersiaga menangkap apa maksudnya. Kita hanya menikmati repetisi baris-barisnya seperti kita mendengar mantra dibacakan, seperti ketika kita mengikuti lagu dolanan anak-anak. Repetisi itu bahkan tak kita tangkap sebagai sekadar kata yang diulang-ulang; tiap kali kalimat yang terbaca di sana datang kembali sebagai pengalaman baru. Dalam sajak di atas, sampiran (Kerling danau di pagi hari. . .” dan seterusnya) yang sama, berubah tiap kali ia terkait dengan teks “isi” yang berubah. Makna 16 baris itu tak bisa kita ikhtisarkan atau tak bisa kita utarakan dengan kata-kata kita sendiri.
Mengalami sebuah sajak tidak sama dengan menelaah; kita tidak keluar, mengambil jarak, dari dalamnya, seperti ketika kita memeriksa tungkai kaki kita, mencari bagian mana yang sakit terbentur tembok. Mengalami Lagu Gadis Itali adalah meresapkan sajak itu, dan dalam proses itu saya bertemu dengan kejutan-kejutan, mungkin kontras, dari bunyi dan penanda, seperti ketika kita menemukan panggilan “bang”—sebuah sebutan yang khas Melayu—di tengah suasana Italia: lonceng gereja, kebun anggur, Teluk Napoli.
Sehabis itu, ketika kita bertanya, berpikir, mengapa ada kejutan-kejutan atau kontras itu, kita pun mulai menginterpretasi.
*
Pada akhir 1960-an saya dan Arief Budiman, seraya memperkenalkan “Metode Gestalt”, menolak analisis karya sebagai metode utama dalam kritik.
Analisis membuat karya seperti sebuah bangunan yang bisa dibongkar, dipreteli, ketika kita ingin menemukan maknanya. Metode Gestalt tak hendak demikian. Dalam metode ini, karya dipersilakan “bergerak” leluasa. Kritik sastra tidak membawa kerangka, standar, taksonomi, dan teori tertentu untuk kemudian dipasang buat menjelaskan karya itu. Kritik “masuk” ke karya itu sendiri (zu den Sachen selbts, untuk meminjam sebentar pengertian fenomenologi) menyerapnya (dan diserapnya), menyimaknya, mendengarkannya, mengalaminya, bukan buat menguji satu hipotesis.
Interpretasi datang kemudian, dengan risiko.
Interpretasi atas karya sastra—yang umumnya dilakukan kritisi—mengandung kemungkinan mengurung dan mengarahkan karya ke dalam suatu arah makna. Sejauh mana makna itu tafsir yang sahih, dan bukan distorsi?
Persoalannya, bisa adakah “interpretasi yang sahih”. Saya ingat kata-kata Ionesco yang pernah saya kutip sekian puluh tahun yang lalu: kritik sastra bukan kepala sekolah, melainkan murid [dari] karya. Karya punya dinamikanya sendiri, persilangan terus-menerus antara kehendak pengarang, pemahaman pembaca, batas dan keluasan yang ada dalam karya itu sendiri. Tak ada formula kesahihan. Tak ada ukuran.
Sebab itu, jika ada sebutan “Paus Sastra” kepada H.B. Jassin tidak berarti ada otoritas tunggal dalam tafsir dan penilaian. Sebutan terkenal itu, diawali oleh sastrawan Gajus Siagian, saya kira hanya semacam cemooh. Banyak sastrawan, dengan pengalaman yang masih terbatas, datang ke Jassin untuk dinilai—dan Jassin memang sering bertindak sebagai guru. Misalnya dalam rubrik “Sorotan” di majalah sastra Kisah.
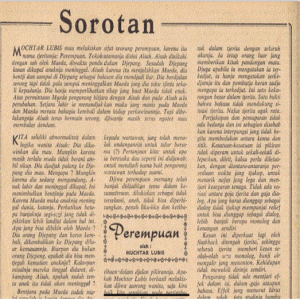
*
Dalam “perdebatan” kami dengan para dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1960-an tentang kritik yang saya sebut di atas, Arief Budiman dan saya mengisyaratkan, otoritas tunggal dalam kritik menyesatkan. Bagi kami, sah saja jika lahir 1000 tafsir dan 1000 penilaian.
Dengan itu pula kami menolak kecenderungan meng-ilmiah-kan kritik sastra—mungkin itu tendensi akademik—apalagi dengan bayang-bayang positivisme. Konsensus bisa terbentuk, tapi terbatas dan “contingent”. Kecemasan akan adanya ukuran yang baku, akan terbentuknya “kanon” karena konsensus adalah kecemasan yang berlebihan. Penilaian selamanya beragam dan tak akan menetap.
Potensi utama kritik sastra adalah menghidupkan kembali karya sebagai pengalaman pada masing-masing pembaca. Pengetahuan linguistik, etimologi, dan cabang lain ilmu bahasa, filsafat, psikoanalisis, sejarah sosial, dan lain-lain hanya membantu.
Menganalisis karya sastra bukan sebuah perbuatan haram, tapi bukan di situ kuncinya untuk membuat karya bicara, bergulat, menyentuh, mengguncang kita.

Goenawan Mohamad
Goenawan Mohamad menulis puisi, esei/kritik, lakon, dan novel. Kumpulan puisinya antara lain Fragmen, Trigris dan Don Quixote. Kumpulan eseinya antara lain Puisi dan Anti Puisi, Estetika Hitam, Albert Camus: Tubuh dan Sejarah, serta Pigura Tanpa Penjara: Esai-Esai Seni Rupa. Lebih dikenal: 14 jilid Catatan Pinggir.

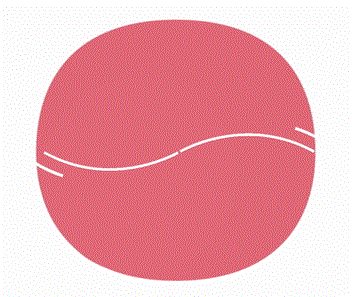
Kritik sastra bukan hanya untuk hidupkan karya sastra juga memasyurkan karya sastra berkulitas dengan cara yang cerdas juga visioner bagi perkembangan sastra ke depan. Makin banyak varian kritik sastra dan perspektif beraneka maka sehat pula jagad sastra
[…] __________. 2021. “Sedikit tentang Kritik”; https://tengara.id/meja-bundar/sedikit-tentang-kritik-sastra-goenawan-mohamad/. […]