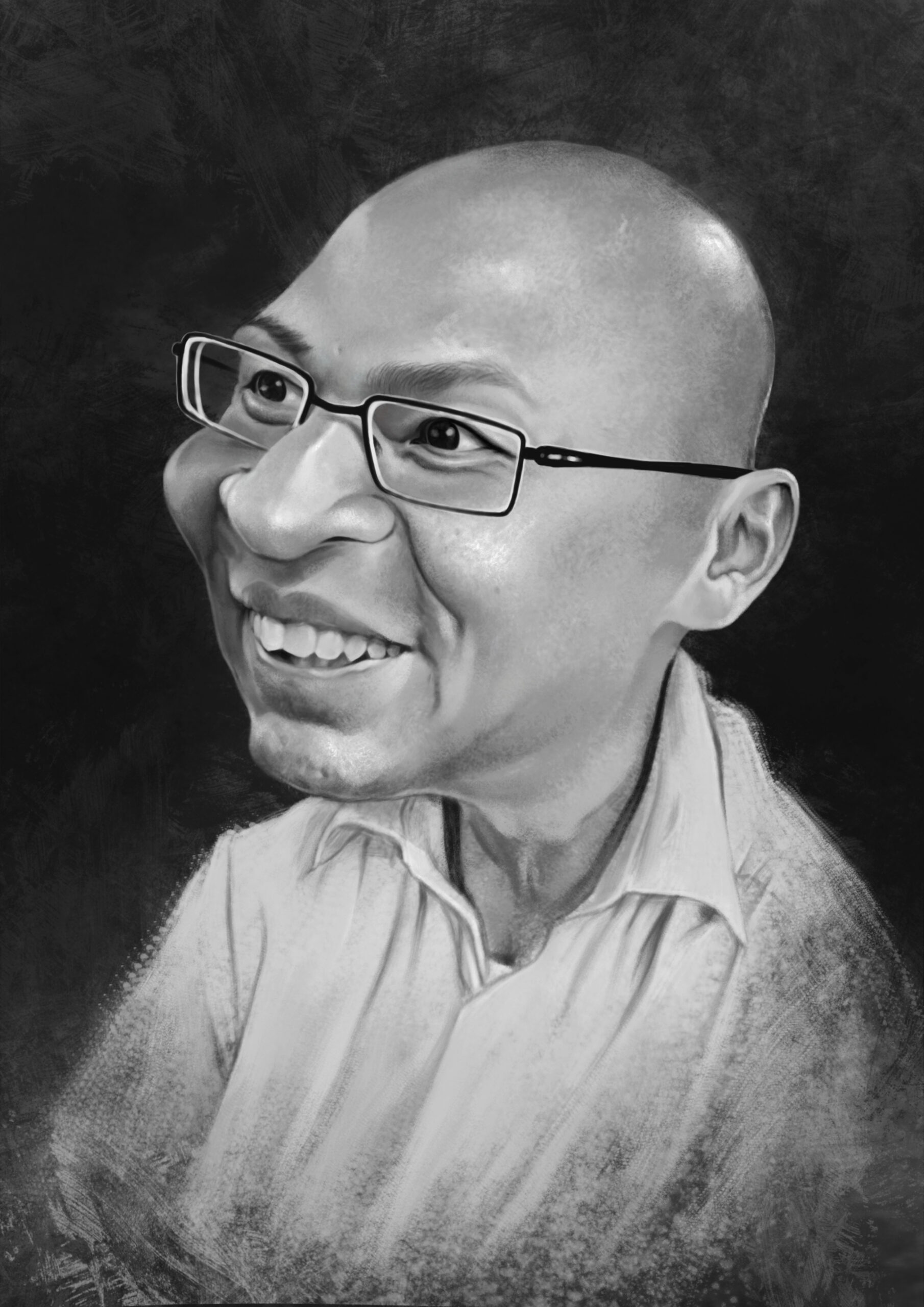Sastra Indonesia modern umumnya dipahami lahir pertama-tama dari semangat kebangsaan ketika “Indonesia” baru eksis dalam imajinasi dan Bahasa Indonesia belum mendapatkan nomenklatur. Akta kelahiran tersebut belakangan berkali-kali ditinjau ulang dengan membuka kemungkinan penanda angka yang lebih tua sekaligus memasukkan berbagai karya yang sebelumnya tidak dianggap memenuhi kategori keindonesiaan. Berbagai upaya senada dilakukan juga terkait tonggak-tonggak penanda ritus penting sepanjang hidup sastra Indonesia modern, memunculkan berbagai pokok dan tokoh yang termarjinalkan oleh satu versi dokumen historiografi.
Kini, ketika kemajuan teknologi melompatkan jangkauan komunikasi antara berbagai pengguna bahasa berbeda sekaligus mengaburkan tapal batas antar bangsa, mungkin diperlukan upaya meninjau ulang sastra Indonesia itu sendiri. Definisi lama adalah titik tolak yang, alih-alih diperlakukan sebagai dokumen yang tak bisa diganggu gugat, mungkin lebih bijak jika diposisikan sebagai gagasan tentang berbagai indikator awal yang memiliki fleksibilitas untuk menyelaraskan diri dengan berbagai pintu masuk baru yang ditawarkan perkembangan zaman. Dengan pandangan inklusif semacam itu, berbagai produk yang selama ini hanya diposisikan sebagai pelengkap, semisal sastra terjemahan, akan memiliki nilai baru yang bisa menambah semarak senarai sastra Indonesia.
Karena “Indonesia” pada dasarnya pertama-tama eksis dalam imajinasi dan tampaknya akan selalu demikian. Tapal batas Indonesia memiliki fleksibilitas untuk mengerut atau mengembang sesuai dengan ujung pangkal cakrawala pemikiran si pemandang. Merengkuh sikap kosmopolit semacam itu saat menautkannya dengan kesusastraan, pemuja partikularitas yang menyuruk ke dalam lokalitas ataupun penyokong universalitas yang melompat ke atas panggung luas sebagai “warga sastra dunia” sama-sama harus dicatat dan mendapat tempat karena jalur sungai mana pun yang diarungi maka ujungnya selalu Indonesia sebagai muara.
Untuk meneroka lebih dalam berbagai persoalan terkait Sastra (di) Indonesia pada masa kini tersebut, redaksi tengara.id mengundang Manneke Budiman, seorang Guru Besar Ilmu Susastra dan Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI). Bidang kajian yang diarungi Manneke sangat luas, meliputi Budaya Populer, Studi Gender & Feminis, Sastra Dunia, sampai Globalisasi, dan Transnasionalisme. Dalam percakapannya dengan redaksi tengara.id, Manneke mengurai berbagai pandangannya mengenai politik pendefinisian sastra Indonesia, posisi terjemahan sastra, imajinasi tentang “Indonesia”, sampai pentingnya melakukan gerak kembali ke sikap kosmopolit para penyair dan pemikir terdahulu.
Berikut percakapan redaksi tengara.id dengan Manneke Budiman.
Definisi Sastra Indonesia
AVIANTI ARMAND
Seperti yang sudah kami sampaikan ke Pak Manneke bahwa tema Tengara edisi ke-11 kali ini adalah “Sastra (di) Indonesia”. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Manneke tentang hal tersebut. Kita mulai dari definisi atas sastra Indonesia, ya. Sampai saat ini, sastra Indonesia didefinisikan berdasarkan tiga kategori yang konvensional: aspek keindonesiaan dalam karya, kewarganegaraan penulis sebagai WNI, dan bahasa Indonesia selaku bahasa yang digunakan dalam karya. Menurut Pak Manneke, apakah tiga kategori ini masih cukup atau sebenarnya perlu kita tinjau ulang?
MANNEKE BUDIMAN
Tidak mungkin kita menambah kategori yang lain karena nanti status atau situasinya akan tetap sama. Mau jadi lima, mau jadi enam, kita akan tetap menghadapi persoalan bahwa secara bersama-sama ketiga kategori itu bisa dijadikan indikator, tetapi tidak bisa dijadikan landasan untuk membuat definisi. Apakah tiga itu bisa menjadi indikator untuk membantu kita mengatakan “ini Sastra Indonesia atau bukan,” bisa. Dengan cara yang sangat luwes. Masing-masing dari ketiga indikator tadi bisa digunakan tetapi pada saat yang sama juga bisa diperluas.
Misalnya, ada orang yang bukan WNI tetapi menulis sastra yang temanya tentang Indonesia, atau tokoh-tokohnya orang Indonesia, berlatar Indonesia, dan latar itu tidak hanya berfungsi sebagai pajangan latar belakang, maka indikator kewarganegaraan Indonesia untuk pengarang di dalam hal itu bisa dia bypass, karena dia masih bisa memenuhi dua kategori yang lain. Indikator itu artinya begitu, ia tidak digunakan untuk membentuk definisi tetapi untuk membantu kita mengatakan “iya, ini bukan atau tidak”.
Bagaimana kalau penulisnya WNI tapi sama sekali tidak berkaitan atau ada hubungan apa-apa dengan keindonesiaan? Dia masih bisa memenuhi indikator bahwa dia adalah WNI. Meskipun indikator yang satu lagi, tema tidak memenuhi, bahasa mungkin masih memenuhi. Tapi, bagaimana kalau dia adalah orang Indonesia tapi tidak menulis sama sekali cerita tentang Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Indonesia? Indonesia masih bisa mengklaim itu adalah sastra Indonesia gitu karena ada dari tiga indikator yang existing masih dipenuhi, gitu.
Indikator bisa bertambah. Mungkin indikator tidak perlu dikurangi karena kita melihat yang tiga itu masih bisa dipakai. Tetapi, seberapa banyak pun kita nanti punya poin indikator, itu tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk definisi. Jadi, kita mau membedakan saja yang sudah berkembang di luar, orang bilang sastra Indonesia itu “ini atau itu”. Fungsinya hanya sebatas untuk mengindikasikan, tapi tidak untuk mendefinisikan.
Kalau cara pandangnya seperti itu, maka kita tidak akan punya persoalan.Persoalan itu baru muncul dan tidak pernah akan bisa terpecahkan kalau kita mau berambisi untuk punya definisi.
AVIANTI
Apakah bahasa Indonesia tidak bisa digunakan sebagai indikator utama untuk melandasi atau menjadi semacam pagar atau kerangka untuk mendefinisikan sastra Indonesia? Misalnya, ditulis oleh orang Indonesia, dengan latar Indonesia tetapi dalam bahasa Inggris. Bisakah karya itu disebut sebagai sastra Indonesia?
MANNEKE
Ya, lagi-lagi cara kita mengerti terminologinya; sebagai indikator utama tidak, tetapi sebagai indikator awal iya. Karena itu kemudian kita tertarik untuk melihat lebih dalam untuk mengetahui apakah suatu karya dapat disebut sastra Indonesia atau bukan. Tapi, fungsinya sebagai indikator awal. Indikator awal bisa dimulai dari salah satu indikator existing, tidak harus dari bahasa. Karena tidak ada indikator yang statusnya lebih utama daripada yang lain. Saya pernah, Ingat tidak, dulu Richard Oh pernah menulis novel The Rainmaker’s Daughter yang ditulis sepenuhnya dalam Bahasa Inggris. Tapi isinya sangat lokal, sangat Indonesia. Richard Oh juga orang Indonesia. Saya tidak akan punya keraguan untuk menganggap novel itu sebagai sastra Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia bisa mengklaimnya sebagai sastra Indonesia. Karena meskipun saya harus membacanya dalam bahasa asing, alam pikiran yang diceritakan dalam karya itu adalah alam kehidupan saya sebagai orang Indonesia Laksmi Pamuntjak juga pernah menerbitkan puisi dalam bahasa Inggris, kan. Tapi, isinya sangat familiar bahwa itu Indonesia.
Seandainya sekarang kita balik nih, orang asing bukan WNI menulis dalam bahasa Inggris tetapi dia bercerita tentang Indonesia. Ini akan lebih sulit sebetulnya untuk mengatakan karyanya bisa diklaim sebagai sastra Indonesia atau tidak. Walaupun kalau saya yang ditanya, saya tidak punya masalah untuk mengatakan bahwa kritik sastra Indonesia atau program studi Sastra Indonesia boleh menggunakan buku itu sebagai materi kajian. Tanpa harus berdebat apakah ia adalah bagian dari sastra Indonesia atau tidak. Nah, sekarang kita buat lebih kompleks lagi. Seandainya ia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu akan lebih memperkuat seandainya saya mau mengatakan bahwa saya bisa menganggapnya sebagai bagian dari khazanah kekayaan sastra Indonesia.
Masalahnya yang membuat kita selama ini berputar-putar dalam benang ruwetkarena keindonesiaan atau Indonesia yang tadinya itu secara historis adalah suatu entitas yang sifatnya politis, lalu kita mau pakai label itu untuk berbagai macam. Untuk apa terminologi “buatan Indonesia”, “sastra Indonesia”, “makanan Indonesia”? Akibatnya justru mempersempit, mereduksi. Jadi, kata “Indonesia” sebagai suatu rujukan yang politismereduksi berbagai macam hal yang belakangan juga ditempeli dengan label “Indonesia”. Kita harus menggunakan kata “Indonesia” tidak dalam pengertian politis, nation state gitu, ya, tetapi betul-betul dalam pengertian yang lebih luwes.
Persoalan ini juga kita hadapi ketika kita mau bicara tentang definisi kebudayaan Indonesia. Ketika kita berhadapan dengan buku yang mengatakan ada sembilan karakter orang Indonesia, selalu orang akan kembali berpulang pada “Indonesia yang mana?”Kalau kita lihat Indonesia sebagai suatu entitas politik, semua ini tidak ada masalah, tapi menjadi masalah ketika label itu diterapkan ke hal-hal yang lain yang bukan politis, misalnya kebudayaan, manusia, kesusastraan.
Kalau saya bicara tentang kurikulum program studi Sastra Indonesia tentu akan sangat jauh lebih terbatas dan lebih restricted. Mereka bisa membuat kriteria yang mengatakan ini boleh jadi kurikulum atau tidak. Tapi di dalam dunia sastra di luar disiplin ilmu sastra Indonesia, itu kita punya keluwesan yang jauh lebih kaya untuk bisa mengatakan, untuk bisa mengakomodasi sebanyak mungkin yang tidak dianggap Indonesia pada tataran formal, sehingga Indonesia-nya tidak dipakai untuk menutup pintu, tetapi justru untuk membuka pintu. Maka, berbagai macam hal yang orang akan ributkan dan jadikan kontroversi sebagai Indonesia atau bukan tetap bisa diwadahi di dalam arena sastra Indonesia ini. Selama ia tidak dianggap sebagai pintu yang harus ditutup tetapi justru sebagai yang harus dibuka.
DEWI ANGGRAENI
Apakah sebenarnya problem utamanya adalah upaya mendefinisikan Sastra Indonesia sendiri? Maksudnya, perkara “keindonesiaan” sebenarnya bisa ditakar atau tidak sih? Kita lihat contoh kasus-kasus yang kondisinya pascakolonial. Kalau dulu sastra Inggris akhirnya jadi sastra berbahasa Inggris, gitu kan, ya, ada istilah anglophone. Terus, sastra Perancis akhirnya diperluas menjadi francophone, bahkan untuk Jepang sendiri akhirnya diperluas jadi sastra berbahasa Jepang. Tapi kondisi kita kan bisa dibilang korban penjajahannya, ya. Apakah mustahil kita memperluas definisi sastra Indonesia? Ataukah sebenarnya keindonesiaan i tidak akan pernah bisa ditakar?
MANNEKE
Bukan ditakar, tetapi bagaimana cara kita punya pintu-pintu masuk untuk bisa mengenali sastra Indonesia. Tapi, setiap pintu itu tidak membuat atau menjadikan takaran. Misalnya, kalau memenuhinya hanya 30% berarti tarafnya rendah. Bahkan mengukur 30%, 50% itu pakai alat ukur apa?, Tidak akan pernah kita menemukannya.
Menurut saya biang keroknya adalah karena orang mau mendefinisikan sastra Indonesia. Selama ini upaya itu dilakukan misalnya antara lain lewat penetapan angkatan-angkatan. Nah, itu kan juga upaya mendefinisikan. Lagi-lagi, teman-teman ingat bahwa angkatan-angkatan sastra yang ditetapkan itu sangat bertumpangtindih dengan politik dan sejarah pada saat itua. Misalnya, Angkatan 66 dan Angkatan 45. Apakah ia menghasilkan suatu school of thought yang baru di dalam sastra? Menjadi suatu movement seperti macam-macam realisme dan romantisisme segala macam di Eropa yang lalu perubahannya menjadi titik momen untuk menandai bahwa “ini yang lama” dan “ini yang baru”?
Hal-hal seperti ini yang memang kemudian membuat kita membuang banyak waktu yang sebetulnya sia-sia; mencoba untuk memahami lebih jauh tentang definisi sastra Indonesia itu apa. Betul, bahwa karena persoalan latar belakang kolonial saja sudah mustahil untuk mendefinisikan Indonesia. Itu terjadi pada semua negara, bangsa bekas jajahan, ya. Tetapi karena kolonialisme juga, ditambah dengan globalisasi, negara-negara yang tidak pernah dijajah dan dulu pernah menjadi kiblat kebudayaan dan peradaban termasuk sastranya juga kebingungan. Tadi Reni [Dewi Anggraeni] dengan tepat mengatakan lihat saja sastra Inggris, lama-lama yang bukan ditulis orang Inggris, tapi dalam bahasa Inggris dianggap sastra Inggris.
Saya ingat dulu, waktu tahun 1980-an awal saya masuk Fakultas Sastra, kami harus membaca Leo Tolstoy, Anton Chekhov, yang tidak ada hubungannya dengan sastra Inggris, tetapi ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Ini ada di berbagai kurikulum sastra Inggris di mana-mana, tidak hanya itu di Indonesia.
Ketika kemudian terjadi migrasi dan mobilitas orang dari bekas jajahan ke pusat-pusat yang dulu menjadi penjajah, misalnya Kazuo Ishiguro, pindah ke Inggris menulis tentang Inggris, tapi orang tahunya dia orang Jepang.. Ini kan tidak bisa dicegah. Kadang-kadang orangnya tidak pindah, tapi naskahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris walaupun bahasa aslinya bukan bahasa Inggris, bisa bahasa Urdu, bisa bahasa Hindi, atau bahasa Melayu. Ini membuat kita semakin tidak mungkin untuk berpikir tentang definisi atau bahkan makin sia-sia untuk mencari definisi.
Bolehkah sekarang orang Inggris melihat Arundhati Roy itu sebagai kekayaannya dia? Tidak ada yang bisa melarang sebetulnya. Seperti halnya kita tidak bisa melarang orang Malaysia bilang rendang punya dia, mengingat ada orang-orang Melayu dan orang Minang yang juga bermigrasi ke situ dan mungkin sudah berketurunan entah berapa generasi. Jadi, culture sastra tidak boleh memang kemudian direduksi dan ditumpangtindihkan dengan yang berbau formal nasional, seperti kewarganegaraan, bahasa resmi. Diaspora juga menghadirkan kompleksitas yang baru, kan. Karena ia masih berbicara dan terobsesi dengan negeri asalnya, tetapi sudah menulisnya dengan bahasa negeri tempat tujuannya.
Lalu, kalau India mengklaim itu Arundhati Roy punya dia, tapi pada saat yang sama Amerika mengklaim itu sebagai sastra Amerika, yang bisa mencegah siapa? Dan dengan alasan atau titik keberangkatan apa orang mau mencegah? Tidak bisa kan, gitu. Maka, daripada mencegah, kita mindset-nya justru mengadopsi dan mengakomodasi. Oke, kita mempelajari dan mengatakan ini sebagai sastra Indonesia, tapi kita bisa memberikan alasan untuk menjustifikasi itu sebagai sastra Indonesia, yang selalu akan bisa dibantah orang lain ketika memakai seperangkat indikator yang lain juga. Ini memang tidak akan ada habisnya. , Tidak ada wasit yang akan bisa mengakhiri, bahkan kalau nanti H.B. Jassin hidup lagi juga dia tidak bisa gmengatakan “ini yang benar” “ini yang salah”.
Maka, bagi saya harus ada semacam proklamasi untuk mengatakan hanya sampai titik ini persoalan definisi itu dibicarakan setelah ini selesai, kita harus say goodbye, tidak lagi akan berkutat dengan definisi.
Sastra Terjemahan
AVIANTI
Kalau mendengar jawaban dari Pak Manneke berarti sebetulnya hampir bisa bilang bahwa anything goes. Semuanya sebetulnya bisa masuk sampai ada yang bilang tidak ya?
MANNEKE
Karena ada yang memang sangat jelas untuk kita bisa mengatakan “itu bukan”. Misalnya satu karya penulis Kenya, namanya Ngũgĩ wa Thiong’o. Dia menulis dalam bahasa Kikuyu, isinya sangat persoalannya lokal Kenya. Tentu saja kita tidak punya pintu masuk apa pun. Kita tidak punya indikator awal apa pun untuk bisa mengklaim itu sebagai sastra Indonesia kan. Nah, bayangkan satu bulan kemudian muncul terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba kita menjadi punya persentuhan dengan karya itu. Ketika tadinya tidak ada indikator awal, tidak ada pintu masuk sama sekali, sebulan kemudian terjadi dan ada. Maka, kita mestinya bisa luwes, switch. Saya bisa berbicara tentang karya ini dalam kerangka penelitian atau kritik sastra Indonesia, atau yang mau nekad bisa memasukkannya dalam kurikulum program studi Sastra Indonesia.
CEP SUBHAN KM
Menyambung jawaban dari Pak Manneke tadi ya. Jawabannya sebenarnya sudah sangat luas, tapi mungkin kita bisa menariknya ke yang lebih sempit, siapa tahu justru menjadi lebih rumit. Tadi sudah dijelaskan terkait, misalnya, penulisnya adalah orang luar, tapi kalau kita bisa terjemahkan, memungkinkan untuk memasukkannya ke sastra Indonesia. Bagaimana jika misalnya kita masuk ke bagian tentang yang dianggap sebagai sastra daerah? Penulisnya jelas orang Indonesia, bahasanya adalah bahasa daerah, dan tema yang diangkat mestinya lokal juga. Bagaimana nanti irisan antara persoalan bahasa daerah dengan bahasa nasional ini?
MANNEKE
Katakanlah cerpen dalam bahasa Sunda 100% gitu ya, kita tidak bilang ada kosakata-kotakata bahasa Indonesia, 100% dalam bahasa Sunda, kita ambil ekstremnya. Maka, saya akan lebih nyaman dan bagi saya akan lebih jelas untuk mengatakan itu adalah sastra Sunda. Jadi, lagi-lagi saya tidak akan menumpangtindihkannya dengan Indonesia yang merupakan suatu kategori nasional. Ia dipakai untuk kewarganegaraan, dipakai untuk batas-batas kedaulatan, dipakai untuk nama republik. Dalam hal ini kita tidak menumpangtindihkan dengan itu. Dengan mengatakan bahwa ia adalah khazanah sastra Sunda tidak berarti mengatakan ia tidak boleh jadi bagian dari sastra Indonesia. Tapi, bagi saya akan lebih jelas segala-galanya simpel saja mengatakan itu sastra Jawa, sastra Sunda, sastra Bali, yang secara kategori formal nasional masih masuk ke dalam kawasan wilayah Indonesia. Sehingga tidak ada kesulitan bagi orang lain yang mau mengatakan bahwa itu sastra Indonesia.
Bayangkan juga perdebatan sampai sekarang, tentang karya-karya yang ditulis pada tahun 1920-an atau sebelumnya oleh penulis-penulis China peranakan dalam bahasa Melayu rendah, yang dilarang oleh Balai Pustaka. Lebih sulit lagi untuk mengatakan sebagai sastra Indonesia sebetulnya. Indonesianya belum ada, bahasanya juga bukan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang yang sudah dibakukan. Cerita-ceritanya sama sekali tidak membawa misi keindonesiaan seperti STA [Sutan Takdir Alisjahbana], Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin pada tahun-tahun 1930-an. Jadi, apanya yang Indonesia? Bahkan ketika tanah tempat mereka hidup dan menulis pun belum lahir sebagai tanah Indonesia.
Tapi, orang ternyata tidak ada kesulitan untuk menganggap itu sastra Indonesia sekarang. Masih dimasukkan. Karya-karya yang berbahasa Melayu dari Sumatera segala macam itu juga diklaim oleh orang Malaysia sebagai sastra Malaysia, misalnya hikayat-hikayat itu. Jadi, apakah ia punya Malaysia atau punya Indonesia? Kita mau sampai kapan memperdebatkan. Tidak akan punya jawaban yang final gitu, lho. Jadi, bagi saya kita boleh mengklaim itu sebagai sastra Indonesia, orang Malaysia juga boleh mengklaim sebagai sastra Malaysia. Selama kita mengertinya tidak ditumpangtindihkan dengan definisi-definisi formal nasional karena begitu masuk ke kawasan itu kita berantem, terjadi sengketa, rebutan kepemilikan. Konsekuensinya di dalam studi-studi sastra di Indonesia tidak menumbuhkan, tidak mengembangkan, tapi malah mempersempit.
Tokoh-tokoh seperti Chairil Anwar, Idrus, dan yang lain-lain pada tahun 1949, tahun 1950-an sudah tidak lagi mempersoalkan itu. Kebudayaan, seni, sastra Indonesia itu milik dunia. Ia tidak terlepas dari kebudayaan dunia. Kita mewarisinya. Kita mengklaim kepemilikan sastra dunia sebagai milik kita. Itu kan menghapus sama sekali keperluan definisi-definisi. Kalau mau kita tempatkan dalam perspektif sekarang, mungkin orang-orang itu kalau bisa dipanggil dan dihidupkan lagi juga akan menentang betul upaya untuk mereduksi sastra Indonesia dengan membuat lebih banyak pagar.
DEWI
Bapak beberapa kali menyebut soal kurikulum sastra Indonesia. Lalu, mengapa kurikulum sastra Indonesia di perguruan tinggi, yang seharusnya melahirkan pemikiran-pemikiran yang mungkin provokatif atau melampaui tidak menghasilkan itu semua? Seperti itu tadi, karya sastra Kenya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan bisa-bisa saja menjadi milik kita. Sehingga ketika kita menulis tentang sastra Indonesia tidak perlu lagi kita berpaku pada sejarah angkatan. Ada apa sebenarnya dibalik semua ini sehingga sastra Indonesia seolah-olah menjadi sempit, bahkan tidak memasukkan karya-karya sastra terjemahan?
MANNEKE
Karena kurikulum sebenarnya adalah proses politik. Dari kurikulum kita bisa tahu cara program studi Sastra Indonesia mendefinisikan sastra Indonesia dengan melihat yang ia t tolak untuk masuk ke dalam kurikulumnya. Jadi, kalau kita mau lihat definisi formal akademik bahwa sastra Indonesia itu apa, sastra Inggris itu apa, sastra China itu apa, lihatlah struktur kurikulum program-program studi sastra. Dengan melihat yang ia tidak masukkan, maka kita tahu.
Tulisan-tulisan orang China diaspora tidak dimasukkan ke dalam sastra Indonesia karena dianggapnya itu China, sementara sastra China sendiri tidak mau memasukkannya karena dianggap Indonesia. Sampai ada di universitas lain yang harus membuat sendiri program studi sastra diaspora untuk menerima ‘sampah-sampah’ yang tidak dikehendaki oleh yang mainstream-mainstream dan yang mapan-mapan itu. Jadi, universitas itu diam-diam juga sudah lama mendefinisikan batasan-batasannya, oleh orang-orang seperti saya dan Reni yang kesibukannya itu sadar tidak sadar mencoba menetapkan garis-garis kedaulatan sastra lewat kurikulum yang kita buat. Sangat relevan, sangat masuk, tetapi tidak berarti karena ini buatan Program Studi Sastra Indonesia FIB UI [Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya Universitas Indonesia] maka pasti benar dan semua yang lain berarti harus mengadopsi.
Imajinasi akan “Indonesia”
AVIANTI
Lalu, bagaimana kita bisa menghidupkan sastra Indonesia sebagai sastra yang berkembang, bernas, kritis, dan hidup dalam keseharian masyarakat? Karena sebetulnya kan kita hidup dengan bahasa yang secara historis, kultural, geografis, dan lain-lain itu sangat kaya dan beragam. Harusnya itu bisa menjadi modal bukan label yang akhirnya merepotkan kita untuk memasukkan masing-masing ke dalam kotak-kotak.
MANNEKE
Saya punya contoh yang menarik.Kalau kita ingat Supernova-nya Dewi Lestari. Saya lupa yang bagian mana, Petir mungkin ya. Di mana nyaris seluruh setting-nya itu terjadinya di luar Indonesia.
AVIANTI
Di Siem Reap ya?
DEWI
Yang Akar kayaknya ya, Pak? Yang di Kamboja.
MANNEKE
Iya, tapi ada yang sampai ke Segitiga Emas di antara perbatasan Myanmar, Thailand, dan apa gitu ya. Ada yang sampai ke Amerika Selatan, ke Amazon, Ke Brazil sana, gitu.
AVIANTI
Oh, Partikel itu.
MANNEKE
Akar, Petir, ya. Tapi tokoh-tokohnya itu ke mana dia pergi dia bisa fasih berbicara bahasa di tempat itu, orang-orang muda yang ke mana pun mereka berada di tengah hutan Amazon, di tempat yang berbahaya di Segitiga Emas, mereka at home dan bisa mingle dengan siapa pun juga yang ada di situ termasuk dengan orang-orang lokalnya. Ini apanya yang Indonesia selain bahasanya dan selain kewarganegaraan penulisnya? Bagi saya dua indikator awal menjadi tidak terlalu penting. Ketika saya membaca dan mengikutinya, pembaca itu bisa kemudian punya visi yang baru tentang Indonesia harusnya seperti apa. Bagi saya ini layak, sangat layak disebut sebagai karya sastra Indonesia. Bahwa ketika kita membuka jendela dan keluar pergi ke dunia yang lain di dalam karya-karya fiksi itu, Indonesia-nya menjadi diperluas. Visi dan pengertian kita tentang Indonesia-nya itu kemudian menjadi luas.
Sama halnya kalau kita membaca suatu karya tentang Indonesia, tidak dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh orang asing yang bukan orang Indonesia. Tapi dengan membaca itu saya juga punya insight yang baru, imajinasi yang baru tentang Indonesia yang selalu dalam dua proses itu, apakah tadi yang contohnya karya Dewi Lestari, termasuk juga sebetulnya Geni Jora karya Abidah El Khalieqy, yang tokohnya pergi ke banyak negara Afrika Utara dan Timur Tengah. Satu sosok perempuan bergaul dengan banyak bangsa meskipun semuanya Islam. Terjadi suatu perluasan terhadap keindonesiaan. Ditulis orang luar, bukan orang Indonesia sama sekali secara formal nasionalitas, tapi membacanya membuat imajinasi dan visi saya tentang Indonesia menjadi baru atau menjadi diperluas. Bagi saya, itu sangat sah untuk menjadi sastra Indonesia. Bukankah perdebatannya STA dan Sanusi Pane di polemik kebudayaan seperti itu. Indonesia itu harus membentuk dirinya dengan betul-betul menggunakan Barat itu sebagai kiblat kemajuannya atau kita harus melihat ke masa lalu yang zaman keemasan itu sebagai titik tolak untuk membangun Indonesia. Tapi mereka berdua tidak bicara tentang Indonesia sebagai negara, melainkan Indonesia sebagai visi dan imajinasi. Mereka bebas berbicara tentang itu tanpa harus kembali diikat oleh pemikiran “tapi kan kita sekarang masih dijajah Belanda” yang akan menutup semua kemungkinan imajinasi.
Tahun 1930-an kekuasaan kolonial masih sangat mapan-mapannya, tapi polemik kebudayaan sudah terjadi dengan sangat seru. Bicara tentang Indonesia yang dilepaskan dari konteks kesejarahannya yang sempit, dibawa ke level alam pikiran, imajinasi sehingga orang bebas melihat Indonesia yang tradisional atau yang modern. Meskipun masih sedang dijajah dan belum ada bayangan kapan akan merdeka atau dengan cara apa akan merdeka. Kita saat ini kalau bicara tentang sastra Indonesia mestinya bisa mengadopsi cara berpikir orang-orang yang terlibat dalam polemik kebudayaan pada saat itu. Tidak dibatasi oleh nasionalitas, oleh bahasa, melainkan lebih pada pemikiran. Pemikiran yang digali dari tradisi lokal atau pemikiran yang dipinjam, diadopsi dari luar negeri, dari dunia di luar Indonesia. Supaya keindonesiaan itu menjadi lebih jelas di dalam imajinasi banyak orang yang masih terjajah bahkan pada saat itu
CEP
Kalau mendengarkan penjelasan barusan itu sepertinya sastra kontekstual misalnya, kita kembali ke lokalitas di satu dekade ke belakang, itu sepertinya bagian yang sehat dari perkembangan sastra dan kebudayaan kita. Tetapi mungkin tidak kalau kita melihat itu dari sudut pandang lain? Misalnya ada kecenderungan ketika kita ingin mengangkat lokalitas atau tradisi, tapi di sisi lain ada restriksi untuk memasukkan hal-hal yang datang dari luar untuk kita kategorikan sebagai asal Indonesia, seperti, misalnya, karya terjemahan. Mungkin tidak kita melihat ada reaksi seperti itu? Artinya meskipun di satu sisi itu merupakan sesuatu yang sehat, tapi di sisi lain akan menjadi hambatan juga untuk berpikir kosmopolit seperti Chairil dan kawan-kawannya tadi.
MANNEKE
Iya, kalau kita melihat kosmopolitanisme itu sebagai atau di dalam dikotomi dengan lokalitas. Tapi, kalau kita membayangkan lokalitas itu adalah bagian dari dunia yang kosmopolit, maka kita tidak punya masalah untuk melihat atau menganggap sama seperti cara berpikirnya Kelompok Gelanggang. Ada dari dunia, the best that the world has produced yang kita serap, kita ambil, tetapi di dalam kita racik sendiri dengan yang kita miliki secara lokal. Hasil racikannya kemudian kita kasih label “made in Indonesia” yang pada gilirannya menjadi sumbangan bagi kebudayaan atau sastra dunia. Dan saya melihat pola ini, itu sudah terjadi sejak abad pertama. Ketika kita dengan sangat luwes, mudah, dan cepat menyerap Hinduisme, Buddhisme, bertahan sampai sekian ratus tahun, disatukan dengan unsur-unsur animisme dan dinamisme yang sudah ada sebelum Hinduisme dan Buddhisme. Islam masuk diserap dengan cukup relatif mudah, berbaur dengan unsur-unsur menjadi sinkretik dengan Hinduisme, Buddhisme, dan bahkan dengan animisme dan dinamisme.
Ketika modernitas Barat masuk, kita juga tidak punya kesulitan. Jadi, kita punya strategi itu sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris itu lebih mudah untuk bikin otak-atik gathuk-nya ya, ada Tiga A: adopt, kita mengambil, kita serap; yang kedua itu adapt, kita adaptasikan, kita adjust dengan yang kita miliki, dijadikan gado-gado, McDonald’s tapi rendang misalnya. Kemudian, kita appropriate, kita bilang ini made in Indonesia. Kita tidak punya kesulitan untuk mengatakan wayang itu kebudayaan asli Indonesia. Meskipun bahan materi ceritanya adalah bukan Indonesia dalam artian animisme dan dinamisme. Tapi, kalau kita menganggap era Hindu-Buddha itu adalah Indonesia, maka iya ia adalah budaya Indonesia.
Jadi, perspektif ini ada secara historis sekian ratus tahun terjadidi dalam proses-proses pembentukan kebudayaan yang sekarang kita sebut sebagai kebudayaan Indonesia itu dan di sastra itu juga terjadi. Tapi, saya tidak tahu persisnya kapan orang mulai resah lalu membuat garis pembatas itu. Membuat genealoginya kapan, asal-muasalnya yang pertama itu kapan? Mulailah mencari-cari apakah Balai Pustaka atau era Melayu rendah China peranakan atau setelah kemerdekaan karena namanya Indonesia dan segala macam. Tapi saya mau memahami sastra Indonesia yang melalui tiga proses itu; mengadopsi, mengadaptasi, dan mengapropriasi.
Di dalam hal itu, maka yang lokal maupun yang kosmopolit, yang terjemahan ataupun yang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa Indonesia, mereka semua ada dalam tiga proses itu. Dan kita boleh dengan yakin dan dengan legal tetap mengatakan itu adalah sastra Indonesia. Cikal bakalnya sudah ada, benih berproses seperti itunya sudah ada, bukan sesuatu yang harus kita ciptakan sekarang demi merespons globalisasi atau demi merespons munculnya fenomena diaspora atau demi merespons kecenderungan kosmopolitan. Tidak. Sudah dari dulu, dari abad pertama yang kita punya rekamannya dalam prasasti-prasasti dan naskah-naskah itu. Itu sama persis seperti yang terjadi sekarang, tapi minus teknologi, itu saja. Teknologi yang mempercepat terjadinya perjumpaan ini, teknologi komunikasi, teknologi internet. Dulu terjadinya berabad-abad dan sekarang terjadinya bisa dengan sangat cepat dan mungkin itu kemudian menggelisahkan orang karena kealamiahannya itu tidak terjadi dan karena tidak alamiah ia datang seperti sebagai suatu yang shocking orang jadi resah.
AVIANTI
Oke, ini mau konfirmasi saja tentang apropriasi. Jangan-jangan keinginan untuk mengindonesiakan atau menentukan identitas sastra Indonesia adalah semacam kepentingan untuk bisa muncul di peta sastra dunia yang sudah terlanjur dikuasai oleh sastra global yang adalah utara global, lengkap dengan ukuran dan teori-teorinya. Karena itu, kita harus tahu siapa kita sebelum bisa ada di dalam peta tersebut. Tapi apakah perlu kita, paling tidak, punya semacam “currency” sendiri dalam bentuk, katakanlah, misalnya teori sastra yang kita produksi sendiri dari lanskap sastra kita sendiri untuk bisa bertukar, bertransaksi di dalam skala global tersebut?
MANNEKE
Yang dijelaskan oleh Avi itu tadi adalah cara yang progresif di dalam upaya mengerti fenomenanya. Tetapi, hal yang sama itu juga bisa terjadi dan dimengerti dari cara yang sangat konservatif. Bahwa ambisi atau kegelisahan yang terlalu besar sekarang ini untuk membuat sastra Indonesia yang lebih punya patokan jelas itu bisa-bisa juga seperti Fadli Zon, gitu lho. Coba lihat kembali, dia mau mencari dengan agak memaksa bukti yang kemudian dia bisa pakai untuk mengatakan bahwa peradaban tertua itu adalah peradaban di Indonesia. Makanya tiba-tiba Gunung Padang hidup lagi, tiba-tiba mau adu tua-tuaan, ketemu tulang yang paling tua itu di Maros, Sulawesi Selatan atau di Filipina, misalnya. Menurut saya itu lebih karena tidak punya kepercayaan diri, bukan karena kegairahan untuk menjadi bagian dari kebudayaan dunia, tetapi karena tidak percaya diri, seolah-olah tidak punya apa-apa, jadi harus mengada-ngadakan.
Itu bukan adopsi, bukan adaptasi, bukan apropriasi, itu ngarang, mengarang bebas. Dan saya lihat itu terjadi gitu, bahwa kita seolah-olah harus yang tertua, yang terutama, yang pertama, yang duluan, khususnya dalam bidang kebudayaan, sejak ada menteri yang ini. Jadi, bahwa kita ingin berpartisipasi dalam kancah yang lebih global dengan menampilkan warna yang lebih jelas dari diri kita sendiri, keinginan itu bisa kita mengerti. Namun, kejelasan itu bagaimana caranya menjelaskannya, memang ini suatu hal yang harus kita pikirkan kembali: apakah untuk itu dituntut adanya parameter yang jelas. Apakah untuk berpartisipasi dan diakuidalam kancah yang global kita mesti betul-betul punya pembeda yang sangat jelas tentang kita itu siapa? Saya yakin orang-orang seperti Chairil dan angkatannya dulu punya pemikiran kalau itu bukan titik tolaknya dia. Titik tolaknya dia adalah ketika kita membuka mata kita, keluar dan melihat dan menemukan banyak hal. Maka, bagaimana ke dalam itu justru menjadi kuat, bukan menguatkan diri di dalam supaya bisa percaya diri ketika bareng-bareng dengan kebudayaan-kebudayaan di dunia yang lain di luar. Tetapi, bagaimana ketika kita melihat dan membuka mata kita keluar, maka ke dalam itu kita bisa menjadi jauh lebih kaya dan melampaui batas-batas yang sesungguhnya, kita terdorong untuk bangun sendiri.
Jadi, ada dua forces yang saling berbenturan sebetulnya. Kita itu mau “berperang” dengan cara menjadi kuat karena kita melihat yang terjadi di luar dan terinspirasi oleh itu, atau, kita mau menjadi kuat duluan di dalam dengan membuat perisai, ketopong, baju zirah supaya ketika keluar kita kemudian siap berhadapan dengan dunia. Ternyata ketika kita keluar dengan berbagai macam perlengkapan perang seperti itu, ternyata dunianya santai-santai saja, tidak sedang dalam keadaan siap berperang, gitu lho. Lalu mereka melihat kita jadi melongo, ini ada perang di mana? Musuhnya siapa? Sangat kelihatan, lho.
Kita lihat saja di YouTube, begitu ada sesuatu yang membanggakan tentang Indonesia, itu komentar di dalam chat-nya itu bisa sangat nasionalis yang berlebih-lebihan, yang kadang-kadang kita sendiri jadi malu. . Selalu tiba-tiba kebesaran diri itu yang dimunculkan, tapi apakah itu strategi untuk menjadi bagian dari dunia? Menurut saya tidak. Apakah cara itu akan berhasil? Ada bukti sejarah tidak, suatu kekuatan yang besar tampil di dunia dengan cara itu, lalu dia bisa betul-betul tetap unggul dan tidak tersentuh oleh yang lain-lain?
Ambil saja bahasa Inggris. Karena kekuasaan imperialisnya itu mengglobal, bahasa Inggris dipakai di mana-mana. Orang-orang yang konservatif yang mau mempertahankan bahasa Inggris itu sangat marah ketika tiba-tiba bahasa Inggris itu dimasuki macam-macam kosakata dari berbagai bangsa yang pernah dijajah dan mereka tidak pernah bisa melakukan apa-apa untuk menyetop itu. Jadi, konsekuensi dari menjadi besar itu ternyata dengan menerima yang kecil-kecil yang lain, tidak dengan menutup pintu. Di dalam sejarah Tiongkok, ketika Mongol menguasai China, saat Dinasti Yuan, bukan kebudayaan China yang terserap ke dalam kebudayaan Mongol, tapi orang-orang Mongol yang kemudian dicinakanselama sekian ratus tahun. Jadi, konsekuensi menjadi besar atau kehendak menjadi besar itu justru adalah dengan membiarkan yang kecil-kecil itu masuk. Tidak menutup pintu dan membayangkan di luar akan berhadapan dengan gajah-gajah besar yang lain yang mungkin semuanya itu mau merendahkan kita atau mau melemahkan kita. Sastra itu sebetulnya bisa menawarkan antidote bagi penyakit-penyakit megalomania seperti yang sekarang dialami oleh Fadli Zon dan kawan-kawannya: Harus nomor satu, harus yang duluan, harus yang tertua, harus yang terbesar, apa-apa mau cari yang terbesar, tertua, terdahulu, gitu.
AVIANTI
Kalau di musik sebetulnya jauh lebih santai ya, dalam arti para pemusik di Indonesia bisa jadi tidak terlalu memikirkan apa itu musik Indonesia dan sebagainya. Lalu keluarlah Tabola Bale dan itu viral sampai ke mana-mana dan itu kan sudah bisa dibilang “penaklukan” kecil kepada dunia musik global. Nah, kalau di sastra ada contohnya tidak? Atau sesuatu dari sejarah sastra kita yang tidak terlalu panjang yang bisa kita jadikan inspirasi?
MANNEKE
Mungkin tidak, ya. Karena literasi kita juga tidak setua tradisi orang bernyanyi. Bahkan di awalnya itu puisi pun dinyanyikan, oleh orang yang profesinya pelipur lara kan, ya. Storyteller yang berceritanya tidak ngomong, tapi nyanyi. Jadi, barangkali interaksi kita dengan tulisan itu masih tidak setua musik. Saya ingat pernah tiba-tiba musik reggae dijadikan koplo. Dan orang tidak ada masalah untuk mengerti bahwa itu reggae, tapi bahwa itu adalah Indonesia. Itu memang lebih disikapi tanpa berantem, tanpa orang harus berbusa-busa dan terengah-engah untuk saling berbantahan seperti yang terjadi di sastra mungkin ya.
Jadi, apakah karena tradisi tulis kita relatif lebih muda, saya tidak tahu, tapi rasanya memang belum ada contohnya. Dan akhirnya yang berusaha diangkat-angkat untuk dijadikan seperti itu tapi dengan keberhasilan yang relatif. Misalnya, La Galigo, mau dikolosalkan, ditulis kembali dengan bahasa yang lebih modern, ditransformasikan menjadi seni pertunjukan, menjadi musik. Tapi kita tidak melihat gaungnya seperti yang terjadi pada musik. Di dalam penerjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa-bahasa asing pun kita masih jauh ketinggalan dari sastra-sastra Afrika yang pernah menjadi jajahannya Prancis, jajahannya Inggris. Saman sudah banyak diterjemahkan dalam banyak bahasa, tapi gaungnya juga tidak sebesar Arundhati Roy, tidak sebesar pengarang-pengarang yang lain yang tidak menulis dalam bahasa Inggris yang lalu diterjemahkan atau menulis dari bahasa Inggris di negaranya sendiri lalu diklaim sebagai bagian dari khazanah sastra Inggris.
Kadang-kadang persoalannya itu bukan karena kualitas atau karena apa, karena mungkin apesnya aja kita tradisinya itu memang sama Belanda. Kalau sama Inggris mungkin kita sudah masuk Penguin Books, kita masuk mana gitu ya, tapi karena sama Belanda, kita tidak beredar. Sementara kita tahu yang India, Singapura, bahkan Malaysia pun lebih beredar. Apakah itu karena ada hubungannya dengan penjajahan atau tidak? Memang ada banyak kemungkinan, ada banyak pemikiran sekarang yang harus dieksplorasi lebih jauh penyebabnya apa. Tapi, saya sangat tidak percaya bahwa itu karena kualitas.
Memang yang bisa masuk ke industri penerbitan internasional besar itu ternyata ada politiknya juga. Sama halnya dengan Vietnam dan Thailand. Filipina lebih karena dalam bahasa Inggris, sementara yang dalam bahasa Spanyol tidak seberuntung yang dalam bahasa Inggris. Kecuali Noli Me Tángere karya José Rizal, itu pun karena dianggap, dipakai sebagai alat perjuangan, maka dia terangkat statusnya. Tidak sekadar sastra, tapi juga sebagai deklarasi perlawanan terhadap penjajahan.
DEWI
Saya tertarik dengan kata-kata Mbak Vivi [Avianti Armand] ya, soal kalau musik kok kayaknya lebih rileks gitu ya. Saya juga melihat kalau tadi Pak Manneke kurang-lebih mengatakan anything goes y. asalkan emosi pembaca bisa relate, bahwa itu Indonesia. Tapi saya merasa fenomena di sastra sekarang kayaknya malah yang ditekankan lokalitas. Walaupun ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi kayak ada unsur bahwa oh yang disebut Indonesia itu “pusat” misalnya atau Jakarta biasanya, sehingga yang meledak atau bahkan menjadi majority sekarang adalah yang justru menekankan lokalitas.
MANNEKE
Yang menang-menang lomba, ya?
DEWI
Betul. Walaupun sebenarnya kita ingin kalau kosmopolit in a real sense ya, artinya yang lokal dibawa, yang dari luar dibawa. Itu yang saya tangkap dari jawaban-jawaban Bapak Tapi ini seolah-olah dari dalam pun ada pertentangan. Sementara yang kosmopolit itu kayak akhirnya sekarang jadi seperti di-judge ya, “oh ini elit” lah “kamu punya privilege” lah apalah. Bapak sendiri ada tanggapan tidak terhadap hal ini? Seharusnya kita bisa merangkul semua, tapi kok sekarang dari dalam seperti mau dipisah lagi.
MANNEKE
Itu sebetulnya ulah kritikusnya, Ren, karena karya-karya yang kita baca yang sangat kembali ke lokalitas itu mereka tidak menolak modernitas, lho. Mereka tidak menolak Barat, tidak menolak asing. Sama seperti halnya karya-karya yang sangat kosmopolit di mana tokoh-tokohnya dan setting-nya terjadi di banyak tempat di luar itu juga tidak menolak lokalitas. Jadi, tidak ada di dalam karya-karya itu dilema atau pertentangan yang sangat tajam, karena novel saya mau mengusung lokalitas, maka saya harus menunjukkan hal-hal yang rendah dan jelek dan negatif tentang kosmopolitan. Itu kan tidak terjadi.
Walaupun pernah ada polemik tentang itu, tetapi yang berpolemik pun itu tidak kemudian mengambil posisi-posisi dikotomis ketika kita membaca karya-karyanya. Jadi, karya-karyanya itu menyikapi the other sebagai yang harus disingkirkan atau ditolak, tapi bahwa dia ingin bicara tentang yang lokal itu jelas, tanpa harus ada rasa permusuhan atau penolakan atau kebencian. Tapi, begitu ke tangan kritikus, seolah-olah kemudian ada gerakan untuk menolak yang kosmopolitan. Dulu, waktu keluar gerakan-gerakan sastra pedalaman dan sastra kepulauan memang ada deklarasi bahwa ini adalah reaksi terhadap Jakarta-sentrisme, terhadap Utan Kayu, Salihara, segala macam Dan itu dinyatakan secara eksplisit, maka orang sengaja itu menulis tentang pulau, tentang laut, tentang desa, dengan akibat apa? Gerakan-gerakan itu ada, tapi kita tidak melihat karya luar biasa yang dihasilkan. Kecuali, bahwa untuk menolak Jakarta harus pakai laut, untuk menolak Jakarta harus pakai pulau, dan menonjolkan segala macam kosakata yang kemudian penuh dengan catatan kaki di bawahnya. Tapi, itu dilakukan dengan sengaja untuk melawan Jakarta.
Nah, dalam 10 terakhir, atau mungkin hanya 5btahun terakhir, kita mulai lihat lebih banyak lagi setting desa, tradisi dikeluarkan lagi, tanpa kepahitan. Tidak ada deklarasi bahwa kami melakukan ini untuk melawan kosmopolitanisme, untuk melawan globalisasi. Saya bisa melihat sisi Indonesia yang lain tanpa kemudian merasa bahwa kalau saya mau menerima itu sebagai keindonesiaan, saya harus menolak yang satunya lagi. Ini tidak terjadi. Entah karena ia belum menjadi gerakan, karena begitu menjadi gerakan ia akan menjadi lebih ekstrem suaranya. Atau karena ya ia bagian dari proses yang memang terjadi secara berbeda pada saat yang sama dengan proses-proses yang lain.
Ada kemunculan karya-karya yang lalu oleh para kritikus diberi label “sastra wangi”, “sastra kelamin” atau sastra apa. Pada saat yang sama kita juga melihat kemunculan dalam skala yang masif sastra-sastra yang berorientasi pada keislaman, ya. Ditulis oleh Helvy Tiana Rosa dan kawan-kawan, Asma Nadia, macam-macam gitu, ya. Ada, tetapi tidak kemudian itu menjadi dua kubu, kecuali di dalam analisis para kritikus yang memang kemudian mau mendramatisir. , Di dalam kenyataannya tidak, lebih longgar seperti di-mixed sebetulnya, ya. Jadi, koeksistensi, ada ini, ada ini, ada ini, di Gramedia semua dikasih tempat.
Yang terjadi justru yang penulis-penulis dengan latar belakang Islam ini yang jauh lebih semangat menulis, hasilnya banyak, sementara yang di sisi satu lagi, seperti Nukila Amal, nunggu tiga, empat tahun sekali kita baru melihat ada karya baru. Maka, jumlahnya lebih sedikit, kritikus nanti menafsirkan “wah, ini mulai terlindas” atau “ter-ini oleh yang Islamis”. Ya, boleh saja, namanya kritik. Tapi, kadang-kadang yang menyebabkan persoalan menjadi ruwet itu ya kita, kritikus, bukan sastrawannya.
Estetis alih-alih Politis
AVIANTI
Dalam Tengara edisi sebelumnya kami membahas tentang kanon sastra, garis besarnya kami mengakui bahwa perlu ada rujukan sebagai titik berangkat untuk membahas tentang Sastra Indonesia. Sudah ada banyak upaya untuk menyusun rujukan tersebut, mulai dari yang berdasarkan angkatan yang sangat politis. Kemudian, sempat ada proyek Pusaka Sastra, sampai terakhir yang bermasalah, yaitu Sastra Masuk Kurikulum n. Apakah Pak Manneke setuju bahwa kita perlu punya semacam daftar rujukan dari berbagai perspektif, gender, lingkungan, geografis, etnis, dan lain-lain, yang bisa kita jadikan awal untuk kita bisa mulai berdiskusi tentang sastra Indonesia?
MANNEKE
Nomor satu, sebelum masuk ke jawaban yang lebih dalam, kanon itu politis. Dan itu betul-betul suatu agenda politik, tetapi masuk lewat akademik. Bahwa ia mau mengatakan ini adalah identitas nasional kita, itu lewat kanon. Dan, begitu masuk ke situ, proyeknya adalah suatu proyek politik, bukan lagi kultural atau literary gitu. Kalau saya, lebih baik kita membuang banyak tenaga dan waktu justru untuk mengkritisi persoalan angkatan-angkatan yang sekarang kadung menjadi mapan. Bahwa ada Balai Pustaka, ada Pujangga Baru, ada kemudian angkatan 45, ada angkatan 66,, ada angkatan Reformasi, itu semua yang menurut saya menciptakan kekacauan luar biasa di dalam pendidikan sastra maupun di dalam cara kita memahami sastra Indonesia.
Kalau kita melihat bagaimana cara rujukan itu dibentuk dalam sejarah Sastra Barat, . ia tidak melihat siapa yang sedang menjadi raja, sedang ada peristiwa politik apa. Tetapi, mereka betul-betul melihat perubahan bentuk, visi, misalnya dari Neo-Klasik berubah jadi Romantis. Mereka dulu menggunakan kejayaan Romawi Yunani klasik sebagai rujukan kesempurnaan seni, maka menghasilkan era Neo-Klasik yang sekian ratus tahun. Tetapi, kemudian ada pemberontakan, bahwa kita harus mengutamakan emosi, individualitas, kedekatan perasaan manusia dengan alam karena punya insting yang sama asal muasalnya, maka tiba-tiba yang sangat ketat, sangat dikotomi itu ditinggal, dan orang kemudian bergeser ke Romantisisme. Jadi, ada movement, bukan politis, tetapi estetik.
Nah, kita tidak sering melihat pergerakan dan perubahan supaya punya acuan untuk bicara tentang sastra Indonesia, yang estetik, bukan politik, tanpa harus dikaitkan dengan Tritura, dengan pemberontakan, revolusi melawan Belanda., Orang-orang tahunya posisinya Chairil, Idrus, itu anti kolaborasi dengan Jepang, dengan Belanda, berseberangan dengan Sukarno. Tetapi, ketika kita melihat pikirannya, bahkan sampai sekarang kita menuduh Chairil melakukan plagiat, kan. Mengambil begitu saja dengan cara yang seolah-olah vulgar, apa yang berasal dari asing, apa yang berasal dari luar. Nah, jadi kalau kita bisa mempelajari kembali itu semua dengan perspektif yang tidak politis, tetapi perspektif yang sungguh-sungguh estetis, apa ya betul terjadi perubahan nyata antara angkatan 45 dan angkatan 66 sehingga harus dibedakan. Apakah betul antara tahun 1966 sampai 1998 itu tidak tumbuh gerakan apapun yang kemudian layak untuk diberi nama angkatan, misalnya. Ini yang bagi saya PR besar yang masih berantakan, dan nggak ada yang beresin, gitu. Jadi, mengkritisi, melihat kembali bangunan angkatan-angkatan yang sudah kadung menjadi mapan itu, untuk menunjukkan bahwa ia tidak bisa lagi bekerja dengan baik untuk menjelaskan sastra Indonesia, dan apa yang harus kita ubah dan harus kita tambah, supaya rujukan itu terbentuk yang baru, tidak dengan yang ada sekarang.
Jadi, bukan soal apakah dia China peranakan atau nggak, apakah dia pakai bahasa apa. Yang harus kita cari adalah ada tidaknya gerakan yang kemudian melahirkan suatu estetika baru yang menjadi dominan dalam suatu periode, meskipun nanti tergantikan oleh yang lain.Kalau mau kita kerjakan, itu akan jadi sumbangan yang besar bagi pengetahuan tentang sastra Indonesia. Bisa mempengaruhi cara orang memahami kurikulum, bisa mempengaruhi cara orang memahami persoalan-persoalan seperti terjemahan, diaspora, dan yang lain-lain.
Kalau kita lihat bukunya Keith Foulcher yang Clearing a Space, itu kan dia bahkan mengatakan sebetulnya tradisinya itu mulai ketika pengarang-pengarang, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia itu menyadur karya-karya besar Eropa, seperti The Count of Monte Cristo, disadur dengan cara dipotong-potong sederhana, jadi bacaan yang sangat populer ketika di Eropa statusnya sudah terangkat sebagai kanon. Dan, itulah yang sebetulnya memperkenalkan kita pada prosa modern di dalam pengertian Barat. Itu terjadinya bahkan sebelum Balai Pustaka, terjadinya bersamaan dengan waktu yang Ibnu Wahyudi sebut lahirnya karya-karya Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu rendah.
Ada orang yang pernah meneliti itu, tapi kita tidak pernah melihat peran atau fungsi dari penelitian karya-karya saduran yang sempat membanjir itu di dalam pembentukan sastra Indonesia, padahal ia membentuk movement, membentuk suatu gerakan estetika. Nggak 100% kita yang lahirkan, karena kan saduran terhadap karya luar. Tapi, kapan kita pernah melahirkan yang 100%? Pengarang besar, Chairil Anwar pun juga menyadur. Dalam penelitian Subagio Sastrowardoyo, Rendra itu meniru karya dramanya Federico Garcia Lorca hampir dengan sangat vulgar. Bagi saya Kelompok Gelanggang itu menyadari betul bahwa ia harus menyerap dan meminjam. Inovasi kita di situ. Kita bukan inventor, tapi kita inovator, ngambil-ngambil yang tidak ada hubungannya, disatu-satukan, koplo-reggae, jadi apa gitu ya, kan. Dan itu membuat kita jadi inovatif, tetapi kita bukan orang yang menciptakan dari nol .
AVIANTI
Betul, betul. Garis bawahnya adalah rujukan dengan basis estetika yang punya kontribusi dalam pembentukan sastra Indonesia itu yang harus kita upayakan ya.
MANNEKE
Sesuatu yang sudah lazim di dalam disiplin ilmu sastra di Barat, tetapi tidak pernah kita tengok dan kita lakukan di sini. Kita masih tergantung peristiwa. Angkatan 1998 karena ada reformasi, padahal 32 tahun Soeharto itu banyak lho gerakan-gerakan ke arah estetika.
AVIANTI
Misalnya?
MANNEKE
Termasuk fiksi-fiksi para perempuan yang punya gaya sendiri, punya cara sendiri untuk membangun narasinya, punya strategi deskripsinya sendiri, pengalaman suasana kebatinan tokoh. Mungkin setelah itu kita tidak temui lagi penggalian yang sedalam itu, walaupun dikritik sebagai yang terlalu domestik, terlalu apolitis. Tetapi, memang, estetik itu tidak harus selalu sangat politis, kan, bisa saja betul-betul menjadi suatu proses yang otonom. Sebelumnya lagi, tahun 1970-an awal itu kan ada juga gerakan puisi mbeling, yang secara terang-terangan memberontak kepada Sapardi Djoko Damono dan sebagainya itu. Ada kemudian mazhab-mazhab Rawamangun, mazhab Salatiga, gitu. Ia cuman seolah-olah numpang lewat, tapi kritikus sastra nggak pernah memperhatikan periode Orde Baru itu secara lebih serius, dianggapnya karena represif, tidak ada apa-apa yang luar biasa gitu, padahal banyak sekali terjadi gitu, di dalam periode 32 tahun itu, tapi cuman satu dua halaman kadang-kadang di buku-buku sastra. Itu Mangunwijaya segala menulis tentang masa kini, tetapi kembali ke zaman Roro Mendut segala macam gitu kan.
AVIANTI
Kita sudah terlanjur terkooptasi dengan “Indonesia” sebagai aspek politis, sehingga kalau kita bicara tentang sastra Indonesia, basis pemikiran itu masih tetap ada dan ternyata susah keluar dari situ.
DEWI
Memang harus didekonstruksi mindset berpikir soal sastra Indonesia.
AVIANTI
Tapi, kenapa kok di musik tidak terjadi hal seperti ini? Kenapa kok di musik tuh orang santai sekali. Dan, justru dengan kesantaian itu, tiba-tiba kita bisa mencuat dan mempunyai nilai tukar di kancah global. Rasanya, tari juga begitu, ya. Kayaknya, sastra aja nih yang agak kebanyakan mikir kali, ya.
CEP
Kebanyakan berantem.
MANNEKE
Kebanyakan orang pinter.
DEWI
Salah kritikus itu memang.
AVIANTI
Ada fenomena yang cukup menarik, Pak Manneke. Kalau kita lihat, belakangan ini, mulai ada anak-anak muda yang membuat puisi dengan bahasa sehari-hari, sesuatu yang tadinya tuh kayak diharamkan. Bukan hanya oleh garis koridor puisi lirisisme, tapi juga penggunaan diksinya. Yang terakhir seperti misalnya Hamzah [Muhammad], atau sebelumnya, Berto Tukan yang membuat kumpulan puisi judulnya Aku Mengenangmu dengan Pening yang Butuh Panadol. Hamzah belum lama mengeluarkan suatu buku puisi yang bahasanya betul-betul sehari-hari, atau yang terakhir yang cukup mutakhir itu,
Cyntha [Hariadi] itu yang menggunakan kosakata-kosakata yang bahasanya orang China Glodok, yang sebenarnya kalau kita cari di puisi-puisi sebelumnya, puisi-puisi koran Tempo ataupun koran Kompas itu tidak ada. Apakah ini sebetulnya sudah menjadi jalan yang “benar”atau gejala-gejala untuk merengkuh sastra ke dalam percakapan sehari-hari? Apakah ini nantinya bisa berkembang menjadi sesuatu yang Indonesia, dengan sangat rileks, gitu?
MANNEKE
Kita memang masih harus melihat. Kasih waktu lagi ke depan. Jadi, memang selalu dalam proses kebudayaan itu akan muncul, istilahnya itu emerging. Ya, tunas-tunas baru yang membedakan diri dari yang dominan dengan perkiraan, kalau melihat penulisan sejarah di mana-mana, salah satunya itu akan bisa kemudian nantinya menggantikan yang sekarang dominan. Yang sekarang dominan kemudian menjadi apa yang disebut sebagai residual, tersisih gitu ya, tapi tidak lagi menjadi dalam bentuk yang dominan.
Nah, ini, nyaris sama, ibaratnya, ada sekian miliar sperma, tapi akhirnya yang bisa ya cuma satu, gitu. Nah, apakah yang satu itu adalah yang sekarang yang sedang muncul, ataukah bukan, atau nanti ada yang lain lagi, itu kita harus memberi waktu yang cukup. Rata-rata, kalau kita melihat gerakan-gerakan sejarah estetika di Eropa, itu paling tidak perlu waktu satu abad, untuk kemudian orang bisa melihat kembali, iya, ada satu kecenderungan yang bertahan hampir selama 100 tahun atau sekitar 80 tahun. Dan, pada saat dia masih dominan, sudah muncul bibit-bibitnya yang baru, yang nanti akan menggantikan. Ketika Romantisisme sedang di akhir puncak-puncaknya, kemudian kita sudah bisa melihat karya-karya yang lebih realistis, yang lebih realis, yang meninggalkan pakem romantik itu, ketika era romantik itu masih berjaya.
Jadi, kalau kita mau lihat, memang kapan persisnya batas pergantiannya tidak ada. Jadi, ketika sekarang sedang ada sesuatu yang dominan, itu akan muncul macam-macam yang lain, seringkali tidak selalu kita tangkap dengan radar kita, tapi kemudian dengan proses yang agak organik, tidak dikebut. Tapi, kalau saya melihat fenomena yang di Wattpad itu. Fenomena Wattpad itu kan orang-orang muda itu nulis fiksi dengan caranya yang seenak-enaknya. Plotnya itu mereka bikin, walaupun katanya menjiplak, tetapi bisa dibikin seliar mungkin, tanpa ada mengenakan parameter-parameter atau batasan-batasan pada dirinya sendiri. Superhero itu bisa bertemu tokoh-tokoh dari K-Pop, masuk dalam petualangan bersama, jatuh cinta di dalam cerita itu. Itu kan gila, ya. Dan, kalau kita lihat Wattpad itu puluhan ribu, tapi seringkali tidak tertangkap oleh kita di media mainstream karena dia medan operasinya di dunia digital di sana. Kemudian sutradara film juga cari naskah di situ, terjadi transaksi di situ. Orang yang asyik membaca karya orang lain, pada saat yang sama juga penulis, yang juga menerbitkan karyanya di situ.
Bagi saya, itu suatu gejala yang pelan-pelan mengambil alih yang dominan, tapi tidak selalu kita sadari bahwa itu terjadi, karena ia terjadinya di arena digital. Dan, kita masih belum bergerak di area itu sebagai kritik sastra. Tapi, kalau lihat kuantitasnya mengerikan sekali, puluhan ribu, yang baca itu juga ribuan, ketika penyair-penyair besar, ketika penyair-penyair besar, dulu saya ingat Pak Sapardi Djoko Damono bilang, “Wah, puisi saya itu kalau setahun bisa laku 1000 aja sudah keajaiban.” Begitu kita lihat Wattpad, pembacanya ribuan Kita kan bisa langsung lihat pembacanya berapa gitu ya, kemudian yang beli berapa. Dan, tidak terjadi yang namanya krisis literasi, minat baca yang sekarat, sedang berada antara hidup dan mati. Tidak. Di situ terjadi sangat luar biasa, sangat intense, tetapi mungkin tidak dianggap literasi, dianggap sebagai anti-literasi, seperti karya-karya yang di luar Balai Pustaka dulu, tidak dilihat, padahal jumlahnya sangat banyak. Lalu, ketika orang membuat Angkatan Balai Pustaka yang dibahas yang sedikit yang berhasil lolos dari sensor kolonial, tapi yang ratusan atau mungkin ribuan di luar itu tidak masuk radar sama sekali. Sehingga angkatan itu tidak bisa dikatakan mewakili keseluruhan fenomena sastra di Indonesia sebetulnya.
Saya selalu takjub setiap melihat Wattpad, sekali-sekali saya masih lihat itu.Ada selebriti-selebritinya sendiri, penulis-penulis yang berhasil sukses, dan yang punya fans yang ribuan itu ada. Jadi, fanbase, fandom, fan culture itu terjadi di situ. Waktu zaman Rendra, yang beli bukunya nggak ada, cuma senang melihat Rendra jerit-jerit di tempat terbuka saja.
CEP
Terima kasih, Pak Manneke.
tengara.id
tengara.id adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas karya sastra Indonesia melalui pembacaan, pembedahan, dan penilaian yang dilakukan dengan landasan argumen dan teori yang bermutu.