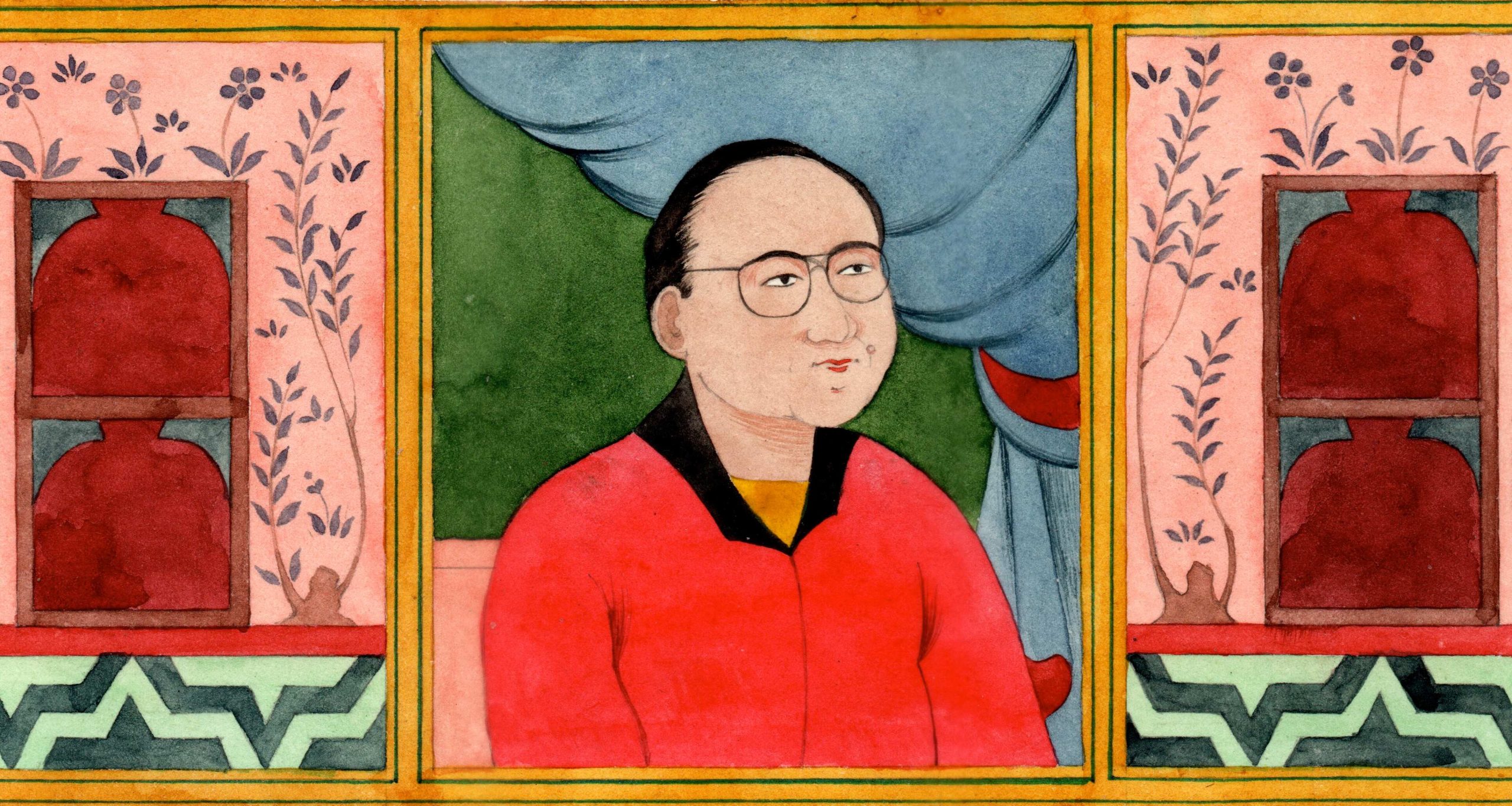Anatomi Intuisi dan Narasi dalam Kerja Kritik H.B. Jassin
Tulisan ini berupaya mengungkap karakter kerja kritik sastra H.B. Jassin, mengidentifikasi bagaimana relasi antara definisi kritik sastra yang dipegang teguh oleh Jassin dengan kerja kritiknya serta, jika memungkinkan, membuat semacam kritik atas kritik yang telah dibuatnya. Pembahasan hal-hal tersebut akan dikaitkan pula dengan kondisi kekinian kritik sastra. Di luar soal tersebut, tulisan ini juga akan menyinggung bagaimana trajektori Jassin sehingga mendapatkan banyak gelar, seperti Paus Sastra Indonesia dan Pembela (/advokat) Sastra Indonesia.
Intuisi sebagai Dasar
Ada dua cara untuk mengetahui karakter kerja kritik sastra H.B. Jassin. Pertama, dengan memahami bagaimana ia merumuskan kritik sastra. Kedua, dengan mencermati kecenderungan umum hasil kerja kritiknya dalam mengkaji sastra Indonesia. Bagian ini akan fokus pada cara pertama, sementara cara kedua akan dipecah pada bagian-bagian berikutnya.
Membaca “Esai dan Studi” dalam Tifa Penyair dan Daerahnya (1952) memunculkan kebingungan. Pada awalnya, Jassin hendak menguraikan perbedaan antara esai dan studi (selanjutnya akan ditulis “kajian”) dengan menunjukkan gaya dan dasar penulisan keduanya. Namun, pada bagian akhir ia justru menyatakan kalau esai adalah kajian juga. Apa yang menentukan sebuah tulisan disebut esai atau kajian adalah sikap jiwa penulisnya: esai selalu subjektif, sedangkan kajian objektif. Sebelum paragraf terakhir ia menulis: esai adalah kajian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, dinyawai oleh penulisnya sendiri. Meski kontradiktif, pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana sikap Jassin dalam menulis kritik sastra: ia mengutamakan pengalaman dibandingkan pengetahuan, dan ia nyawai karya-karyanya dengan subjektivitasnya.
Dalam esai “Kritik”, di buku yang sama, Jassin menganggap kritik adalah bagian dari esai. Dan sebagaimana esai, dalam memberikan pertimbangan baik atau buruk atas suatu karya sastra, kritik juga mengutamakan pengalaman daripada pengetahuan. Ia bahkan menyarankan sebaiknya seorang kritikus memiliki bakat sebagai seniman/sastrawan sebab jiwa seniman hanya dapat dimengerti oleh mereka yang memiliki bakat seniman. Menurut Jassin, seorang sastrawan tidak bisa mengambil bahan-bahan penulisannya dari buku-buku lain, tetapi terutama dari kehidupan. Begitu pula kritikus harus menulis berdasarkan pengalaman sehingga pertimbangannya adalah pertimbangan orang yang berpengalaman.
“Buku-buku lain” adalah pengetahuan, sementara kehidupan adalah pengalaman. Bila kita mencermati karya-karya Jassin, terbentang bagaimana ia menilai kandungan karya sastra dengan mempertimbangkan pengalaman kehidupannya sendiri, semisal saat membahas karya-karya Angkatan 66. Tidak hanya itu, ia juga mengaitkan karya sastra dengan pengalaman hidup para penulisnya berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan sejumlah penulis, baik secara langsung maupun melalui surat menyurat, sehingga untuk memulai kajian atas karya seorang penulis Jassin sering mendedah dulu siapa dan bagaimana kehidupan penulisnya. Namun, sebelum sampai pada pertimbangan pengalaman-pengalaman tersebut, apa yang paling penting adalah mengalami karya sastra berbekal intuisi.
Dalam sejumlah tulisan dan pernyataan di sejumlah wawancara, Jassin konsisten dengan pendapatnya bahwa karya sastra harus dikaji dengan intuisi. Bahkan pada pidato pengukuhan doktor kehormatannya ia menulis: “.…penyelidikan kesusastraan bukan hanya pekerjaan otak, tetapi terutama pekerjaan hati yang ikut bergetar dengan objek penyelidikan dan sebagai penyelidikan harus mengandung serta memantulkan kembali getaran-getaran itu.” Barangkali klise menyatakan “apa yang ditulis dengan hati harus diterima pula dengan hati”, tetapi itulah dasar kerja kritik Jassin. Intuisi ditempatkan lebih tinggi dibandingkan teori.
Hal inilah yang membedakan kerja kritik Jassin dengan kritik sastra masa kini, terutama kritik akademik. Kita dapat melihat bagaimana kritik sastra akademik sekarang lebih banyak dibebani dengan pengetahuan teori daripada eksplorasi kritikus terhadap karya sastra dengan mengurai bagaimana pengalaman perasaan si kritikus terhadap karya yang dikajinya. Maka, kita seringkali melihat judul karya kritik akademik selalu memenuhi formula: “(objek formal) dalam (objek material)”, semisal “Hegemoni Tandingan dalam Kumpulan Puisi…” atau “Kritik Gender dalam Antologi Puisi…”, atau dalam format sebaliknya: “Novel …: Analisis Wacana Kritis”, dan sejenisnya. Lihat pula daftar isi sejumlah karya akademik di kampus yang biasanya disusun berdasarkan konsep-konsep teoretis yang diaplikasikan daripada berdasarkan temuan kajian. Ini menunjukkan bahwa para pengkaji cenderung mencari konsep-konsep teoretis pada karya yang dibahas, bukan mengungkap apa yang dikandung karya sastra. Maka kita temukan buku-buku berjudul, semisal, Gastronomi Sastra, Ekologi Sastra, dan Wisata Sastra. Di waktu bersamaan pula muncul gagasan yang menomorduakan sastra dengan sekadar uthak-athik-gathuk sastra dengan disiplin ilmu lainnya. Ada yang bermasalah dalam dunia akademik sastra yang melahirkan teori fisika sastra, matematika sastra, fisika sastra, dan lain-lain, tanpa dasar ontologis dan epistemologis yang kokoh.
Berbeda dengan contoh cara kerja di atas, Jassin selalu meneroka masalah yang dihadirkan dalam sastra. Karya sastra diteropong bagian-bagiannya, dihubungkan satu dengan lainnya, untuk mendapatkan suatu penilaian yang menyeluruh, tentang isinya, semangat yang dibawanya, dan seninya.[1] Ia berangkat dari pengalamannya membaca karya sastra yang sedang dikajinya, bukan dari pengetahuan akan teori-teori yang jelas dikuasainya. Ia paham eksistensialisme, tetapi ia tidak berbasa-basi tentang hal tersebut saat membahas puisi-puisi Chairil. Ia juga mengerti naturalisme, tetapi hanya yang terkait dengan karya puisi Kirjomulyo yang dibahasnya, selebihnya tidak. Ia tahu puisi “Kamar”-nya Chairil mengandung 3 x 4 m, tetapi tidak mengaitkannya dengan matematika[2], melainkan dengan tradisi penulisan sebelumnya yang belum memasukkan angka dalam puisi, dan pemaknaannya sesuai dengan konteks puisi itu dituliskan.
Sementara dari kalangan praktisi masa kini, banyak kritik berupa perbandingan antar-karya. Tentu, ini jadi tak adil bagi karya yang dikaji. Apalagi jika yang dikaji adalah karya penulis pemula yang kadang dibandingkan dengan penulis dunia. Ada banyak teknik penulisan, ada banyak definisi karya sastra, masing-masing penulis bebas memilih untuk mengaplikasikan. Menjadi naif kalau puisi yang ditulis dengan semangat antipuisi dibandingkan dengan puisi lirik. Jassin tidak membandingkan antara karya satu penyair dengan karya lainnya, kecuali sebagai representasi zaman atau ketika masyarakat sastra sedang membahas hal tersebut. Kalau pun ada perbandingan, ia tak mengurai soal kualitas mana yang lebih baik, tetapi sekadar mendeskripsikan kandungan masing-masing karya.
Sebab Jassin menjadikan intuisi sebagai dasar kerja kritiknya, karya-karyanya sebagian besar ditulis sebagai respons atas pernyataan orang lain atau peristiwa kesusastraan yang tengah aktual.
Responsif
Ada tiga penyair yang puisi-puisinya dibahas cukup mendalam oleh Jassin, yakni Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Kirjomulyo. Ketika membahas karya Amir Hamzah dan Kirjomulyo, Jassin tak bisa melepaskan sosok Chairil. Ia menulis Amir Hamzah Raja Pujangga Baru salah satunya karena dipantik omongan Chairil kalau puisi-puisi penyair Setanggi Timur itu “duistere poezie” (puisi gelap). Hasilnya, ia dengan cukup terang memaparkan bahwa kegelapan tidak terletak pada puisi-puisi Amir Hamzah, tetapi ada pada kepala pembaca yang belum cukup memiliki pengetahuan yang digunakan sebagai dasar penulisan: tarikh dan filsafat Islam. Sementara ketika membahas karya Kirjomulyo, ia menyempatkan diri untuk menanggapi beberapa pendapat yang menyatakan karya penulis Romance Perjalanan ini telah lepas dari keterpengaruhan Chairil. Dalam tinjauan Jassin, jejak Chairil masih hadir dalam beberapa puisi Kirjo.
Bagian awal esai tentang Angkatan 45 (1951) juga merupakan tanggapan Jassin atas beberapa keberatan terhadap penamaan itu, terutama terkait angka yang merujuk tahun kemerdekaan. Nama “Angkatan 45” sejatinya dikenalkan oleh Rosihan Anwar dalam Majalah Siasat (9 Januari 1949). Jassin meminjam nama itu dengan dasar yang berbeda dari Rosihan. Salah satu keberatan penamaan ini adalah pertanyaan apakah mereka yang tak ikut berjuang layak dianggap sebagai Angkatan 45? Jassin menjawab bahwa soal perjuangan tidak hanya terkait dengan hal fisik, karya sastra yang merepresentasikan sikap ketidaksetujuan atas penjajahan juga merupakan bagian perjuangan.
Apa yang menarik adalah fakta bahwa telah banyak sebutan untuk angkatan ini, termasuk yang berasal dari para sastrawan masa itu, di antaranya Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Perang, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Pembebasan, dan Generasi Gelanggang, tetapi tidak populer. Selang setahun setelah penerbitan tulisan Jassin tentang Angkatan 45, Aoh. K Hadimadja (yang beberapa tulisannya juga direspons oleh Jassin melalui “Kesusastraan dan Politik” dan “Humanisme Universil” dalam Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai) menulis Beberapa Paham Angkatan 45 (1952) dan beberapa dekade kemudian Keith Foulcher menyetujui terjemahan kajian akademiknya menjadi “Angkatan 45: Sastra, Politik Kebudayaan, dan Revolusi Indonesia” (1994) meskipun ia mengkritik kerja Jassin yang baginya kurang meninjau latar sejarah dengan komprehensif.
Buku Angkatan 66: Prosa dan Puisi tak lain juga adalah respons terhadap Ajip Rosidi yang menulis “Sumbangan Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia kepada Perkembangan Sastra Indonesia”. Bagi Jassin ada beberapa kelemahan dalam tulisan tersebut. Pertama, diksi “terbaru” memiliki kekaburan makna sebab angkatan yang terbaru sebentar lagi tidak akan paling baru lagi. Kedua, pengambilan contoh yang timpang untuk merepresentasikan penyair yang mewakili generasinya, misalnya, untuk Pujangga Baru nama Amir Hamzah tidak muncul. Ketiga, pernyataan Ajip yang mengatakan bahwa Angkatan Terbaru belajar pada kebudayaan Indonesia, bukan seperti angkatan terdahulu yang belajar ke luar negeri, padahal sebagian besar sastrawan yang masuk dalam Angkatan Terbaru itu pun bersinggungan dengan dunia internasional.
Akan panjang jika membahas satu demi satu karya Jassin yang kebanyakan merupakan respons atas tulisan atau pernyataan orang lain dan/atau peristiwa kebudayaan (semisal Pengadilan Puisi dan Penyair Muda di Depan Forum) yang terjadi pada masanya. Apa yang perlu digarisbawahi adalah, selain konsisten merespons, Jassin tidak sekadar menguraikan kelemahan tulisan atau pernyataan yang disanggahnya, tetapi menawarkan jawaban yang lebih logis dan mudah diterima. Barangkali, karena tulisan-tulisannya yang bernada korektif itulah karyanya lebih lekat kepada pembaca sastra di Indonesia.
Lalu bagaimana dengan pembagian periodisasi sastra Indonesia berdasarkan Angkatan yang dibuat Jassin? Bukankah justru banyak kritik atas penyusunan sejarah sastra dengan cara seperti itu?
Angkatan Jassin
“Apa pun yang dikatakan Balfas tentang ulasan sastra saya, toh buku-buku saya masih dipakai oleh anak-anak SMA dan mahasiswa Fakultas Sastra.[3] Orang-orang masih mengutip pendapat yang saya ucapkan 20 atau 30 tahun yang lalu. Saya sendiri heran….. Tapi ternyata saya lihat sastrawan pilihan saya itu bisa survive. Seperti Amir Hamzah yang saya namakan Raja Penyair Pujangga Baru dan Chairil Anwar yang saya namakan Pelopor Angkatan 45.”
Ucapan Jassin di atas menerbitkan pertanyaan: mengapa pendapat dan hasil kajiannya, terutama tentang Angkatan sastrawan, bahkan sampai sekarang masih banyak dijadikan rujukan afirmatif padahal telah banyak dikritik. Jika karya Amir Hamzah dan Chairil Anwar masih survive, apakah memang karena kajiannya atau karena kualitas karya kedua penyair?[4]
Kritik atas kerja Jassin sebenarnya tidak hanya dari Balfas, ada pula Rustandi Kartakusumah, Subagio Sastrowardoyo, Ajip Rosidi, Sri Rahayu Prihatmi, Harry Aveling, dan Rachmat Djoko Pradopo. Penyusunan sejarah sastra berdasarkan Angkatan yang digagas Jassin[5] menimbulkan beberapa keberatan. Pertama, soal dasar pengambilan angkatan sebagai kategori dianggap tidak objektif. Jassin sendiri mengakui kajiannya tidak disusun terlalu objektif. Kedua, penamaan “angkatan” dianggap memposisikan sastra sebagai pendompleng pada bidang politik. Jassin tidak mengiyakan, tetapi baginya “…timbulnya suatu angkatan selalu harus disertai unsur estetika, politik, dan sejarah.” Apakah benar ia memposisikan estetika pada tempat pertama saat menggagas angkatan sastra?
Kita akan melihatnya pada dua angkatan sastra yang lekat dengannya, yaitu Angkatan 45 dan Angkatan 66. Perlu dijernihkan dulu bahwa sebelum Jassin mengikrarkan adanya Angkatan 45, sejatinya sudah ada gerakan sejumlah sastrawan (dengan beragam sebutan seperti Angkatan Baru, Angkatan Kemerdekaan, dan Generasi Gelanggang) yang mengkritik generasi Pujangga Baru dalam soal bentuk dan isi karya sastra dengan menawarkan kebaruan dalam karya mereka. Dapat dikatakan, Jassin hanya menangkap, merangkum, sekaligus menegaskan upaya pembaruan yang dilakukan oleh kumpulan sastrawan tersebut. Ada banyak pernyataan dan sikap sastrawan (semisal Asrul Sani, Sitor Situmorang, dan tentu saja Chairil Anwar) yang dijadikan dasar Jassin saat mengurai prinsip kerja dan nilai karya para sastrawan Angkatan 45.
Ini berbeda dengan Angkatan 66 yang disusun, selain untuk merespons Ajip Rosidi, sebagai semacam upaya mengambil kecenderungan umum dalam karya-karya sastrawan masa itu, dalam hal bentuk dan isi. Tidak ada satu pun pernyataan sastrawan masa itu yang dimasukkan sebagai dasar argumen Jassin dari luar karya mereka. Semisal suara Taufiq Ismail, Bur Rasuanto, dan Mansur Samin, diambil dari karya mereka. Jassin memperlakukan baris-baris kata yang dikutipnya dari puisi dan prosa Angkatan 66 seolah pernyataan langsung penulisnya, sebagai fakta sosial dengan meletakkannya pada konteks sejarah masa itu. Ia tak melakukan tinjauan bolak-balik dari dalam karya dan luar karya sebagaimana pernah dilakukannya saat membahas Angkatan 45.
Estetika menjadi muara Jassin dalam menjelaskan Angkatan 45, terutama saat membandingkannya dengan generasi Pujangga Baru. Bagaimana ia mengambil sampel karya juga lebih atas dasar kebaruan estetika—meskipun sebagian ditunjukkan oleh para sastrawannya sendiri. Politik memang sesekali muncul dalam uraian, terutama saat menjelaskan sikap Angkatan 45, tetapi posisi politik di sini hanya lekatan konteks sejarah yang menerangkan bagaimana estetika baru mulai muncul. Ini sangat berbeda saat Jassin menyusun Angkatan 66, sampai ia sendiri menyatakan: “Memang benar, secara estetika, karya Angkatan 45 dengan 66 tak banyak berbeda. Namun, saya melihat segi sejarah dan politik yang begitu kuat.” Tentu, “tak banyak berbeda” tidak sama dengan “tak berbeda”, tetapi kalimat terakhir menjunjukkan bagaimana Angkatan 66 digagas dan disusun: estetika kalah dibandingkan sejarah dan politik.
Dalam “Bangkitnya Satu Generasi” yang membuka buku Angkatan 66 Prosa dan Puisi, Jassin sempat menyinggung bahwa kelebihan angkatan ini adalah memperhatikan sudut estetis. Namun, ia tak mengurai sudut estetis yang bagaimana dan seperti apa sebagaimana dulu ia menguraikan estetika Angkatan 45. Jassin justru jatuh pada sikap politis. Alih-alih membandingkan estetika karya Angkatan 66 dengan generasi terdahulu, ia justru membandingkannya dengan estetika Lekra. Jassin menyatakan tema sentral Angkatan 66 adalah perjuangan, religius, dan Pancasila. Pancasila menjadi pembeda sebab perjuangan dan religiusitas sudah lama diangkat dalam karya-karya sastra masa sebelumnya.[6]
Ia lebih banyak menguraikan karya sastra Angkatan 66 sebagai cerminan kondisi sosial sebelum 1966, tentang represifnya PKI di tahun-tahun sebelumnya, dan saat puisi dijadikan media untuk berdemonstrasi. Sebagaimana diketahui, Jassin termasuk korban praktik politik yang dijalankan PKI pada masa itu. Ia berbeda pandangan dengan Lekra dan sempat beberapa kali mendapatkan serangan bahkan sampai dipecat dari tempatnya mengajar sehingga alih-alih merumuskan Angkatan dengan netral, ia justru memihak dan menyimpulkan kalau Angkatan 66 membawa kesadaran nurani manusia, sesuatu yang menurutnya tak dimiliki oleh pengarang-pengarang Lekra.
Di akhir tulisannya, Jassin menyimpulkan angkatan sastra akan lahir setiap 15 – 20 tahun. Bila kita gunakan pernyataan ini sebagai dasar kelahiran generasi baru sastra, angkatan yang disusun Jassin justru kurang memenuhi kriteria tersebut. Pujangga Baru (1933) berjarak 12 tahun ke Angkatan 45, sementara Angkatan 66 berjarak 21 tahun dengan Angkatan 45. Meskipun demikian, angkatan yang dirumuskan Jassin lebih banyak diterima dan diperbincangkan daripada yang digagas oleh Rendra, Ajip Rosidi, Abdul Hadi WM serta Harry Aveling).
Kekuatan Narasi
Keberatan ketiga terhadap konsep Angkatan H.B. Jassin tertuju pada kata “angkatan” yang dinilai problematis. Jassin sendiri tak pernah menerangkan perihal mengapa ia memilih “angkatan” dibandingkan istilah lain. Istilah ini saat digunakan Takdir kali pertama juga tak menimbulkan keberatan. Tak menutup kemungkinan Jassin yang responsif pasti akan menerangkan panjang lebar sekiranya “angkatan” dipermasalahkan sejak mula mempublikasikan Angkatan 45. Kritik tajam terhadap penggunaan istilah ini datang dari kalangan akademisi, salah satunya dari Rachmat Djoko Pradopo.
Dalam pandangan Pradopo, istilah “angkatan” cenderung subjektif. Ia mendefiniskan angkatan sebagai sekumpulan sastrawan yang hidup dalam suatu kurun masa atau menempati suatu periode tertentu.[7] Meskipun ia mendefiniskan “angkatan” tanpa merujuk ke Jassin, setidaknya ia tidak segegabah beberapa akademisi yang mengkritisi soal “angkatan” ini dengan mempermasalahkan tahun lahir dan tahun penulisan. Padahal jelas, Jassin mendasarkan angkatan pada karya (tahun penulisan) bukan pada waktu kelahiran. Pradopo menawarkan agar “angkatan” diganti dengan “periode” yang dirujuknya dari René Wellek (1954) sebagai suatu masa yang dikuasai sebuah sistem norma sastra, standar, dan konvensi sastra yang pemunculan, penyebaran, keberagaman, integrasi, dan kelenyapannya dapat dirunut.
Masih bersandar pada Wellek, Pradopo menyatakan kesusatraan jangan dikonsepsi hanya sebagai cermin pasif atau tiruan perkembangan politik, masyarakat, atau bahkan daya intelektual manusia, tetapi hendaknya ditetapkan dengan kriteria sastra yang murni. Tentu, pernyataan tersebut diarahkan sebagai kritik terhadap Angkatan 66 yang digagas Jassin. Pradopo lalu menawarkan sekaligus mencontohkan penyusunan sejarah sastra dengan metode estetika resepsi yang dipinjamnya dari Hans Robert Jauss (1970). Hasilnya adalah sekumpulan daftar tahun, sastrawan, ciri intrinsik, dan ciri ekstrinsik karya-karya terkait. Pradopo seolah mengulang susunan sejarah sastra yang dibangun oleh Jassin (dan beberapa penyusun sebelumnya) dengan membariskannya pada tahun-tahun secara kronologis (dan sayangnya pemilihan tahun ini juga masih mengacu apa yang telah disusun dan sesuai “ramalan” Jassin). Apa yang membedakannya hanya tambahan ciri intrinsik, yang berupa rangkuman kecenderungan umum atas karya-karya yang terbit pada kurun tertentu. Sementara ciri ekstrinsik masih lekat juga seperti dalam paparan Jassin dan para penulis terdahulu.
Upaya Pradopo adalah yang kesekian, setelah Boejoeng Saleh, Bakri Siregar, Ajip Rosidi, dan Nugroho Notosusanto, dalam penyusunan sejarah sastra Indonesia. Namun, kembali pada pernyataan di atas yang belum terjawab, mengapa karya Jassin yang lebih banyak diterima oleh masyrakat sastra Indonesia? Karya-karya tersebut memang menawarkan perspektif yang berbeda dari apa yang digunakan Jassin, tetapi hampir seluruhnya, meminjam istilah anak zaman sekarang, salfok pada sejarah, bukan fokus pada sastra. Dalam karya-karya tersebut terlihat bagaimana sastra diperlakukan sebagai fakta sosial, ditulis menyerupai penulisan sejarah pada umumnya, dan dibandingkan–bahkan hampir jatuh pada verifikasi–dengan kondisi sosial, serta sedikit mengungkapkan estetika. Padahal, apa yang ditawarkan Wellek dan Jauss, misalnya, sangat menjanjikan seandainya Pradopo berhasil membuat sejarah sastra berdasarkan aspek yang murni sastra, semisal, “Metafora Alam dalam Sajak Indonesia Dekade 1930-an” atau “Sinisme Prosa Indonesia Masa Revolusi.”
Selain faktor eksternal di atas, konsep Angkatan yang dibangun Jassin lebih banyak diterima juga karena metode penulisannya. Metode penulisan yang digunakan tidak hanya eksploratif, tetapi juga naratif. Ia bisa mengungkapkan sisi estetika bersamaan dengan konteks sejarah dengan alur yang kronologis. Jassin tidak hanya membawa angka tahun dan daftar sastrawan, tetapi menghadirkan peristiwa sejarah melalui karya yang dikutipnya sembari menguraikan estetikanya. Ia meyakini untuk menikmati—dan tentu mengkaji—karya sastra bukan hanya dari segi keindahan bahasa, melainkan perlu pula pengetahuan kemasyarakatan dan kesejarahan.
Harris (1994) mencatat bahwa penafsiran makna yang dimaksudkan pengarang tidak akan pernah lebih dari kemungkinan. Di sisi lain, penafsiran yang benar selalu terancam oleh kegagalan pembaca untuk mengenali unsur-unsur operatif konteks. Meskipun demikian, tingkat kemungkinan benarnya sebuah penafsiran cukup tinggi dan apabila ada kesalahan selalu berpotensi diperbaiki dengan penemuan unsur-unsur lebih lanjut dari konteks yang melingkupi lahirnya karya sastra. Sejarah sastra internal tunduk pada ketidakcukupan dalam pemilihan sampel, dan seringkali ada bidang yang lebih luas dari mana sampel tersebut harus dipilih. Sejarah sastra eksternal cenderung mengabaikan atau menekankan beberapa kondisi penjelas demi membangun narasi yang menarik. Jassin bekerja dalam dua aras itu, ia memilih contoh dengan mengabaikan keluasan bidang (yang mewujud dalam tema) yang ditulis oleh seorang penulis. Sementara dalam hal ekstenal, ia berkarib dekat dengan para sastrawan sehingga kondisi bagaimana karya ditulis atau setidaknya tujuan mengapa karya itu ditulis mampu menjadi bahan narasi penyusunan sejarah sastranya. Sebagaimana disinggung di atas, menurut pandangan Harris, sejarawan sastra bekerja dengan data dan komentar naratif. Nah, Jassin menjadikan unsur intrinsik sebagai data yang dipilihnya (tidak pada Angkatan 66) untuk kemudian dikomentari secara naratif berbekal pengetahuannya akan konteks kreatif kekaryaan seorang sastrawan.
Penulis-penulis sejarah sastra Indonesia[8] yang disinggung di atas kebanyakan hidup sezaman dengan Jassin, tetapi hanya Jassin yang mampu menarasikan bagaimana peristiwa terjadi dan hadir dalam karya sastra. Jassin menyadari dan mengakui kalau tulisannya tidak terlalu objektif sehingga ukuran ilmiah sepatutnya tidak diterapkan untuk menilai hasil kerjanya. Barangkali daripada menulis karya yang terlalu objektif, ia memilih menulis karya dengan naratif, dan ternyata hasilnya lebih efektif. Karya yang naratif itu tampaknya sulit hadir jika Jassin tak memiliki relasi dan keakraban dengan para tokoh sastra yang dibahasnya.
Relasi, Intimasi, dan Legitimasi
Kebiasaan membaca yang dibawanya dari rumah membuat Jassin tak kikuk ketika bertemu dengan Sutan Takdir Alisjahbana. Bahkan, koleksi pengetahuan yang didapatnya dari buku-buku yang dibacanya sejak kecil mampu membekalinya untuk bercengkrama soal Pujangga Baru, kesusastraan, dan bahasa, dengan tokoh yang waktu itu tengah menjadi pentolan Pujangga Baru. Takdir terkesan dengan anak muda ini sampai menawarkan pendidikan calon pimpinan redaksi. Jassin menerima tawaran itu sehingga pada suatu pagi di Batavia, 1 Februari 1940, ia mulai bekerja di kantor Balai Pustaka. Ia masuk dalam tim redaksi yang di dalamnya ada Takdir, Tulis Sutan Sati, Armijn Pane, Aman Dt. Madjoindo, dan Nur Sutan Iskandar. Bersama tokoh-tokoh sastrawan tersebut, ia bertugas menyusun resensi buku-buku yang akan dimuat di sejumlah media. Menurut pengakuannya, resensi-resensi itu yang kemudian dibukukannya dalam Kesusatraan Indonesia dalam Kritik dan Esai.
Itu adalah awal bagaimana relasi Jassin di dunia sastra mulai tersusun. Ia berada di pusat sastra masa itu: Balai Pustaka. Dari relasi itu, ia mulai mengembangkan bacaannya ke bidang psikologi dan filsafat atas saran para tokoh Pujangga Baru. Ia juga semakin akrab dengan para sastrawan muda masa itu, terutama Chairil Anwar. Apa yang istimewa dari Jassin adalah bagaimana relasi itu tidak dijaganya dengan pujian. Ia kerap berbeda pandangan dengan beberapa orang, termasuk dengan Takdir.
Relasi itu juga dijaganya dengan menjalin keakraban melalui surat-menyurat. Dalam surat-suratnya kita bisa melihat bagaimana Jassin bersimpati dan menaruh empati. Kepada S. Rukiah, ia memberi dukungan mental saat penyair tersebut dituduh melakukan plagiasi. Jassin menawarkan bantuan dengan catatan Rukiah berkenan mengirimkan mana sajak-sajak yang dianggap plagiat dan surat-surat tuduhan yang menyerangnya. Kepada Ibu Saleha, ibunda Chairil Anwar, Jassin mengabarkan kondisi kesehatan si anak hilang dan menawarkan bantuan mengurus Chairil. Kepada Iwan Simatupang, yang sajaknya ia hantam, ia pun berkirim surat dan menyemangati agar tetap semangat menulis.
Tidak hanya itu, Jassin dalam surat-suratnya juga menyampaikan gagasan yang merupakan tanggapan atas “serangan” terhadapnya dan ia menulis juga soal bagaimana menilai puisi. Beberapa esai telah Jassin tulis untuk menanggapi Balfas yang kritis kepadanya, tetapi baginya itu tidak cukup sehingga ia menulis surat yang cukup panjang kepada Balfas yang menyerangnya habis-habisan karena menugukan Chairil Anwar. Dalam surat-suratnya kepada Balfas, Jassin membabar soal tugas dan tanggung jawab penyair yang merupakan pangkal perbedaan mereka dalam menilai Chairil. Kepada Subagio, ia tak segan memuji bahwa Simphoni merupakan kumpulan puisi tentang hidup yang bisa diterimanya (baca: dihayati) meskipun ada perbedaan pandangan antara mereka dengan merentangkan pembahasan bagaimana pemahaman tentang “bawah sadar” dalam teori Freud antara dirinya dan Subagio berbeda.
Relasi dan intimasi yang dibangun oleh Jassin ini semakin kuat dengan dukungan lembaga tempatnya bekerja, yang memberinya legitimasi untuk mengangkat karya mana yang akan dibahas.
Ia tercatat sebagai redaktur penerbit Balai Pustaka dan beberapa majalah, seperti Panji Pustaka, Panca Raya Mimbar Indonesia, Siasat, Kisah, Sastra, dan Horison. Posisinya sebagai redaktur membuatnya bisa menyeleksi karya sastra sebelum diterbitkan—karya-karya yang nantinya menjadi topik kajiannya. Barangkali sebab inilah pembahasan-pembahasan para pakar sejarah sastra tidak bisa lepas dari Jassin. Para pakar itu tidak bisa memunculkan nama baru sebab mereka membahas karya yang sudah diseleksi Jassin. Legitimasi juga didapatkannya karena pekerjaannya sebagai pengajar dan peneliti sastra di Universitas Indonesia. Dengan ketiga hal tersebut, Jassin kerap menjadi pembela bagi para sastrawan.
Dua Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45
Sejak esai “Seni Seniman Penikmat Seni”, yang jadi pembuka buku Tifa Penyair dan Derahnya, Jassin berperan sebagai pembela para sastrawan. Di masa itu ada sikap tak asyik dari para cendekiawan mengenai hasil karya sastrawan. Mereka yang kebanyakan telah menamatkan sekolah menengah itu menganggap aktivitas mengarang tak lebih sebagai lamunan para pengangguran. Mereka bahkan menyarankan para sastrawan untuk membuat sajak-sajak yang sekali baca langsung dimengerti, tidak sukar, tidak terlalu dalam maknanya, dan tidak panjang-panjang. Bagi Jassin ini adalah sikap konyol yang menunjukkan kalau para cendekiawan itu tidak mengikuti perkembangan sastra Indonesia yang pada masa itu sudah bergerak ke arah yang lebih tinggi. Para sastrawan masa itu sudah dewasa, tak lagi bicara soal khayalan berkasmaran sampai pelaminan, tetapi sudah berfilsafat dengan pandangan hidup dan cita-cita mandiri. Jassin menyarankan peminat sastra, termasuk para cendekiawan itu, untuk melatih diri, memperluas wawasan dengan studi, agar bisa menikmati karya sastra pada zaman itu, alih-alih meminta para penulis untuk menyesuaikan dengan selera mereka yang justru akan membuat karya sastra statis, atau bahkan menurun kualitasnya.
Dalam catatan Pamusuk Eneste, Jassin rajin membela para sastrawan, baik secara personal, seperti Amir Hamzah, Chairil Anwar, Kirjomulyo, Hamka, Subagio Sastrowardoyo, Goenawan Mohamad, dan Abdul Hadi WM, dan secara komunal seperti Angkatan 66 dan Forum Penyair Muda. Selain kepada Ki Panjikusmin, pembelaan Jassin paling dikenal sekaligus legitimatif adalah kepada Chairil Anwar.
Bukan rahasia umum kalau Jassin dan Chairil demikian karib, saking akrabnya mereka pernah berkelahi. Ah tidak, bukan berkelahi, sebab Chairil tak pernah membalas pukulan Jassin meskipun sempat berniat membalasnya dengan berlatih angkat besi segala. Menariknya, keakraban di antara keduanya, tak pernah menurunkan legitimasi Jassin yang menyebut kawannya sebagai Pelopor Angkatan 45. Padahal, bisa saja kita ngedumel: “Ah dia kan cuma muji-muji kawan sendiri.” Bukankah memang demikian, hanya ada sedikit kritik dalam tulisan yang memberi gelar pelopor tersebut?
Buku Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 dibuka dengan pernyataan tentang waktu yang tepat untuk membahas karya sang penyair setelah tujuh tahun wafat. Jassin secara tersirat mengungkapkan kekurangan si penyair, walau sayangnya itu tak terkait puisi, tetapi soal cara hidup, yang justru langsung diantisipasinya dengan: “saya tidak merasa mempunyai kompetensi untuk menyoroti sudut moral dari seniman ini.”. Barangkali karena memang tak punya kompetensi menilai moral, Jassin memilih mendudukkan perkara plagiat yang pernah memojokkan Chairil dengan memberikan jalan: bedakan antara terjemahan, saduran, dan plagiat. Bahkan, ia membelanya dengan cukup lugas: “Pada hemat saya sekalipun misalnya ditemui semua hasil-hasil Chairil Anwar plagiat, tak dapat disangkal bahwa lepas dari soal itu, ia sebagai penerjemah, masih berjasa telah membaharui persajakan Indonesia sesudah perang yang nyata lain dari yang tercapai sebelum perang.” Hmm…. Jassin kawan yang baik bukan?
Dalam “Tanggung Jawab Pengarang Jangan Digeserkan pada Masyarakat”, Jassin menilai ada kekeliruan yang jamak ditemui saat menilai karya seorang seniman. Seniman, termasuk pengarang, dapat dinilai dari dua hal, yakni upaya si pengarang dalam menulis dan kualitas karyanya. Menurut Jassin, hal pertama kerap dilupakan. Nah, atas dasar dua hal tersebut itulah tampaknya esai yang menempatkan Chairil sebagai Pelopor Angkatan 45 digagas. Maka wajar kalau dalam buku tersebut Jassin menjelaskan beberapa coretan dan catatan dalam kertas berisi puisi Chairil yang diterimanya sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Chairil memiliki watak ulet: tak pernah menulis puisi sekali jadi sebab setiap kata dipilih dengan matang.
Buku ini lebih terasa sebagai pembelaan terhadap karya Chairil Anwar sehingga bagian yang menguraikan puisi hasil terjemahan dan/atau saduran lebih banyak daripada bahasan tentang nilai puisi milik penyairnya. Mungkin saja Jassin tak ingin mengulang apa yang telah ditulisnya dalam sebuah esai panjang berjudul sama dengan judul buku tersebut. Perlu diketahui bahwa ada dua tulisan Jassin berjudul Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45. Tulisan pertama termuat sebagai salah satu esai dalam Kesusastraan Indonesia dalam Kritik dan Essay (Cetakan pertama, 1953) dan tulisan kedua dimuat sebagai catatan pembuka untuk buku Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 (Cetakan pertama, 1954). Apa yang sudah dibahas di atas adalah berdasarkan tulisan kedua. Lalu bagaimana isi tulisan pertama, apakah sama subjektifnya atau lebih objektif?
Jassin mengawali esainya dengan mengetengahkan perbedaan antara Pujangga Baru dan Angkatan Baru dari situasi zaman sampai estetika kedua angkatan tersebut. Situasi yang berbeda membawa pengungkapan yang berbeda dalam karya sastra. Angkatan baru menggunakan daya ungkap langsung, menanggalkan tradisi lama yang berbunga kata. Bagi Jassin, Chairil menjadi pelopor dalam angkatan baru karena sikapnya dan karyanya. Dalam bagian-bagian tertentu, ia mengulik kaitan antara sikap hidup kepenyairan Chairil dengan puisi-puisi karyanya. Ada konsistensi yang ditemukannya. Ia juga mengurai kandungan eksistensialisme dalam puisi-puisi Chairil yang ekspresif, yang merupakan kebaruannya. Selain itu, bagi Jassin sajak-sajak Chairil revolusioner dalam bentuk dan isi. Kebaruan bentuk ditunjukkan melalui sejumlah metafora, asosiasi, dan internalisasi simbol aljabar dalam puisi dengan gaya yang ekspresif. Sementara kebaruan isi ditunjukkan melalui individualisme yang kritis terhadap alam. Selain mengungkap kebaruan isi dan bentuk puisi, Jassin juga memaparkan bagaimana kebaruan itu bisa ditemukan melalui pergaulan Chairil yang melintasi beragam profesi: dari abang becak sampai Bung Sjahrir, dari komponis sampai pelukis. Diungkap pula bagaimana luasnya bacaan Chairil. Bagi saya esai ini lebih layak melengkapi buku “Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45” sebagai prolog, sementara yang selama ini menjadi catatan pembuka selayaknya jadi epilog.
Simpulan
Sastra itu relatif. Sejarah juga demikian. Bergantung siapa menulis, bergantung siapa menafsir. Jassin telah banyak menafsir karya sastra dengan mengandalkan intuisinya dan menyusun sejarah sastra dengan metode penulisan yang naratif. Beberapa orang keberatan dengan hasil kerja kritiknya yang kerap “membaptis” sastrawan dan beberapa yang lain keberatan dengan penyusunan sejarah sastra Indonesia berdasarkan angkatan yang diidentikkan sebagai proses kanonisasi yang telah meminggirkan sejumlah karya tertentu. Keberatan-keberatan yang ada—termasuk yang terdapat dalam esai ini—sejatinya telah menunjukkan pada kita bahwa kerja kritik Jassin memiliki banyak kekurangan. Meskipun banyak dikritik, karya-karya Jassin masih populer dan pendapatnya masih banyak diikuti. Hal ini merupakan dampak dari aktivitasnya di luar menulis kritik, yakni membangun relasi dan intimasi dengan sejumlah sastrawan hingga tak segan memberikan pembelaan. Pekerjaannya sebagai redaktur dan peneliti turut pula mendukung capaian kerja kritiknya. Lepas dari segala kekurangannya, hendaknya hasil kerja kritik Jassin dijadikan sebagai pemantik untuk menulis lebih dalam tentang hal-hal yang pernah dikajinya. Ia telah memberikan sejumlah petunjuk, apakah petunjuknya itu benar atau keliru harus dikaji lagi. Sebagai petunjuk ia bisa mengarahkan pada sesuatu yang benar jika kita tahu. Pertanyaannya, seberapa tahu kita akan segala yang telah ditulis Jassin?
Daftar Bacaan
Erll, Astrid. 2014. “Generation in Literary History: Three Constellations of Generationality, Genealogy, and Memory” dalam New Literary History , SUMMER 2014, Vol. 45, No. 3 (SUMMER 2014), hlm. 385- 409. Diterbitkan oleh The Johns Hopkins University Press, https://www.jstor.org/stable/24542733.
Fry, N. 1981. “Literary History” dalam New Literary History , Winter, 1981, Vol. 12, No. 2, Interpretation and Literary History (Winter, 1981), hlm. 219-225. Diterbitkan oleh The Johns Hopkins University Press, https://www.jstor.org/stable/468667.
Harris, W.V. 1994. “What Is Literary “History”? dalam College English , April 1994, Vol. 56, No. 4 (April 1994), hlm. 434-451, https://www.jstor.org/stable/378337.
Jassin, H.B. 1955. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay. Jakarta: Gunung Agung.
Jassin, H.B. 1962. Amir Hamzah Raja Penyair Pujangga Baru. Jakarta: Gunung Agung.
Jassin, H.B. 1963. Pujangga Baru: Prosa dan Puisi. Jakarta: Gunung Agung.
Jassin, H.B. 1977. Tifa Penyair dan Daerahnya. Jakarta: Gunung Agung.
Jassin, H.B. 1983. Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia. (Editor: Pamusuk Eneste) Jakarta: Gramedia.
Jassin, H.B. 1984. Surat-Surat H.B. Jassin 1943-1983. (Editor: Pamusuk Eneste). Jakarta: Gramedia.
Jassin, H.B. 1985. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei III. Jakarta: Gramedia.
Jassin, H.B. 1985. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei IV. Jakarta: Gramedia.
Jassin, H.B. 2013. Angkatan 66: Prosa dan Puisi. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Jassin, H.B. 2018. Chairil Anwar Pelopor Angkatan ‘45. Yogyakarta: Narasi.
Jaus, H.R. dan E. Benzinger. 1970. “Literary History as a Challenge to Literary Theory” dalam New Literary History , Autumn, 1970, Vol. 2, No. 1, A Symposium on Literary History (Autumn, 1970), hlm. 7-37. Diterbitkan oleh The Johns Hopkins University Press, https://www.jstor.org/stable/468585.
Pradopo, R.D. 2013. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rosidi, A. 1988. Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
Summit, J. 2010. “Literary History and the Curriculum: How, What, and Why” dalam Profession. hlm. 141-150. Diterbitkan oleh Modern Language Association, https://www.jstor.org/stable/41419872.
Wellek, R. dan A. Warren. 1954. Theory of Literature. London: Lowe & Brydone.
[1] Lihat esai “Kritik” dalam Tifa Penyair dan Daerahnya.
[2] Silakan simak https://youtu.be/ZL0c2VnRWHI?t=4093 untuk mengetahui bagaimana beberapa akademisi mengaitkan sastra dan matematika, tetapi tidak mengaitkannya dengan konteks zaman dan perkembangan puisi kontemporer.
[3] Sampai sekarang, beberapa kampus masih menggunakan buah pikiran Jassin dalam mengelompokkan generasi sastra Indonesia. Karya-karya yang dibahas, yang dijadikan contoh, juga masih cenderung sama dari tahun ke tahun. Bandingkan dengan Stanford University yang dalam kurikulum pembelajarannya mendefinisikan sebuah karya sebagai perwakilan periode tertentu yang ditentukan setiap tahun oleh sebuah tim dengan metode kolaboratif. Lihat Summit, J. 2010. “Literary History and the Curriculum: How, What, and Why” dalam Profession. pp. 141-150. Published by: Modern Language Association.
[4] Khusus Chairil, dalam suratnya kepada Balfas, Jassin menulis: “Ada orang mengatakan Chairil Anwar dibesarkan oleh Jassin. Ini bohong. Idrus dan Chairil Anwar besar sendiri.” Menarik pula untuk mencari sebab mengapa nama Kirjomulyo tidak disebut oleh Jassin dalam pernyataan di atas. Bukankah Jassin yang membaptisnya sebagai Penyair Alam? Apakah karena Kirjo tidak merepresentasikan kecenderungan gaya dan tema karya penyair semasanya sebagaimana dua nama pertama? Atau Jassin merasa kajiannya tentang puisi-puisi Kirjo merupakan salah satu kegagalannya? Pertanyaan-pertanyaan terkait Kirjo sejatinya menarik untuk diperikan, tetapi tidak dalam tulisan ini, mungkin di lain kesempatan (atau mungkin ada yang tertarik mengkajinya?).
[5] Sebetulnya Jassin bukanlah orang yang mengawali penyebutan “angkatan” dalam sastra. Sutan Takdir Alisjahbana lebih dulu menulis “angkatan baru” dalam pengantarnya di buku Puisi Baru (1946). Namun, tiga buku Jassin tentang Angakatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66 menjadikan ia sasaran kritik tentang penggunaan istilah tersebut di bidang sastra.
[6] Bandingkan dengan kritik Ajip Rosidi terhadap Angkatan 66 dalam “Masalah Angkatan dan Periodisasi Sastra Indonesia” dalam Sejarah Sastra Indonesia (1988)
[7] Istilah “angkatan” yang digunakan Jassin lebih dekat pada “generasi” sebagaimana diterangkan Erll (2014) sebagai sesuatu yang disusun dari konstelasi diskursif, atau kumpulan, di mana politik, berbagai bentuk pengetahuan, teknologi, dan praktik budaya berinteraksi. Ini berbeda dengan pengertian generasi secara umum sebagai sesuatu yang terberi dari bagian sejarah.
[8] Frye (1981) pernah terkejut mendapatii kebanyakan sejarah sastra hanya berkaitan dengan daftar nama dan angka peristiwa. Padahal, menurutnya sejarah sastra sangat berkaitan dengan konvensi dan genre, baik secara diakronis maupun sinkronis. Penulisan sejarah sastra Indonesia belum banyak menyentuh aspek genre dan masih banyak berlangsung secara sinkronis.

Saeful Anwar
Saeful Anwar adalah staf pengajar di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Menulis Persada Studi Klub dalam Arena Sastra Nasional (UGM Press, 2017) dan Ruang-Ruang Kemungkinan dalam Kritik Sastra Akademik (Jejak Pustaka, 2024).